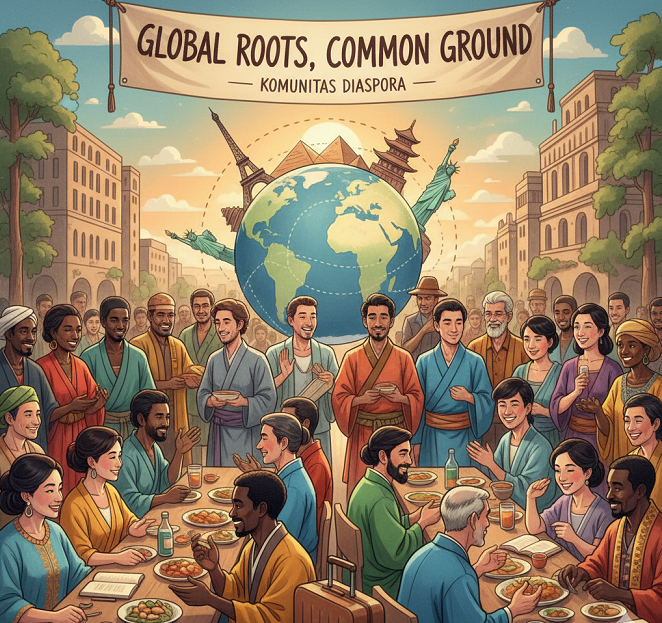Peran Komunitas Diaspora sebagai Jembatan Transnasional dalam Hubungan Tanah Air dan Negara Baru
Komunitas diaspora merupakan fenomena global yang jauh melampaui konsep migrasi biasa, bertindak sebagai aktor unik dalam dinamika hubungan internasional dan pembangunan transnasional. Definisi fungsional diaspora mencakup beberapa karakteristik inti: adanya perpindahan dari tanah air, baik secara sukarela maupun terpaksa; penyebaran ke berbagai wilayah di luar negara asal; pembentukan komunitas yang terorganisir di negara tujuan; serta pemeliharaan identitas etnis dan budaya asal yang kuat.
Aspek fundamental yang membedakan diaspora adalah kesadaran kolektif mereka untuk mempertahankan ikatan emosional yang kuat dengan tanah leluhur, sebuah ikatan yang bersifat multi-generasi. Donald M. Nonini menekankan dimensi temporal bahwa diaspora menggabungkan pengalaman migrasi individu dengan sejarah kolektif penyebaran kelompok, yang terus membentuk kembali komunitas mereka di luar negeri selama setidaknya dua generasi. Komunitas diaspora, dalam konteks ini, adalah “komunitas imajiner” yang secara sadar mengikat anggotanya sebagai bagian dari kelompok etnonasional, terlepas dari waktu dan jarak geografis.
Pengakuan dan pemanfaatan kelompok ini sebagai “sumber daya strategis” oleh negara asal menandai perbedaan penting dalam pendekatan kebijakan. Jika diaspora hanya dipandang sebagai migran biasa, kebijakan cenderung terbatas pada aspek ketenagakerjaan dan perlindungan konsuler. Namun, dengan melihat mereka sebagai aktor transnasional dan aset bangsa, ruang lingkup pelibatan meluas secara signifikan, mencakup transfer pengetahuan, soft power, dan fasilitasi investasi. Pendekatan proaktif ini menjadi justifikasi penting bagi pembentukan lembaga-lembaga khusus diaspora di tingkat negara asal.
Komunitas diaspora juga berperan dalam produksi budaya yang bersifat hibriditas dan liminalitas. Ini berarti mereka tidak hanya melestarikan budaya etnis asal, tetapi juga berinteraksi dan beradaptasi dengan identitas etnik dan pribumi di negara tujuan. Interaksi ini menghasilkan nilai dan kebiasaan yang lebih baru, di mana elemen liminalitas—kemampuan beroperasi di batas dua budaya—justru menjadi kekuatan. Diaspora yang hibrid, terutama generasi kedua dan seterusnya, memiliki kemampuan unik untuk menerjemahkan dan mengadaptasi nilai-nilai negara asal ke dalam konteks budaya negara baru, menghasilkan penerimaan yang lebih kuat di tingkat masyarakat akar rumput (grassroots) negara tujuan.
Diaspora sebagai Aktor Non-Negara dan Sumber Daya Strategis
Dalam disiplin Hubungan Internasional, diaspora diakui sebagai aktor non-negara (non-state actor) yang otonom, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan antara negara asal dan negara penerima, melampaui jalur diplomatik formal. Kehadiran jaringan transnasional yang diintensifkan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi digital memungkinkan diaspora untuk tetap terhubung dengan tanah air dan berjejaring satu sama lain dengan lebih mudah.
Jaringan ini memungkinkan diaspora untuk bertindak sebagai broker dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan investasi hingga kolaborasi akademik dan sains. Pada dasarnya, kemampuan diaspora untuk memobilisasi sumber daya—finansial, manusia, dan sosial—melalui ikatan emosionalnya dengan negara asal, menjadikannya komponen krusial dalam diplomasi modern dan strategi pembangunan nasional.
Diaspora sebagai Jembatan Budaya dan Aktor Diplomasi Publik (Soft Power)
Diplomasi Publik dan Peningkatan Citra Negara Asal
Salah satu peran paling vital dari komunitas diaspora adalah bertindak sebagai “jembatan budaya” yang memfasilitasi pemahaman dan hubungan antara negara asal dan negara tujuan. Diaspora secara efektif menjadi “duta budaya” tak resmi, memperkenalkan tradisi, nilai-nilai, dan bahasa negara asal mereka kepada masyarakat di negara tempat tinggal.
Peran ini diakui secara luas sebagai bagian penting dari diplomasi publik atau soft power suatu negara. Filipina, misalnya, melihat diaspora sebagai bentuk baru dari soft power yang disebut ‘people-powered diplomacy,’ menekankan kekuatan hubungan antar-individu. Melalui jaringan people-to-people yang mereka bangun, diaspora berfungsi sebagai sumber informasi dan perspektif otentik, membantu membentuk opini publik terkait isu-isu yang melibatkan negara asal. Mereka secara efektif memfasilitasi dialog antarbudaya dan memperkuat hubungan internasional, jauh lebih cepat dan luwes daripada mekanisme diplomatik formal antar-pemerintah.
Kekuatan diplomasi yang dimotori diaspora terletak pada kemampuannya beroperasi di tingkat grassroots (akar rumput), yang menghasilkan penerimaan budaya yang lebih otentik dan berkelanjutan. Sementara hubungan Government-to-Government (G-to-G) seringkali bersifat kaku dan terikat protokol, jaringan diaspora (People-to-People/P-to-P) memanusiakan hubungan antarnegara. Ketika masyarakat negara tujuan mengonsumsi budaya atau berinteraksi dengan diaspora, hal ini membangun pemahaman dan dukungan yang lebih dalam terhadap kerjasama bilateral.
Studi Kasus: Gastrodiplomasi dan National Branding
Gastrodiplomasi, atau penggunaan kuliner sebagai alat diplomasi budaya, merupakan contoh nyata bagaimana diaspora mengkapitalisasi peran mereka. Komunitas diaspora sering menggunakan kuliner sebagai cara yang efektif untuk national branding dan menarik pariwisata. Misalnya, makanan Indonesia yang diperkenalkan oleh diaspora di luar negeri dapat menjadi alasan kuat bagi wisatawan internasional untuk berkunjung ke Indonesia.
Strategi ini telah diadopsi oleh negara-negara lain. Thailand, misalnya, meluncurkan program ekspansi dan promosi makanan pada tahun 2002 dengan tagline ‘Taste of Thailand,’ didukung pendanaan signifikan dari pemerintah. Demikian pula, negara-negara middle power seperti Taiwan juga menggaungkan wisata budaya mereka melalui makanan. Kasus sukses pengusaha diaspora yang mendistribusikan bumbu Rendang di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional dapat menembus pasar internasional.
Lebih dari sekadar citra, diplomasi budaya ini secara fungsional menciptakan korelasi langsung dengan kerjasama ekonomi. Masyarakat yang familier dan menghargai budaya suatu negara cenderung lebih terbuka untuk menerima produk dan investasi dari negara tersebut. Promosi kuliner, misalnya, secara langsung menciptakan permintaan pasar yang kemudian dapat diisi dan diperkuat oleh jaringan bisnis diaspora (ekspor-impor). Dengan demikian, soft power yang dibangun diaspora bertindak sebagai pendahulu komersial, memuluskan jalan bagi produk domestik.
Pengaruh Kebijakan Luar Negeri dan Lobi Politik
Peran diaspora juga meluas ke ranah politik dan kebijakan luar negeri. Sebagai aktor non-negara, mereka dapat terlibat dalam kegiatan lobi, berusaha memengaruhi kebijakan publik di negara tujuan demi kepentingan negara asal, terutama dalam isu-isu ekonomi.
Diaspora juga memegang peran kunci dalam membentuk opini publik terkait isu-isu sensitif yang melibatkan tanah air merek. Mereka dapat bertindak sebagai mediator dan menyediakan perspektif unik dalam upaya resolusi konflik atau mendukung inisiatif perdamaian di negara asal. Kegiatan mereka dapat memfasilitasi dialog dan pertukaran yang pada akhirnya mendukung hubungan diplomatik formal, yang menunjukkan bagaimana peran non-formal mereka dapat memberikan landasan bagi hubungan Government-to-Government (G-to-G) yang lebih stabil.
Transfer Pengetahuan dan Sirkulasi Sumber Daya Manusia (Human Capital)
Dari Brain Drain ke Brain Circulation
Secara historis, migrasi profesional dan akademisi berkeahlian tinggi seringkali dipandang sebagai brain drain, suatu kerugian permanen bagi negara asal. Namun, paradigma ini telah bergeser secara signifikan menjadi konsep yang lebih positif dan dinamis, seperti knowledge transfer, knowledge exchange, knowledge circulation, dan yang paling utama, brain circulation.
Konsep brain circulation berargumen bahwa arus keluar pengetahuan dan keterampilan yang dihasilkan dari mobilitas orang-orang terampil tidak berarti kerugian bagi negara asal. Sebaliknya, keberadaan diaspora yang sukses di luar negeri dapat meningkatkan citra positif negara asal di mata internasional dan, yang lebih penting, memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi kembali ke tanah air. Diaspora yang kembali ke negara asal atau berkolaborasi secara jarak jauh membawa pengalaman, keahlian, dan jaringan global baru yang sangat berharga.
Model Transfer Pengetahuan Non-Repatriatif
Terdapat dua model utama dalam transfer pengetahuan dari diaspora:
- Repatriasi: Model tradisional di mana migran yang memiliki keahlian tinggi kembali secara fisik ke negara asalnya.
- Jaringan Transnasional (Non-Repatriatif): Model yang tidak mensyaratkan kembalinya diaspora secara fisik. Sebaliknya, pengetahuan dan keterampilan mereka disalurkan kembali melalui jaringan sosial dan profesional, menghubungkan mereka ke negara asal melalui kolaborasi jarak jauh.
Model non-repatriatif ini menghilangkan biaya dan hambatan relokasi fisik. Diaspora profesional yang sukses di luar negeri seringkali memiliki standar gaji dan kondisi kerja yang sulit dipenuhi di negara asal, menjadikan repatriasi penuh tidak praktis. Dengan model knowledge circulation virtual, negara asal dapat memanfaatkan keahlian mereka secara on-demand melalui platform digital, kolaborasi riset, dan program pertukaran. Model ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa, memberikan akses ke jaringan pengetahuan dan keterampilan global.
Kontribusi dalam Penelitian, Inovasi, dan Pengembangan Teknologi
Diaspora akademisi dan profesional menjadi katalis penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara asal. Mereka memfasilitasi kolaborasi internasional dalam riset dan inovasi. Lembaga pemerintah, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Indonesia, secara aktif memperbanyak kolaborasi riset dengan diaspora. Tujuannya adalah mempercepat transfer teknologi dan inovasi, terutama dalam bidang-bidang strategis.
Pelibatan diaspora berkeahlian tinggi—mulai dari ilmuwan di laboratorium Eropa hingga profesional di kancah global—adalah komponen krusial dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang suatu negara, seperti Visi Indonesia Emas 2045. Mereka adalah aset bangsa yang membawa perspektif lintas budaya dan praktik terbaik dari pusat-pusat inovasi global (seperti Silicon Valley), menjadikannya saluran tercepat untuk mengimpor teknologi baru, etos kerja modern, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kontribusi Ekonomi: Pilar Keuangan dan Investasi Transnasional
Kontribusi ekonomi diaspora bersifat multiaspek, mencakup aliran modal stabil (remitansi) hingga investasi produktif jangka panjang (Foreign Direct Investment atau FDI).
Remitansi: Arus Modal Stabil bagi Negara Berkembang
Remitansi, atau pengiriman uang oleh pekerja migran, merupakan salah satu aliran modal terpenting bagi negara berkembang. Secara global, aliran remitansi diperkirakan mencapai USD 857 miliar pada tahun 2023. Angka ini diproyeksikan terus meningkat, mencapai USD 905 miliar pada tahun 2024.
Signifikansi makro dari remitansi sangat besar, terutama bagi negara berpendapatan rendah dan menengah, yang menerima sekitar USD 131 miliar pada tahun 2023. Remitansi ini secara konsisten lebih besar daripada Foreign Direct Investment (FDI), dan bahkan telah meningkat sebesar 57% dalam dekade terakhir, kontras dengan penurunan FDI sebesar 41% dalam periode yang sama. Remitansi memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan mendukung daya beli domestik. Banyak negara telah mengembangkan kebijakan untuk mempermudah pengiriman remitansi dengan biaya rendah, mengakui potensi ekonomi ini.
Meskipun remitansi memberikan injeksi modal konsumtif yang stabil, remitansi-lah yang menyediakan stabilitas ekonomi mikro bagi rumah tangga dan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama di tengah krisis global. Namun, untuk pembangunan struktural jangka panjang, peran diaspora dalam FDI menjadi lebih strategis.
Diaspora sebagai Katalis Perdagangan dan Investasi
Diaspora berfungsi sebagai jembatan bisnis yang efisien, memfasilitasi hubungan perdagangan antara negara asal dan negara tujuan. Dengan pemahaman mendalam tentang pasar internasional dan jaringan bisnis yang luas, komunitas diaspora memainkan peran penting dalam memajukan perdagangan internasional.
Secara khusus, mereka memperkuat promosi produk UMKM di pasar global [9]. Dukungan ini dapat berupa inisiatif formal (seperti webinar Diaspora Trade Talk Series yang diselenggarakan BNI Tokyo) atau inisiatif informal (membuka jaringan distribusi dan mempromosikan produk, seperti yang terlihat dalam Gastrodiplomasi).
Peran Strategis Diaspora dalam Menarik Foreign Direct Investment (FDI)
Diaspora adalah faktor penting dalam menarik FDI ke negara asal. Mereka membantu meningkatkan FDI dengan membawa investasi langsung dari negara tujuan atau dengan menjadi perantara bagi investor asing non-diaspora. Diaspora berfungsi sebagai penghubung tepercaya yang dapat mengurangi ketidakpastian informasi (informational asymmetries) bagi investor asing.
Daya ungkit FDI yang disalurkan melalui diaspora cenderung lebih besar daripada remitansi, karena investasi produktif ini menghasilkan transfer teknologi, praktik manajemen modern, dan penciptaan lapangan kerja struktural. Oleh karena itu, kebijakan harus bergeser dari sekadar mempermudah aliran remitansi (pendekatan reaktif) menjadi secara aktif memfasilitasi investasi dan jaringan bisnis diaspora (pendekatan proaktif).
Penelitian ekonometri panel menunjukkan bahwa institusi yang dibentuk negara untuk mendukung diaspora memiliki korelasi positif dan signifikan secara statistik terhadap volume aliran FDI. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerangka kelembagaan yang terstruktur. Institusi diaspora yang kuat memberikan saluran komunikasi yang andal, menghilangkan hambatan birokrasi, dan menumbuhkan tingkat kepercayaan yang dibutuhkan oleh investor (baik diaspora maupun non-diaspora) untuk investasi jangka panjang.
Perbandingan antara aliran modal diaspora menunjukkan pentingnya strategi kebijakan terintegrasi:
Table 1: Perbandingan Global Remitansi Diaspora vs. Foreign Direct Investment (FDI)
| Indikator Ekonomi | Data Global (Tahun Referensi) | Dampak Kualitatif (Fokus Utama) | Sumber Utama Data |
| Total Remitansi Global | USD 857 miliar (2023) | Stabilitas, Pengentasan Kemiskinan, Konsumsi Mikro. Arus lebih stabil. | World Bank |
| Perkiraan Remitansi ke Negara Berpendapatan Rendah-Menengah | USD 131 miliar (2023) | Dukungan langsung terhadap daya beli domestik. | World Bank |
| Perbandingan dengan FDI Global | Remitansi 57% lebih tinggi dari FDI dalam dekade terakhir (FDI menurun 41%) | Transfer Teknologi, Penciptaan Lapangan Kerja, Akses Pasar Global. Arus lebih volatil dan sensitif terhadap risiko. | World Bank/GMDAC |
Tantangan dan Hambatan Sistemik dalam Pelibatan Diaspora
Meskipun potensi diaspora sangat besar, pelibatan mereka menghadapi tantangan sistemik, terutama terkait aspek hukum, politik, dan kelembagaan.
Permasalahan Hukum dan Status Kewarganegaraan
Status kewarganegaraan merupakan hambatan fundamental yang membatasi diaspora berkeahlian tinggi untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan negara asal. Bagi mereka yang telah berganti kewarganegaraan, terdapat kesulitan besar, termasuk ketidakmampuan memiliki properti dan tanah, hambatan karier dalam proyek-proyek strategis atau berteknologi tinggi yang sensitif, serta kendala bepergian ke negara asal dengan leluasa.
Status hukum yang tidak pasti dapat membatasi diaspora berkeahlian tinggi untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis negara asal karena adanya persyaratan keamanan dan kepemilikan yang ketat. Jika talenta kunci tidak dapat berpartisipasi secara legal karena status kewarganegaraan, negara asal kehilangan akses ke keahlian yang sangat dibutuhkan, padahal mereka telah sukses membawa harum nama bangsa.
Tuntutan untuk diterapkannya kewarganegaraan ganda tidak terbatas (dual nationality) semakin meningkat sebagai respons terhadap realitas globalisasi, namun ini masih menjadi pertimbangan hukum dan politik yang kompleks bagi Pemerintah dan DPR RI.
Hambatan Iklim Investasi dan Birokrasi di Negara Asal
Investor diaspora, meskipun memiliki ikatan emosional (yang berfungsi sebagai insentif investasi awal), pada akhirnya mencari kondisi yang sama dengan investor asing non-diaspora: stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi yang efektif.
Hambatan yang dihadapi diaspora investor bersifat identik dengan hambatan investasi asing lainnya. Ketidakpastian politik dan keamanan, seperti yang disebabkan oleh kerusuhan atau gejolak sosial-politik, dapat membatalkan kepercayaan investor dengan cepat, meningkatkan persepsi risiko, dan menghambat aliran modal masuk. Oleh karena itu, insentif khusus diaspora akan sia-sia jika dasar-dasar iklim usaha yang stabil (seperti reformasi perizinan, penguatan BKPM, dan kepastian hukum) tidak dipenuhi secara menyeluruh.
Meskipun pemerintah telah menggodok Peraturan Pemerintah untuk memfasilitasi diaspora (terutama eks-WNI), masalah navigasi sistem hukum dan birokrasi yang berbelit di negara asal masih menjadi tantangan yang memerlukan percepatan reformasi.
Marjinalisasi dan Konflik Sosial di Negara Tuan Rumah
Diaspora di negara tuan rumah sering menghadapi marjinalisasi dan tantangan sosial. Dalam beberapa kasus, perbedaan nilai dan praktik budaya dapat menimbulkan ketegangan atau konflik dengan masyarakat setempat. Bagi pekerja migran, marjinalisasi ekonomi, intimidasi, diskriminasi, atau bahkan status ilegal merupakan risiko yang rentan terhadap eksploitasi.
Selain itu, masalah komunikasi, seperti kurangnya kemampuan berbahasa asing (misalnya, Bahasa Inggris yang memadai), dapat membatasi peluang karier dan potensi gaji bagi pekerja migran, seperti yang dicontohkan dalam studi kasus di resepsionis. Status sosial dan ekonomi yang rendah juga dapat menimbulkan stereotip negatif dan kecemburuan sosial dari pekerja lokal, meskipun kadang kala diaspora dinilai lebih jujur, setia, dan rajin oleh majikan.
Strategi Pelibatan dan Rekomendasi Kebijakan Strategis
Pelibatan diaspora secara optimal memerlukan strategi kelembagaan, reformasi hukum, dan sinergi antara negara dan sektor swasta.
Pengembangan Kerangka Kelembagaan Diaspora Nasional
Untuk mengoptimalkan potensi diaspora, dukungan pemerintah dalam kerangka kelembagaan yang kuat sangat mendesak. Pembentukan Badan Diaspora Nasional yang terpusat dan terkoordinasi—yang telah diusulkan sejak Kongres Diaspora Indonesia pertama pada tahun 2012 —diperlukan untuk menjadi pijakan strategis.
Pelibatan diaspora harus didasarkan pada komunikasi dua arah dan kemampuan mengombinasikan kepentingan nasional dengan kepentingan pribadi dan sosial diaspora. Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, perlu terus mendorong diaspora untuk aktif membangun negeri.
Model Pelibatan Diaspora Internasional Komparatif
Negara-negara lain telah berhasil merumuskan strategi kelembagaan yang efektif:
Studi Kasus India: Pravasi Bharatiya Divas (PBD)
PBD (Non-Resident Indian Day) diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri India (MEA) bersama federasi industri besar (FICCI, CII). Acara ini bertujuan untuk mengingat kontribusi NRI (Non-Resident Indians) terhadap pembangunan bangsa. Sejak 2015, formatnya diubah menjadi biennial (dua tahunan) dengan konferensi tematik di antara periode tersebut.
Keberhasilan model India terletak pada integrasi negara-industri. Keterlibatan FICCI dan CII memastikan bahwa agenda PBD selaras dengan kebutuhan sektor swasta (perdagangan, investasi), menjadikan pertemuan formal ini berorientasi pada hasil terukur (seperti deal bisnis atau Memorandum of Understanding riset). Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan diaspora harus terintegrasi dengan kepentingan ekonomi nasional, bukan sekadar urusan budaya atau konsuler.
Studi Kasus Filipina: People-Powered Diplomacy
Filipina memandang diaspora tidak hanya penting untuk diplomasi publik, tetapi sebagai bentuk soft power baru yang disebut people-powered diplomacy. Fokus utama Filipina adalah memaksimalkan kontribusi ekonomi dari pekerja migran, dengan pertumbuhan ekonomi yang moderat sebagian besar disumbangkan oleh pengiriman uang (remitansi) dari luar negeri.
Table 2: Perbandingan Model Kelembagaan Diaspora dan Fokus Kebijakan Global
| Negara Asal | Mekanisme Pelibatan Utama | Fokus Utama Kontribusi | Strategi Kelembagaan | Tujuan Strategis |
| India | Pravasi Bharatiya Divas (PBD) | Investasi (FDI), Teknologi, Lobi Politik Global. | Kemenlu (MEA), Federasi Industri (FICCI, CII) | Mengelola jaringan global dan menciptakan platform dialog tingkat tinggi. |
| Filipina | People-Powered Diplomacy | Remitansi, Ketenagakerjaan Migran, Pembangunan Ekonomi. | Fokus perlindungan dan fasilitasi pengiriman uang | Memaksimalkan kontribusi ekonomi dari tenaga kerja migran. |
| Indonesia (Eksisting) | Kongres Diaspora (2012), Inisiatif Kolaborasi Riset (BRIN) | Knowledge Transfer, Promosi Budaya (Gastrodiplomasi) | Fragmentasi (Kemenlu, BRIN, usulan Badan) | Peningkatan Soft Power dan mengejar Brain Circulation. |
Reformasi Regulasi: Memfasilitasi Investasi dan Status Hukum
Reformasi regulasi adalah kunci untuk membuka potensi penuh diaspora. Mengingat sensitivitas politik terkait Dwi-Kewarganegaraan tidak terbatas, langkah taktis pertama yang penting adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang memfasilitasi eks-WNI. Regulasi ini harus dirancang untuk menghilangkan hambatan non-politik yang krusial, seperti hak properti, izin kerja, dan kemampuan memiliki saham mayoritas dalam investasi strategis. Ini merupakan cara cepat untuk memberikan hak-hak non-politik kepada diaspora tanpa harus melalui perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan yang memakan waktu lama.
Selain itu, program kolaborasi riset antar-universitas, seminar internasional, dan beasiswa khusus bagi peneliti diaspora harus diintensifkan untuk mengakselerasi knowledge transfer non-repatriatif.
Kesimpulan
Komunitas diaspora berfungsi sebagai jembatan transnasional yang tidak tergantikan, memainkan peran ganda sebagai duta budaya (melalui soft power dan diplomasi publik) dan agen ekonomi (melalui remitansi, perdagangan, dan FDI) antara tanah air dan negara baru. Kemampuan mereka untuk memadukan identitas (hibriditas) memungkinkan terciptanya hubungan yang otentik dan kuat di tingkat people-to-people, yang menjadi fondasi bagi kerjasama formal G-to-G.
Namun, potensi strategis ini terhambat oleh masalah struktural, terutama status kewarganegaraan dan iklim usaha yang tidak stabil. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pelibatan diaspora sangat bergantung pada komitmen negara asal untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang terstruktur dan reformasi regulasi yang memberikan kepastian hukum dan politik.
Untuk mengoptimalkan peran diaspora dalam memengaruhi kebijakan luar negeri, transfer pengetahuan, dan ekonomi, direkomendasikan lima langkah strategis:
- Institusionalisasi Terpusat: Segera membentuk atau menguatkan Badan Diaspora Nasional yang terpusat untuk memastikan koordinasi lintas sektor (Kemenlu, kementerian ekonomi, dan lembaga riset seperti BRIN).
- Reformasi Hukum Taktis: Mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah untuk memberikan hak-hak investasi, properti, dan karier strategis kepada diaspora yang telah berganti kewarganegaraan, sebagai langkah awal sebelum membahas Dwi-Kewarganegaraan tidak terbatas.
- Penguatan Iklim Investasi Dasar: Membenahi masalah fundamental kepastian hukum, reformasi birokrasi (seperti OSS dan penguatan BKPM), dan menjaga stabilitas politik, karena insentif emosional diaspora tidak akan bertahan di tengah tingginya risiko usaha.
- Akselerasi Knowledge Circulation: Mengintensifkan program kolaborasi riset jarak jauh dan beasiswa diaspora, berfokus pada model non-repatriatif untuk mengimpor teknologi dan keahlian global tanpa hambatan relokasi.
- Soft Power yang Terintegrasi Ekonomi: Menyediakan dukungan pendanaan dan jaringan formal untuk People-Powered Diplomacy, khususnya melalui Gastrodiplomasi dan promosi UMKM, yang berfungsi sebagai pendahulu untuk meningkatkan ekspor dan perdagangan bilateral.