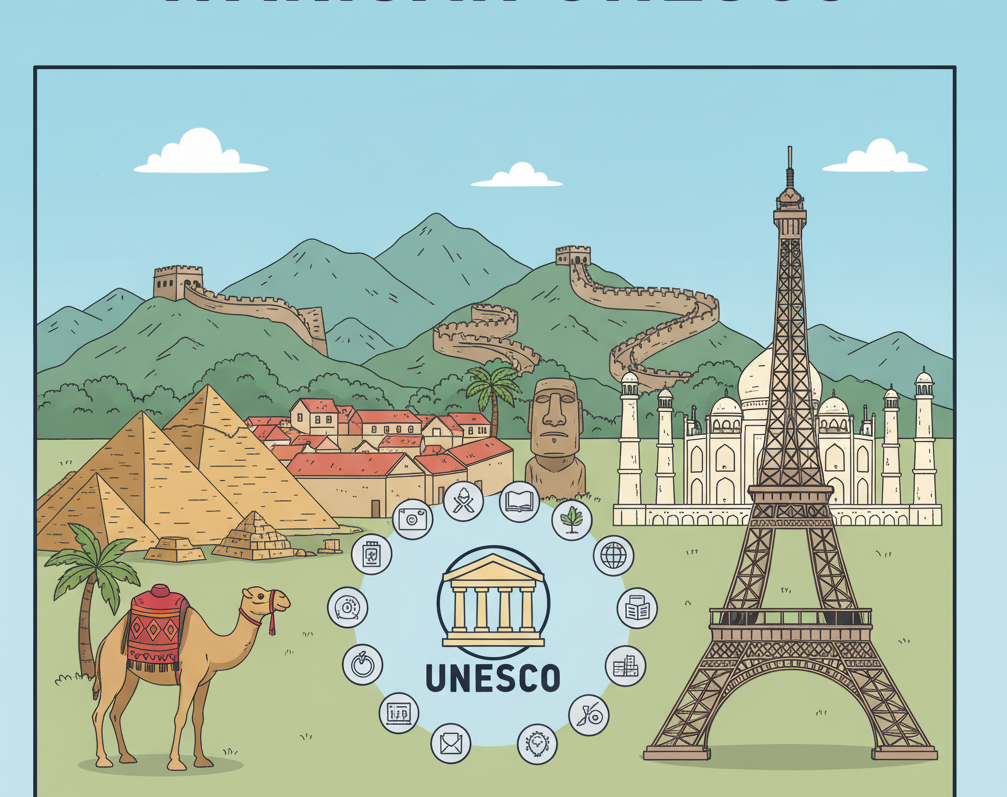Analisis Kritis Warisan Dunia UNESCO
Pendahuluan dan Kerangka Konvensional Warisan Dunia
Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, yang diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 16 November 1972, merupakan landasan hukum internasional yang signifikan dalam upaya konservasi global. Instrumen ini bertujuan untuk melindungi warisan yang nilainya melampaui batas-batas kepentingan nasional, menjadikannya warisan bersama bagi seluruh umat manusia.
Program Warisan Dunia berakar pada mandat UNESCO yang lebih luas: mempromosikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama di bidang pendidikan, sains, dan budaya. Keberhasilan pelestarian situs seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan program-program ilmiah UNESCO, seperti Program Manusia dan Biosfer, yang meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Selain itu, inisiatif seperti Komisi Oseanografi Antarpemerintah dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan berkontribusi pada kerangka kerja holistik yang mendukung pelestarian aset budaya dan alam.
Republik Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi ini pada 6 Juni 1989. Ratifikasi ini menjadikan situs-situs bersejarah dan alami di Indonesia memenuhi syarat untuk diinskripsi dalam Daftar Warisan Dunia, menunjukkan komitmen negara terhadap upaya konservasi internasional.
Implikasi Strategis Pasal 3 Konvensi
Pasal 3 Konvensi menetapkan bahwa setiap Negara Pihak bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mendelineasi properti Warisan Dunia yang terletak di wilayahnya. Walaupun Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value – OUV) bersifat global, tanggung jawab de facto untuk perlindungan dan pengelolaan berada di tangan kedaulatan nasional. Kerangka ini menciptakan ketegangan strategis yang signifikan. Ketika sebuah situs menghadapi ancaman serius, seperti kerusakan akibat pariwisata berlebihan (overtourism) atau proyek pembangunan domestik yang tidak terkelola, peran UNESCO terbatas pada pemberian peringatan atau memasukkan situs tersebut ke dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya. Institusi internasional ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan, menekankan bahwa komitmen konservasi yang efektif harus berakar kuat dalam kebijakan dan investasi nasional.
Definisi Nilai Warisan (Budaya, Alam, Campuran)
Status Warisan Dunia diberikan berdasarkan konsep OUV, yang didefinisikan sebagai nilai yang sangat istimewa sehingga melampaui kepentingan nasional dan memiliki signifikansi bagi generasi sekarang dan mendatang dari seluruh umat manusia.
Warisan yang dilindungi dibagi menjadi dua kategori utama, dengan kategori Campuran (Budaya dan Alam) mencakup keduanya:
- Warisan Budaya: Meliputi monumen (seperti karya arsitektur, patung monumental, atau prasasti), kelompok bangunan, dan situs (termasuk situs arkeologi).
- Warisan Alam: Terdiri dari formasi fisik dan biologis, formasi geologi dan fisiografi (termasuk habitat flora dan fauna yang terancam), dan situs alami yang memiliki manfaat ilmiah, konservasi, atau estetika yang luar biasa.
Kriteria Penilaian Nilai Universal Luar Biasa (OUV) dan Kondisi Pelestarian
Eksplorasi Mendalam 10 Kriteria OUV
Untuk mencapai status Warisan Dunia, sebuah properti harus memenuhi setidaknya satu dari sepuluh kriteria OUV, yang diuraikan dalam paragraf 77 Pedoman Operasional. Kriteria (i) hingga (vi) berlaku untuk warisan budaya, sedangkan kriteria (vii) hingga (x) berlaku untuk warisan alam.
Kriteria Budaya (i–vi)
Kriteria ini menilai pencapaian artistik, pertukaran nilai-nilai manusia, dan bukti peradaban yang unik. Kriteria (i), yang menuntut representasi “mahakarya jenius kreatif manusia,” adalah salah satu yang paling ketat, sering diterapkan pada ikon tunggal seperti Candi Borobudur.
Salah satu kriteria budaya yang memiliki implikasi signifikan terhadap keberlanjutan dan risiko lingkungan adalah Kriteria (v). Kriteria ini menilai apakah properti merupakan contoh luar biasa dari pemukiman tradisional, penggunaan lahan, atau laut yang representatif dari suatu budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan, terutama ketika properti tersebut menjadi rentan di bawah dampak perubahan yang tidak dapat diubah. Dengan secara eksplisit menyebut kerentanan terhadap perubahan, kriteria (v) memaksa Negara Pihak untuk mengajukan rencana manajemen yang berfokus pada mitigasi risiko proaktif, menghadapi ancaman seperti krisis iklim atau pembangunan yang merusak.
Kriteria (vi) mencakup situs yang secara langsung terkait dengan peristiwa, tradisi hidup, ide, kepercayaan, atau karya seni dan sastra yang memiliki signifikansi universal, seperti inskripsi Sumbu Kosmologis Yogyakarta.
Kriteria Alam (vii–x)
Kriteria ini berfokus pada keindahan alam, proses geologi, dan keanekaragaman hayati. Kriteria (ix) mencari contoh luar biasa yang mewakili proses ekologi dan biologis yang signifikan dalam evolusi ekosistem. Sementara Kriteria (x) secara spesifik menargetkan habitat alami paling penting dan signifikan untuk konservasi keanekaragaman hayati in-situ. Kriteria (x) ini adalah dasar penetapan OUV untuk situs-situs alam penting di Indonesia, seperti Taman Nasional Komodo dan Ujung Kulon.
Kondisi Integritas, Keaslian, dan Manajemen
Selain memenuhi kriteria OUV, properti yang dinominasikan harus memenuhi kondisi pelestarian, yaitu integritas dan keaslian.
- Integritas (Integrity): Properti, terutama yang alam dan bentang budaya, harus utuh dan mencakup semua elemen penting yang diperlukan untuk mengekspresikan OUV-nya. Pedoman Operasional mendefinisikan integritas dalam paragraf 88.
- Keaslian (Authenticity): Kondisi ini lebih relevan untuk properti budaya, yang mensyaratkan kredibilitas atribut warisan sebagai sumber informasi yang jujur dan dapat dipercaya.
Kombinasi antara warisan budaya dan alam menghasilkan Bentang Budaya (Cultural Landscapes), yang diakui sebagai properti budaya yang mewakili “karya gabungan alam dan manusia”. Indonesia telah berhasil menginskripsi Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana (2012). Keberhasilan inskripsi ini di bawah kriteria seperti (v) menekankan pentingnya sistem filosofis dan interaksi berkelanjutan dengan lingkungan. Namun, sebuah properti yang diakui karena interaksi berkelanjutannya, seperti Subak, dapat terancam kehilangan OUV jika mengalami pembangunan atau perubahan yang merusak integritas lingkungannya. Hal ini menggarisbawahi bahwa kelangsungan hidup tradisi dan sistem pengelolaanlah yang menjadi syarat utama penetapan OUV, dan Negara Pihak harus menjamin kelangsungan hidupnya.
Mekanisme Operasional dan Siklus Nominasi
Fungsi Strategis Daftar Tentatif (Tentative List – TL)
Daftar Tentatif (TL) adalah langkah awal yang wajib dalam proses nominasi Warisan Dunia. Properti yang akan dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia tidak dapat dipertimbangkan oleh Komite Warisan Dunia kecuali properti tersebut telah tercantum dalam TL Negara Pihak.
Negara Pihak diwajibkan menyerahkan TL setidaknya satu tahun sebelum mengajukan nominasi formal. Jeda waktu ini sangat penting untuk melakukan studi awal, mengidentifikasi potensi OUV, menilai kebutuhan pengelolaan dan perlindungan, serta memungkinkan masukan dari para ahli warisan alam dan budaya.
Penyusunan TL dianjurkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, pemerintah, LSM, dan perwakilan ICOMOS/IUCN, untuk memastikan legitimasi dan komitmen konservasi jangka panjang di tingkat lokal. Negara Pihak juga didorong untuk meninjau dan memperbarui TL mereka setidaknya setiap sepuluh tahun.
Proses Nominasi Formal dan Evaluasi Teknis
Proses evaluasi teknis nominasi dilakukan selama periode satu tahun yang ketat oleh dua Badan Penasihat utama: Dewan Internasional untuk Monumen dan Situs (ICOMOS) untuk warisan budaya, dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) untuk warisan alam. Proses ini dirancang sebagai filter kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa hanya situs dengan nilai universal luar biasa yang benar-benar diakui.
Langkah-langkah evaluasi teknis meliputi:
- Tinjauan Eksternal: Dokumen nominasi didistribusikan kepada jaringan ahli independen, termasuk anggota komisi spesialis IUCN (seperti WCPA).
- Misi Lapangan: Ahli IUCN, seringkali bersama ICOMOS untuk situs Campuran atau Bentang Budaya, melakukan evaluasi langsung di lokasi yang dinominasikan (biasanya antara Juli dan Oktober). Mereka bertemu dan berdiskusi dengan otoritas nasional, lokal, LSM, dan komunitas setempat.
- Analisis Komparatif Global: Untuk kriteria alam (ix) dan (x), IUCN meminta Pusat Pemantauan Konservasi Dunia Lingkungan PBB (UNEP-WCMC) untuk melakukan analisis komparatif global. Tujuannya adalah memastikan properti tersebut benar-benar unik dan luar biasa dibandingkan dengan situs sejenis di seluruh dunia.
- Panel dan Tulisan Akhir: Panel Warisan Dunia IUCN/ICOMOS meninjau dokumen nominasi, tulisan misi lapangan, dan hasil analisis komparatif. Mereka menghasilkan tulisan evaluasi akhir (diserahkan kepada Pusat Warisan Dunia pada April/Mei tahun berikutnya) yang berisi rekomendasi formal kepada Komite Warisan Dunia.
Pengambilan Keputusan oleh Komite Warisan Dunia
Berdasarkan tulisan teknis dan rekomendasi dari ICOMOS dan IUCN, Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee – WHC) membuat keputusan akhir mengenai inskripsi properti. Meskipun rekomendasi Badan Penasihat sangat didasarkan pada sains dan konservasi, keputusan akhir oleh Komite Warisan Dunia, sebagai badan antarpemerintah, dapat dipengaruhi oleh pertimbangan diplomatik atau politik.
Sebagai contoh, pada tahun 2023, Komite menolak rekomendasi teknis untuk memasukkan kota Venesia ke dalam Daftar Warisan Dunia yang Terancam. Konflik antara penilaian teknis dan keputusan politik menunjukkan dinamika kompleks dalam pengelolaan Daftar Warisan Dunia. Jika proses teknis diabaikan, atau jika keterlibatan komunitas diabaikan selama tahap TL, hal ini berpotensi melemahkan kredibilitas program dan menyebabkan konflik manajemen pasca-inskripsi, seperti yang terlihat dalam kasus pembangunan infrastruktur di beberapa situs warisan alam.
Dampak Strategis dan Pendanaan Konservasi
Manfaat Status Warisan Dunia: Pengakuan dan Soft Power
Status Warisan Dunia memberikan pengakuan internasional yang sangat besar, berfungsi sebagai alat soft power yang efektif dan meningkatkan nation branding suatu negara di panggung global. Pengakuan ini secara langsung meningkatkan daya tarik situs, menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Peningkatan pariwisata internasional ini dapat memicu peningkatan pendapatan lokal dan nasional, sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai konservasi.
Analisis Pendanaan: World Heritage Fund (WHF)
Pendanaan untuk aktivitas konservasi didukung oleh World Heritage Fund (WHF). Sumber daya WHF terdiri dari kontribusi wajib dan sukarela yang dibayarkan oleh Negara Pihak (negara yang telah meratifikasi Konvensi) berdasarkan Pasal 16.1 dan 16.2, serta kontribusi sukarela dari pemerintah, yayasan, sektor swasta, dan masyarakat umum.
Secara finansial, WHF menyediakan sekitar US$3 juta per tahun untuk mendukung berbagai kegiatan yang diminta oleh Negara Pihak di seluruh dunia. Jumlah ini, ketika dibagi di antara 1.223 properti Warisan Dunia secara global , menunjukkan bahwa nilai finansial utama status WH tidak terletak pada dana langsung yang disediakannya. Sebaliknya, WHF berfungsi sebagai dana bantuan darurat, yang dialokasikan oleh Komite Warisan Dunia dengan prioritas tinggi diberikan kepada situs yang paling terancam.
Status Warisan Dunia lebih tepat dipandang sebagai katalisator, yang memicu pendanaan nasional, investasi asing langsung, dan donasi swasta melalui peningkatan profil global. Namun, kesuksesan branding ini membawa konsekuensi serius. Peningkatan pengunjung yang dihasilkan oleh branding status WH dapat menciptakan kewajiban biaya yang besar jika manajemen pariwisata tidak memadai. Misalnya, kasus overtourism di Borobudur telah menyebabkan kerusakan fisik yang memerlukan investasi mitigasi yang signifikan. Oleh karena itu, keuntungan dari peningkatan pariwisata harus segera dan transparan diinvestasikan kembali dalam strategi konservasi untuk menjamin kelangsungan integritas OUV situs.
Ancaman Konservasi Global dan Pengelolaan Risiko di Abad ke-21
Status Global dan Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya
Per tahun 2024, Daftar Warisan Dunia mencakup 1.223 properti yang tersebar di 168 Negara Pihak. Selain daftar utama, terdapat Daftar Situs Warisan Dunia dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger), yang berfungsi sebagai mekanisme peringatan internasional. Properti dimasukkan ke dalam daftar ini ketika menghadapi ancaman serius, baik aktual maupun potensial, yang membutuhkan tindakan korektif mendesak dan memprioritaskan alokasi Bantuan Internasional dari WHF.
Ancaman yang memaksa sebuah situs masuk ke Daftar Bahaya sangat beragam, mulai dari konflik bersenjata hingga pembangunan yang tidak terkendali. Contoh terbaru adalah Biara St. Hilarion/Tell Umm Amer di Palestina, yang pada tahun 2024 diinskripsi secara bersamaan ke Daftar Warisan Dunia dan Daftar Bahaya, sebuah pengakuan nilai OUV sekaligus kebutuhan perlindungan darurat di tengah konflik.
Ancaman Mayor I: Dampak Perubahan Iklim
Perubahan iklim telah menjadi ancaman eksistensial bagi banyak situs Warisan Dunia, terutama properti alam. Tulisan UNESCO dan IUCN (2022) menyajikan bukti ilmiah yang mengkhawatirkan: diproyeksikan sepertiga gletser yang termasuk dalam situs Warisan Dunia akan hilang pada tahun 2050, terlepas dari upaya mitigasi yang dilakukan. Salah satu contoh ikonik yang terancam adalah gletser terakhir di puncak Gunung Kilimanjaro, Tanzania.
Fenomena ini disebabkan oleh erosi yang semakin cepat sejak tahun 2000, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 58 miliar ton es setiap tahun—setara dengan penggunaan air tahunan di Perancis dan Spanyol. Selain ancaman terhadap bentang alam, pengikisan gletser ini juga berkontribusi pada hampir lima persen kenaikan permukaan laut global.
Temuan bahwa sepertiga gletser tersebut “tidak dapat diselamatkan” memaksa pergeseran paradigma konservasi. Konservasi bergeser dari pelestarian abadi menjadi upaya untuk mendokumentasikan dan mengurangi kerugian, sambil mendesak pengurangan cepat emisi CO2 global sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan dua pertiga gletser yang tersisa.
Ancaman Mayor II: Fenomena Overtourism
Overtourism, didefinisikan sebagai kepadatan atau keramaian turis yang berlebihan yang menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal dan membebani kehidupan sehari-hari , adalah ancaman yang dipicu oleh keberhasilan branding status Warisan Dunia.
Studi kasus di Indonesia, khususnya Candi Borobudur, menyoroti risiko ini. Overtourism di Borobudur telah menyebabkan kerusakan signifikan pada batu candi dan menghasilkan eksternalitas negatif, termasuk degradasi budaya dan ketergantungan ekonomi lokal yang tidak sehat pada sektor pariwisata. Faktor pendorong overtourism meliputi kemajuan teknologi, kurangnya kesadaran publik, dan perilaku turis yang tidak pantas.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi mitigasi komprehensif. Kebijakan yang diusulkan mencakup langkah-langkah ekologis (seperti pembatasan akses, penetapan batas waktu, dan transportasi ramah lingkungan) dan langkah-langkah ekonomi (seperti penyesuaian harga tiket) untuk menyeimbangkan pelestarian dan promosi pariwisata berkelanjutan. Kegagalan dalam mengelola jumlah pengunjung secara kuantitatif akan secara eksponensial mengurangi integritas OUV situs.
Studi Kasus Nasional: Dinamika Warisan Dunia UNESCO di Indonesia
Tinjauan 10 Situs Warisan Dunia Indonesia
Indonesia telah meratifikasi Konvensi pada tahun 1989 dan kini memiliki total 10 properti yang terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia—tertinggi di Asia Tenggara—yang terdiri dari 6 situs Budaya dan 4 situs Alam.
Situs-situs awal yang diinskripsi pada tahun 1991 didominasi oleh situs klasik dan alami, termasuk Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan diversifikasi tematik, dengan inskripsi warisan yang lebih kompleks: Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (2019) dan Sumbu Kosmologis Yogyakarta dan Tengara Bersejarahnya (2023). Selain itu, Indonesia juga aktif dalam Jaringan Geopark Global UNESCO, yang berfokus pada konservasi warisan geologis, seperti Kaldera Toba, Meratus, dan Kebumen.
Daftar Situs Warisan Dunia UNESCO di Indonesia
| Situs | Jenis | Tahun Inskripsi | Provinsi Utama |
| Candi Borobudur | Budaya | 1991 | Jawa Tengah |
| Candi Prambanan | Budaya | 1991 | Yogyakarta/Jawa Tengah |
| Taman Nasional Ujung Kulon | Alam | 1991 | Banten dan Lampung |
| Taman Nasional Komodo | Alam | 1991 | Nusa Tenggara Timur |
| Situs Manusia Purba Sangiran | Budaya | 1996 | Jawa Tengah |
| Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera | Alam | 2004 | Aceh, Jambi, Lampung |
| Lanskap Budaya Subak Bali | Budaya | 2012 | Bali |
| Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto | Budaya | 2019 | Sumatera Barat |
| Sumbu Kosmologis Yogyakarta | Budaya | 2023 | DI Yogyakarta |
| TOTAL | 10 (6 Budaya, 4 Alam) |
Isu Manajemen dan Konservasi Utama (Borobudur dan Komodo)
Status Warisan Dunia Indonesia saat ini diuji oleh tantangan manajemen yang kompleks, khususnya di dua situs ikonik:
Candi Borobudur
Sebagai mahakarya jenius kreatif manusia (kriteria i), Borobudur sangat rentan terhadap overtourism. Kepadatan pengunjung yang tinggi telah menyebabkan masalah signifikan, terutama kerusakan fisik pada batu candi. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan pariwisata berkelanjutan, seperti pembatasan akses dan penyesuaian harga tiket, sebagian karena kesadaran yang terbatas di kalangan wisatawan dan masyarakat lokal tentang dampak negatif overtourism. Tantangan di Borobudur menunjukkan bahwa tanpa investasi yang berani dalam mitigasi dan edukasi, manfaat branding status WH dapat terlampaui oleh biaya degradasi OUV.
Taman Nasional Komodo
Taman Nasional Komodo diakui karena OUV alamnya (kriteria x), yakni sebagai habitat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati in-situ. Namun, situs ini menghadapi ancaman serius dari pembangunan infrastruktur pariwisata yang masif. Rencana pengembangan ini telah memicu peringatan dari UNESCO dan protes dari organisasi lingkungan (seperti WALHI) mengenai dampak lingkungan dan sosial.
Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Komodo telah menyebabkan “transformasi koersif” masyarakat adat Suku Komodo, di mana konservasi dan pariwisata digunakan sebagai pembenaran untuk meminggirkan penduduk lokal. Kasus Komodo berfungsi sebagai ujian bagi komitmen Indonesia terhadap semangat Konvensi 1972, terutama dalam menjaga integritas situs alam yang harus mencakup dimensi sosial-ekologis. Peringatan UNESCO dan konflik sosial mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi harus tunduk pada persyaratan konservasi yang ketat dan keadilan sosial, agar integritas habitat dan OUV tidak hilang.
Kesimpulan
Program Warisan Dunia UNESCO tetap menjadi kerangka kerja internasional yang tak tertandingi untuk perlindungan OUV, berhasil mendaftarkan 1.223 properti di seluruh dunia. Namun, analisis menunjukkan bahwa status bergengsi ini kini menghadapi ancaman eksistensial ganda di Abad ke-21. Di satu sisi, status ini menghasilkan soft power dan pendapatan pariwisata yang besar; di sisi lain, ia memaparkan situs pada dua tekanan terbesar: ancaman perubahan iklim global yang tidak dapat dihindari dan tekanan overtourism lokal yang merusak.
Bagi Indonesia, yang merupakan pemimpin dalam jumlah situs WH di Asia Tenggara, tantangan kritisnya adalah menyeimbangkan manfaat strategis ini dengan kewajiban konservasi jangka panjang. Kasus Borobudur dan Komodo menggarisbawahi perlunya kebijakan yang berani dan transparan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian integritas situs.
Berdasarkan analisis ancaman dan dinamika operasional, direkomendasikan empat area kebijakan utama untuk meningkatkan keberlanjutan Warisan Dunia:
- Prioritas Pengelolaan Risiko Iklim dan Geologis: Negara Pihak harus mengintegrasikan temuan ilmiah mengenai ancaman iklim, seperti tulisan UNESCO/IUCN tentang hilangnya gletser , ke dalam semua rencana manajemen risiko situs. Ini termasuk memprioritaskan situs-situs yang secara eksplisit dinilai rentan (Kriteria v) dan meningkatkan peran aktif dalam diplomasi iklim internasional.
- Mitigasi Overtourism melalui Kontrol Kuantitatif: Negara Pihak harus beralih dari model ekstraksi pariwisata (kuantitas) ke model kualitas, dengan menerapkan strategi mitigasi yang efektif. Ini mencakup penetapan batas kapasitas pengunjung harian yang ketat, implementasi kebijakan harga dinamis, dan diversifikasi penawaran turis untuk mengurangi tekanan pada area inti properti (misalnya, di Borobudur).
- Memperkuat Keadilan Warisan dan Hak Komunitas Lokal: Keterlibatan dan persetujuan komunitas lokal, sebagaimana dianjurkan dalam tahap Daftar Tentatif , harus menjadi prasyarat non-negosiabel dalam proses manajemen situs, terutama di situs alam dan bentang budaya (Komodo). Pembangunan infrastruktur pariwisata harus secara eksplisit mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat.
- Optimalisasi Pendanaan Konservasi Mandiri: Mengingat bahwa World Heritage Fund (US$3 juta per tahun) hanya menyediakan bantuan terbatas dan darurat , Negara Pihak harus mengembangkan mekanisme pendanaan mandiri yang kuat. Pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata (termasuk penyesuaian tarif tiket) harus dihubungkan secara wajib dan transparan dengan program konservasi jangka panjang untuk memastikan bahwa biaya yang ditimbulkan oleh pariwisata dapat segera diatasi.