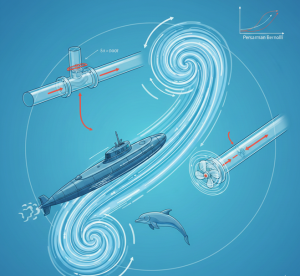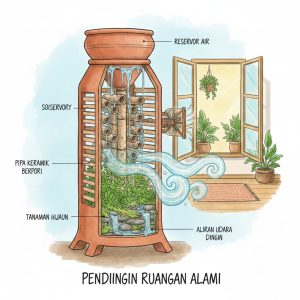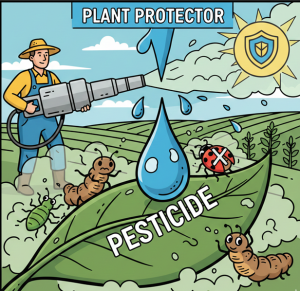Warisan Dunia Tak Benda Kebudayaan Indonesia di UNESCO
Definisi dan Filosofi Konvensi UNESCO 2003
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), atau Intangible Cultural Heritage (ICH), mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan, termasuk instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya terkait, yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan, dalam beberapa kasus, individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Definisi ini berlandaskan pada Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, sebuah instrumen hukum internasional yang berfokus pada keberlanjutan tradisi dan praktik alih-generasi, bukan sekadar objek museum atau artefak statis.
Konvensi 2003 menekankan bahwa nilai utama WBTB terletak pada proses pewarisan dan kemampuan komunitas untuk terus mereproduksi dan menghidupkan tradisi tersebut. UNESCO mengklasifikasikan ICH ke dalam lima Domain utama: (1) Tradisi Lisan dan Ekspresi, (2) Seni Pertunjukan, (3) Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan, (4) Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta, serta (5) Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional. Klasifikasi ini berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami struktur dan fungsi setiap warisan budaya Indonesia.
Perlu ditekankan bahwa Konvensi 2003 secara filosofis menempatkan komunitas lokal sebagai pemilik dan pelestari inti dari warisan tersebut. Oleh karena itu, pengakuan oleh UNESCO (Inskripsi) bukanlah tujuan akhir dari upaya pelestarian, melainkan sebuah sarana untuk mengaktifkan kembali peran komunitas dalam perlindungan (safeguarding). Pengakuan global berfungsi sebagai katalisator untuk menarik perhatian pemerintah, mengamankan dukungan dana, dan memulai program konservasi terstruktur yang sangat penting untuk tradisi yang rentan terhadap kepunahan akibat modernisasi dan perubahan sosial.
Arsitektur Perlindungan Budaya Indonesia: Nasional vs. UNESCO
Indonesia mengelola kekayaan budayanya melalui arsitektur perlindungan berjenjang. Sebelum mengajukan nominasi ke tingkat internasional, suatu karya budaya harus melalui proses inventarisasi dan penetapan di tingkat nasional. Sistem Warisan Budaya Tak Benda Nasional (WBTb Nasional), yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), berfungsi sebagai database dan saringan awal. Daftar WBTb Nasional mencakup ribuan elemen dari seluruh provinsi, mulai dari Rencong, Tato Mentawai, hingga Sie Reuboh, yang menunjukkan komitmen luas untuk pendokumentasian internal.
Penetapan WBTb Nasional merupakan langkah pertama dalam prosedur teknis dan proses pencatatan yang wajib dipenuhi. Hanya elemen yang telah teruji dan terverifikasi secara nasional yang kemudian dapat diusulkan ke UNESCO, memastikan bahwa setiap nominasi internasional memiliki basis data yang kuat dan dukungan komunitas yang jelas. Arsitektur berjenjang ini menunjukkan komitmen strategis Indonesia untuk mendokumentasikan dan memverifikasi kekayaan budayanya secara internal terlebih dahulu. Pendekatan ini memitigasi risiko usulan yang lemah di mata dunia, sekaligus menegaskan kedaulatan dan kepemilikan budaya Indonesia sebelum memasuki arena diplomasi internasional yang kompetitif.
Indonesia dalam Diplomasi ICH: Komitmen dan Strategi
Sebagai Negara Pihak Konvensi 2003, Indonesia menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam diplomasi ICH melalui Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO (KWRI UNESCO). Strategi diplomasi budaya Indonesia memiliki tujuan ganda. Pertama, memastikan pengakuan global untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran, yang pada gilirannya memperkuat kebanggaan lokal dan dukungan perlindungan domestik. Kedua, menggunakan kekayaan budaya yang diakui (seperti Wayang, Batik, dan Keris) sebagai media soft power di kancah internasional.
Upaya pendaftaran WBTB ke ICH UNESCO adalah tindakan nyata pemerintah dalam mengelola warisan yang sarat dengan nilai-nilai budaya sekaligus sebagai upaya diplomasi budaya di tingkat dunia. Pengakuan ini tidak hanya memberikan status prestisius, tetapi juga membuka akses terhadap bantuan teknis dan dana konservasi dari UNESCO, serta mendukung pengembangan produk budaya yang dikategorikan sebagai produk ekonomi kreatif.
Katalog Intangible Cultural Heritage Indonesia di UNESCO (2008–2024)
Indonesia memiliki sejumlah besar elemen budaya tak benda yang telah diinskripsi dalam berbagai daftar UNESCO, terutama Daftar Representatif (RL), Daftar Perlindungan Mendesak (USL), dan Daftar Program Terbaik untuk Perlindungan (BSP).
Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan (Representative List/RL)
Daftar Representatif adalah kumpulan elemen WBTB yang bertujuan untuk memastikan visibilitas warisan budaya tak benda dan mendorong dialog yang menghargai keragaman budaya. Mayoritas elemen Indonesia terdaftar dalam kategori ini.
Periode awal inskripsi (2008–2010) berfokus pada elemen-elemen ikonik yang secara luas diakui sebagai identitas bangsa, seperti Kris, Wayang, Batik, dan Angklung. Data inskripsi dari 2008 hingga 2024 menunjukkan puncak awal inskripsi, diikuti oleh inskripsi strategis yang lebih kompleks (2015-2024). Inskripsi terbaru (2020-2024) menunjukkan pergeseran fokus menuju elemen transnasional (Pantun, Kebaya, Kolintang/Balafon) dan sistem pengetahuan (Jamu), menandakan strategi diplomasi yang lebih luas dan kooperatif.
Table Esensial I: Inskripsi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia di UNESCO (2008–2024)
| Nama Warisan Budaya | Tahun Inskripsi | Jenis Daftar | No. Registrasi | Asal Daerah Kunci | Status |
| Kris Indonesia | 2008 | RL | 00112 | Jawa, Bali | Singular |
| Wayang (Teater Boneka) | 2008 | RL | 00063 | Jawa | Singular |
| Batik Indonesia | 2009 | RL/BSP | 00170 | Jawa (Pekalongan, Yogyakarta) | Singular |
| Angklung Indonesia | 2010 | RL | 00393 | Jawa Barat (Sunda) | Singular |
| Tiga Genre Tari Tradisional Bali | 2015 | RL | 00617 | Bali | Singular |
| Pinisi: Seni Pembuatan Perahu | 2017 | RL | 01197 | Sulawesi Selatan (Suku Konjo) | Singular |
| Tradisi Pencak Silat | 2019 | RL | 01391 | Indonesia (Umum) | Singular |
| Pantun | 2020 | RL | 01613 | Melayu | Transnasional (dengan Malaysia) |
| Gamelan | 2021 | RL | 01607 | Jawa, Bali, Sunda | Singular |
| Budaya Sehat Jamu | 2023 | RL | 01972 | Indonesia (Umum) | Singular |
| Kebaya: Pengetahuan, Keterampilan, Tradisi, dan Praktik | 2024 | RL | 02090 | Asia Tenggara | Transnasional (dengan 4 negara) |
| Praktik Budaya Balafon dan Kolintang | 2024 | RL | 02131 | Sulawesi Utara (Kolintang) | Transnasional (dengan 3 negara Afrika) |
Daftar Warisan Budaya yang Membutuhkan Perlindungan Mendesak (Urgent Safeguarding List/USL)
Daftar Perlindungan Mendesak (USL) adalah kategori yang diperuntukkan bagi warisan budaya yang kelangsungan hidupnya terancam serius oleh faktor-faktor seperti kurangnya pelaku, globalisasi, modernisasi, atau bencana alam. Inskripsi ke dalam daftar ini berfungsi sebagai pengumuman alarm, menuntut intervensi kebijakan yang terfokus.
Indonesia memiliki tiga elemen yang terdaftar di USL:
- Tari Saman (2011): Meskipun merupakan seni pertunjukan yang populer, Tari Saman dari suku Gayo Lues, Aceh, diinskripsi ke USL untuk menyoroti kerentanan transmisinya. Pengakuan ini berhasil mendorong lebih banyak upaya pelatihan dan pengajaran kepada generasi muda di Aceh, memicu kembali pelestarian di tingkat lokal.
- Noken (2012): Tas multifungsi buatan tangan masyarakat Papua diinskripsi karena menghadapi ancaman serius, terutama terkait dengan penurunan jumlah pewaris keterampilan dan tantangan dalam penyediaan bahan baku tradisional.
- Reog Ponorogo (2024): Seni pertunjukan tradisional dari Jawa Timur ini baru-baru ini diinskripsi ke USL. Studi terkait menunjukkan bahwa Reog menghadapi masalah regenerasi pelaku budaya dan kelemahan regulasi lokal yang mendukung pelestariannya.
Daftar Program Terbaik untuk Perlindungan (Best Safeguarding Practices/BSP)
Daftar BSP mengakui program, proyek, atau kegiatan yang paling berhasil mencerminkan prinsip dan tujuan Konvensi ICH.
- Edukasi dan Pelatihan Batik Indonesia (2009): Program ini diakui sebagai model praktik terbaik pelestarian (BSP No. 00318). Program ini, yang dikerjakan bersama Museum Batik Pekalongan, mengintegrasikan pelatihan keterampilan Batik ke dalam kurikulum formal dan non-formal, mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga Politeknik. Pengakuan ini diberikan bersamaan dengan inskripsi Batik di RL, menegaskan bahwa Indonesia menghubungkan pengakuan global dengan kerangka implementasi edukasi yang kuat.
Analisis Kategorisasi dan Domain ICH UNESCO Indonesia
Pemetaan Domain: Holisme Budaya Indonesia
Analisis teknis terhadap kategorisasi UNESCO menunjukkan bahwa budaya Indonesia secara inheren bersifat multidomain, yang berarti sebagian besar elemen WBTB mencakup empat hingga lima domain klasifikasi sekaligus. Fenomena ini merefleksikan pandangan dunia holistik di Indonesia, di mana praktik ritual, seni, kerajinan, dan pengetahuan ekologis terjalin erat dan tidak dapat dipisahkan.
Perbedaan yang mencolok terlihat antara elemen yang relatif “singular” (seperti Kris, yang dominan di domain Traditional Craftsmanship) dengan elemen “holistik” seperti Angklung, Gamelan, atau Pencak Silat, yang mencakup hampir semua domain. Hal ini menggarisbawahi bahwa bagi banyak tradisi Indonesia, sistem pengetahuan spiritual dan praktik sosial adalah bagian integral dari produk fisik atau seni pertunjukan yang dihasilkan.
Table Esensial II: Klasifikasi Domain UNESCO untuk Warisan Budaya Tak Benda Kunci Indonesia
| Nama Warisan Budaya | Oral Traditions & Expressions | Performing Arts | Social Practices, Rituals, & Festive Events | Knowledge & Practices concerning Nature & the Universe | Traditional Craftsmanship |
| Kris Indonesia (2008) | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| Wayang (2008) | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Batik Indonesia (2009) | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
| Angklung Indonesia (2010) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pinisi (2017) | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
| Traditions of Pencak Silat (2019) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Gamelan (2021) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Jamu Wellness Culture (2023) | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| Noken (USL, 2012) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Studi Kasus Kompleksitas Multidomain (Pencak Silat dan Gamelan)
Gamelan (2021) merupakan contoh warisan yang melibatkan semua domain. Gamelan diakui bukan hanya sebagai musik ansambel (Performing Arts), tetapi juga mencakup Traditional Craftsmanship (keterampilan pembuatan instrumen), Knowledge and Practices concerning Nature (pemilihan bahan, proses penyelarasan nada), Oral Traditions (pewarisan musikal non-tertulis), dan Social Practices (peran sentralnya dalam ritual dan perayaan adat).
Demikian pula, Tradisi Pencak Silat (2019) mencakup aspek fisik dan spiritual. Selain sebagai seni bela diri dan pertunjukan (Performing Arts), Pencak Silat melibatkan Oral Traditions (seperti sapaan, pantun, dan filosofi). Praktisi diajarkan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam (Knowledge of Nature), serta mempraktikkan keterampilan tradisional untuk membuat senjata dan kostum (Traditional Craftsmanship).
Dimensi Filosofis dan Signifikansi Kultural Warisan Utama
Warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO tidak didasarkan pada nilai estetika semata, tetapi pada kekayaan simbol dan kedalaman filosofis yang diwariskan lintas generasi.
Keris: Simbol Objektivitas Nilai dan Kesempurnaan Hidup
Keris Indonesia, diinskripsi pada 2008, diposisikan sebagai perwujudan obyektivitas ide, nilai, norma, dan etika bermasyarakat. Filosofi yang terkandung dalam Keris mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, etika, dan estetika. Secara mendalam, Keris menyimbolkan tentang penyatuan diri dengan Sang Pencipta (manunggaling kawula Gusti) dan pencapaian kesempurnaan hidup. Pengakuan Keris dalam domain Traditional Craftsmanship secara implisit mengakui bahwa proses pembuatannya oleh seorang Empu adalah proses spiritual dan filosofis, bukan sekadar teknik metalurgi.
Wayang: Media Kontemplasi dan Refleksi Moral
Wayang, khususnya Wayang Kulit, adalah seni pertunjukan yang berfungsi sebagai sarana hiburan yang mendidik. Peran sentral dipegang oleh dalang yang bertindak sebagai penyampai pesan moral dan etika. Setiap tokoh dalam lakon mengajarkan nilai moral tertentu, mendorong penonton pada kontemplasi dan refleksi.
Meskipun masih populer, Wayang menghadapi dinamika modernisasi. Untuk bersaing dengan hiburan kontemporer, seringkali lakon dan alur cerita dipersingkat atau diubah, dan iringan musik tradisional diganti dengan lagu-lagu pop. Perubahan ini berisiko menghilangkan beberapa fitur khas Wayang dan pesan moral intinya. Pemerintah telah merespons hal ini dengan mengalokasikan anggaran dan mengajak masyarakat untuk “sering menonton wayang” sebagai bagian dari upaya pelestarian yang berkelanjutan.
Batik: Kekayaan Simbol dan Identitas Kebangsaan
Batik Indonesia diakui UNESCO (2009) berdasarkan kekayaan simbolisme dan makna filosofis kehidupan rakyat Indonesia yang terkandung di dalamnya. Batik diyakini sebagai salah satu dari sepuluh kebudayaan asli bangsa Indonesia, dengan bukti pola ragam hias sederhana sudah ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di luar pengaruh Hinduisme atau Buddhisme seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Pengakuan global ini memiliki dampak transformasional terhadap identitas nasional. Indonesia secara resmi menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Langkah ini berhasil mengintegrasikan warisan budaya ini ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya simbol kebanggaan nasional, digunakan sebagai gaya fesyen formal maupun informal.
Jamu: Pengetahuan Alam dan Kesejahteraan Holistik
Inskripsi Jamu wellness culture pada tahun 2023 menandai pengakuan terhadap sistem pengetahuan tradisional. Jamu dikategorikan dalam domain Knowledge and Practices concerning Nature, Social Practices, Rituals, and Festive Events, dan Traditional Craftsmanship. Jamu, sebagai obat tradisional yang didominasi herbal, mencerminkan pengetahuan ekologis tradisional (TEK) yang mendalam mengenai penggunaan akar, kulit, bunga, dan buah-buahan. Pengakuan Jamu membuka dimensi baru dalam diplomasi budaya Indonesia. Ini memposisikan negara ini sebagai penjaga sistem pengetahuan tradisional yang relevan bagi isu kesehatan dan kesejahteraan global. Hal ini juga memberikan peluang besar untuk pengembangan pariwisata berbasis wellness dan ekonomi kreatif, sejalan dengan dukungan pemerintah terhadap produk budaya nasional.
Strategi Perlindungan dan Praktik Pelestarian (Safeguarding Practices)
Kriteria Nominasi dan Peran Kunci Komunitas Lokal
Proses nominasi WBTB ke UNESCO menuntut pemenuhan kriteria ketat yang mencakup nilai budaya yang meningkatkan jati diri, berfungsi sebagai identitas komunitas, perlu diwariskan turun temurun, dan tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam kerangka Indonesia, peran komunitas lokal sangat sentral. Pemerintah pusat berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan komunitas untuk mempersiapkan data nominasi. Komunitas adalah pendukung yang jelas bagi warisan budaya tersebut, memastikan bahwa tradisi tersebut diadaptasi dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dukungan dan partisipasi aktif dari komunitas lokal adalah prasyarat mutlak yang menentukan kelayakan inskripsi oleh UNESCO.
Analisis Kasus Urgent Safeguarding List (USL): Indikasi Kegagalan Safeguarding Dini
Inskripsi elemen pada USL (Tari Saman, Noken, Reog Ponorogo) bukanlah sebuah stigma, melainkan penanda bahwa strategi perlindungan awal (safeguarding) domestik memerlukan intervensi dan sumber daya tambahan yang mendesak.
Kasus Noken (2012), yang menghadapi ancaman kepunahan keterampilan dan tantangan bahan baku, telah mendorong upaya dokumentasi dan rekontekstualisasi. Universitas Jayapura, misalnya, melakukan penelitian intensif tentang Noken dan berencana membuka ruangan khusus di museum, menunjukkan upaya kolektif untuk menstabilkan pengetahuan dan keterampilan tersebut.
Studi komparatif terhadap Reog Ponorogo (USL 2024) dan Wayang Kulit Yogyakarta menyoroti perlunya integrasi kebijakan. Reog saat ini menghadapi tantangan regenerasi pelaku budaya dan kelemahan dalam regulasi daerah, yang menyebabkan fokus pelestarian cenderung bersifat seremonial dan kurang berkelanjutan. Hal ini berkebalikan dengan pelestarian Wayang Kulit di Yogyakarta, yang berhasil membangun kerangka hukum lokal yang kuat (Perda), partisipasi masyarakat yang aktif, dan dukungan kelembagaan yang memberdayakan ekonomi seniman. Data ini menunjukkan bahwa keberlanjutan WBTB yang diakui secara internasional sangat bergantung pada integrasi hukum daerah dan viabilitas ekonomi bagi para pelaku budaya
Analisis Praktik Terbaik (Best Safeguarding Practices/BSP)
Indonesia memiliki contoh praktik pelestarian yang diakui global, yang dapat dijadikan model:
- Edukasi Batik di Pekalongan (BSP 2009): Program ini mewakili model sukses di mana pelestarian Traditional Craftsmanship diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal, memastikan kontinuitas keterampilan kepada generasi muda.
- Pelestarian Angklung: Setelah diakui UNESCO (2010), upaya pelestarian Angklung semakin intensif, didukung oleh pemerintah pusat dan daerah (Pemda Jawa Barat). Kegiatan ini mencakup fasilitasi pertunjukan, pendirian Rumah Angklung di Bandung, dan pelaksanaan Pasanggiri (perlombaan) yang secara aktif mendorong praktik Performing Arts dan Social Practices Angklung.
Dampak Globalisasi dan Tantangan Regenerasi
Dampak Positif Pengakuan UNESCO
Pengakuan UNESCO membawa dampak positif yang luas. Secara internal, pengakuan global secara signifikan membangkitkan kesadaran dan kebanggaan komunitas lokal, memotivasi mereka untuk terus menjadi penjaga warisan budaya. Secara eksternal, pengakuan tersebut memfasilitasi diplomasi budaya dan potensi dukungan pendanaan. Indonesia menerima dukungan teknis dan dana konservasi dari UNESCO, serta dukungan pengembangan produk budaya yang dikategorikan sebagai produk ekonomi kreatif. Dampak positif ini terutama dirasakan di sektor hilir (produksi dan penjualan).
Konflik Keberlanjutan: Sektor Hulu vs. Hilir
Meskipun pengakuan UNESCO memicu permintaan global dan pertumbuhan sektor hilir (komersialisasi), terdapat risiko serius berupa ketidakseimbangan dengan sektor hulu. Sektor hulu meliputi penyediaan bahan baku, keberlanjutan sumber daya alam, dan, yang paling krusial, regenerasi keterampilan para pembuat tradisional.
Apabila perhatian hanya terfokus pada penjualan dan promosi (hilir), sementara penyediaan bahan baku (misalnya, bambu berkualitas untuk Angklung atau bahan pewarna alami untuk Batik) dan pelatihan Traditional Craftsmanship diabaikan, maka keberlanjutan inti tradisi akan terancam. Analisis ini menunjukkan perlunya investasi kebijakan yang seimbang antara permintaan pasar global dan jaminan pasokan keterampilan serta bahan baku tradisional.
Isu Hak Klaim dan Pengakuan Transnasional
Pengakuan UNESCO memberikan perlindungan hukum internasional bagi warisan budaya, yang sangat penting mengingat risiko klaim oleh negara lain yang dapat merugikan Indonesia. Pengakuan ini mengikat Indonesia pada kewajiban pelestarian.
Secara diplomatis, Indonesia kini mengambil langkah maju melalui strategi nominasi transnasional. Nominasi bersama untuk Pantun (dengan Malaysia) dan Kebaya (dengan empat negara ASEAN) merupakan langkah strategis yang mengubah potensi konflik klaim menjadi kolaborasi regional. Pendekatan ini mengakui adanya warisan bersama di Asia Tenggara sambil secara tegas menegaskan peran dan tanggung jawab Indonesia dalam pelestariannya.
Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Masa Depan
Penguatan Tata Kelola ICH Nasional (WBTb Nasional)
Sistem WBTb Nasional harus berfungsi secara maksimal sebagai basis data dan mekanisme penyaringan yang ketat. Semua elemen budaya yang tercatat harus memiliki rencana perlindungan yang terperinci dan dapat dilaksanakan secara lokal sebelum dipertimbangkan untuk diajukan ke UNESCO. Ini adalah prasyarat untuk memastikan bahwa setiap elemen yang dinominasikan telah melalui fase pelestarian domestik yang memadai.
Implementasi Sistem Jaminan Keberlanjutan (Sustainable Safeguarding Model)
Sistem pelestarian harus mengadopsi model terintegrasi yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Pemerintah Daerah wajib didorong untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi ICH pasca-inskripsi, mencontoh keberhasilan Yogyakarta. Hal ini sangat mendesak terutama bagi elemen-elemen yang terdaftar di USL, seperti Reog Ponorogo, yang membutuhkan kerangka hukum lokal yang kuat untuk menopang regenerasi. Keberlanjutan harus didukung oleh pemberdayaan ekonomi seniman dan pelaku budaya, memastikan bahwa pelestarian didorong oleh viabilitas mata pencaharian, bukan semata-mata oleh inisiatif seremonial.
Strategi Diplomasi Budaya Berbasis Pengetahuan
Indonesia harus memaksimalkan inskripsi elemen yang melibatkan sistem pengetahuan (seperti Jamu dan Pinisi) dan elemen transnasional (Kebaya) untuk memperluas jangkauan diplomasi ke sektor-sektor non-seni, seperti kesehatan, maritim, dan pariwisata. Selain itu, peningkatan kajian akademis dan penelitian (seperti studi intensif terhadap Noken) harus menjadi komponen wajib dalam Rencana Tindak Lanjut pasca-inskripsi. Ini memastikan bahwa diplomasi budaya didukung oleh manajemen pengetahuan yang kredibel dan berkelanjutan.
Kesimpulan Akhir
Indonesia telah berhasil memetakan kekayaan budaya tak bendanya di kancah global. Pencapaian ini menegaskan status Indonesia sebagai pusat peradaban dengan warisan yang mendalam dan multidomain. Tantangan sesungguhnya yang dihadapi Indonesia saat ini berada pada tahap pasca-inskripsi: bagaimana memastikan pendanaan, regenerasi, dan relevansi budaya di tengah arus globalisasi tanpa mengorbankan nilai filosofis intinya. Keberhasilan pelestarian ditentukan oleh sinergi yang kuat antara kebijakan nasional, regulasi lokal, dan komitmen komunitas sebagai penjaga warisan yang berdaulat dan berkelanjutan.