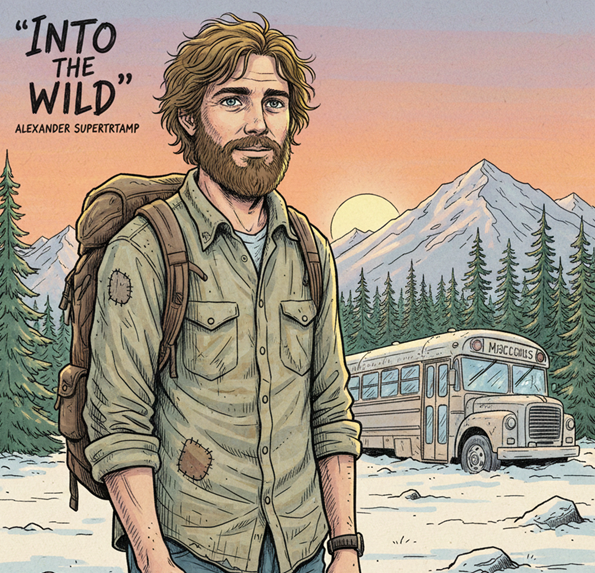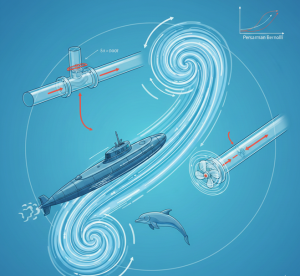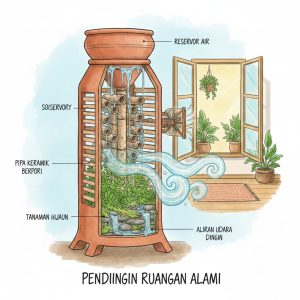Seni Kontemporer sebagai Vektor Dekolonisasi: Analisis Kritis Globalisasi Suara Global South dan Perombakan Narasi Historis
Epistemologi Seni Lintas Budaya dan Globalisasi Suara
Seni kontemporer dalam konteks globalisasi berfungsi sebagai arena yang kompleks, bukan sekadar ruang dialog harmonis. Peran ganda ini menempatkan seni sebagai jembatan yang memungkinkan pertukaran budaya, sekaligus sebagai medan kontestasi yang menantang struktur kekuasaan yang mengakar. Memahami peran seni dalam konteks lintas budaya menuntut pengakuan terhadap dinamika kekuatan yang terlibat.
Mendefinisikan Jembatan Lintas Budaya: Antara Dialog dan Kontestasi
Seni modern memberikan seniman sebuah platform fundamental untuk dialog dan pertukaran lintas budaya, memungkinkan mereka menciptakan karya yang mencerminkan identitas hibrida dengan merangkul beragam pengaruh kultural. Ekspresi ini tidak hanya terbatas pada perayaan keragaman. Secara paralel, seni bertindak sebagai forum untuk komentar dan kritik budaya. Melalui medium seperti satir, seni visual, atau pertunjukan, seniman dapat mengangkat isu-isu sosial dan politik dalam budaya mereka, mempertanyakan identitas budaya yang berlaku, dan mendorong pemikiran kritis dengan mengkritik konvensi atau struktur kekuasaan.
Namun, upaya untuk membangun “jembatan” ini dihadapkan pada tantangan filosofis yang signifikan. Perdebatan mengenai estetika lintas budaya, yang disarankan oleh Stephen Davies, hanya mungkin terjadi jika ada sikap saling menghormati. Sebuah kritisisme penting muncul dari Samer Akkach, yang memperingatkan bahwa “rangkulan inklusif” (inclusivistic embrace) terhadap perbedaan justru berisiko melenyapkan keunikan yang ingin dipahami.
Risiko ini menggarisbawahi bahwa konsep “jembatan” bukanlah jalan tol yang mulus menuju penggabungan horizon (fusion of horizons), melainkan sebuah arena negosiasi yang tegang. Jika karya seni dari Global South hanya diakui atau dinilai melalui kerangka estetika Barat—misalnya, melalui lensa Teori Institusional Dickie, seperti yang dipertanyakan oleh John Powell —maka proses inklusi ini dapat berubah menjadi kooptasi. Oleh karena itu, globalisasi suara yang sukses harus secara aktif mempertahankan lokalitas dan spesifisitas budaya. Ini membutuhkan keterlibatan yang mendalam dari pembawa pengetahuan lokal (local knowledge carriers) dan medium itu sendiri, sebagaimana ditekankan oleh Julie Nagam.
Kerangka Teoretis Dekolonisasi: Sejak dalam Pikiran hingga Praktik Kuratorial
Proyek dekolonisasi dalam seni modern jauh melampaui kritik politik superfisial; ia menuntut restrukturisasi epistemologis. Hal ini selaras dengan pemikiran Gayatri Chakravorty Spivak, yang menegaskan bahwa dekolonisasi harus dimulai “sejak dalam pikiran”. Langkah ini berarti menantang dan membongkar asumsi dasar mengenai estetika, nilai, dan historiografi yang telah diinternalisasi sejak era kolonial.
Dalam ranah praktik budaya, upaya dekolonisasi terlihat nyata melalui penegasan kedaulatan identitas. Dalam konteks sastra, hal ini diwujudkan melalui penggunaan bahasa lokal sebagai identitas (misalnya Bahasa Indonesia) dan pelestarian kekayaan adat istiadat yang sempat terhapus karena terbawa impian atau gagasan modern yang dianggap canggih. Penegasan kembali warisan budaya ini—seperti yang dicontohkan dalam kekayaan adat istiadat—adalah tindakan perlawanan terhadap homogenisasi yang dipaksakan oleh modernitas yang berpusat di Barat.
Secara institusional, kerangka dekolonisasi ini telah diintegrasikan ke dalam praktik kuratorial kontemporer. Kurator kini bergerak untuk menantang narasi konvensional dengan membangun narasi besar yang menghubungkan arsip sejarah dengan praktik seni kontemporer, seperti yang diwujudkan dalam pameran bertajuk (De)colonising Gesture. Keberhasilan praktik dekolonial ini terletak pada sifatnya yang interdisipliner, menghubungkan kritik filosofis (Spivak) dengan tindakan kuratorial dan sastra (Pramoedya Ananta Toer). Jika dekolonisasi hanya berfokus pada kritik politik, tanpa mengatasi kerangka kognitif dan estetik yang mendominasi, ia tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, kurator kini dituntut untuk menjadi sejarawan kritis yang menggunakan transhistoricity dan translocality sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan visi kuratorial dan menulis ulang sejarah seni dunia.
Peningkatan Visibilitas Global South: Pergeseran Geopolitik Institusional
Peningkatan visibilitas seniman dari Global South (Asia, Afrika, Amerika Latin) di panggung seni global tidak hanya merupakan fenomena tren, melainkan hasil dari pergeseran geopolitik dan tekanan kritik pascakolonial terhadap institusi-institusi seni mapan. Perubahan ini tercermin dalam strategi akuisisi museum, krisis restitusi, dan munculnya platform pameran tandingan.
Akuisisi Museum Barat dan Paradoks Inklusi
Institusi seni raksasa di Global North, seperti Tate Modern, telah merespons tuntutan representasi dengan secara eksplisit memperluas jangkauan koleksinya di luar Eropa dan Amerika Utara, fokus pada wilayah Timur Tengah, Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Upaya ini telah dilembagakan melalui pembentukan komite akuisisi spesialis, yang paling menonjol adalah Latin American Acquisitions Committee (LAAC) yang didirikan pada tahun 2002. Komite ini secara proaktif berupaya menggeser narasi sejarah seni museum yang selama ini berpusat pada kanon Euro-AS
Pergeseran ini menghasilkan data kuantitatif yang jelas. Sejak tahun 2000, Tate telah mengakuisisi 623 karya dari kawasan di luar Eropa dan Amerika Utara. Angka ini mencakup 317 karya dari Amerika Latin dan 35 karya dari kawasan Asia Pasifik, serta karya dari Timur Tengah dan Afrika. Meskipun statistik ini menunjukkan komitmen kelembagaan untuk inklusi, terdapat ketidakseimbangan yang signifikan. Jumlah akuisisi dari Amerika Latin jauh melampaui kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat dekolonisasi, proses inklusi ini asimetris. Perubahan sering kali didorong oleh jaringan filantropis yang terfokus (didukung oleh anggota komite LAAC), yang berarti bahwa inklusi dalam kanon Barat masih sangat bergantung pada sumber daya finansial dan struktur kekuasaan di Global North.
Krisis Restitusi dan Dekolonisasi Kepemilikan
Isu kepemilikan artefak kolonial telah mentransformasi perdebatan dekolonisasi dari wacana naratif menjadi masalah kedaulatan fisik dan politik. Desakan global telah memaksa Eropa untuk menghadapi warisan penjarahan budaya mereka.9 Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka mengakui perlunya mengembalikan warisan budaya Afrika, menekankan “kejahatan tak terelakkan dari penjajahan Eropa”.10
Tulisan yang ditugaskan oleh Macron, yang dibuat oleh ekonom Senegal Felwine Sarr dan ahli sejarah seni Prancis Benedicte Savoy, menjadi katalisator bagi perjuangan negara-negara Afrika untuk mendapatkan kembali benda-benda yang diambil selama zaman kolonial. Sebagai respons, Macron berjanji untuk mengembalikan 26 benda bersejarah ke Benin, menjadikannya pemimpin Eropa pertama yang melakukan pengembalian tersebut. Skala masalahnya sangat besar; diperkirakan sekitar 90% warisan budaya Afrika saat ini tersimpan di Eropa, dengan Museum Quai Branly Paris sendiri menyimpan sekitar 70 ribu objek dari Afrika.
Tuntutan restitusi ini secara efektif membongkar klaim universalis dari museum Barat, seperti dalih British Museum yang menyatakan diri sebagai “museum dunia, untuk dunia” dan institusi yang hanya meminjamkan benda bersejarah. Jika mayoritas warisan budaya suatu benua disimpan di museum penjarah, klaim universalitas tersebut runtuh. Secara kausal, tindakan restitusi ini bertepatan dengan pendirian Museum Peradaban Warga Kulit Hitam (Museum of Black Civilizations) di Senegal. Kehadiran museum baru yang didanai China ini menegaskan bahwa negara-negara Global South siap dan mampu menjadi kurator bagi narasi dan sejarah mereka sendiri, menjadikan pengembalian artefak sebagai penegasan kedaulatan politik atas aset budaya.
Platform Global South sebagai Tandingan (The Counter-Hegemonic Biennale)
Di sisi Global South, infrastruktur seni mulai aktif membangun kerangka kerja tandingan untuk menantang dominasi poros transatlantik. Biennale Jogja (BJ), khususnya melalui Equator Series, mengadopsi kerangka kerja geopolitik yang unik, bermitra dengan negara atau wilayah di zona khatulistiwa (dimulai dengan India pada 2011). Premis ini secara eksplisit bertujuan untuk “menulis ulang sejarah seni dunia” (rewriting of world art history). BJ menggunakan konsep Translocality dan Transhistoricity untuk mengembangkan visi kuratorial, menjadikannya model dekolonisasi praktik kelembagaan.
Strategi kuratorial ini penting karena menempatkan Global South, yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan biennale di Global Nort, sebagai produsen aktif teori dan narasi, bukan lagi sekadar subjek pasif. Penegasan narasi baru ini juga terlihat dalam ajang internasional, seperti London Design Biennale 2025, yang melalui paviliun ‘Wura’ memposisikan Global South bukan sebagai renungan (afterthought) melainkan sebagai kekuatan pendorong inspirasi dan transformasi global.
Selain inisiatif kelembagaan, pasar seni juga menunjukkan pergeseran fokus regional. Pameran seni kontemporer Afrika, seperti AKAA (Africa Contemporary Art Fair) di Paris, dan peningkatan visibilitas maestro Asia Tenggara (seperti Affandi, yang telah menggelar pameran tunggal di Eropa dan AS sejak 1950-an), menunjukkan bahwa pusat-pusat kekuatan seni sedang didesentralisasi. Meskipun pengakuan ini seringkali masih melalui platform Barat, munculnya platform regional yang independen menantang monopoli kuratorial tradisional.
Tabel 1 merangkum pergeseran struktural ini, menyoroti bagaimana berbagai institusi merespons tuntutan dekolonisasi secara nyata.
Table 1. Pergeseran Fokus Geopolitik dalam Institusi Seni Global dan Regional
| Institusi/Inisiatif | Fokus Geografis Kontemporer | Strategi Kuratorial/Aksi | Implikasi Dekolonisasi |
| Tate Modern Acquisitions | Latin America, Asia Pacific, Middle East, Africa | Pembentukan komite akuisisi spesialis (LAAC) untuk menggeser narasi historis. | Integrasi representasi non-Barat ke dalam koleksi permanen; namun, terdapat risiko tokenisme/asimetri dalam akuisisi. |
| Biennale Jogja | Negara/Wilayah Ekuatorial (Equator Series) | Kerangka kerja geopolitik untuk kolaborasi dan dialog translocal; tujuan: rewriting world art history. | Menetapkan pusat gravitasi seni tandingan; mentransformasi Global South dari subjek menjadi produsen teori dan kuratorial. |
| Museum Eropa (Prancis) | Artefak Afrika (Benin) | Restitusi koleksi yang dijarah sebagai pengakuan kejahatan kolonial dan tanggapan terhadap tulisan Sarr/Savoy | Membongkar kepemilikan kolonial; memberdayakan infrastruktur budaya lokal (Museum of Black Civilizations, Senegal). |
| London Design Biennale | Global South (‘Wura’) | Memposisikan Global South sebagai kekuatan pendorong inspirasi dan transformasi, berfokus pada representasi yang setara | Menantang anggapan Global South sebagai afterthought (bahan renungan) atau sekadar objek eksotisme. |
Dekolonisasi Narasi: Studi Kasus Kritik Historiografi dan Estetika
Perjuangan dekolonisasi narasi dalam seni modern sering kali diwujudkan melalui kritik langsung terhadap representasi visual dan struktur historiografi yang diwariskan dari masa kolonial. Seniman dari Global South secara sadar menggunakan praktik mereka untuk membalikkan citra yang dilekatkan oleh kekuasaan dominan.
Melawan Estetika Kolonial: Kritik Mooi Indie
Di Indonesia, perlawanan terhadap kolonialisme tidak hanya bersifat politik, tetapi juga estetis, yang paling jelas terlihat dalam kontestasi terhadap gaya Mooi Indie (Hindie Indah). Mooi Indie adalah gaya lukisan yang dipromosikan selama era kolonial Belanda, yang mengutamakan citra pemandangan ideal dan eksotisasi, yang berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan kolonial dengan menampilkan Hindia Belanda sebagai wilayah yang damai dan tenteram.
Pelukis seperti Affandi tampil sebagai oposisi terdepan terhadap narasi visual ini. Affandi menggunakan gaya lukisan yang ekspresif, dengan goresan yang timbul, melengkung, dan tebal, mengutamakan perasaan dan pengalaman pribadinya. Pilihan estetika ini merupakan penolakan formal terhadap representasi yang menenangkan dan eksotis yang disajikan oleh kolonialisme. Ini adalah tindakan dekolonisasi visual pada tingkat goresan, merebut kembali hak untuk merepresentasikan realitas dengan cara yang jujur dan subyektif, bertentangan dengan kebutuhan propaganda kolonial.
Kritik Historiografi Hegemonik Melalui Sastra dan Seni
Dekolonisasi narasi menuntut seni untuk melampaui kritik visual menuju pembongkaran sejarah tertulis. Historiografi yang berpusat pada Eropa secara sistematis memarjinalkan suara dan perspektif lokal. Untuk membalikkan kondisi ini, seniman dan intelektual Global South harus secara eksplisit menggunakan karya mereka sebagai medan tafsir estetis dan ideologis.
Sastra, sebagai bentuk seni, telah lama menjadi instrumen pembongkaran ideologi dominan. Karya-karya Pramoedya Ananta Toer menghadirkan kritik yang tajam terhadap historiografi hegemonik dan sistem politik yang manipulatif.Dengan struktur alur yang berlapis dan bahasa yang kompleks, Pramoedya menggunakan sastra untuk menyusun ulang kesadaran sejarah dari perspektif pribumi yang terpinggirkan.
Dalam praktik kuratorial, peran ini sekarang diemban oleh kurator kontemporer. Kurator mengambil peran sejarawan kritis, meresonansikan arsip sejarah dengan praktik seni kontemporer untuk membangun narasi yang menantang pandangan konvensional dan memulihkan warisan lokal yang terhapus. Apabila tren ini berlanjut, seni kontemporer tidak hanya akan berfungsi sebagai cermin untuk merefleksikan identitas, tetapi sebagai kekuatan aktif yang membentuk dan menata ulang pemahaman kolektif kita tentang masa lalu.
Seni sebagai Instrumen Kritik Struktur Kekuasaan Global
Seni kontemporer dari Global South memiliki peran dualistik: merayakan keragaman sambil secara fundamental mengkritik struktur kekuasaan yang menghasilkan ketidaksetaraan. Dualitas ini menempatkan seni sebagai alat yang transformatif, sebagaimana disimpulkan dalam metafora klasik.
Seni sebagai Kekuatan Pendorong Perubahan Sosial dan Politik
Bertolt Brecht pernah menyatakan bahwa, “Seni bukanlah cermin untuk merefleksikan dunia, tetapi palu yang dengannya kita membentuknya”. Pandangan ini memposisikan seni kritik sebagai instrumen penting dalam menantang status quo dan menjadi katalisator bagi kemajuan sosial. Dalam masyarakat di mana struktur kekuasaan cenderung mengakar dan ketimpangan terus berlanjut, seni kritik berfungsi sebagai alat perlawanan yang esensial terhadap pembungkaman suara-suara kritis.
Kritik struktural ini meluas melampaui isu pascakolonial tradisional hingga mencakup kritik terhadap kapitalisme global kontemporer. Jurnal akademik yang berfokus pada Global South mendefinisikan wilayah ini sebagai “imajiner resisten” dari subjek politik transnasional yang terbentuk akibat pengalaman subordinasi bersama di bawah kapitalisme global. Seniman Global South menggunakan kreasi mereka untuk secara langsung menyoroti isu-isu sosial dan politik di budaya mereka, mempertanyakan konvensi, dan mengkritik praktik-praktik yang melanggengkan ketidaksetaraan
Jangkauan Globalisasi Kritik melalui Platform Digital
Perkembangan teknologi telah secara signifikan mengubah geopolitik distribusi seni. Platform digital memberikan ruang tanpa batas, memungkinkan karya seni menyebar secara luas dan menjangkau audiens global, memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan kritik tetap terlindungi. Demokratisasi akses ini telah mengurangi ketergantungan seniman Global South pada kurator dan galeri Barat sebagai gatekeeper utama.
Keterbatasan fisik, seperti yang dialami selama pandemi, telah mempercepat adopsi teknologi. Di Yogyakarta, misalnya, praktik kuratorial dialihkan ke proyek-proyek yang memanfaatkan teknologi internet dan simulasi untuk memproduksi dan menyajikan karya. Munculnya platform pameran seni digital modern lokal, seperti NUSAN di Indonesia , menunjukkan upaya regional untuk secara mandiri mempromosikan narasi seni lintas budaya. Platform digital dan komunitas online (seperti ArtStation atau DeviantArt ) memperkuat kemampuan seni kritik untuk menjangkau audiens global, sekaligus memungkinkan seniman mengontrol narasi dan pasar mereka sendiri, melampaui batas-batas ruang pamer fisik tradisional.
Analisis Kritis Dualitas Seni Kontemporer
Analisis mendalam terhadap seni kontemporer dari Global South mengungkapkan sifatnya yang berkepala dua: ia adalah mediator dan sekaligus kritikus. Seni merayakan keragaman dengan memadukan unsur-unsur lokal dalam konteks global (misalnya, musik kontemporer Indonesia yang menggabungkan koreografi, lirik, dan instrumentasi ritmis budaya lokal). Namun, pada saat yang sama, seni ini menantang kekuatan yang membentuk dunia tersebut, dengan target utama adalah struktur kekuasaan global.
Table 2 menyajikan sintesis dualitas fungsi seni kontemporer, yang berfungsi sebagai jembatan yang memediasi sekaligus palu yang membentuk realitas.
Table 2. Seni Kontemporer: Dualitas Peran (Jembatan Lintas Budaya vs. Kritik Kekuasaan)
| Dimensi Fungsional | Jembatan Lintas Budaya (Perayaan Keragaman) | Kritik Struktur Kekuasaan Global (Dekolonisasi) | Contoh & Referensi Kritis |
| Tujuan Utama | Mendorong dialog, pertukaran, dan ekspresi identitas hibrida. | Membongkar ideologi dominan, menantang status quo, mengkritik praktik kultural dan politik. | |
| Fokus Naratif | Penggunaan elemen lokal/tradisional (koreografi, instrumentasi ritmis) dalam karya kontemporer. | Isu sosial/politik, kritik terhadap historiografi hegemonik, menentang pembungkaman. | |
| Risiko | Runtuhnya perbedaan budaya melalui inclusivistic embrace (Akkach). | Kooptasi kritik oleh pasar seni global (kritik yang ‘dikomersialkan’). | |
| Prinsip Teoretis | Pengalaman lintas budaya transformatif (Fongaro), melibatkan pengetahuan lokal (Nagam). | Seni sebagai ‘Palu’ untuk membentuk realitas (Brecht), dekolonisasi sejak dalam pikiran (Spivak). |
Kesimpulan
Analisis ini menegaskan bahwa seni kontemporer Global South adalah kekuatan yang tak terhindarkan dalam perombakan kanon seni dunia. Keberhasilannya terletak pada kemampuan intrinsiknya untuk beroperasi secara dualistik: ia memediasi pertukaran budaya yang diperkaya, sambil secara eksplisit menantang asal-usul struktural ketidaksetaraan global, yang diwarisi dari kolonialisme dan didorong oleh kapitalisme kontemporer.
Globalisasi suara dari Global South tidak hanya tentang peningkatan volume atau frekuensi pameran, tetapi tentang kualitas narasi yang disampaikan—kedaulatan bahasa, kontrol kuratorial, dan kedaulatan kepemilikan. Keberhasilan inisiatif seperti Biennale Jogja Equator Series dan tuntutan restitusi artefak dari museum Eropa menunjukkan bahwa Global South telah bertransisi dari menjadi objek kajian menjadi subjek yang aktif menentukan historiografi dan nilai estetik global.
Rekomendasi Institusional dan Praktik Kuratorial
Untuk memastikan bahwa momentum dekolonisasi ini berkelanjutan dan transformatif, langkah-langkah strategis berikut harus dipertimbangkan:
- Restrukturisasi Kelembagaan Lintas Batas: Museum dan institusi seni di Global North harus melampaui praktik akuisisi tokenistik. Mereka harus mengadopsi kerangka kuratorial dekolonial yang melibatkan local knowledge carriers dan melanjutkan proses pengembalian artefak yang dijarah secara lebih luas dan sistematis. Ini bukan hanya masalah etika, tetapi reformasi struktural yang diperlukan untuk mendapatkan kembali legitimasi di panggung global.
- Pemberdayaan Platform Global South: Dukungan finansial dan infrastruktur harus diarahkan pada biennale, museum, dan platform regional (seperti Equator Biennales dan platform digital seperti NUSAN ) yang secara independen mendefinisikan kanon dan historiografi mereka sendiri. Institusi-institusi ini harus diberdayakan untuk menjadi pusat produksi teori seni global, yang mampu mendialogkan wacana lokal secara langsung ke tingkat internasional.
- Mempertahankan Kritik Estetika dan Ideologis: Praktik oposisional, seperti yang dilakukan oleh Affandi melawan Mooi Indie dan Pramoedya melawan historiografi hegemonik, harus terus didorong. Seniman harus memanfaatkan ruang digital yang demokratis untuk menyebarkan kritik mereka terhadap struktur kekuasaan, memastikan bahwa seni mempertahankan fungsi utamanya sebagai “palu” perlawanan, bukan sekadar komoditas pasar global.
Trajektori masa depan seni global akan ditentukan oleh negosiasi yang berkelanjutan antara kekuatan finansial Global North dan kedaulatan naratif Global South. Jika tren saat ini (restitusi dan pameran equator independen) terus menguat, sistem seni global akan bergerak menuju model yang benar-benar post-sentris, di mana tidak ada satu hegemon tunggal yang mendominasi nilai estetika atau narasi sejarah, memaksa tinjauan ulang total terhadap historiografi seni yang selama ini berpusat pada Eropa.