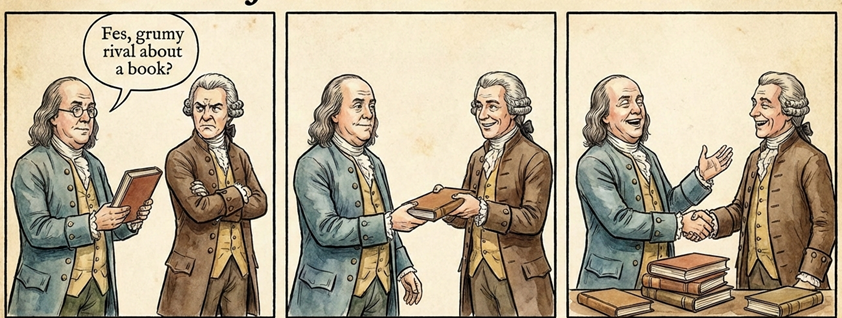Hospitalitas Lintas Batas: Ajaran Kebaikan dalam Menyambut Orang Asing dari Yunani Kuno hingga Krisis Pengungsi Modern
Introduksi: Paradigma Hospitalitas Lintas Batas
Laporan ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif signifikansi abadi dari hospitalitas (keramahan) lintas batas, menganalisis evolusinya dari kewajiban moral yang disakralkan di dunia kuno hingga perumusannya sebagai prinsip hukum internasional pada masa kini. Hospitalitas dalam konteks ini tidak didefinisikan sekadar sebagai tindakan sosial yang sopan, tetapi sebagai kewajiban moral universal (universal moral imperative) yang melampaui batas geografis dan kronologis. Peradaban-peradaban besar di masa lalu, meskipun terpisah oleh jarak dan doktrin, melembagakan perlindungan bagi yang paling rentan—orang asing, pengembara, atau tamu—sebagai bagian integral dari tatanan sosial mereka.
Jangkauan analisis laporan ini mencakup pelacakan konsep ini, mulai dari sanksi ilahi dalam mitologi kuno (seperti Xenia Yunani) hingga manifestasinya dalam kerangka hukum kedaulatan negara modern. Sebelum adanya konsep hak asasi manusia modern, masyarakat telah mengkodifikasi solidaritas transnasional sebagai kodrat sosial purba. Studi ini berargumen bahwa kewajiban kuno untuk melindungi orang asing—seperti yang diwujudkan dalam Xenia Yunani , Atithi Devo Bhava India , dan prinsip Musafir Abrahamik —berfungsi sebagai archetype etis dan fondasi filosofis bagi prinsip perlindungan pengungsi modern, terutama non-refoulement yang terkandung dalam Pasal 33 Konvensi Status Pengungsi 1951. Kegagalan dalam menegakkan prinsip-prinsip kuno ini memiliki konsekuensi yang berat, baik secara sosial maupun ilahi, menunjukkan bahwa perlindungan bukanlah tindakan belas kasihan tetapi kewajiban ketat.
Struktur dan Cakupan Analisis
Laporan ini disusun dalam tujuh bagian tematik untuk memberikan perbandingan yang mendalam antara sumber etika kuno dan penerapannya dalam kerangka hukum internasional. Analisis ini secara khusus menyoroti ketegangan yang melekat antara kedaulatan negara (hak untuk mengontrol perbatasan) dan tuntutan kemanusiaan universal (hak untuk mencari perlindungan). Transformasi kewajiban ini dari hukum sakral menjadi hukum positif menimbulkan pertanyaan krusial mengenai apakah sistem modern mampu mempertahankan kekuatan moral absolut yang dianut oleh peradaban pendahulu.
Xenia: Kewajiban Ilahi dan Ujian Moral di Yunani Kuno
Etos Oikos (Rumah Tangga) dan Xenia (Hospitalitas): Landasan Sosial dan Politik
Xenia adalah salah satu konsep moral dan sosial yang paling fundamental di Yunani Kuno. Istilah ini didefinisikan sebagai hukum atau adat untuk menawarkan perlindungan dan keramahan kepada orang asing. Xenia berfungsi sebagai instrumen diplomasi dan keamanan dalam dunia kuno yang terfragmentasi. Secara etimologis, xenia berasal dari akar Indo-Eropa ghos-ti, yang merujuk pada ‘seseorang yang padanya hukum hospitalitas berlaku’. Menariknya, akar kata ini juga merupakan sumber dari kata-kata yang merujuk pada orang luar, yang dapat disambut atau dikhawatirkan. Ambiguitas ini menunjukkan bahwa tindakan menerima orang asing adalah tindakan yang berisiko, yang hanya dapat diatasi dan diikat oleh hukum sosial yang ketat.
Kewajiban xenia terikat erat dengan oikos, atau rumah tangga. Oikos adalah unit sosial dan politik dasar dalam masyarakat Yunani. Kegagalan untuk menjalankan xenia tidak hanya memicu hukuman ilahi; kegagalan ini secara fundamental mengancam tatanan sosial yang diwakili oleh oikos. Sebagai contoh, kegagalan para Pelamar untuk menunjukkan xenia di rumah Odysseus tidak hanya dipandang sebagai tindakan tidak bermoral, tetapi juga sebagai pelanggaran berat yang mengancam struktur kekuasaan dan kekayaan rumah tangga bangsawan Ithaca , yang pada akhirnya membenarkan kekerasan ekstrem (pembantaian) untuk memulihkan ketertiban.
Zeus Xenios dan Sanksi Keagamaan: Mengapa Melanggar Xenia adalah Kejahatan Ilahi
Di Yunani Kuno, hospitalitas bukanlah masalah diskresi individu; itu adalah kewajiban keagamaan yang ketat. Otoritas tertinggi yang menjamin pelaksanaan xenia adalah Zeus, Sang Raja Petir dan Penguasa Jagat Raya. Zeus secara spesifik dikenal sebagai Zeus Xenios, pelindung tamu dan orang asing.
Kewajiban xenia menjadi absolut karena ia ditempatkan di bawah perlindungan sanksi ilahi Zeus. Melanggar xenia dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap otoritas kosmik Zeus. Kehadiran sanksi keagamaan yang kuat ini adalah mekanisme purba untuk memastikan bahwa individu yang paling rentan menerima perlindungan dari kerabat yang kuat. Analisis menunjukkan bahwa jika oikos adalah fondasi negara kota (polis), maka xenia adalah hukum internasional kuno yang menjaga interaksi antar-polis. Kegagalan xenia pada akhirnya dianggap sebagai kegagalan peradaban itu sendiri, yang memerlukan intervensi ilahi atau pembalasan.
Xenia dalam Epik Homer: Studi Kasus Model Baik dan Buruk
Epik Homer, khususnya The Odyssey, berfungsi sebagai teks didaktik utama yang menunjukkan fungsi dan konsekuensi dari xenia dalam masyarakat. Odyssey dapat dilihat sebagai serangkaian ujian moral berulang tentang hospitalitas, yang menentukan nasib karakter di dalamnya.
Epik tersebut menyajikan model baik dan buruk dari xenia, yang berfungsi sebagai contoh bagi masyarakat untuk meniru atau menghindarinya. Karakter yang gagal menjalankan xenia menerima hukuman setimpal dengan pelanggaran ilahi mereka. Contoh paling mencolok adalah Polyphemus, raksasa Cyclops yang melanggar hukum tamu dan dihukum dengan kebutaan. Demikian pula, para Pelamar di rumah Odysseus yang menyalahgunakan xenia dan merusak oikos dibantai secara brutal. Sebaliknya, karakter yang memberikan xenia dengan baik dihargai, atau setidaknya mendapatkan akhir yang mereka inginkan. Hal ini mengafirmasi bahwa mereka yang mempraktikkan xenia adalah orang yang baik dan saleh.
Hukuman yang keras dan terperinci dalam epik ini menegaskan bahwa perlindungan orang asing bukanlah pilihan amal, melainkan prasyarat untuk stabilitas internal dan ketertiban kosmik.
Etika Universal di Dunia Kuno: Dari Abraham hingga Upanishad
Hospitalitas sebagai kewajiban moral bukanlah monopoli peradaban Yunani-Romawi. Tradisi-tradisi yang terpisah ribuan kilometer dan berbeda doktrin menunjukkan konsistensi filosofis yang luar biasa dalam menempatkan perlindungan orang asing pada tingkat yang tinggi, seringkali disakralkan.
Kewajiban dalam Tradisi Abrahamik: Konsep Musafir dan Tanggung Jawab Komunitas
Agama-agama Abrahamik—Yudaisme, Kristen, dan Islam—adalah serangkaian agama monoteistik yang menghormati tokoh Abraham. Meskipun istilah “Agama Abrahamik” adalah penemuan abad ke-20 untuk memasukkan Islam bersama Yudaisme dan Kristen , ketiga tradisi ini berbagi komitmen mendasar untuk menyediakan bagi yang rentan, termasuk musafir (pengembara atau orang asing dalam perjalanan).
Dalam Islam, musafir memiliki status yang dihormati dan dilindungi secara teologis. Ayat-ayat Al-Qur’an, seperti Surat Al-Baqarah Ayat 177, menekankan kebenaran iman dan ketakwaan mereka yang memberikan harta kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir). Perlindungan ini bukan hanya dorongan moral, tetapi termanifestasi dalam keringanan hukum yang spesifik (rukhsah). Seorang musafir diperbolehkan untuk meringkas sholat, menjama’ sholat, dan membatalkan puasa wajib Ramadhan—dengan kewajiban menggantinya di luar Ramadhan.
Penyediaan keringanan hukum ini menunjukkan pengakuan formal dan struktural oleh agama terhadap kerentanan dan kesulitan yang melekat pada kondisi bergerak. Status musafir menciptakan preseden bahwa kebutuhan praktis orang yang bergerak harus diutamakan, bahkan di atas norma-norma hukum ibadah lokal.
Hospitalitas di Asia Selatan: Prinsip Atithi Devo Bhava
Di Asia Selatan, tradisi Hindu mengkodifikasi hospitalitas melalui prinsip Atithi Devo Bhava, yang secara literal berarti ‘Tamu adalah Tuhan’. Mantra ini berasal dari Taittiriya Upanishad (Shikshavalli I. 11.2).
Prinsip ini menempatkan tamu (Atithi) di antara tokoh-tokoh sentral yang harus dihormati dan disembah—seperti Ibu (Mātṛdevo bhava), Ayah (Pitṛdevo bhava), dan Guru (Ācāryadevo bhava). Dengan menempatkan tamu setara dengan figur ilahi atau dihormati, tradisi ini menetapkan hospitalitas sebagai kewajiban spiritual yang hampir absolut. Dalam konteks modern, prinsip ini telah diintegrasikan ke dalam kebijakan publik; Pemerintah India meluncurkan kampanye Atithi Devo Bhava di bawah tema Incredible India untuk meningkatkan nilai-nilai keramahan di kalangan pemangku kepentingan industri pariwisata, termasuk petugas imigrasi dan polisi. Ini menunjukkan upaya untuk menerjemahkan etika kuno menjadi praktik pelayanan yang bertanggung jawab.
Studi Komparatif: Kesamaan Moral dalam Menerima Orang Asing
Meskipun berbeda dalam konteks budaya, waktu, dan doktrin, Xenia, prinsip Musafir, dan Atithi Devo Bhava memiliki inti moral yang identik. Kewajiban-kewajiban ini memiliki Sumber Kewajiban Transenden (sanksi ilahi atau kitab suci), menuntut Perlindungan Absolut (penyediaan kebutuhan dasar), dan mengakui Pengakuan Kerentanan yang melekat pada status orang asing/pengembara. Kehadiran kewajiban mutlak untuk melindungi orang asing di peradaban yang dipisahkan oleh ribuan kilometer menunjukkan bahwa hospitalitas adalah bagian dari etika kemanusiaan dasar (natural law), yang dikodifikasikan dalam cara yang berbeda untuk menjaga ketertiban moral dan sosial.
Untuk menganalisis kesamaan moral dan spiritual ini, disajikan perbandingan komparatif berikut:
Nilai Inti Hospitalitas Lintas Budaya
| Peradaban/Tradisi | Konsep Kunci | Sumber Doktrin/Ilahi | Sifat Kewajiban | Status ‘Orang Asing’ |
| Yunani Kuno | Xenia (Hospitalitas) | Zeus Xenios | Kewajiban Mutlak (Moral & Agama) | Tamu, Ujian Moral |
| India Kuno/Hindu | Atithi Devo Bhava | Taittiriya Upanishad | Kewajiban Spiritual (Penyembahan) | Dewa yang Berwujud |
| Agama Abrahamik (Islam) | Haqqu al-Musafir | Al-Qur’an (e.g., Al-Baqarah 177) | Kewajiban Fungsional dan Keringanan Hukum | Orang yang Berhak Mendapat Perhatian Khusus |
Jembatan Filosofis: Transformasi Kewajiban Moral menjadi Hukum Universal
Dari Etika Komunitas Kuno ke Etika Kemanusiaan Modern
Abad ke-20 menandai transisi penting: nilai-nilai hospitalitas, yang dulunya terikat pada oikos atau komunitas keagamaan, harus diinstitusionalisasikan ke tingkat global melalui kerangka hukum sekuler. Transformasi konseptual ini memindahkan fokus dari kewajiban tuan rumah kepada hak asasi individu yang dilindungi oleh hukum.
Namun, transformasi ini memunculkan konflik utama: konflik antara kedaulatan negara—hak negara untuk mengontrol perbatasan dan siapa yang masuk—versus konsep hak asasi manusia universal, khususnya hak untuk mencari perlindungan. Jauh berbeda dengan sanksi ilahi kuno (misalnya, hukuman Zeus ), sanksi hukum internasional (seperti Konvensi 1951) selalu memerlukan negosiasi dan kompromi antar-negara berdaulat. Ini berarti bahwa kewajiban tersebut berubah sifatnya: dari mutlak (moral) menjadi terikat atau bersyarat (hukum). Hukum internasional modern berupaya menginstitusionalisasikan kembali “Xenia” di tingkat global, tetapi harus melakukannya dengan mengakui realitas politik kedaulatan.
Prinsip Kemanusiaan sebagai Fondasi Hukum Perlindungan Internasional
Trauma akibat Perang Dunia II dan gelombang pengungsi pascaperang menciptakan kebutuhan mendesak untuk melembagakan kembali etika perlindungan. Hasilnya adalah Konvensi Status Pengungsi 1951, yang menyatukan kembali gagasan perlindungan dengan meletakkannya di bawah payung hukum yang universal. Konvensi ini didasarkan pada asumsi umum bahwa pengungsi merupakan sekelompok orang yang rentan karena situasi di negara asal mereka dan keamanan jiwa mereka terancam. Dengan demikian, hukum internasional modern berupaya mengkodifikasi kewajiban kemanusiaan yang setara dengan Xenia purba: melindungi mereka yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri.
Meskipun tujuannya sama, pergeseran dari “kewajiban yang sakral” menjadi “hak yang dapat digugat” mengubah dinamika kekuasaan. Ini memberikan alat hukum, tetapi juga memungkinkan negosiasi dan penolakan berdasarkan persyaratan ketat yang diatur dalam klausul pengecualian.
Non-Refoulement sebagai Xenia Abad ke-21: Analisis Konvensi Pengungsi 1951
Konvensi Status Pengungsi 1951: Pilar Hukum Perlindungan
Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah fondasi utama perlindungan pengungsi internasional, mewajibkan seluruh negara pihak untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Konvensi ini tidak hanya mengatur hak-hak pengungsi, tetapi juga menetapkan kewajiban pengungsi terhadap negara tuan rumah. Inti dari komitmen hukum ini adalah prinsip bahwa pengungsi tidak boleh dipulangkan ke negara di mana mereka akan menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan.
Analisis Mendalam Prinsip Non-Refoulement (Pasal 33)
Prinsip non-refoulement adalah prinsip utama Konvensi 1951 dan termuat dalam Pasal 33. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara di mana dia akan menghadapi ancaman serius terhadap hidup dan kebebasannya. Dalam esensinya, non-refoulement adalah manifestasi hukum dari etos xenia purba yang menuntut perlindungan mutlak bagi tamu dari bahaya.
Prinsip ini tidak statis. Telah terjadi perkembangan, di mana non-refoulement kini mencakup perlindungan terhadap penyiksaan atau bentuk lain dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, dan perampasan kehidupan yang sewenang-wenang. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai pengungsi dan mendapatkan perlindungan ini, seseorang harus memiliki alasan yang kuat bahwa jiwanya terancam jika kembali ke negara asalnya. Ini menunjukkan bahwa, tidak seperti Xenia yang menuntut kepercayaan mutlak kepada tamu , sistem modern menuntut proses verifikasi yang ketat (alasan yang kuat) untuk memvalidasi klaim perlindungan.
Batasan dan Pengecualian Non-Refoulement
Perbedaan utama antara Xenia moral yang mutlak dan non-refoulement hukum yang terkondisi terletak pada klausul pengecualian. Perlindungan non-refoulement tidak dapat diklaim oleh mereka yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara penerima atau yang telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana serius dan dikategorikan sebagai bahaya bagi masyarakat.
Pengecualian ini mencerminkan kompromi yang tidak terhindarkan antara etika universal dan kepentingan kedaulatan negara. Konvensi 1951 adalah Xenia yang difilter oleh kebutuhan keamanan nasional. Meskipun prinsip ini bertujuan untuk meniru kewajiban moral kuno untuk melindungi yang tidak berdaya, keberadaan pengecualian yang ketat menunjukkan bahwa hukum modern masih gagal mencapai idealisme moral absolut yang dianut oleh peradaban kuno.
Hak-hak Pengungsi: Manifestasi Hospitalitas Minimum yang Dilegalkan
Konvensi 1951 merinci serangkaian hak yang merupakan manifestasi minimum dari hospitalitas yang dilegalkan, memastikan standar perlakuan tertentu. Hak-hak ini mencakup :
- Hak untuk tidak dihukum karena secara ilegal masuk pada wilayah negara pihak (Pasal 31).
- Hak untuk bekerja (Pasal 17).
- Hak atas perumahan (Pasal 21).
- Hak atas pendidikan publik (Pasal 22).
- Hak atas bantuan publik (Pasal 23).
- Hak atas dokumen perjalanan (travel documents) (Pasal 28).
Pengungsi berhak mendapatkan standar yang sama yang didapat oleh warga negara asing di negara penerima, dan dalam banyak kasus, mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara itu sendiri.
Perbandingan langsung antara model kuno dan modern mengungkapkan ketegangan yang mendasarinya:
Transisi dari Kewajiban Moral Kuno ke Mandat Hukum Internasional
| Dimensi | Xenia (Kewajiban Moral Kuno) | Prinsip Non-Refoulement (Mandat Hukum Modern) | Tegangan Kunci |
| Sumber Kewajiban | Ilahi (Zeus), Tradisi Sosial | Konvensi Status Pengungsi 1951 (Pasal 33) | Kedaulatan Ilahi vs. Kedaulatan Negara |
| Objek Perlindungan | Tamu/Pengembara (individu tak dikenal) | Pengungsi (berdasarkan definisi Konvensi, memerlukan alasan yang kuat) | Kepercayaan Mutlak vs. Prosedur Verifikasi |
| Konsekuensi Pelanggaran | Hukuman Ilahi/Sosial, Kehancuran Oikos | Pelanggaran Hukum Internasional, Sanksi Politik/Diplomatik | Moral Mutlak vs. Hukum Terkondisi |
| Ruang Lingkup Hak | Makanan, Tempat Tinggal, Perlindungan | Hak Fungsional (Pekerjaan, Pendidikan, Dokumen Perjalanan) | Kewajiban Tuan Rumah vs. Hak Pengungsi |
Krisis Kemanusiaan Modern: Tantangan dan Kegagalan dalam Menerapkan Hospitalitas
Studi Kasus Global: Respons terhadap Gelombang Pengungsi
Prinsip non-refoulement secara terus-menerus diuji oleh krisis pengungsi modern. Banyak negara, terutama dalam konteks pergerakan populasi skala besar di Mediterania atau Asia Tenggara, menghadapi konflik antara kewajiban hukum internasional dan tekanan domestik.
Isu kedaulatan versus kemanusiaan menjadi sangat akut di negara-negara yang, meskipun mengakui prinsip perlindungan, menolak ratifikasi Konvensi 1951. Sebagai contoh, beberapa negara, termasuk Indonesia, memilih untuk memandang isu pengungsi sebagai masalah hukum dan keamanan nasional daripada kewajiban moral universal yang mengikat secara formal. Mereka yang menentang ratifikasi sering berargumen bahwa kewajiban hukum yang ketat akan membebani negara secara ekonomi dan keamanan, mencerminkan kompromi politik yang bertentangan dengan semangat absolut Xenia.
Kesenjangan Etika-Hukum: Ketika Kepentingan Nasional Mengalahkan Kewajiban Universal
Dalam banyak kasus, negara memilih interpretasi hukum yang sempit terhadap Konvensi 1951. Mereka seringkali menguatkan dan memperluas pengecualian yang diatur dalam Pasal 33 (ancaman keamanan atau kejahatan serius) , dibandingkan dengan menjamin hak-hak pengungsi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum internasional telah menginstitusionalisasikan hak pengungsi, kewajiban perlindungan tersebut tetap rentan terhadap perhitungan politik berbasis kepentingan nasional.
Kesenjangan ini terjadi karena sanksi moral kuno (hukuman ilahi) lebih efektif dalam menegakkan kewajiban mutlak daripada sanksi hukum internasional (sanksi diplomatik atau politik) yang dapat dinegosiasikan. Hukum modern memang menciptakan perlindungan yang lebih adil dan terprosedur, tetapi kehilangan kekuatan moral mutlak yang melekat pada konsep seperti Atithi Devo Bhava (Tamu adalah Tuhan).
Isu Sekuritisasi dan Kriminalisasi Orang Asing: Kontras dengan Etos Xenia
Tren global menunjukkan adanya sekuritisasi dan kriminalisasi pengungsi, di mana mereka sering dibingkai sebagai ancaman keamanan atau beban ekonomi. Praktik ini merupakan kontras tajam dengan etos Xenia atau Atithi Devo Bhava.
Dalam tradisi kuno, tamu atau orang asing dilihat sebagai potensi berkah, atau setidaknya sebagai ujian moral yang harus dilalui dengan sukses. Kegagalan xenia oleh Polyphemus adalah kegagalan moral individu. Sebaliknya, di era modern, penolakan hospitalitas seringkali dilembagakan melalui kebijakan perbatasan yang ketat dan prosedur birokrasi yang lambat. Ini menunjukkan bahwa di era modern, kepercayaan telah digantikan oleh prosedur birokrasi, yang mungkin lebih adil secara prosedural tetapi secara etis terasa kurang murni.
Peran Aktor Non-Negara dan Masyarakat Sipil
Dalam menghadapi kegagalan struktural pemerintah untuk menerapkan hospitalitas universal, aktor non-negara dan masyarakat sipil telah muncul sebagai pembawa obor Xenia modern. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas keagamaan, dan individu seringkali turun tangan untuk mengisi kesenjangan perlindungan, menyediakan makanan, tempat tinggal, dan bantuan yang secara hukum harus disediakan oleh negara. Tindakan ini merupakan cerminan nyata dari kewajiban moral kuno, di mana komunitas (bukan negara) yang pertama kali dipanggil untuk menjalankan tugas hospitalitas.
Simpulan dan Rekomendasi: Menegakkan Kembali Nilai Kebaikan Lintas Batas
Sintesis: Kebutuhan Mendesak untuk Integrasi Etika Kuno ke dalam Kebijakan Modern
Analisis ini menyimpulkan bahwa prinsip non-refoulement (Pasal 33 Konvensi 1951) adalah manifestasi struktural yang diperlukan dari Xenia , tetapi prinsip ini telah kehilangan kekuatan moral mutlaknya karena adanya klausul pengecualian yang luas dan penafsiran yang sempit. Hukum perlindungan pengungsi modern berfungsi sebagai jembatan yang rapuh antara idealisme moral kuno dan realitas kedaulatan negara. Perlindungan yang efektif membutuhkan pengakuan kembali bahwa kewajiban untuk menyambut orang asing melampaui perhitungan biaya-manfaat. Hospitalitas Lintas Batas adalah dasar untuk tatanan global yang stabil dan beradab—sebuah ajaran yang sudah ada sejak Zeus menghukum mereka yang melanggar hukum tamunya.
Rekomendasi Kebijakan: Mendorong Hospitalitas Struktural
Untuk memulihkan kekuatan moral dalam kerangka hukum perlindungan modern, direkomendasikan beberapa langkah kebijakan:
- Penguatan Interpretasi Pasal 33:Negara-negara pihak Konvensi 1951 harus didorong untuk menginterpretasikan pengecualian non-refoulement secara ketat. Prioritas harus diberikan pada perkembangan prinsip perlindungan yang mencakup jaminan terhadap penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Penolakan untuk memulangkan pengungsi tidak boleh didasarkan pada perhitungan ekonomi atau politik, melainkan pada penilaian yang ketat terhadap risiko ancaman jiwa.
- Integrasi Pendidikan Etika:Lembaga imigrasi, petugas perbatasan, dan pemangku kepentingan pariwisata—seperti yang dicontohkan dalam kampanye Atithi Devo Bhava India —harus diwajibkan menjalani pelatihan yang mengintegrasikan nilai-nilai hospitalitas kuno. Pembingkaian orang asing sebagai “tamu” atau “orang yang dilindungi secara ilahi” akan menantang tren sekuritisasi dan mendorong perlindungan yang lebih manusiawi.
- Pengakuan Hak Fungsional Musafir:Negara penerima harus memastikan bahwa hak-hak minimum pengungsi yang diatur dalam Konvensi (bekerja, perumahan, pendidikan) dipenuhi secara proaktif. Pengakuan terhadap hak fungsional ini, serupa dengan keringanan yang diberikan kepada musafir , adalah kunci untuk memastikan integrasi yang bermartabat dan meminimalkan kerentanan pengungsi di negara tuan rumah.
Kesimpulan Akhir
Hospitalitas Lintas Batas adalah sebuah imperatif yang terukir dalam sejarah peradaban manusia. Baik melalui sanksi ilahi Zeus Xenios, kemuliaan Atithi Devo Bhava, maupun keringanan bagi musafir, tugas untuk melindungi orang asing dari bahaya telah lama diakui sebagai pondasi kebenaran moral dan ketertiban sosial. Meskipun Konvensi Pengungsi 1951 menyediakan kerangka hukum yang vital, ia hanya dapat efektif jika negara-negara memilih untuk mengimplementasikannya bukan sekadar sebagai kewajiban hukum yang terpaksa, tetapi sebagai penegasan kembali dari kewajiban moral universal yang telah dijunjung tinggi sejak zaman kuno. Kegagalan untuk melakukannya berarti mengundang kekacauan, yang dalam mitologi Yunani, selalu diikuti oleh murka para dewa.