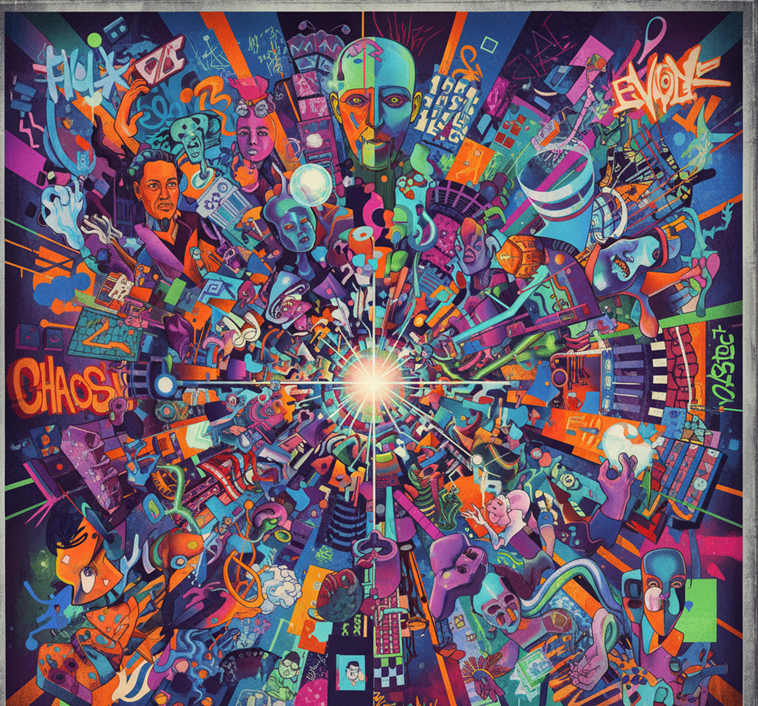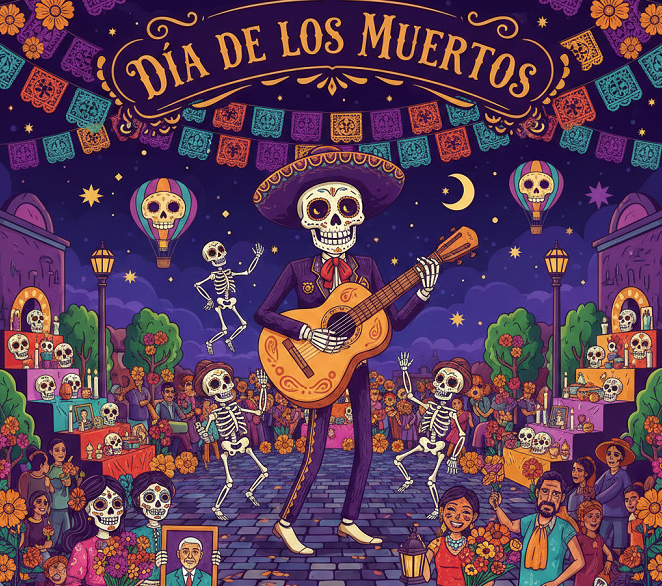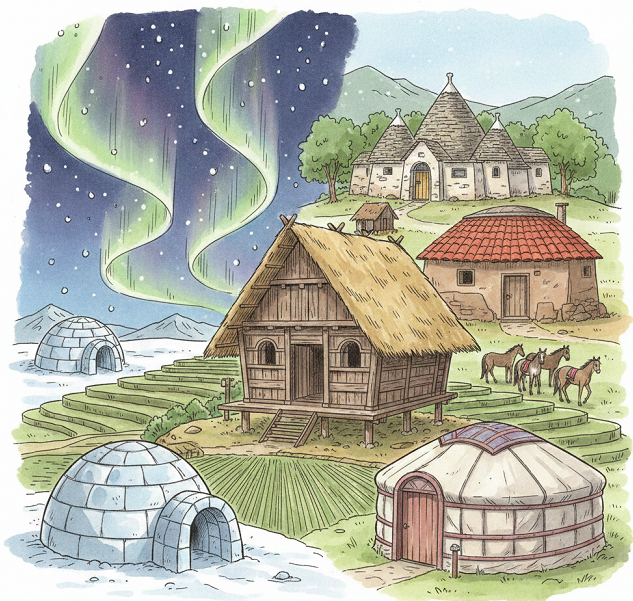Membingkai Seni Kontemporer Global Sebagai Arena Kritik
Sejarah seni rupa global secara sistematis telah disajikan melalui lensa narasi Eurosentris, sebuah perspektif yang secara eksplisit atau implisit mengklaim universalitas aplikasinya, yang konsekuensinya adalah menyingkirkan bentuk-bentuk budaya non-Barat. Dominasi historis ini berakar kuat pada warisan kolonialisme dan imperialisme modern. Praktik kolonialisme, yang bergerak di tiga lapangan (politik, ekonomi, dan kebudayaan), dilakukan melalui penaklukan oleh bangsa yang lebih kuat terhadap bangsa yang lemah.
Hubungan penjajah-terjajah menempatkan wacana superioritas—Barat sebagai subjek (‘kita’ atau ‘we’) yang berhak mengarahkan, sementara Timur adalah ‘yang lain’ (‘the other’ atau ‘they’) yang diatur dan inferior. Selain eksploitasi sumber daya manusia dan alam, imperialisme modern memaksakan model ekonomi dan politik yang terikat pada pasar global, mewariskan psikologi kolektif dan struktur kekuasaan yang ditetapkan pada masa kolonial. Oleh karena itu, Seni Kontemporer Global (SKG) muncul di Abad ke-21 seiring dengan perkembangan teknologi dan kesadaran global, yang secara signifikan meningkatkan akses terhadap citra dan informasi kontekstual dari berbagai seniman di seluruh dunia. Peningkatan akses ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memicu permintaan global untuk revisi narasi historis dan pengakuan kontribusi yang sebelumnya terpinggirkan.
Definisi Konseptual Kunci
Seni Kontemporer Global (Global Contemporary Art)
Seni Kontemporer Global didefinisikan secara akademis sebagai karya seni yang muncul sejak sekitar tahun 1980 Masehi hingga saat ini. SKG berupaya melampaui batas-batas yang telah dikenal, mengangkat pengetahuan dan pengalaman yang melampaui kosakata dan indra tradisional, dan didukung oleh kesadaran global serta kemajuan teknologi. Fenomena seni kontemporer kini dipahami dan dialami dalam konteks global yang kompleks. Sejarawan seni mencatat bahwa SKG mencakup spektrum yang luas, mulai dari Flashbacks to Modernism hingga praktik-praktik site-specific yang kerap dipamerkan di pameran global seperti biennale. Analisis menunjukkan bahwa SKG bukan sekadar kumpulan seni dari berbagai belahan dunia, melainkan sebuah proyek kritis yang secara sadar berupaya memisahkan diri dari silsilah modernisme yang terikat pada ekspresionisme dan abstraksi ala Barat (rute Paris ke New York). Pergeseran ini merupakan pengakuan mendasar bahwa praktik-praktik yang telah lama mendefinisikan seni non-Barat harus diakui, memaksa kanon Barat untuk mengakui sumber-sumber kreatif di luar batas tradisionalnya.
Dekolonisasi dalam Seni (Decolonization in Art)
Dekolonisasi dalam seni merepresentasikan pergeseran fundamental dalam cara karya seni diciptakan, dikurasi, dipamerkan, dan diinterpretasikan. Tujuan utamanya adalah menantang narasi dan institusi yang berpusat di Barat (Western-centric) yang selama ini mendominasi industri seni, dan bekerja untuk mengembalikan serta mengangkat suara dan perspektif yang terpinggirkan dalam dunia seni global. Sejarah kolonial telah meninggalkan warisan berupa praktik akuisisi museum, praktik pameran, dinamika pasar seni, dan struktur kekuasaan institusional yang perlu dikritik dan dirombak. Dekolonisasi menuntut pengakuan akan keterkaitan struktur penindasan yang berbeda—kolonialisme, rasisme, patriarki, dan kapitalisme—yang memengaruhi semua komunitas, terutama yang berada di luar budaya dominan.
Pilar-Pilar Strategi Dekolonisasi Narasi
Dekolonisasi narasi dalam seni rupa bukan hanya sekadar tentang mengubah subjek atau gaya visual karya, melainkan restrukturisasi kekuatan pada tingkat institusional, naratif, dan ekonomi. Untuk memahami kritik terhadap hegemoni pengetahuan, penting untuk menerapkan kerangka teori pasca-kolonial. Diskursus dekolonisasi dalam praktik seni kontemporer sangat dipengaruhi oleh karya-karya Edward Said dan Homi Bhabha, serta diskursus dekolonial yang dipelopori oleh Walter Mignolo, yang semuanya kritis terhadap cara Barat menghegemoni sistem pengetahuan global.
Pendekatan ini menyiratkan bahwa kemajuan dekolonisasi harus diukur bukan hanya dari seberapa sering seniman Global South dipamerkan (visibilitas), tetapi dari seberapa jauh seni Global South berhasil mendobrak dan merevisi historiografi seni global secara struktural. Dengan demikian, tulisan ini akan menelusuri bagaimana tiga pilar strategi dekolonisasi (Institusional, Narasi, dan Ekonomi) beroperasi dalam lanskap seni kontemporer, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:
Pilar Strategi Dekolonisasi dalam Seni Kontemporer
| Pilar Dekolonisasi | Fokus Kritis | Tujuan Utama | Manifestasi Praktis (Contoh) |
| Institusional | Struktur Kekuatan, Kurasi Eurosentris, dan Pengambilan Artefak | Reformasi Kebijakan Koleksi dan Pameran | Repatriasi Artefak, Akuisisi Seni Global South (Tate Modern), Kurasi yang Ditulis Ulang. |
| Narasi | Historiografi Seni Barat yang Mengeliminasi, Stereotip Ras dan Gender | Reclaiming Narratives (Pengembalian Narasi), Identitas, dan Memori Kultural | Karya Wangechi Mutu (Kritik gender/ras), El Anatsui (Kritik materialitas kolonial). |
| Ekonomi/Pasar | Dominasi Borjuis, Sentralisasi Kekuatan Pasar di Barat | Desentralisasi dan Pemberian Kedaulatan Finansial kepada Seniman | Pemanfaatan NFT/Blockchain untuk HAKI dan Penjualan Langsung, Pembentukan Art Fair Regional (Africa Basel). |
Mekanisme Globalisasi Suara Non-Barat: Platform Dan Institusi
Peningkatan visibilitas seniman dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin di panggung seni global difasilitasi oleh berbagai mekanisme kelembagaan. Mekanisme ini dapat dibagi menjadi dua kategori strategis: strategi inklusi vertikal yang dipimpin oleh institusi Barat, dan strategi kedaulatan horizontal yang diinisiasi oleh Global South sendiri.
Peran Ekshibisi Skala Besar: Biennale dan Art Fair
Biennale Global (Venice): Inklusi dengan Tensi
Venice Biennale atau La Biennale di Venezia, yang didirikan pada tahun 1895 untuk mempromosikan kegiatan seni modern tanpa membedakan negara, telah menjadi panggung prestise yang ikonik. Dalam beberapa tahun terakhir, institusi sentral ini telah menunjukkan upaya yang nyata untuk meningkatkan representasi yang sebelumnya terpinggirkan. Misalnya, Venice Biennale ke-59 dikurasi oleh Cecilia Alemani dan didominasi oleh seniman perempuan, sehingga turun dalam catatan sejarah sebagai “Women’s Biennale”. Contoh karya yang ditampilkan adalah instalasi naratif oleh Zineb Sedira dari Aljazair
Meskipun inklusi ini meningkatkan visibilitas seniman Global South (GS) dan seniman perempuan, fenomena ini mewakili sebuah Strategi Inklusi Vertikal, di mana institusi sentral Barat yang mengundang seniman GS ke dalam bingkai kuratorialnya. Walaupun memberikan platform, strategi ini rentan terhadap kritik tokenisasi, di mana representasi dilakukan tanpa reformasi struktural mendalam terhadap kanon itu sendiri.
Biennale Regional (Jogja Equator): Diplomasi Lintas-Selatan
Berlawanan dengan model Venice, inisiatif seperti Biennale Jogja Equator (BJE) di Indonesia menawarkan posisi yang berbeda untuk memandang internasionalisme. BJE secara eksplisit memposisikan Indonesia sebagai penghubung di medan internasional, berdasarkan semangat historis Konferensi Asia-Afrika (KAA). Landasan utama BJE adalah diplomasi budaya, yang membaca kembali relasi kawasan (misalnya, Indonesia-India) yang terputus akibat pembentukan negara-negara kolonial. Semangat ini menantang konsep pusat kekuasaan (siapa yang menentukan “Tenggara”?).
Model BJE adalah contoh dari Strategi Horizontal Kedaulatan, yang tidak hanya mencari tempat duduk di meja Barat, tetapi menuntut penciptaan peta geopolitik budaya yang baru, fokus pada relasi South-South. Sementara platform global seperti Venice memberikan visibilitas yang diperlukan, platform regional seperti Jogja memberikan agency yang lebih substansial, karena menantang gagasan bahwa legitimasi harus datang dari Barat. Keberadaan forum regional ini adalah manifestasi upaya dekolonisasi yang beroperasi pada tingkat geopolitik-kuratorial.
Transformasi Institusi Museum Mayor
Kebijakan Akuisisi dan Kanonisasi Global
Institusi museum besar telah mengakui peran mereka dalam memelihara narasi Eurosentris dan kini berupaya melakukan pergeseran kelembagaan. Tate Modern, misalnya, telah memperluas koleksinya secara agresif di luar Eropa dan Amerika Utara, dengan fokus pada Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Akuisisi penting meliputi karya-karya dari Aljazair, Lebanon, Iran, dan Mesir, serta karya dari Asia Pasifik (Do Ho Suh, Subodh Gupta) dan Afrika Selatan (Santu Mofokeng).
Kebijakan ini bertujuan untuk memperkaya koleksi dan memperluas jangkauan geografisnya, memasukkan modernisme dan seni kontemporer non-Barat ke dalam sejarah seni global. Sebuah contoh nyata adalah kolaborasi Tate Modern untuk pameran Nigerian Modernism, yang menampilkan 50 seniman selama periode transformatif 1940-an hingga 1980-an. Yang menarik, pameran ini difasilitasi melalui kemitraan strategis dengan institusi keuangan Nigeria (Access Holdings Plc dan Coronation Group). Peran korporasi Afrika dalam mendanai kanonisasi budaya mereka di institusi Barat menunjukkan bahwa legitimasi global kini difasilitasi oleh kekuatan ekonomi Global South sendiri, sebuah bentuk diplomasi budaya korporat. Meskipun hal ini mengubah ketergantungan historis, ia juga mengikat legitimasi budaya pada modal kapitalis, menimbulkan ketegangan antara dekolonisasi naratif dan kapitalisasi pasar.
Peran Kuratorial dalam Pembacaan Ulang Sejarah
Dalam konteks dekolonisasi, peran kurator telah berevolusi dari sekadar pengelola koleksi menjadi pencipta narasi dan pengalaman yang dapat memperkaya pemahaman audiens. Institusi kini menghadapi tantangan etika kurasi yang mendalam, terutama terkait isu repatriasi artefak budaya yang diperoleh selama era kolonial. Institusi harus bergerak melampaui kebijakan inklusi yang bersifat tokenisasi dan secara aktif berinvestasi dalam re-reading history (pembacaan ulang sejarah), memastikan narasi kuratorial menghormati kedaulatan budaya dan membalikkan historiografi yang bias.
Dinamika Pasar Seni Global dan Munculnya Ruang Niche
Pasar seni kontemporer Afrika dan Asia telah menjadi subjek fokus yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini didukung oleh Art Fair yang mulai menyesuaikan fokus geografis mereka. Art Basel Hong Kong, misalnya, menunjukkan perhatian yang kuat terhadap ekosistem seni Asia, terutama Asia Tenggara, mengakui kerumitan sejarah dan keragaman etnisnya.
Lebih lanjut, inisiatif desentralisasi pasar muncul melalui pembentukan pameran khusus (niche fair). Pendirian Africa Basel di Basel, Swiss, misalnya, didedikasikan sebagai platform untuk galeri yang berspesialisasi dalam seni dari Afrika dan diasporanya, bertujuan untuk memasuki “adegan yang benar-benar global”. Tujuan pameran ini tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga politik, berjuang untuk inklusi dan posisi yang sah bagi negara-negara Afrika yang kurang terwakili (seperti Zambia). Upaya-upaya ini menunjukkan pergeseran struktural pasar global menuju desentralisasi yang ditandai dengan beragam aktor yang tersebar secara geografis.
Seni Sebagai Kritik Struktur Kekuasaan Global
Seni kontemporer menjadi wadah yang sangat efektif untuk melancarkan kritik terhadap struktur kekuasaan global yang diwarisi dari masa kolonialisme, imperialisme, dan patriarki. Seniman Global South sering kali menggunakan material, konteks, dan narasi yang menantang hegemoni Eurosentris.
Membongkar Trauma Kolonial, Imperialisme, dan Eksploitasi
Karya seni kontemporer secara eksplisit mengkritik hegemoni, imperialisme, dan kolonialisme Barat. Imperialisme modern, meskipun tidak lagi dalam bentuk pemerintahan fisik langsung, terus memanifestasikan dirinya melalui eksploitasi ekonomi dan keterikatan pada pasar global.4
Kritik Materialitas Kolonial (El Anatsui)
Seniman Ghana, El Anatsui, terkenal dengan karya instalasinya yang menyerupai kain metalik monumental, dibuat dari ribuan tutup botol minuman keras bekas dan kabel tembaga. Material ini bukan dipilih secara acak. Tutup botol, yang merupakan sisa-sisa konsumsi alkohol yang dilegalkan secara massal, secara inheren membawa bobot sejarah perdagangan trans-Atlantik, di mana minuman keras sering digunakan sebagai alat tukar yang merusak masyarakat Afrika pasca-kolonial. Anatsui mengubah sisa-sisa eksploitasi dan konsumerisme menjadi seni tinggi yang spektakuler. Tindakan ini merupakan reklamasi materialitas, menyuntikkan narasi kontra-hegemoni ke dalam material yang secara langsung terkait dengan sirkuit ideologis dan ekonomi masa lalu.
Kritik Indiferensi Media dan Eksploitasi Sumber Daya (Richard Mosse dan Alfredo Jaar)
Kritik terhadap eksploitasi sumber daya Global South sering diungkapkan melalui perlawanan terhadap narasi media Barat yang bias. Richard Mosse, dalam instalasi filmnya The Enclave (2013) tentang konflik di Republik Demokratik Kongo, menggunakan film inframerah Kodak—teknologi yang awalnya dikembangkan oleh militer Amerika Serikat untuk pengawasan—untuk mendokumentasikan medan perang. Pemandangan pegunungan dan hutan yang kaya klorofil (sumber daya alam yang menjadi akar konflik) ditampilkan dengan warna merah muda menyala (bubblegum pink). Penggunaan lensa teknologi imperial ini secara ironis mengungkap apa yang tidak ingin dilihat oleh Barat: tragedi yang diabaikan. Mosse mengkritik konflik yang tragis dan terlupakan, di mana jutaan orang meninggal akibat perang yang didorong oleh eksploitasi mineral.
Di Amerika Latin, seniman seperti Alfredo Jaar menyoroti indiferensi barbar media Barat, yang ia sebut sebagai “sikap rasis terang-terangan”, terhadap genosida Rwanda 1994. Karyanya menyelidiki bagaimana liputan media Barat tentang Afrika direduksi menjadi tiga subjek sempit—hewan, kelaparan, dan penyakit—dengan mengabaikan budaya dan kehidupan benua tersebut. Jaar menunjukkan bahwa setiap citra merepresentasikan konsepsi ideologis dunia, dan seniman harus terlibat dengan dunia untuk menghasilkan karya yang lebih dari sekadar dekorasi. Seniman ini membongkar sirkuit ideologis yang direproduksi sehari-hari dengan menyuntikkan kritik tajam melalui penggunaan material dan metode.
Reorientasi Narasi Gender dan Ras
Membongkar Stereotip melalui Hibriditas (Wangechi Mutu)
Wangechi Mutu, seniman kelahiran Kenya, menjadi tokoh penting dalam kritik gender dan ras pasca-kolonial melalui karya kolase dan seni hibridnya. Kolasenya, yang menggambarkan figur perempuan sureal yang terdiri dari serpihan gambar makhluk hidup dan non-hidup, bertujuan untuk mengubah perspektif audiens. Mutu secara strategis menantang stereotip yang ada tentang kelompok terpinggirkan (terutama perempuan kulit hitam) dengan melebih-lebihkan atau mengkarikaturisasi mereka. Mutu berhasil menyusupkan kebenaran sosial dengan “semacam sihir” agar kritik tersebut dapat meresap ke dalam psikis lebih banyak orang.
Kritik Ruang Institusional
Mutu juga mengkritik “kesunyian kotak putih” (white cube) museum. Ia menganggap ruang pameran tradisional Barat terasa asing dan pasif bagi audiens baru. Mutu mendekati ruang museum seolah-olah itu adalah kanvas kosong yang harus ditantang, bukan hanya ‘taman bermain’ baginya, karena secara historis, ruang itu tidak pernah dirancang untuknya. Kritik ini memperluas dekolonisasi dari narasi visual ke kritik terhadap etiket dan arsitektur institusi yang mempertahankan dominasi budaya.
Dalam konteks Asia, seniman perempuan Asia menantang konsep “Asianness” yang seringkali menjadi label eksotis yang awalnya membawa mereka ke perhatian global. Mereka menggunakan kesaksian (testimony) sebagai metode penting dalam diskursus publik dan kolektif, yang secara tegas menolak narasi “genius artistik soliter” yang sering kali merupakan domain seniman laki-laki.
Kedaulatan Budaya Dan Lokalitas Dalam Estetika Kontemporer
Kekuatan seni kontemporer Global South terletak pada kemampuannya untuk berdialog dengan modernitas sambil menegaskan kembali kedaulatan budaya dan kearifan lokal. Seni rupa kontemporer harus berfungsi sebagai perekat sosial dan medium untuk merayakan keberagaman di tingkat lokal, sebelum melompat ke panggung global.
Sinkretisme dan Kearifan Lokal
Perupa kontemporer di Asia, khususnya di Indonesia, secara aktif menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan estetika modern. Mereka membawa kearifan lokal ke panggung global, menciptakan karya-karya yang menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seni rupa tradisional tidak hanya dipandang sebagai ekspresi individu tetapi juga sebagai perekat sosial yang merayakan dan mempererat keterhubungan budaya dalam masyarakat lokal. Perayaan akar rumput, seperti Festival Seni Desa di Karangdowo, adalah contoh krusial dari upaya bottom-up untuk mengapresiasi dan melestarikan kekayaan budaya lokal.
Pelestarian warisan budaya melalui seni kontemporer harus didukung oleh pendidikan seni rupa yang memadai. Pendidikan ini berfungsi sebagai wadah untuk meneruskan tradisi sambil merangsang perkembangan kreativitas generasi mendatang.
Menegaskan Cultural Sovereignty dan Dekolonisasi Pengetahuan
Praktik seni dekolonial menekankan pada metodologi Pribumi (Indigenous methodologies) dan praktik kolaboratif berbasis komunitas. Hal ini mencakup upaya reklamasi budaya, revisi historis, dan interpretasi kontemporer terhadap pengetahuan tradisional yang sebelumnya direndahkan atau diabaikan oleh sistem kolonial.
Sebagai contoh, wacana dekolonisasi pengetahuan telah menjadi fokus utama dalam praktik kolektif di kawasan Timur Indonesia, sebagaimana diangkat dalam Makassar Biennale Arts. Upaya ini menegaskan bahwa globalisasi seni harus dibangun dari fondasi lokal yang kuat. Jembatan lintas budaya yang sukses harus dikuatkan di tingkat lokal (kedaulatan budaya), untuk memastikan bahwa visibilitas global yang ditawarkan oleh institusi Barat tidak menghasilkan asimilasi atau sekadar tokenisasi narasi, melainkan pengakuan yang otentik terhadap cultural sovereignty.
Dekolonisasi Pasar Seni Melalui Revolusi Digital
Meskipun ranah naratif dan institusional telah mengalami dekolonisasi, pasar seni tetap merupakan sirkuit kekuatan yang didominasi oleh kaum borjuis. Dalam era kontemporer, seni rentan menjadi seni yang konsumtif, di mana selera murni diabaikan demi dominasi pasar. Hal ini menempatkan otonomi seni di bawah belenggu Global Art yang konsumtif. Revolusi digital, terutama melalui teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT), menjanjikan desentralisasi yang mungkin mengatasi hegemoni pasar tradisional.
Peran Teknologi Blockchain (NFT) dalam Desentralisasi Pasar
Teknologi NFT menawarkan potensi besar bagi pelaku industri kreatif di Global South, termasuk Indonesia, dengan menyediakan cara baru untuk membeli dan menjual karya seni secara virtual dan terbuka ke seluruh dunia. NFT berpotensi menjadi alat dekolonisasi ekonomi yang signifikan karena beberapa alasan:
- Transparansi dan Penjualan Langsung: NFT memungkinkan penjualan karya secara daring, menghilangkan perantara tradisional (dealer, galeri Barat) yang selama ini menjadi pusat hegemoni pasar dan sering kali mematok harga karya seni rupa murni yang berpotensi memiliki nilai jual tinggi.
- Perlindungan Kedaulatan Intelektual: Dengan menggunakan sistem blockchain yang mengadopsi transparansi dan keamanan, NFT memungkinkan karya tercatat dan terdaftar secara resmi (HAKI), mengurangi tingkat pembajakan dan kerugian bagi pencipta. Ini sangat penting untuk menegaskan kedaulatan kekayaan intelektual seniman Global South.
- Kedaulatan Budaya Adat: Terdapat proyek-proyek NFT yang dipimpin oleh komunitas Adat (Indigenous-led) yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan mempromosikan seni dan budaya mereka, sekaligus menawarkan model pendanaan baru yang independen bagi sektor kreatif.
Acara global seperti NFT NYC berfungsi sebagai platform konvergensi yang mendorong pengembangan ekosistem NFT dalam seni digital, memberikan panggung bagi proyek-proyek baru dan seniman independen di tengah gelombang ekonomi digital.
Risiko dan Pembentukan Neo-Circuit Ideologis
Meskipun potensi desentralisasi NFT sangat radikal, terdapat tantangan dan risiko yang perlu dianalisis. Pasar NFT masih berpotensi menjadi tempat bagi beragam penipuan (scams). Lebih lanjut, seniman sebagai kreator sering kali hanya diberikan gambaran yang menggiurkan terkait metaverse dan kenaikan harga yang fantastis, sementara NFT dalam jangka waktu pendek belum sepenuhnya dapat menggantikan karya seni konvensional.
Analisis kritis menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan NFT, meskipun menjanjikan kebebasan dari perantara Barat tradisional, berisiko menciptakan Neo-Circuit Ideologis baru. Kebebasan dari dealer digantikan oleh ketergantungan pada infrastruktur teknologi (platform NFT, marketplace, mata uang kripto) yang mayoritas masih dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan teknologi Global North. Oleh karena itu, dekolonisasi pasar seni memerlukan upaya yang melampaui perubahan medium semata, yaitu pembangunan infrastruktur teknologi yang aman dan kedaulatan data yang melindungi seniman dari bentuk eksploitasi digital yang baru.
Kesimpulan
Seni kontemporer berfungsi sebagai jembatan lintas budaya yang krusial, memainkan peran ganda dalam merayakan keragaman dan melancarkan kritik terhadap struktur kekuasaan global yang tidak adil. Peningkatan visibilitas seniman dari Global South—baik Asia, Afrika, maupun Amerika Latin—adalah hasil dari konvergensi antara tekanan aktivisme dekolonial, adaptasi institusional (museum dan biennale), dan munculnya teknologi desentralisasi (NFT).
Terdapat dua strategi utama yang beroperasi: Inklusi Vertikal (institusi Barat yang membuka pintu) dan Kedaulatan Horizontal (Global South yang membangun pusat naratif dan ekonominya sendiri, seperti Biennale Jogja Equator dan Africa Basel). Kemajuan dekolonisasi sejati diukur dari keberhasilan strategi horizontal ini, yaitu kemampuan untuk menciptakan narasi yang tidak hanya diakui, tetapi juga dimiliki dan dikontrol, dengan menantang asumsi hegemoni Eurosentris di setiap tingkatan, mulai dari kurasi material (El Anatsui) hingga politik ruang (Wangechi Mutu).
Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai lanskap seni global, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memastikan momentum dekolonisasi naratif dan struktural berlanjut:
- Komitmen Institusional Melampaui Tokenisasi: Museum dan institusi seni global harus memperkuat komitmen mereka untuk dekolonisasi institusional, yang mencakup investasi jangka panjang pada penelitian dan re-reading history (pembacaan ulang sejarah) untuk memasukkan modernisme non-Barat secara integral, bukan hanya sebagai tambahan. Harus ada upaya yang tulus dalam proses repatriasi artefak budaya dan pengarusutamaan kurator serta akademisi dari Global South dalam posisi kunci.
- Penguatan Peta Geopolitik Budaya Alternatif: Dukungan terhadap platform regional dan inisiatif South-South seperti Biennale Equator harus ditingkatkan. Platform-platform ini adalah kunci untuk menghasilkan teori dan kritik seni yang berakar pada realitas lokal dan sejarah geopolitik yang unik, serta untuk membangun kedaulatan naratif yang independen dari pusat-pusat Barat.
- Pembangunan Infrastruktur Digital yang Aman dan Adil: Pemanfaatan teknologi desentralisasi (NFT/Blockchain) harus diakui sebagai alat dekolonisasi ekonomi yang potensial. Namun, pengembangan platform digital harus disertai dengan mitigasi risiko penipuan dan pembangunan kerangka kerja (HAKI dan keamanan) yang menjamin kedaulatan data dan kepemilikan finansial bagi seniman Global South. Kegagalan untuk mengendalikan infrastruktur digital hanya akan menggantikan hegemoni pasar konvensional dengan Neo-Circuit eksploitasi teknologi.