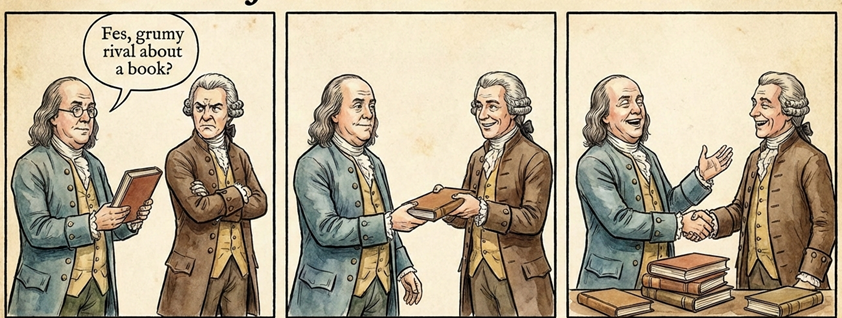Tinjauan Tren Hidup Bersama Tanpa Perkawinan (Kohabitasi) di Berbagai Negara Asia
Kohabitasi didefinisikan secara operasional sebagai pengaturan hidup bersama yang menyerupai pernikahan namun tidak diresmikan melalui ikatan legal formal. Di wilayah Barat, kohabitasi telah berkembang menjadi praktik yang menyerupai pernikahan, bahkan menjadi gaya hidup alternatif yang mapan. Namun, konteks Asia menyajikan dikotomi yang lebih nuansial mengenai tujuan dan peran kohabitasi.
Terdapat dualitas dalam peran kohabitasi: sebagai Prekursor Pernikahan (Trial Marriage) atau sebagai Alternatif Pernikahan (Alternative Lifestyle). Di banyak masyarakat Asia, meskipun tren kohabitasi meningkat, fenomena ini cenderung berfungsi sebagai tahapan pengujian sebelum komitmen formal. Hal ini konsisten dengan norma sosial yang kuat di sebagian besar Asia, di mana pernikahan masih dipandang sebagai tujuan akhir dari suatu hubungan intim. Peningkatan kohabitasi di Tiongkok, misalnya, dipandang sebagai fase yang diterima secara sosial sebelum pernikahan resmi. Hal ini menyoroti bahwa, di Asia, motif utama kohabitasi adalah untuk mendapatkan kejelasan dan kedalaman hubungan, menguji rutinitas bersama, dan memastikan kesiapan pasangan sebelum mengikat janji suci.
Kohabitasi dalam Kerangka Transisi Demografi Kedua (SDT) di Asia
Kohabitasi adalah salah satu elemen penanda Transisi Demografi Kedua (SDT), sebuah tahap demografi pasca-industrial yang ditandai oleh peningkatan usia menikah, penurunan tingkat fertilitas, dan kenaikan angka perceraian. Tren ini jelas terlihat di Asia, di mana penundaan pernikahan dan kenaikan singlehood terjadi lebih cepat dibandingkan di Barat.
Namun, di Asia Timur, perkembangan SDT menunjukkan karakteristik yang terhambat. Meskipun terjadi penurunan drastis dalam tingkat pernikahan dan fertilitas, hal ini tidak diikuti oleh penyebaran kohabitasi atau kelahiran di luar nikah yang signifikan (kecuali di Filipina). Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan struktural. Perubahan sosial dan ekonomi yang masif (seperti peningkatan pendidikan dan kemandirian wanita) berbenturan dengan norma keluarga tradisional dan kewajiban gender yang masih kaku. Akibatnya, alih-alih memilih gaya hidup alternatif (kohabitasi jangka panjang atau melahirkan di luar nikah), banyak individu, terutama wanita, memilih untuk menunda atau menghindari pembentukan keluarga secara keseluruhan.
Heterogenitas Fenomena Kohabitasi di Benua Asia
Analisis kohabitasi di Asia tidak dapat diperlakukan sebagai entitas tunggal karena adanya perbedaan besar dalam sejarah kultural dan kerangka hukum.
- Asia Timur (Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan): Dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme yang menempatkan pernikahan sebagai dasar organisasi sosial , tren utama adalah penundaan pernikahan karena biaya yang mahal dan penolakan peran gender yang tidak setara. Kohabitasi di sini sering berfungsi sebagai trial marriage yang rasional secara ekonomi.
- Asia Selatan (India): Meskipun masyarakatnya sangat konservatif, sistem yudisial India telah menunjukkan progresivitas yang signifikan dengan mengakui dan melindungi hubungan live-in.
- Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, Thailand): Wilayah ini menunjukkan kontradiksi hukum yang tajam. Beberapa negara (seperti Thailand dan Filipina) menunjukkan prevalensi kohabitasi yang relatif lebih tinggi, sementara negara-negara dengan hukum agama kuat (seperti Malaysia dan Indonesia) memberlakukan kriminalisasi atau pembatasan yang ketat terhadap hidup bersama tanpa ikatan sah.
Lanskap Regional: Tren, Pendorong Utama, dan Kontradiksi Kultural
Asia Timur: Krisis Pernikahan dan Reaksi terhadap Ketimpangan Gender
Negara-negara Asia Timur menghadapi krisis demografi yang dipicu oleh pola pernikahan. Di Korea Selatan dan Taiwan, telah terjadi peningkatan substansial dalam fenomena late singlehood (individu yang tidak pernah menikah pada usia 45 hingga 49 tahun). Misalnya, di Korea Selatan dan Taiwan, tingkat late singlehood di kalangan pria telah mencapai 20% atau lebih pada tahun 2020, sebuah lonjakan signifikan dari tahun 2010.
Peningkatan singlehood ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi dan ideologi gender.
Pendorong Ekonomi: Beban Biaya Pernikahan
Biaya pernikahan yang melonjak telah menjadi penghalang struktural utama. Di Tiongkok, krisis caili (mas kawin atau bride price) telah mengubah ritual budaya tradisional menjadi kewajiban finansial yang melumpuhkan, terutama bagi pria pedesaan dan kurang terdidik. Kenaikan biaya ini berkontribusi pada penurunan tajam dalam pendaftaran pernikahan, yang mencapai rekor terendah 7.64 juta pada tahun 2021. Demikian pula di Korea Selatan, salah satu alasan utama mengapa responden yang belum menikah menghindari pernikahan adalah kurangnya sumber daya finansial, terutama bagi pria (38%). Hal ini terkait tradisi di mana keluarga pengantin pria diharapkan menanggung sebagian besar beban keuangan untuk pernikahan dan perumahan.
Kemandirian Wanita dan Penolakan Peran Gender
Perluasan pendidikan tinggi bagi wanita telah meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, yang secara langsung mengurangi daya tarik institusi pernikahan tradisional. Di Korea, penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan sebagian disebabkan oleh peningkatan kemandirian ekonomi wanita dan perubahan komposisi pasar pernikahan. Banyak wanita muda Korea menolak pernikahan yang masih didominasi oleh norma male breadwinner dan pembagian kerja domestik yang sangat tidak setara.
Maka, kohabitasi muncul sebagai solusi rasional yang bersifat ganda. Secara ekonomi, hidup bersama memungkinkan pasangan berbagi biaya hidup, terutama biaya perumahan yang tinggi di kawasan urban. Secara ideologis, kohabitasi menunda komitmen terhadap peran gender kaku yang masih melekat pada pernikahan formal. Meskipun kohabitasi masih dianggap berbeda dari pernikahan dalam hal status legal dan pengakuan sosial, semakin banyak pasangan di Tiongkok yang memandangnya sebagai trial marriage yang diterima secara sosial sebelum menikah secara formal.
Asia Selatan (India): Progresivitas Yudisial Melawan Stigma Sosial
Di India, fenomena live-in relationships telah mengalami perkembangan hukum yang unik, di mana Mahkamah Agung telah mengambil peran progresif. Putusan-putusan penting telah menetapkan bahwa hidup bersama secara konsensual antara orang dewasa yang sah bukanlah pelanggaran pidana atau ilegal, melainkan berada di bawah hak konstitusional atas kebebasan berekspresi (Article 19) dan hak untuk hidup (Article 21).
Perkembangan yudisial ini memberikan perlindungan terbatas tetapi signifikan. Wanita dalam hubungan live-in yang berlangsung lama dan menyerupai pernikahan (in the nature of marriage) berhak mencari perlindungan dan tunjangan (maintenance) di bawah Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005. Lebih lanjut, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi jangka panjang diakui sah (legitimate) dan memiliki hak waris atas properti milik orang tua mereka, baik properti yang diperoleh sendiri maupun properti leluhur.
Namun, terlepas dari kemajuan hukum ini, kohabitasi masih menghadapi stigma sosial yang kuat di masyarakat India yang didominasi oleh pola pikir konservatif. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan bersifat reaktif (berbasis kasus ke kasus dan penafsiran yudisial) dan tidak memberikan kerangka statutori yang jelas, terutama terkait hak properti langsung bagi pasangan itu sendiri (selain perlindungan bagi wanita dan anak).
Asia Tenggara: Keberagaman Motif dan Kendala Hukum Agama
Asia Tenggara menunjukkan pola yang sangat beragam, dari sistem hukum yang lebih sekuler hingga negara-negara dengan kontrol moral berbasis hukum agama yang ketat.
- Thailand dan Filipina: Negara-negara ini menunjukkan adopsi kohabitasi yang lebih terbuka. Di Filipina, kohabitasi adalah fenomena yang terdokumentasi dan sering mendahului pernikahan, dengan prevalensi 4.9% dari kelompok kohort pada tahun 2005. Di Thailand, studi pada pekerja migran di Bangkok menunjukkan bahwa tekanan orang tua terkait pernikahan berkurang di lingkungan urban, memudahkan pasangan untuk memilih kohabitasi sebagai prelude to marriage.
- Malaysia dan Indonesia (Kriminalisasi): Di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kohabitasi menghadapi tantangan hukum yang signifikan.
- Malaysia: Hukum Syariah menganggap kohabitasi (terutama Khalwat atau berdekatan secara intim antara pria dan wanita Muslim yang bukan mahram) sebagai pelanggaran pidana. Bahkan muncul usulan agar non-Muslim yang melakukan khalwat dengan Muslim juga dihukum di pengadilan sipil, mencerminkan adanya upaya untuk memperluas kontrol moral. Malaysia juga tidak memiliki kerangka hukum perdata untuk melindungi kepentingan properti kohabitan non-Muslim, menempatkan mereka pada risiko kerugian finansial yang besar saat berpisah.
- Indonesia: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru), yang akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan, mengatur kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) sebagai delik aduan. Pengaduan dibatasi hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang paling terdampak, yaitu suami atau istri (bagi yang sudah menikah) atau orang tua atau anak (bagi yang belum menikah). Meskipun ini membatasi intervensi publik, ketentuan ini tetap menjadikannya potensi pelanggaran pidana yang dapat digunakan oleh keluarga yang menentang hubungan tersebut.
- Vietnam: Secara budaya, hidup bersama masih dilihat sebagai komitmen yang sangat besar. Budaya ini menuntut pernikahan sebagai tujuan hubungan, dan jika pasangan hidup bersama terlalu lama (misalnya, lebih dari 2 tahun) tanpa menikah, hal itu dapat mempersulit wanita untuk menemukan pasangan serius di masa depan.
Pendorong Sosial-Ekonomi: Mengapa Pasangan Memilih Kohabitasi
Pemilihan kohabitasi, terutama di perkotaan Asia, didasarkan pada kombinasi rasionalitas ekonomi dan pergeseran nilai ideologis, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mereformasi institusi pernikahan tradisional.
Beban Finansial Pernikahan Formal
Biaya upacara, mas kawin, dan terutama penyediaan perumahan yang layak di kota-kota besar telah menjadi faktor pendorong utama penundaan atau penghindaran pernikahan. Di Tiongkok, caili telah melumpuhkan prospek pernikahan bagi pria pedesaan yang miskin. Di Korea, tuntutan untuk menanggung biaya perumahan merupakan beban besar bagi pihak pria. Kohabitasi menawarkan solusi praktis dan segera bagi pasangan muda untuk mengurangi beban biaya hidup yang tinggi di perkotaan, memungkinkan mereka menghemat atau berbagi pengeluaran sewa, yang merupakan bentuk rasionalitas ekonomi langsung.
Pergeseran Nilai Gender dan Peningkatan Pendidikan Wanita
Peningkatan tingkat pendidikan, terutama di kalangan wanita, telah memberdayakan individu untuk membuat pilihan yang lebih terinformasi tentang pasangan hidup dan waktu pernikahan. Wanita yang lebih berpendidikan cenderung menunda pernikahan, mencari stabilitas finansial dan menuntut hubungan yang lebih egaliter. Bagi banyak wanita di Asia Timur, pernikahan tradisional menyiratkan pembagian kerja domestik yang tidak setara, yang ingin mereka hindari. Kohabitasi memungkinkan pasangan untuk menguji hubungan dan menegosiasikan pembagian tanggung jawab yang lebih adil sebelum terikat secara formal.
Kohabitasi sebagai Mekanisme Risk Assessment (Trial Marriage)
Di banyak negara Asia, di mana stigma perceraian masih kuat, kohabitasi dipandang sebagai sarana untuk mitigasi risiko. Pasangan menggunakan fase hidup bersama sebagai trial run untuk menilai kebiasaan sehari-hari, kondisi hidup, dan stabilitas emosional satu sama lain, sehingga memperkuat fondasi hubungan jangka panjang. Hal ini selaras dengan temuan bahwa kohabitasi di Tiongkok seringkali berfungsi sebagai prekursor langsung menuju pernikahan. Tujuannya bukan untuk menghindari komitmen, tetapi untuk memastikan komitmen yang dibuat adalah pilihan yang matang dan terinformasi, bukan sekadar kewajiban budaya.
Konteks Urban dan Gaya Hidup: Hubungan Vertikalitas dan Privasi
Hunian Vertikal sebagai Fasilitator Kohabitasi
Di tengah urbanisasi yang tak terhindarkan dan keterbatasan lahan di megacity seperti Jakarta , hunian vertikal (apartemen atau rumah susun) menjadi solusi arsitektural yang dominan. Selain lokasinya yang strategis dekat pusat bisnis dan transportasi umum (sejalan dengan konsep Transit-Oriented Development/TOD) , hunian vertikal juga menyediakan konteks sosial yang mendukung gaya hidup non-tradisional, termasuk kohabitasi.
Peningkatan jumlah unit apartemen di kota-kota besar secara tidak langsung memfasilitasi tren kohabitasi karena lingkungan ini menawarkan privasi yang terjaga. Kehidupan di apartemen seringkali ditandai oleh isolasi sosial, meskipun secara fisik padat. Ketersediaan anonimitas ini sangat penting bagi pasangan kohabitasi yang ingin menghindari pengawasan dan tekanan sosial dari keluarga besar atau komunitas tradisional. Dengan demikian, lingkungan fisik urban menjadi fasilitator sosial, menawarkan perlindungan dari kendali institusional dan keluarga yang memaksakan norma pernikahan.
Tantangan Hidup Bersama di Ruang Terbatas dan Dampak Lingkungan
Gaya hidup apartemen, meskipun praktis, menghadirkan serangkaian tantangan, terutama bagi pasangan yang tinggal di unit kecil (tipe studio atau 1BR). Ruang terbatas menuntut strategi desain yang cerdas, seperti penggunaan furnitur multifungsi (misalnya, tempat tidur dengan laci atau meja lipat) dan penerapan konsep open plan untuk menciptakan ilusi ruang yang lebih luas.
Kebisingan Kronis dan Regulasi
Salah satu keluhan signifikan di hunian vertikal adalah masalah kebisingan. Suara langkah kaki, renovasi unit tetangga, atau kebisingan luar dapat mengganggu kenyamanan. Kebisingan kronis ini bukan hanya masalah fisik; paparan polusi suara berulang-ulang, yang merupakan risiko umum di apartemen bertingkat, dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, berkontribusi pada stres, depresi, dan kelemahan fisik. Untuk mengatasi masalah ini, solusi peredam suara seperti pemasangan sound barrier (pagar pembatas akustik), panel akustik, atau plafon kedap suara yang profesional sering dibutuhkan.
Pasangan kohabitasi juga harus mematuhi aturan dan regulasi ketat yang ditetapkan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). P3SRS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, berfungsi mengelola aspek kehidupan bersama, mulai dari keuangan hingga penyelesaian konflik. Konflik antara penghuni dan pengelola sering terjadi, menunjukkan tantangan tata kelola yang bersifat sangat lokal.
Kebutuhan Kesejahteraan Mental dan Hewan Peliharaan
Di tengah isolasi yang ditawarkan oleh kehidupan vertikal, kepemilikan hewan peliharaan (pet ownership) terbukti menjadi mekanisme coping yang penting untuk kesehatan mental. Interaksi dengan hewan peliharaan, seperti kucing atau anjing, dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan secara signifikan melalui pelepasan hormon oksitosin. Selain itu, hewan peliharaan berfungsi sebagai sahabat setia yang efektif mengurangi perasaan kesepian yang lazim di era digital.
Namun, hal ini seringkali bertentangan dengan peraturan P3SRS. Banyak apartemen melarang atau membatasi secara ketat pemeliharaan hewan. Akibatnya, pasangan yang memilih hidup bersama dan mencari dukungan emosional dari hewan peliharaan sering kali terpaksa mencari apartemen pet-friendly yang merupakan kategori premium (seperti Verde Residence, Kemang Village, atau Aerium Residence di Jakarta). Ketersediaan hunian pet-friendly ini secara tidak langsung mendukung kesejahteraan mental segmen demografi yang memilih gaya hidup non-tradisional.
Implikasi Hukum: Kerentanan dan Perlindungan Pasangan Kohabitasi
Kerangka hukum di Asia sebagian besar terbagi antara model yang berfokus pada status formal (pernikahan) dan model yang berfokus pada fungsi hubungan (mirip pernikahan), yang secara signifikan mempengaruhi kerentanan pasangan kohabitasi.
Ketidakjelasan Hak Properti dan Finansial Pasangan yang Berpisah/Meninggal
Di yurisdiksi yang mengadopsi sistem hukum berbasis status (seperti Hong Kong), tidak ada konsep “pernikahan hukum umum” (common law marriage). Akibatnya, pasangan kohabitasi tidak menikmati hak otomatis yang sama dengan pasangan menikah terkait pembagian properti bersama, tunjangan (alimony), atau warisan saat berpisah atau meninggal.
Jika salah satu pasangan meninggal tanpa surat wasiat (intestate), pasangan kohabitasi yang masih hidup tidak memiliki hak otomatis untuk berbagi warisan. Klaim finansial hanya dapat diajukan melalui hukum properti umum, kontrak, atau, dalam kasus Hong Kong, melalui Inheritance (Provision for Family and Dependants) Ordinance, di mana pasangan harus membuktikan bahwa mereka didukung secara substansial oleh pasangannya sebelum kematian. Ketidakberadaan kerangka hukum statutori yang jelas ini meninggalkan ambiguitas dan kerentanan finansial yang tinggi, memaksa pasangan untuk bergantung pada interpretasi yudisial yang kompleks.
Perlindungan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan
Meskipun hak pasangan kohabitasi sering tidak dilindungi, hak anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut cenderung mendapatkan perlindungan yang lebih kuat di Asia:
- India: Anak yang lahir dari hubungan live-in jangka panjang diakui sah dan memiliki hak waris penuh atas properti orang tua.
- Singapura: Terlepas dari status pernikahan orang tua, kedua orang tua biologis secara hukum wajib menyediakan pemeliharaan (maintenance) bagi anak, dan pengadilan umumnya memberikan hak asuh bersama (joint custody) berdasarkan kepentingan terbaik anak.
- Thailand: Ayah yang tidak menikah dapat mengajukan legitimasi anak dan hak asuh, meskipun ini memerlukan persetujuan dari ibu dan/atau proses penentuan melalui pengadilan.
Dalam kasus kekerasan, kerangka hukum di beberapa yurisdiksi juga memberikan perlindungan. Misalnya, di Hong Kong, Domestic and Cohabitation Relationships Violence Ordinance memberikan hak kepada korban untuk mencari ganti rugi dan perintah pengadilan, menempatkan kohabitan pada status yang sama dengan pasangan menikah dalam konteks perlindungan dari kekerasan domestik.
Kepemilikan Strata Title dan Kewajiban Bersama
Aspek properti semakin kompleks dalam konteks hunian vertikal di Indonesia dan negara Asia lainnya, yang menggunakan sistem Strata Title. Kepemilikan ini bersifat terbatas waktu (Hak Guna Bangunan/HGB, biasanya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun).
Pasangan kohabitasi yang memiliki unit strata title diwajibkan membayar dua jenis biaya kolektif: Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) untuk operasional rutin, dan Sinking Fund (dana cadangan) untuk perbaikan struktural besar di masa depan (misalnya, perbaikan atap atau penggantian lift). Dana cadangan ini tidak dapat dikembalikan kepada penghuni.
Jika pasangan kohabitasi membeli unit secara bersama-sama, sangat penting bagi mereka untuk memiliki dokumen yang mengatur kontribusi masing-masing. Tanpa kontrak yang jelas, sengketa kepemilikan menjadi risiko krusial, terutama karena sistem strata title itu sendiri hanya mengatur kepemilikan unit fisik dalam struktur yang lebih besar, bukan status hubungan kepemilikan antar-pasangan.
Solusi: Kontrak Kohabitasi (Cohabitation Agreements)
Mengingat tingginya kerentanan hukum di sebagian besar Asia, mitigasi risiko melalui dokumentasi legal menjadi langkah yang sangat vital. Cohabitation Agreements berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dengan secara eksplisit menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kontrak ini harus mencakup: penentuan kepemilikan aset yang diperoleh bersama, pembagian hutang, dan pembagian properti jika terjadi perpisahan. Dokumentasi seperti rekening bank gabungan atau perjanjian properti sangat penting untuk memperkuat klaim di masa depan, terutama di yurisdiksi seperti India di mana pengakuan tergantung pada bukti bahwa hubungan tersebut menyerupai pernikahan.
Tabel 2: Kerentanan Hukum dan Perlindungan Anak bagi Pasangan Kohabitasi di Asia (Kasus Pilihan)
| Yurisdiksi | Pengakuan Legal Hubungan | Hak Properti Pasangan (Pasca-pisah) | Legitimasi & Warisan Anak | Perlindungan Kekerasan Domestik |
| Hong Kong | Tidak Ada (Mitos Common Law Marriage) | Klaim berdasarkan Hukum Properti Umum/Kontrak | Ya, diatur di bawah Ordinance terkait | Ya, dilindungi di bawah Domestic and Cohabitation Relationships Violence Ordinance |
| India | Diakui sebagai “In the Nature of Marriage” (Yudisial) | Ambiguitas Tinggi; Perlu Bukti Kontribusi | Ya, memiliki hak waris penuh atas properti orang tua | Ya, berhak atas perlindungan dan tunjangan (maintenance) di bawah PWDVA |
| Malaysia (Muslim) | Tidak Diakui (Dapat Dikriminalisasi oleh Syariah) | Tidak Ada Perlindungan Statutori Khusus | Perlu Proses Legitimasi | Tergantung yurisdiksi dan status agama |
| Singapura | Tidak Diakui sebagai Perkawinan | Klaim berdasarkan Hukum Kontrak/Trust Properti | Ya, kedua orang tua wajib memberikan maintenance | Perlindungan tersedia |
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Sintesis Temuan Kunci
Tren hidup bersama tanpa pernikahan di Asia adalah manifestasi kompleks dari modernisasi yang cepat dan resistensi budaya yang kuat. Secara umum, kohabitasi di Asia lebih cenderung berfungsi sebagai fase pengujian (trial marriage) yang rasional dan pragmatis, bukan sebagai alternatif permanen terhadap pernikahan, yang masih memegang nilai sosial yang dominan. Fenomena ini didorong oleh:
- Hambatan Ekonomi: Kenaikan biaya pernikahan (seperti caili di Tiongkok dan biaya perumahan di Korea) yang melumpuhkan prospek generasi muda.
- Otonomi Gender: Peningkatan pendidikan wanita yang memicu penolakan terhadap peran gender tradisional dan menuntut hubungan yang lebih setara.
- Lingkungan Urban: Kehidupan vertikal di kota besar menyediakan privasi yang diperlukan untuk menghindari pengawasan keluarga dan komunitas.
Namun, di tengah pertumbuhan tren ini, kerentanan hukum bagi pasangan kohabitasi tetap menjadi masalah krusial. Kerangka hukum di sebagian besar Asia didasarkan pada status formal pernikahan, meninggalkan pasangan yang tidak menikah tanpa hak otomatis atas properti bersama atau warisan, meskipun hak anak-anak cenderung lebih terlindungi.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan analisis terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan hukum, laporan ini mengajukan rekomendasi kebijakan berikut:
Reformasi Institusi Pernikahan dan Peran Gender
Pemerintah di Asia Timur harus mengatasi pendorong struktural penundaan pernikahan. Ini termasuk kebijakan untuk mengurangi beban finansial pernikahan yang tidak rasional (misalnya, menekan biaya caili atau menyediakan insentif perumahan yang setara) dan secara aktif mempromosikan kesetaraan gender dalam pembagian kerja domestik. Membuat pernikahan lebih terjangkau dan setara akan membantu mengintegrasikan kembali generasi muda yang skeptis terhadap institusi tradisional.
Harmonisasi Perlindungan Hukum Fungsional
Yurisdiksi dengan sistem hukum berbasis status (seperti Hong Kong dan Singapura) harus mempertimbangkan penerapan undang-undang yang memberikan perlindungan fungsional minimal bagi pasangan yang telah hidup bersama untuk jangka waktu yang signifikan. Perlindungan ini harus mencakup hak-hak dasar, seperti pembagian aset yang diperoleh bersama selama masa kohabitasi dan tunjangan dukungan untuk pasangan yang secara finansial dependen, untuk mengurangi kerentanan ekstrem pasca-perpisahan.
Edukasi dan Advokasi Kontrak
Pemerintah dan lembaga nirlaba harus meningkatkan kesadaran publik mengenai kerentanan hukum kohabitasi dan mendorong penggunaan alat mitigasi risiko. Ini termasuk advokasi ekstensif tentang pentingnya menyusun Perjanjian Kohabitasi (Cohabitation Agreements) yang jelas serta membuat surat wasiat, terutama untuk melindungi hak waris pasangan di yurisdiksi yang ambigu secara hukum (seperti India).
Meninjau Ulang Regulasi Moral (Moral Law Review)
Di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki hukum agama yang kuat (Malaysia, Indonesia), perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap regulasi yang mengkriminalisasi kohabitasi. Meskipun perlindungan moral komunitas penting, kerangka hukum harus menyeimbangkan hal tersebut dengan hak-hak pribadi dan otonomi individu. Penggunaan delik aduan dalam KUHP Indonesia harus dipantau untuk memastikan bahwa itu tidak digunakan secara eksploitatif untuk melanggar privasi individu yang memilih untuk hidup bersama.