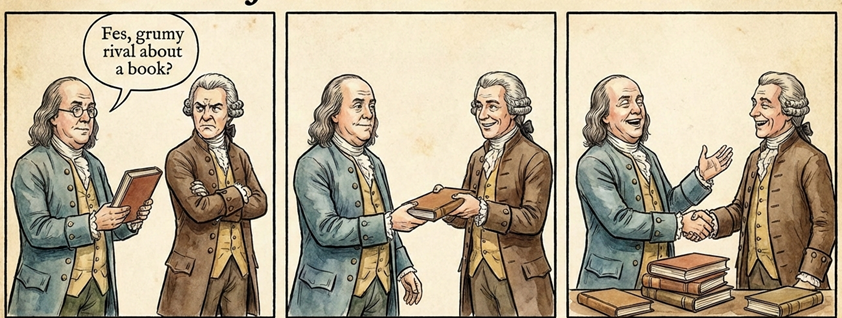Tren Plant-Based Food Lokal Indonesia: Dari Kearifan Lokal Hingga Inovasi Pasar Modern
Tren pangan berbasis nabati (Plant-Based Food, PBF) di Indonesia menunjukkan karakteristik pasar yang hibrida, berdiri di atas fondasi protein nabati tradisional yang kuat sekaligus didorong oleh permintaan produk alternatif modern (alt-meat dan dairy alternatives). Pangan nabati lokal (PNL), seperti Tempe dan Tahu, telah lama menjadi sumber protein utama dan terjangkau di nusantara. Pasar PBF modern diproyeksikan tumbuh pesat. Analisis menunjukkan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) pasar Makanan dan Minuman Nabati Indonesia berkisar antara 7.02% hingga 9.18% hingga tahun 2033. Kedelai tetap menjadi bahan baku dominan, namun inovasi yang memanfaatkan biodiversitas lokal non-kedelai, seperti jamur dan nangka, menjadi kunci diferensiasi. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, investasi strategis harus difokuskan pada peningkatan kualitas sensorik produk PBF modern agar dapat mengatasi hambatan utama konsumen, yaitu rasa dan harga. Selain itu, pemanfaatan saluran on-trade (restoran dan katering) terbukti efektif sebagai alat pemasaran strategis untuk memperkenalkan dan memvalidasi produk premium kepada konsumen arus utama.
Pendahuluan: Definisi dan Paradigma Pangan Nabati Indonesia
Konteks Global vs. Konteks Lokal: Mendefinisikan Plant-Based
Secara global, Plant-Based Diet (PBD) didefinisikan sebagai pola makan yang mengutamakan konsumsi makanan yang berasal dari tanaman—seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan susu nabati—meskipun masih memungkinkan konsumsi makanan hewani dalam jumlah yang sangat terbatas (fleksitarian). Di pasar Barat, transisi ke PBD sering didorong oleh faktor etika atau lingkungan.
Sebaliknya, di Indonesia, konsep pangan nabati telah terintegrasi dalam kearifan lokal selama berabad-abad. Pangan nabati bukan merupakan tren baru, melainkan telah menjadi bagian integral dari identitas kuliner dan sumber protein esensial bagi mayoritas penduduk. Tempe, makanan fermentasi asli Jawa, adalah contoh utama PNL yang telah menjadi kearifan lokal dunia. PNL di Indonesia secara inheren terkait dengan ketersediaan pangan lokal, ekonomi, dan biaya, menyediakan protein yang sangat bergizi dengan harga yang sangat ekonomis.
Dualitas Konsumsi Protein: Paradoks Sosio-Ekonomi
Pola konsumsi protein di Indonesia menunjukkan dualisme yang dipengaruhi kuat oleh status sosial-ekonomi (SES) dan tingkat urbanisasi. Kelompok masyarakat dengan SES yang lebih rendah cenderung memiliki frekuensi konsumsi protein nabati yang lebih tinggi, terutama yang bersumber dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Konsumsi ikan juga lebih sering dilaporkan oleh populasi pulau pedesaan dan kelompok dengan pendapatan serta pendidikan yang lebih rendah di Indonesia, yang berfungsi sebagai sumber protein tradisional berkualitas tinggi.
Kontrasnya, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan modernisasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berkorelasi dengan frekuensi konsumsi protein hewani, khususnya unggas, daging merah, telur, dan produk susu yang lebih tinggi. Daging dan produk hewani sering kali dipandang sebagai simbol status dan aspirasi modern. Oleh karena itu, ketika pasar PBF modern menawarkan produk alt-meat premium, mereka tidak hanya bersaing dengan daging dalam hal profil nutrisi dan rasa, tetapi juga melawan nilai aspirasi dan status yang melekat pada konsumsi hewani. Produk PBF modern yang berhasil harus diposisikan sebagai pilihan superior yang didorong oleh kesadaran nutrisi dan etika, alih-alih sekadar pengganti yang lebih murah, untuk menarik kelompok SES menengah ke atas yang menjadi target pasar utama produk alternatif premium.
Pilar Tradisional: Tinjauan Mendalam atas Staples Nabati Lokal
Tempe: Kekuatan Fermentasi, Fungsionalitas, dan Budaya
Tempe adalah fondasi historis pangan nabati Indonesia dan studi kasus yang luar biasa mengenai produk PBF yang sukses secara global. Tempe diproduksi melalui proses fermentasi kedelai utuh dengan jamur Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae.
Keunggulan Tempe terletak pada profil nutrisinya yang unggul. Berbeda dengan tahu, tempe merupakan produk kedelai utuh yang menghasilkan kandungan protein, serat, dan vitamin yang lebih tinggi. Proses fermentasi secara signifikan meningkatkan daya cerna protein karena memecah strukturnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lebih lanjut, proses ini juga menciptakan probiotik alami, membantu menjaga keseimbangan flora usus, dan menjadikan tempe sebagai pilihan yang ideal bagi mereka yang menjalani diet tinggi protein atau memiliki masalah pencernaan. Secara budaya, tempe memiliki peran yang sangat penting; ungkapan “Tiada hari tanpa tempe” mencerminkan nilai sosial-ekonomi dan kultural yang mendalam. Varian tempe yang difermentasi lebih lama, yaitu tempe semangit, merupakan bumbu khas yang penting dan digunakan dalam setidaknya 28 jenis lauk pauk dan kudapan tradisional Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti sayur lodeh dan bubur tumpang. Minat global yang tinggi terhadap tempe, terutama dari negara-negara seperti Amerika, Australia, dan Belanda, telah meningkatkan nilai produk kearifan lokal ini di panggung internasional.
Pangan Nabati yang Berakar dalam Tradisi Kuliner
Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang secara alami sudah berbasis nabati dan mudah diadaptasi ke gaya hidup vegan/vegetarian tanpa memerlukan formulasi berteknologi tinggi. Hidangan pokok seperti Gado-Gado, yang merupakan salad hangat dengan sayuran, tahu, tempe, kentang rebus, dan saus kacang yang kaya rasa, merupakan contoh hidangan PBF yang bergizi dan populer secara nasional. Demikian pula, hidangan seperti Nasi Goreng dan Mie Goreng dapat dengan mudah diubah menjadi sepenuhnya nabati hanya dengan menghilangkan atau mengganti telur dan kerupuk yang mungkin mengandung ikan/udang.
Konsep penggunaan bahan nabati untuk meniru atau menggantikan daging juga bukan hal baru. Kuliner tradisional Minangkabau, misalnya, telah lama mengenal Rendang Jengkol atau Rendang Jamur. Penggunaan Sayur Nangka (nangka muda) sebagai komponen utama lauk-pauk, seperti dalam Nasi Padang atau kuliner khas Bali (Balung Nangka), menunjukkan bahwa konsep substitusi tekstur daging sudah ada dalam budaya kuliner. Ketersediaan protein berkualitas tinggi dengan harga yang sangat rendah, seperti yang ditawarkan oleh Tempe dan Tahu, menetapkan patokan yang tinggi bagi produk PBF modern. Produk alt-meat premium harus menawarkan nilai tambah yang signifikan, baik dalam hal replikasi tekstur kompleks (seperti dendeng atau pulled pork vegan) maupun kenyamanan, untuk membenarkan harganya yang jauh lebih mahal. Jika tidak, Tempe akan tetap menjadi pilihan rasional bagi mayoritas konsumen.
Analisis Pasar Plant-Based Modern Indonesia (2024-2033)
Ukuran Pasar dan Proyeksi Pertumbuhan
Pasar makanan dan minuman nabati di Indonesia diperkirakan menunjukkan pertumbuhan yang substansial. Meskipun terdapat variasi dalam metrik nilai pasar (yang mungkin disebabkan oleh perbedaan metodologi valuasi, yaitu apakah pasar tempe/tahu tradisional dimasukkan atau tidak), tren kenaikan terlihat jelas. Nilai pasar diperkirakan mencapai sekitar USD 539.6 Juta pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh dengan CAGR rata-rata 7.02% hingga 9.18% hingga tahun 2033.
Tabel 4.1: Metrik Pasar Utama Makanan dan Minuman Nabati Indonesia (2024-2033)
| Metrik | Estimasi Nilai Pasar (2024) | Proyeksi CAGR | Pangsa Bahan Baku Terbesar (2024) | Segmen Dominan (Form) |
| Data Pasar | USD 539.6 Juta – USD 1.12 Triliun* | 7.02% – 9.18% (2025-2033) | Kedelai (40.04%) | Chilled / Shelf-Stable (85.67%) |
Segmentasi Pasar Berdasarkan Tipe Produk
Kedelai (soy) saat ini memimpin pangsa pasar bahan baku, mencakup 40.04% dari total pasar pangan nabati pada tahun 2024. Namun, di masa depan, protein kacang polong (pea protein) diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang signifikan, diperkirakan mencapai 7.19% CAGR hingga tahun 2030.
Segmen Dairy Alternative Beverages (DABs) adalah pendorong pertumbuhan kunci. Konsumen beralih ke alternatif susu nabati seperti susu kedelai (Soy Milk), susu almond (Almond Milk), dan inovasi lokal lainnya karena alasan kesehatan (terutama intoleransi laktosa) dan kekhawatiran lingkungan terkait produksi susu hewani. Selain itu, produk alternatif seperti es krim non-dairy, keju non-dairy, dan yogurt non-dairy juga semakin melengkapi pilihan yang ada di pasar.
Dalam hal format produk, produk chilled atau shelf-stable mendominasi pasar, menguasai 85.67% pangsa pasar pada tahun 2024. Dominasi ini mencerminkan keterbatasan infrastruktur rantai dingin di Indonesia, di mana produk yang stabil pada suhu ruang atau yang membutuhkan pendinginan ringan lebih mudah didistribusikan ke berbagai wilayah. Meskipun demikian, segmen produk beku diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 7.45%, seiring dengan peningkatan penetrasi freezer rumah tangga dan perluasan ritel modern di area urban kelas menengah.
Struktur Distribusi dan Saluran Penjualan
Saluran off-trade (ritel, supermarket, dan online) merupakan saluran distribusi utama, menguasai 54.33% pangsa pasar pada tahun 2024. Supermarket dan hipermarket berfungsi sebagai titik utama penemuan produk bagi konsumen Indonesia, sementara platform ritel online mengalami pertumbuhan pesat dan menyediakan akses langsung ke konsumen, terutama bagi merek-merek baru.
Meskipun menyumbang volume yang lebih rendah, saluran on-trade (layanan makanan, restoran, dan katering) menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan (6.43% CAGR hingga 2030). Saluran ini memiliki fungsi yang melampaui penjualan. Kemitraan strategis antara merek lokal (misalnya, Green Rebel) dengan rantai restoran besar seperti Starbucks, ABUBA Steak, dan Pepper Lunch berfungsi sebagai titik trial atau pengenalan yang efektif. Dengan memperkenalkan opsi nabati di lingkungan restoran yang tepercaya, keraguan konsumen terhadap rasa dan tekstur produk alt-meat dapat diatasi. Konsumen yang telah mencoba dan menyukai produk di restoran cenderung lebih yakin untuk membelinya dalam bentuk ritel di supermarket, menjadikannya strategi pemasaran yang sangat efektif untuk membangun loyalitas.
Dinamika Konsumen: Motivasi, Barikade, dan Demografi
Pendorong Konsumsi: Kesehatan Fisiologis dan Etika
Adopsi PBF di Indonesia didorong oleh dua kategori motivasi utama:
- Kesehatan Fisiologis (Push Motivation): Ini adalah pendorong utama adopsi makanan nabati di Indonesia. Konsumen memilih PBF karena mencari pola makan yang dianggap lebih sehat, rendah kalori, rendah lemak, dan bebas kolesterol. Faktor krusial lainnya adalah masalah pencernaan dan intoleransi laktosa, yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa Push Motivation (terkait dengan mood atau perasaan yang lebih baik secara fisik) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kesejahteraan subjektif konsumen dibandingkan motivasi eksternal, menegaskan bahwa PBF diadopsi karena memberikan manfaat kesehatan personal yang segera terasa.
- Lingkungan dan Etika (Pull Motivation): Kesadaran terhadap isu lingkungan dan etika, seperti kesejahteraan hewan dan dampak mitigasi perubahan iklim, semakin mempengaruhi keputusan pembelian. Mengurangi konsumsi hewani sangat penting dalam upaya mengurangi emisi karbon global yang berasal dari industri makanan.
Hambatan Kunci (Price Sensitivity dan Sensory Gap)
Meskipun motivasi untuk beralih ke PBF tinggi (73% responden Indonesia menyatakan pernah mengonsumsi makanan nabati per November 2021) , industri ini masih menghadapi tantangan substansial:
- Kesenjangan Sensorik (Sensory Gap): Produk PBF modern di pasar sering kali tidak memiliki visual, rasa, dan tekstur yang meyakinkan, menyebabkan konsumen kembali ke sumber protein hewani.
- Sensitivitas Harga: Mayoritas konsumen (60%) menginginkan produk PBF memiliki harga yang kompetitif atau sebanding dengan produk berbasis daging. Karena produk alt-meat berteknologi tinggi sering kali diposisikan sebagai premium, memenuhi tuntutan paritas harga menjadi tantangan utama yang menghambat adopsi massal.
Melihat bahwa motivasi internal (kesehatan fungsional yang segera dirasakan) cenderung lebih dominan dibandingkan manfaat etika yang abstrak bagi sebagian besar konsumen, merek PBF harus mengutamakan narasi manfaat kesehatan yang nyata dan dapat diukur. Strategi pemasaran perlu berfokus pada klaim fungsional (misalnya, kaya serat, bebas laktosa, meningkatkan kesehatan usus) yang dapat membenarkan harga premium produk, daripada hanya mengandalkan daya tarik etika lingkungan atau kesejahteraan hewan, kecuali di ceruk pasar vegan/vegetarian inti.
Tabel 5.1: Matriks Motivasi Konsumen Indonesia dalam Adopsi Plant-Based
| Kategori Motivasi | Sifat Motivasi | Contoh Lokal Kunci | Implikasi Strategis |
| Kesehatan Fisiologis | Internal (Push) | Bebas Laktosa, Kesehatan Pencernaan | Pemasaran harus fokus pada klaim fungsional (solusi masalah kesehatan), bukan hanya klaim nutrisi abstrak. |
| Etika/Lingkungan | Eksternal (Pull) | Kesejahteraan Hewan, Dampak Iklim | Mendorong inovasi natural content dan transparansi sumber bahan baku. |
Inovasi Produk Lokal: Diferensiasi Melalui Biodiversitas Indonesia
Keunggulan kompetitif jangka panjang bagi industri PBF Indonesia terletak pada pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal yang melimpah dan belum sepenuhnya tereksplorasi, beralih dari ketergantungan tunggal pada kedelai impor.
Pengembangan Daging Alternatif Berbasis Non-Kedelai
Inovasi yang memanfaatkan bahan baku asli Indonesia memungkinkan replikasi rasa dan tekstur comfort food Asia secara autentik:
- Nangka Muda (Artocarpus heterophyllus): Nangka muda adalah bahan lokal yang sangat potensial karena secara alami memiliki tekstur berserat yang sangat mirip dengan daging yang direbus atau dimasak lambat (pulled/shredded meat). Nangka telah digunakan dalam masakan seperti Balung Nangka (hidangan iga Balinese dengan nangka) dan Sayur Nangka. Merek lokal memanfaatkan nangka untuk menciptakan rendang dan dendeng vegan. Selain itu, tanaman nangka juga memiliki sifat farmakologis sebagai anti-inflamasi dan antioksidan, yang menambah nilai fungsionalnya.
- Jamur: Jamur, khususnya jenis dengan kaki yang padat (kaki jamur), digunakan secara luas oleh perusahaan teknologi pangan lokal seperti Meatless Kingdom. Kemampuan jamur untuk meniru tekstur padat dan berserat menjadikannya bahan utama untuk produk pengganti daging yang kompleks, seperti dendeng cabai, rendang jamur, dan rempela vegan.
- Inovasi Tempe Lanjut: Tempe, sebagai bahan baku utama, terus diinovasi menjadi format modern dan serbaguna. Contohnya termasuk pengembangan Tempe Meatball sebagai alternatif daging nabati yang lezat dan bergizi , serta Garam Bumbu Tempe, yang dikeringkan dan dihaluskan sebagai alternatif bumbu makanan non-MSG. Inovasi ini meningkatkan nilai ekonomi dan fungsional tempe.
Inovasi Minuman Nabati dari Sumber Lokal
Minuman alternatif susu juga mengalami diversifikasi, memanfaatkan kacang-kacangan dan umbi-umbian lokal yang lebih ekonomis dan melimpah:
- Kacang Hijau (Mung Bean): Kacang hijau dimanfaatkan sebagai alternatif susu sapi dan kedelai karena kaya nutrisi dan relatif ekonomis. Kacang hijau telah diolah menjadi produk turunan, termasuk Susu Kental Manis Nabati dan yogurt nabati.
- Umbi-umbian (Tubers): Umbi lokal, seperti singkong, uwi putih (Dioscorea alata), dan ubi jalar ungu, dieksplorasi sebagai bahan dasar untuk susu prebiotik dan substitusi tepung. Pemanfaatan umbi-umbian tidak hanya mengurangi ketergantungan pada kedelai atau biji-bijian impor tetapi juga menawarkan potensi manfaat kesehatan tambahan (misalnya, sebagai sumber prebiotik).
Tabel 6.1: Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Non-Kedelai dalam Inovasi Plant-Based Indonesia
| Bahan Baku Lokal | Kategori Aplikasi Modern | Contoh Produk Inovasi | Keunggulan Kompetitif Lokal |
| Nangka Muda (Artocarpus heterophyllus) | Daging Alternatif (Pulled/Shredded) | Rendang Nangka Vegan, Pulled Nangka BBQ | Tekstur berserat alami, integrasi mudah dengan bumbu tradisional (rendang). |
| Jamur (Kaki Jamur, Shiitake) | Daging Alternatif (Mimic Meat) | Dendeng Cabai Jamur, Rempela Vegan, Sosis | Tekstur yang padat, sumber protein berteknologi pangan lokal. |
| Kacang Hijau (Vigna radiata) | Alternatif Susu & Fermentasi | Yogurt Sari Kacang Hijau, SKM Nabati | Nilai gizi tinggi, ekonomis, sumber lokal berlimpah. |
| Umbi-umbian (Singkong, Uwi) | Alternatif Susu & Tepung | Susu Prebiotik Singkong, Substitusi Tepung Uwi | Diversifikasi bahan baku, potensi prebiotik, dukungan petani lokal. |
Regulasi, Tantangan, dan Rekomendasi Strategis
Lingkungan Regulasi BPOM
Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengatur ketat klaim dan pelabelan produk pangan berbasis nabati, terutama yang berorientasi vegan. Produk makanan vegan kemasan dikategorikan sebagai produk risiko tinggi dalam pendaftaran BPOM.
Regulasi BPOM Nomor 31 Tahun 2018 mengharuskan klaim vegan (logo atau tulisan) harus dibuktikan melalui analisis DNA yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi atau ditunjuk pemerintah, guna memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan makanan berbasis hewani, termasuk madu. Selain itu, produsen wajib menyertakan Informasi Nilai Gizi (ING) pada label dan mematuhi skema pendaftaran klaim pangan, di mana kata “vegan” hanya boleh dicantumkan pada label, bukan pada nama jenis makanan. Regulasi ini memastikan transparansi dan keaslian produk bagi konsumen yang termotivasi oleh faktor diet atau etika.
Peluang Bisnis dan Keunggulan Kompetitif Lokal
Wirausaha lokal memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam mengembangkan PBF dibandingkan dengan produk hewani:
- Biaya Bahan Baku yang Lebih Rendah: Bahan baku nabati lokal, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran, cenderung lebih murah dan mudah diperoleh dari petani lokal dibandingkan dengan bahan hewani, yang memungkinkan wirausaha mencapai margin keuntungan yang lebih besar.
- Kemudahan Pengolahan dan Penyimpanan: Makanan awetan dari bahan nabati seringkali lebih mudah diolah dan disimpan tanpa memerlukan teknologi pendinginan ekstrem atau rantai dingin yang canggih. Hal ini sangat menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin belum memiliki peralatan industri skala besar.
- Fleksibilitas Inovasi: Bahan nabati dapat diolah menjadi berbagai varian produk yang menarik dan beragam, memberikan fleksibilitas tinggi bagi inovator untuk menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan pasar yang terus berubah.
Rekomendasi Strategis untuk Pertumbuhan Pasar
Berdasarkan analisis pasar, motivasi konsumen, dan tantangan yang dihadapi, berikut adalah rekomendasi strategis untuk mendorong pertumbuhan pasar PBF lokal:
- R1: Peningkatan Investasi dalam Teknologi Sensorik dan R&D: Industri harus mengalihkan fokus R&D dari sekadar pengganti nutrisi menjadi penyempurnaan kualitas sensorik (rasa, tekstur, aroma). Penggunaan biodiversitas lokal (seperti nangka dan jamur) harus dioptimalkan melalui teknologi pangan untuk menciptakan replika daging yang meyakinkan, mengatasi sensory gap yang menjadi penghalang utama konsumen.
- R2: Memanfaatkan Saluran On-Trade untuk Validasi Produk: Kemitraan strategis dengan jaringan restoran besar (Quick Service Restaurants dan Fine Dining) harus diperluas. Saluran on-trade berfungsi sebagai media pemasaran yang efektif untuk memvalidasi kualitas produk di mata konsumen, mendorong trial, dan pada akhirnya, meningkatkan pembelian di saluran ritel (off-trade).
- R3: Prioritas Pemasaran Kesehatan Fungsional: Mengingat motivasi kesehatan fisiologis lebih dominan bagi konsumen arus utama, komunikasi pemasaran harus menekankan manfaat kesehatan fungsional yang nyata (misalnya, gut health, bebas laktosa, rendah lemak jenuh) untuk membenarkan harga premium. Fortifikasi produk dengan vitamin dan mineral juga harus ditonjolkan untuk meningkatkan daya tarik nutrisi.
- R4: Bio-Inovasi dan Integrasi Rantai Pasok: Mendorong penelitian dan komersialisasi sumber nabati non-kedelai lokal (umbi-umbian, kacang hijau, nangka) untuk membangun keunggulan kompetitif unik yang berbasis pada kekayaan hayati Indonesia. Integrasi rantai pasok dengan petani lokal akan membantu menjamin stabilitas biaya bahan baku dan mendukung ekonomi lokal.
Kesimpulan
Pasar plant-based food lokal di Indonesia adalah ekosistem yang dinamis, didukung oleh warisan pangan tradisional (Tempe, Tahu) dan didorong oleh gelombang inovasi modern. Pertumbuhan pasar yang diproyeksikan kuat (CAGR 7.02%–9.18%) menunjukkan pergeseran perilaku konsumen menuju pilihan yang didorong oleh kesehatan pribadi dan kepedulian lingkungan.
Tantangan utama pasar adalah mengatasi kesenjangan harga dan kualitas sensorik produk alt-meat premium agar dapat bersaing dengan daging, yang masih dianggap sebagai simbol status sosial. Keberhasilan di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan inovator lokal untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia (Nangka, Jamur) untuk menciptakan produk alt-meat dan dairy alternatives yang otentik, bergizi, dan relevan secara kultural. Dengan strategi yang berfokus pada kesehatan fungsional dan memanfaatkan saluran on-trade sebagai katalis adopsi, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk tidak hanya memenuhi permintaan domestik yang terus meningkat tetapi juga menjadi pemimpin global dalam menyediakan solusi PBF Asia yang berakar pada kearifan lokal.