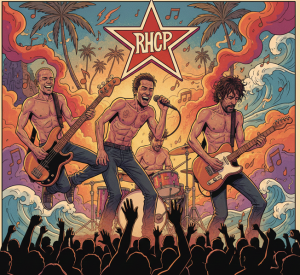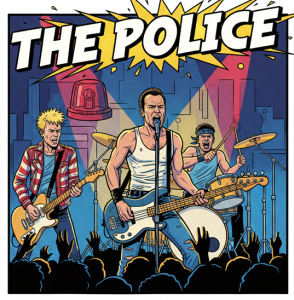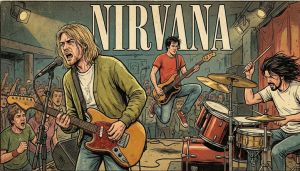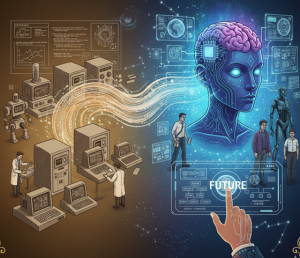Slow Fashion vs Fast Fashion dalam Konteks Keberlanjutan Global
Konteks Krisis Keberlanjutan dalam Industri Tekstil
Industri fesyen modern saat ini berada di persimpangan jalan kritis akibat dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Data menunjukkan bahwa sektor ini telah tumbuh menjadi salah satu penyumbang polusi industri terbesar secara global. Industri fesyen bertanggung jawab atas 10% polusi global dan, menurut perkiraan lain, menghasilkan 8% emisi karbon global, angka yang secara mengejutkan melampaui gabungan emisi dari sektor penerbangan dan pelayaran internasional.
Skala polusi ini menempatkan sektor tekstil pada titik krisis makroekonomi dan lingkungan, memaksa evaluasi ulang model bisnis tradisional yang linier (produksi-pakai-buang). Urgensi ini mendorong perlunya pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih sirkular dan regeneratif, menjadikan perdebatan antara Mode Cepat (Fast Fashion, FF) dan Mode Lambat (Slow Fashion, SF) sebagai isu sentral dalam agenda keberlanjutan. Fakta bahwa emisi fesyen melampaui sektor transportasi global menggarisbawahi bahwa masalah ini telah bertransisi dari sekadar pilihan konsumen individu menjadi masalah infrastruktur global yang menuntut intervensi regulasi di tingkat tertinggi.
Fast Fashion (FF) didefinisikan sebagai model bisnis yang bertujuan untuk membawa koleksi yang meniru tren terbaru ke pasar secepat dan semurah mungkin. Produksi dilakukan secara massal dengan kualitas rendah dan harga sangat terjangkau, didorong oleh dorongan konsumen untuk membeli produk terbaru. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan melalui volume penjualan yang tinggi dan siklus perputaran stok yang cepat.
Slow Fashion (SF) adalah antitesis langsung dari FF, sekaligus menjadi konsep sentral dalam gerakan mode berkelanjutan. SF mengadvokasi sistem manufaktur yang menghormati manusia, lingkungan, dan kesejahteraan hewan, berfokus pada strategi desain, produksi, konsumsi, penggunaan, dan penggunaan kembali yang etis dan berkelanjutan SF mewakili model bisnis yang berpusat pada etika, memperlambat konsumerisme, dan menghargai lingkungan, berlawanan dengan praktik industri FF yang mengeksploitasi sumber daya murah dan tenaga kerja.
Analisis mendalam menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas: peningkatan kecepatan produksi secara sistemik setara dengan penurunan nilai kualitas. Kecepatan produksi yang ekstrem, yang dapat mencapai 24 koleksi per tahun, secara inheren memaksa penggunaan bahan baku yang lebih murah dan proses yang dipercepat. Hal ini secara sistemik menurunkan standar kualitas pakaian, menjadikannya ‘disposable’ (sekali pakai) dalam persepsi konsumen, yang merupakan prasyarat kegagalan model bisnis FF dalam konteks keberlanjutan sejati.
Anatomi Fast Fashion: Mekanisme dan Dampak Ekonomi
Model Bisnis Quick Response (QR) dan Hiper-Produksi
FF dipelopori oleh pengecer besar seperti Zara dan H&M, yang mendefinisikan kembali lanskap ritel global. Model ini sukses karena kemampuannya memanfaatkan produksi Quick Response (QR) dan integrasi vertikal. QR memungkinkan waktu dari desain hingga pakaian diletakkan di rak toko dikurangi secara drastis, dari berbulan-bulan menjadi hitungan minggu.
Dalam lima belas tahun pertama abad ke-21, produksi pakaian global meningkat dua kali lipat. Percepatan ini tercermin dalam peningkatan tajam siklus tren. Merek-merek Eropa yang dulunya merilis dua koleksi per tahun (musim panas/dingin) kini merilis sebanyak 24 koleksi per tahun, atau 50 hingga 100 microseasons. Percepatan ini didorong oleh meniru tren yang sedang populer di kalangan selebriti dan desainer, lalu memproduksi imitasinya dalam waktu sesingkat mungkin.
Analisis Harga Rendah dan Kualitas Rendah sebagai Strategi Pasar
Strategi utama FF adalah menawarkan harga yang sangat terjangkau, membuat pakaian trendi dapat diakses oleh berbagai kalangan konsumen. Namun, keberlanjutan strategi harga rendah ini bergantung pada dua faktor: produksi massal dan kualitas rendah. Kualitas rendah secara sengaja memperpendek umur pakaian, secara efektif mengubah pakaian dari produk investasi jangka panjang menjadi komoditas sekali pakai. Konsumen dikondisikan untuk melihat pakaian sebagai barang sekali pakai, yang secara langsung memicu pembelian impulsif dan laju pembuangan yang tinggi.
Akibat dari perubahan nilai ini, tingkat pemanfaatan pakaian menurun hingga 36% antara tahun 2003 dan 2018. Parahnya, sepertiga wanita muda percaya bahwa suatu pakaian dianggap ‘usang’ setelah hanya dipakai satu atau dua kali. Hal ini menghasilkan 300.000 ton pakaian dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Inggris setiap tahun, menjadikannya industri limbah yang tumbuh paling cepat di sana.
Greenwashing Fast Fashion: Inkompatibilitas dengan Keberlanjutan Sejati
Meskipun banyak merek FF melakukan upaya greenwashing melalui klaim keberlanjutan, atau penggunaan label “eco” atau “green”, model bisnis inti mereka secara fundamental tidak kompatibel dengan keberlanjutan yang sejati.
Paradoks yang muncul adalah: bahkan ketika merek FF mengklaim menggunakan bahan daur ulang, skala overproduction dan tingkat pembuangan yang masif meniadakan setiap potensi manfaat lingkungan yang diklaim. Kecepatan Quick Response (QR) yang sukses dalam logistik, ketika diterapkan pada manufaktur global, justru menciptakan tekanan yang tak terhindarkan pada rantai pasok hilir (pabrik) untuk menjaga biaya tetap rendah. Tekanan ini seringkali diselesaikan melalui eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, greenwashing dalam FF hanya menutupi masalah struktural inti yang melibatkan volume, bukan material.
Biaya Lingkungan (The Planetary Toll): Jejak Fast Fashion
Dampak lingkungan dari Fast Fashion bersifat sistemik, mempengaruhi iklim, air, dan tanah di seluruh dunia.
Jejak Karbon dan Emisi Gas Rumah Kaca (GHG)
Industri fesyen secara keseluruhan bertanggung jawab atas 1.2 miliar ton emisi karbon setiap tahun. Dengan menyumbang antara 8% hingga 10% dari total emisi karbon global, industri ini menghasilkan lebih banyak CO2 daripada gabungan penerbangan internasional dan pelayaran. Emisi ini berasal dari seluruh siklus hidup garmen, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga berakhir di TPA. Skala emisi ini menegaskan bahwa mitigasi dalam sektor tekstil adalah urgensi iklim.
Konsumsi dan Polusi Air: Tekanan pada Sumber Daya Global
Industri fesyen diakui sebagai industri paling intensif air kedua di dunia, mengkonsumsi sekitar 79 miliar meter kubik air per tahun, atau bahkan 93 miliar meter kubik menurut data lain.
Angka kuantitatif yang paling kritis adalah kebutuhan air untuk produksi kapas. Kapas, yang merupakan serat alami paling umum, membutuhkan 7.000 hingga 29.000 liter air untuk memproduksi satu kilogram kapas mentah. Untuk memproduksi satu kaus katun rata-rata, dibutuhkan 2.700 liter air—jumlah yang cukup untuk diminum oleh satu orang selama 2,5 tahun. Praktik pertanian kapas yang intensif air ini menyebabkan tekanan air yang ekstrem di wilayah yang sudah kekurangan air, seperti kasus Laut Aral yang hampir menghilang akibat pengalihan air untuk irigasi kapas.
Selain konsumsi air, sekitar 20% polusi air industri global berasal dari pewarnaan dan perawatan tekstil. Proses ini melibatkan penggunaan sekitar 8.000 bahan kimia sintetis. Setelah digunakan, air yang terkontaminasi tersebut (limbah cair) dibuang ke saluran air, terutama di negara berpenghasilan rendah hingga menengah (LMICs) seperti Tiongkok dan India, menyebabkan kerusakan lingkungan parah dan risiko kesehatan bagi komunitas lokal.
Krisis Limbah Tekstil dan Kolonialisme Sampah (Waste Colonialism)
Perilaku konsumsi telah berubah drastis: rata-rata konsumen sekarang membeli 60% lebih banyak pakaian dibandingkan tahun 2000, tetapi setiap pakaian disimpan hanya setengah lebih singkat. Karena kualitasnya yang rendah dan desainnya yang cepat usang, pakaian FF dengan cepat dianggap sebagai limbah. Di Uni Eropa, sekitar 12 kg pakaian per orang dibuang setiap tahun. Meskipun diyakini bahwa 95% pakaian yang dibuang ke TPA dapat digunakan kembali atau di-upcycle, kenyataannya kurang dari setengah pakaian bekas dikumpulkan untuk digunakan kembali, dan hanya 1% yang didaur ulang menjadi pakaian baru.
Isu limbah ini diperburuk oleh fenomena Waste Colonialism (Kolonialisme Sampah), di mana negara-negara maju (Global North) mengeksternalisasi biaya lingkungan mereka ke negara-negara Global South. Contoh mencolok terjadi di Accra, Ghana, di mana 15 juta item pakaian bekas tiba setiap minggunya di Pasar Kantamanto. Karena mayoritas pakaian FF impor ini berkualitas sangat rendah, pakaian tersebut tidak dapat dijual kembali. Akibatnya, jutaan garmen ini berakhir sebagai gunung sampah raksasa atau dibakar, melepaskan asap beracun. Limbah tekstil ini juga menyumbat jalur air, mencemari Korle Lagoon dengan mikroplastik yang bahkan kini ditemukan dalam stok ikan dan ASI.
Kegagalan sistem sirkular saat ini, di mana hanya 1% pakaian didaur ulang kembali menjadi pakaian baru, menyoroti bahwa solusi teknologi dan infrastruktur daur ulang serat-ke-serat masih jauh tertinggal dibandingkan laju produksi FF.
Tabel 3.1. Metrik Dampak Lingkungan Industri Fashion (Didominasi Fast Fashion)
| Indikator Dampak | Data Kuantitatif (Estimasi Tahunan) | Keterangan Signifikan |
| Emisi Karbon Global | 8% hingga 10% dari emisi global | Melebihi gabungan emisi penerbangan internasional dan pelayaran. |
| Total Konsumsi Air | 93 miliar meter kubik per tahun | Menimbulkan tekanan besar pada sumber daya air global. |
| Kebutuhan Air per Kaos Katun | 2,700 liter | Setara dengan air minum satu orang selama 900 hari. |
| Polusi Air Industri | 20% polusi air industri global | Terutama dari pewarnaan dan pemrosesan tekstil (penggunaan 8.000 zat kimia). |
| Tingkat Daur Ulang Pakaian ke Pakaian Baru | Hanya 1% | Menyoroti ketidakmampuan sistem saat ini dalam mencapai sirkularitas sejati. |
Biaya Sosial dan Etika (The Human Cost) Fast Fashion
Model bisnis FF secara fundamental bergantung pada eksternalisasi biaya produksi, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada tenaga kerja.
Eksploitasi Tenaga Kerja di Rantai Pasok Global
Sekitar 90% dari produksi pakaian global dialihdayakan ke LMICs, di mana barang-barang ini diproduksi dengan cepat dan biaya murah. Eksploitasi tenaga kerja dalam industri FF menjadi isu yang marak. Isu-isu etika utama meliputi upah yang tidak adil (seringkali di bawah upah minimum), kurangnya jaminan kesehatan dan keselamatan, jam kerja yang berlebihan, kekerasan fisik, dan penghambatan upaya pembentukan serikat pekerja.
Di negara-negara penghasil produk, seperti Bangladesh, pekerja seringkali tidak menerima upah minimum meskipun tuntutan produksi massal harus dipenuhi dengan cepat. Film dokumenter seperti “The True Cost” dan “Nike Sweatshops” mengkonfirmasi bahwa mekanisme eksploitasi ini terjadi di berbagai lokasi, termasuk Bangladesh dan Indonesia, dengan aspek dominan eksploitasi yang bervariasi dari upah hingga keselamatan kerja.
Keterkaitan antara Kecepatan Produksi dan Pelanggaran Etika
Terdapat korelasi terbalik yang kuat antara kecepatan siklus produksi dan standar etika. Semakin cepat siklus Quick Response FF, semakin besar tekanan yang diberikan pada pabrik pemasok untuk memenuhi batas waktu yang ketat. Tekanan waktu ini diterjemahkan menjadi pemotongan biaya operasional, yang hampir selalu mengorbankan upah, keselamatan, dan kondisi kerja para pekerja. Konsumen FF sering kali tidak menyadari biaya manusia yang tertanam dalam produk yang mereka beli.
Selain itu, eksploitasi ini tidak hanya disebabkan oleh keserakahan korporat, tetapi juga didukung oleh konteks ekonomi, sosial, dan politik tertentu, serta kebijakan ketenagakerjaan di negara-negara penghasil. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah eksploitasi menuntut perubahan kebijakan di tingkat makro LMICs, bukan sekadar audit yang dilakukan oleh merek-merek Barat.
Slow Fashion: Antitesis dan Prinsip Keberlanjutan Holistik
Slow Fashion (SF) menawarkan jalan keluar dari siklus destruktif Fast Fashion, berpusat pada filosofi intensionalitas dan produksi yang etis.
Filosofi Kualitas, Durabilitas, dan Desain Timeless
SF mendorong konsumen untuk menjauhi gaya yang cepat berlalu yang didikte oleh siklus musiman FF. Sebaliknya, SF berfokus pada kualitas tinggi, konstruksi yang kuat, dan desain timeless atau klasik yang melampaui tren musiman. SF memungkinkan konsumen untuk membangun lemari pakaian yang serbaguna dan tahan lama, yang tidak hanya mencerminkan identitas dan nilai pribadi tetapi juga mengurangi kebutuhan untuk membeli secara terus-menerus.
Filosofi ini mencakup seluruh siklus hidup pakaian, di mana perawatan, perbaikan, perubahan, dan penyimpanan pakaian yang benar menjadi bagian integral untuk memaksimalkan umur pakai dan mengurangi limbah. Pergeseran ini membutuhkan konsumen untuk melangkah mundur dari budaya kepuasan instan FF dan mengajukan pertanyaan mendalam sebelum membeli: “Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Apakah item ini dibuat secara bertanggung jawab?”.
Model Produksi Etis dan Transparansi Rantai Pasok
Berlawanan dengan praktik alih daya FF, SF melibatkan pengrajin lokal (local artisans) dan menjaga produksi dalam ‘komunitas produktif’. Model ini membatasi intermediasi, membuat proses produksi lebih transparan, dan memberikan nilai budaya serta material yang lebih besar kepada konsumen.
SF secara inheren memiliki margin waktu yang lebih besar dalam siklus produksi (umumnya 6-12 bulan, berbanding 2-4 minggu pada FF), yang memungkinkan perhatian yang lebih detail terhadap praktik etika. Merek-merek SF seperti Nudie Jeans dan Everlane berkomitmen untuk memastikan upah yang adil (fair wages) dan kondisi kerja yang aman, serta memberikan transparansi penuh mengenai rantai pasok mereka. Dengan mendukung produsen skala kecil dan kerajinan, SF juga memupuk ketahanan ekonomi di tingkat lokal.
Internalisasi Biaya dan Material Berkelanjutan
SF secara konsisten menggunakan material yang ramah lingkungan, organik, atau daur ulang. Pilihan material yang progresif dan desain abadi adalah inti dari model ini.
Harga jual SF yang lebih tinggi mencerminkan internalisasi biaya lingkungan dan sosial—yaitu, biaya penuh (upah yang adil, material berkelanjutan, dan proses non-polutif) telah dimasukkan ke dalam harga produk. Ini merupakan refleksi ekonomi yang jauh lebih jujur dibandingkan model FF yang menyembunyikan biaya tersebut melalui eksternalisasi dampak negatif.
Analisis Komparatif Kuantitatif dan Kualitatif
Perbandingan antara Fast Fashion dan Slow Fashion menunjukkan perbedaan fundamental yang melampaui sekadar harga.
Metrik Kualitas dan Daya Tahan Produk
Kualitas merupakan pembeda utama. Produk FF dicirikan oleh kualitas yang rendah, umur pakai yang sangat pendek, dan penggunaan material murah (seringkali sintetis) yang dirancang untuk cepat ketinggalan tren.
Sebaliknya, produk SF diprioritaskan untuk memiliki kualitas dan konstruksi yang tinggi, memastikan daya tahannya. Filosofi desainnya yang abadi memungkinkan pakaian SF tetap relevan terlepas dari perubahan musiman.
Evaluasi Ekonomi Konsumen: Konsep Cost Per Wear (CPW)
Meskipun pakaian SF memiliki harga awal yang lebih mahal, analisis ekonomi konsumen harus berdasarkan konsep Cost Per Wear (CPW), atau biaya per pemakaian, yang merupakan nilai yang dinilai berdasarkan frekuensi penggunaan dibandingkan harga awal.
Dengan daya tahan dan umur pakai yang jauh lebih lama, pakaian SF memberikan nilai ekonomi jangka panjang yang unggul, menghasilkan CPW yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan FF. Pakaian FF, meskipun harganya murah saat dibeli, memiliki CPW yang tinggi karena sifatnya yang cepat dibuang. SF mendorong investasi dalam lemari pakaian yang lebih sedikit tetapi lebih baik, menghemat waktu, uang, dan stres yang tidak perlu akibat siklus konsumsi yang terus-menerus.
Tabel 6.1. Perbandingan Komprehensif Model Bisnis: Fast Fashion vs. Slow Fashion
| Aspek Kunci | Fast Fashion (Mode Cepat) | Slow Fashion (Mode Lambat) |
| Filosofi Inti | Hiper-konsumsi, Tren Cepat, Harga Rendah, Kepuasan Instan. | Intensionalitas, Etika, Kualitas, Timeless Style. |
| Siklus Desain-ke-Rak | Sangat Cepat (2-4 minggu); Hingga 24 koleksi/tahun. | Lambat dan Terukur (6-12 bulan); Fokus pada daya tahan. |
| Kualitas & Daya Tahan | Rendah, bahan murah (sering sintetis), umur pakai sangat pendek. | Tinggi, fokus pada konstruksi dan material berkelanjutan/alami. |
| Transparansi Rantai Pasok | Rendah; rantai pasok panjang dan kompleks, memfasilitasi eksploitasi. | Tinggi; transparansi penuh tentang asal-usul dan praktik kerja. |
| Nilai Ekonomi Konsumen (CPW) | Harga awal murah, tetapi Cost Per Wear (CPW) tinggi karena cepat dibuang. | Harga awal tinggi, tetapi CPW rendah karena umur pakai panjang |
Jalan ke Depan: Transisi menuju Ekonomi Tekstil Sirkular
Mitigasi dampak FF dan adopsi prinsip SF memerlukan intervensi di tiga tingkatan: perilaku konsumen, regulasi industri, dan inovasi teknologi.
Mengubah Pola Konsumsi dan Mengatasi Limbah
Langkah-langkah berbasis konsumen untuk melawan FF melibatkan pengadopsian praktik reduce, repair, and reuse. Ini termasuk mempelajari keterampilan perbaikan dasar dan up-cycling untuk memperpanjang masa pakai garmen lama.
Thrifting (membeli barang bekas) adalah solusi sederhana namun efektif untuk mengatasi dampak buruk FF dengan memperpanjang siklus hidup produk, terutama di tengah peningkatan drastis jumlah pakaian yang dibuang. Namun, meskipun penting, solusi berbasis konsumen seperti thrifting tidak memadai untuk mengatasi volume limbah skala FF yang masif (misalnya, 15 juta item per minggu di Ghana). Solusi sistemik, yang berfokus pada pengurangan overproduction melalui regulasi produksi, adalah satu-satunya cara untuk memitigasi krisis skala makro.
Tuntutan Regulasi dan Kebijakan Global: European Green Deal (EGD)
Urgensi krisis mode telah mendorong badan-badan internasional untuk bertindak. Uni Eropa (UE) secara aktif mengadopsi regulasi untuk mengurangi limbah tekstil dan meningkatkan siklus hidup produk, sebagai bagian dari tujuan ekonomi sirkular pada tahun 2050.
Inisiatif kunci adalah European Green Deal (EGD), di mana Circular Economy Action Plan (CEP) menempatkan tekstil di garis depan reformasi. EGD memperkenalkan regulasi seperti Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), yang akan memaksa produsen—termasuk pemain kunci industri tekstil global seperti Indonesia—untuk mendesain ulang produk agar lebih tahan lama, mudah diperbaiki, dan dapat didaur ulang.
Regulasi seperti EGD bukan hanya hambatan perdagangan, tetapi juga pendorong keunggulan kompetitif. Perusahaan yang berinvestasi dalam desain berkelanjutan dan mengadopsi prinsip SF akan memiliki keuntungan jangka panjang di pasar global yang semakin diatur.
Strategi Inovasi dan Sistem Produksi Closed-Loop
Transisi ke keberlanjutan menuntut inovasi material dan sistem. SF memelopori penggunaan material berbasis tumbuhan yang progresif dan sistem closed-loop. Meskipun saat ini hanya 1% pakaian didaur ulang menjadi pakaian baru, investasi besar dalam teknologi daur ulang serat-ke-serat harus ditingkatkan secara eksponensial. Tujuannya adalah untuk menciptakan kapasitas infrastruktur yang mampu menangani volume limbah tekstil global, menuju target ekonomi sirkular yang sejati.
Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis
Analisis komparatif antara Fast Fashion dan Slow Fashion menunjukkan bahwa kedua model ini tidak dapat hidup berdampingan dalam kerangka keberlanjutan yang autentik. Fast Fashion, yang didasarkan pada hiper-produksi dan eksternalisasi biaya sosial serta lingkungan, secara fundamental bertentangan dengan kebutuhan planet dan etika global. Slow Fashion, sebaliknya, menawarkan kerangka kerja holistik yang mengintegrasikan etika, kualitas, dan transparansi, merefleksikan biaya produksi yang sesungguhnya.
Sinkronisasi Nilai Konsumen dan Keberlanjutan
Slow Fashion menyediakan jalur bagi konsumen untuk menyelaraskan nilai etika dan lingkungan mereka dengan pilihan berpakaian, memandang pakaian sebagai bentuk ekspresi diri yang didasarkan pada apresiasi yang sadar dan bukan hanya kepuasan instan. Pergeseran ini sangat penting untuk menciptakan permintaan pasar yang berkelanjutan.
Rekomendasi Aksi
Berdasarkan evaluasi kritis ini, rekomendasi strategis berikut disajikan untuk memfasilitasi transisi industri tekstil global:
- Untuk Regulator dan Pembuat Kebijakan:
- Menerapkan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) secara global, yang membebankan biaya pengelolaan limbah dan polusi produk kepada produsen Fast Fashion.
- Mempercepat adopsi kerangka kerja Ecodesign (seperti ESPR), menetapkan standar wajib untuk daya tahan, kemampuan perbaikan, dan daur ulang semua produk tekstil yang memasuki pasar.
- Mengatur klaim greenwashing secara ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas merek.
- Untuk Industri Fast Fashion (Merek Besar):
- Mengurangi drastis volume produksi tahunan dan menghentikan model microseasons.
- Melakukan investasi signifikan dalam peningkatan kualitas produk, dengan garansi minimal 5-10 tahun masa pakai, menggeser fokus dari harga awal rendah ke Cost Per Wear yang rendah.
- Untuk Industri Slow Fashion (Merek Berkelanjutan):
- Terus mendukung transparansi penuh dalam rantai pasok dan praktik etika.
- Mencari cara untuk meningkatkan skalabilitas produksi lokal dan artisanal tanpa mengorbankan kualitas dan nilai-nilai inti.
- Untuk Konsumen:
- Memprioritaskan konsep Cost Per Wear (CPW) di atas harga awal.
- Mengadopsi pola pikir reduce, repair, reuse dan mendukung pasar barang bekas (thrifting) untuk memperpanjang siklus hidup produk.