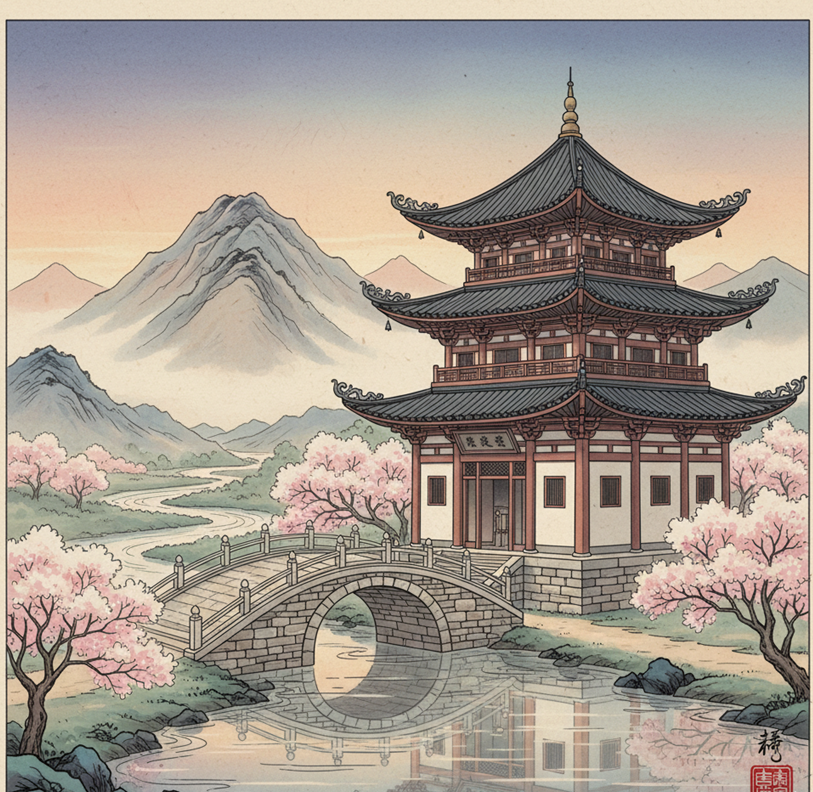Ulasan Arsitektur Asia dari Era Klasik hingga Modernitas
Arsitektur Asia mewakili sebuah mosaik budaya, sejarah, dan lingkungan yang sangat kompleks. Kesulitan dalam merangkumnya dalam satu ciri tunggal timbul dari kenyataan bahwa ia adalah hasil paduan dinamis berbagai tradisi, baik yang bersifat internal regional maupun eksternal, yang berasal dari Eropa, Asia Tengah, dan Timur. Studi arsitektur di benua ini memerlukan pendekatan multidimensi yang melampaui deskripsi struktural semata, melibatkan analisis terhadap fondasi filosofis, adaptasi lingkungan, klasifikasi historis, hingga kontestasi ideologis di era modern.
Sejarah arsitektur di Asia sering dikelompokkan berdasarkan periode waktu—zaman kuno, abad pertengahan, dan modern —dan juga berdasarkan manifestasi keagamaannya. Misalnya, arsitektur India, yang dikenal sebagai Sthapatya-kala atau “seni membangun,” mencakup gaya candi Hindu, arsitektur Islam, klasik barat, dan gaya modern. Namun, yang membedakan arsitektur Asia secara fundamental adalah perannya sebagai cerminan kosmologi. Bangunan di wilayah Asia didesain dengan keyakinan bahwa keindahannya tidak hanya dilihat dari aspek indrawi manusia, tetapi juga dari mitos yang berlaku di lingkungannya. Perspektif ini menciptakan makna ruang yang tidak selalu dapat ditangkap oleh indra belaka, menjadikan bangunan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas, pusat sosial, dan cerminan dinamika budaya masyarakat.
Analisis terhadap tradisi arsitektur Asia menunjukkan bahwa perancangan tidak hanya berpusat pada fungsi, melainkan juga pada batas-batas teologis dan filosofis. Struktur monumental, seperti candi dan istana, seringkali dirancang sebagai makrokosmos yang dapat dihuni, di mana orientasi, pilihan material, dan bahkan sistem rekayasa seperti drainase harus selaras dengan hukum kosmik. Arsitektur di Asia, dengan demikian, berfungsi sebagai representasi ruang total (total space), di mana yang spiritual dan yang material berkoeksistensi.
Fondasi Kosmologi Dan Etis Penciptaan Ruang
Prinsip-prinsip arsitektur Asia diatur oleh fondasi etika dan kosmologi yang dalam, yang secara langsung menentukan hierarki ruang, materialitas, dan interaksi antara manusia dan alam.
Etika Spiritual Asia Selatan (Dharma, Karma, Ahimsa)
Di Asia Selatan, prinsip-prinsip etis yang berasal dari Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme membentuk landasan bagi desain spiritual. Dharma adalah konsep sentral yang mewujudkan gagasan tentang “cara hidup yang benar” dan “jalan kebenaran.” Ini mencakup kewajiban, hak, dan kebajikan moral, berfungsi sebagai prinsip panduan untuk mencapai keharmonisan dan kebenaran. Dalam konteks spiritual, “Jalan Dharma” dalam Buddhisme Mahayana merujuk pada perjalanan menuju pencerahan, sementara dalam Hinduisme (khususnya Vaishnavisme), ia adalah landasan moral dan etika yang diikuti untuk pemenuhan spiritual dan tugas moral.
Prinsip Ahimsa (antikekerasan) merupakan etika moral utama dalam Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme, yang melarang menyakiti makhluk hidup, baik secara fisik maupun emosional. Ahimsa mendorong kepedulian dan belas kasihan, yang secara implisit memengaruhi bagaimana arsitektur berinteraksi dengan lingkungannya dan penghuninya.
Kosmologi ini diterjemahkan ke dalam tata ruang melalui simbolisme:
- Mandala: Simbol spiritual berupa desain geometris yang melambangkan keteraturan kosmos dan digunakan dalam meditasi untuk mencapai fokus, kesatuan, dan keseimbangan. Di Buddhisme Tantrik, mandala merupakan bagian kunci dari praktik meditasi Anuttarayoga Tantra.
- Teratai (Lotus): Melambangkan kemurnian, pencerahan, dan kesucian dalam ajaran Buddha. Simbol ini juga digunakan dalam Hinduisme (Vaishnavisme) untuk menggambarkan keindahan ilahi (misalnya, Mata Teratai atau Tangan Teratai pada dewa-dewi seperti Krishna dan Radha).
Dualitas Filosofis Asia Timur (Konfusianisme dan Taoisme)
Asia Timur, terutama Tiongkok, didominasi oleh dua aliran pemikiran yang kontras namun saling melengkapi, yang memberikan arahan desain yang terstruktur dan organik.
Konfusianisme menekankan harmoni sosial dan etika melalui nilai-nilai seperti Ren (cinta kasih), Li (rituals, kesusilaan), dan Xiao (bakti anak/filial piety). Kontribusi Konfusianisme kepada masyarakat modern terletak pada penekanan tanggung jawab individu dalam masyarakat, bukan hak pribadi, yang bertujuan menciptakan persatuan dan keharmonisan (tianxia yi jia). Implikasi arsitekturalnya adalah pembangunan ruang yang formal, simetris, dan terstruktur dengan poros yang jelas untuk memperkuat hierarki sosial (wulun, lima hubungan) dan otoritas.
Kontrasnya adalah Taoisme, yang mencari harmoni melalui alamiah. Tao adalah Yang-Mutlak, bahan dasar segala sesuatu, yang sederhana, tanpa bentuk, dan geraknya spontan (tzu jan). Ajaran kuncinya adalah Wu Wei (non-aksi), yang berarti “tidak berbuat secara dibuat-buat” (wei), melainkan bertindak selaras dengan alam semesta dan kodrat alamiah murni (Te). Taoisme menolak pandangan bahwa manusia adalah pengada istimewa atau “pusat” segala-galanya, melainkan ko-eksisten dengan makhluk lain. Lao Tzu dalam Tao Te Ching Bab 38 menyiratkan bahwa hilangnya Te (kebajikan alamiah) digantikan secara berturut-turut oleh perikemanusiaan, keadilan, dan akhirnya, ketentuan upacara (Li Konfusianis)—menunjukkan bahwa intervensi sosial yang kaku hanya muncul ketika kemurnian alamiah telah hilang.
Arsitektur Tiongkok klasik menyajikan resolusi spasial terhadap dualitas ini. Struktur politik dan publik yang rigid mencerminkan etika Li Konfusianis, sementara ruang privat, seperti taman klasik dan desain lanskap, menganut estetika Wu Wei yang organik dan fluid. Arsitektur di Asia Timur berfungsi sebagai penyeimbang sosial: ketika masyarakat terlalu terstruktur, estetika alam harus dipanggil untuk memulihkan keharmonisan.
Fondasi Moralitas Islam (Akhlak, Adab, Taqwa) dan Etika Nusantara
Di Asia Tenggara, fondasi etika Islam berfokus pada Taqwa (kesalehan), yang merupakan kunci kedekatan dengan Allah dan berkontribusi pada pembentukan Akhlak (karakter atau moral internal). Akhlak dibedakan dari Adab, di mana Akhlak adalah kondisi mental yang menghasilkan perilaku baik atau buruk, sedangkan Adab cenderung merujuk pada tata krama atau disiplin eksternal. Arsitektur dan praktik Islam dirancang untuk membantu pembentukan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.
Dalam konteks Nusantara, Budi Pekerti (kerangka moral Jawa/Melayu) secara hakiki mencakup lima jangkauan perilaku, salah satunya adalah sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Hal ini secara filosofis mendukung praktik arsitektur vernakular Asia Tenggara (rumah panggung, material alami) yang menghormati lingkungan dan bertujuan agar bangunan tidak berdampak negatif bagi orang lain. Etika tradisional seperti Budi Pekerti melihat arsitektur sebagai bagian dari sistem alam-sosial yang holistik, di mana ketidakharmonisan fisik dan moral saling terkait.
Perbandingan Konsep Filosofis Asia dan Implikasinya pada Desain Ruang
| Filosofi/Etika | Wilayah Fokus | Konsep Inti | Implikasi Arsitektural Utama | Cakupan Spasial |
| Konfusianisme | Asia Timur | Li (Ritual), Xiao (Bakti Anak), Ren (Kemanusiaan) | Tata letak berhierarki, simetri formal, penekanan pada poros, struktur kaku | Ruang Publik, Istana Kekaisaran, Bangunan Administratif |
| Taoisme | Asia Timur | Wu Wei (Non-Aksi), Naturalistik | Keselarasan dengan alam, minim intervensi, spontanitas bentuk, fluiditas, estetika batu dan air | Taman Klasik, Eremitase, Arsitektur Lanskap |
| Dharma (Hindu/Buddha) | Asia Selatan & Tenggara | Tatanan Kosmik, Karma, Ahimsa | Orientasi kosmik (Mandala), bentuk stupa (perjalanan spiritual), penghindaran kekerasan | Kuil, Candi, Stupa Monumen |
| Islam | Asia Barat Daya & Tenggara | Tauhid, Taqwa, Akhlak | Pola geometris (kesatuan tak terbatas), kaligrafi, penekanan pada ruang komunal (halaman) | Masjid, Madrasah, Halaman (Courtyard) |
Arsitektur Klasik: Tipologi Dan Fusi Regional
Arsitektur Kuil Hindu dan Indo-Islam di Asia Selatan
Arsitektur India, sebagai inti dari Asia Selatan, menunjukkan keragaman yang kaya. Arsitektur candi Hindu secara tradisional dibagi menjadi gaya Nagara (India Utara) dan Dravidian (India Selatan, contohnya Kuil Meenakshi). Struktur arsitektur tertua yang bertahan di India umumnya adalah arsitektur potongan batu (rock-cut architecture), termasuk kuil-kuil Buddha, Hindu, dan Jain (contoh terkenal adalah Kuil Kailash di Gua Ellora). Monumen-monumen ini dirancang untuk mewujudkan konsep makrokosmos dan mikrokosmos.
Setelah kedatangan Islam, munculah Arsitektur Indo-Islam, dimulai sejak masa Kesultanan Delhi. Puncak fusi arsitektural ini dicapai pada masa Arsitektur Mughal, yang menghasilkan mahakarya seperti Taj Mahal. Gaya Indo-Islam ini kemudian memengaruhi gaya regional lainnya, seperti Rajput dan Sikh.
Arsitektur Masjid dan Simbolisme Islam di Asia
Arsitektur Islam, yang mencakup wilayah geografis yang luas dari Spanyol hingga Asia Tenggara selama empat belas abad peradaban , dicirikan oleh elemen-elemen yang memadukan fungsi, estetika, dan spiritualitas, seperti kubah, menara, dan pola geometris yang rumit. Masjid, sebagai pusat arsitektural Islam, berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat pembelajaran (madrasah), dan pertemuan sosial.
Simbolisme Elemen Utama:
- Kubah (Dome): Secara simbolis, kubah melambangkan bola langit (celestial sphere). Dalam konteks dinasti seperti Safavid (Persia), kubah sering memiliki bentuk tiga dimensi, setengah lingkaran dengan ujung runcing, dan ditutup dengan ubin keramik berwarna untuk menambah kedalaman dan signifikansi spiritual.
- Menara (Minaret): Berfungsi sebagai menara tinggi yang khas untuk adzan (panggilan shalat). Menara Safavid cenderung berbentuk silinder, dihiasi ornamen dan warna, dan terbuat dari bata atau marmer.
- Halaman (Courtyard): Merupakan ruang terbuka komunal yang vital, berfungsi menciptakan rasa ketenangan dan memfasilitasi pertemuan komunitas, yang esensial bagi fungsi sosial masjid.
- Pola Geometris dan Kaligrafi: Pola geometris rumit (yang mencerminkan penekanan pada simetri geometris dan elemen dekoratif) dan kaligrafi menghiasi fasad, kubah, dan interior. Secara simbolis, pola geometris ini mencerminkan konsep ciptaan Allah yang tak terbatas.
Pemilihan ornamen yang non-figuratif, seperti pola geometris dan kaligrafi, memberikan arsitektur Islam sebuah bahasa visual yang abstrak dan teologis yang dapat diterima secara universal di berbagai budaya yang ditaklukkannya. Dengan menghindari figurasi, arsitektur ini memungkinkan fusi yang sukses dengan tradisi lokal di berbagai wilayah (termasuk India dan Asia Tenggara), tanpa mengkompromikan prinsip fundamental Tauhid. Pendekatan desain ini bersifat holistik, menggabungkan pertimbangan praktis dengan simbolisme spiritual.
Arsitektur Asia Tenggara: Sinkretisme, Adaptasi Iklim, Dan Rekayasa
Asia Tenggara menunjukkan evolusi arsitektur yang didominasi oleh adaptasi iklim tropis dan pembangunan monumen yang monumental, mencerminkan sinkretisme budaya yang kompleks.
Kompleks Candi Megah dan Warisan Kerajaan
Wilayah ini dikenal karena kompleks candi kerajaannya yang megah:
- Angkor Wat (Kamboja): Dibangun pada paruh pertama abad ke-12 di bawah Raja Suryavarman II, awalnya didedikasikan sebagai kuil Hindu untuk Dewa Wisnu, sebelum bertransisi menjadi kuil Buddha. Angkor Wat merupakan pusat signifikan Kerajaan Khmer yang membentang luas dan kini berfungsi sebagai simbol identitas nasional Kamboja.
- Borobudur (Indonesia): Mencerminkan kejayaan Dinasti Syailendra, candi Buddha ini menggambarkan perjalanan spiritual dalam ajaran Buddhis melalui susunan reliefnya. Susunan stupa utamanya yang dibiarkan kosong diduga melambangkan kebijaksanaan tertinggi (kasunyatan), yaitu kesempurnaan ketiadaan ketika jiwa terbebas dari lingkaran samsara.
Salah satu aspek penting Borobudur adalah keunggulan rekayasanya. Meskipun dibangun dari struktur batu, Candi Borobudur dilengkapi dengan sistem hidrologi canggih, termasuk 100 saluran air berbentuk makara. Sistem drainase ini dirancang untuk mengalirkan air hujan secara efisien, menjaga stabilitas struktur batu dan melindunginya dari kerusakan. Analisis terhadap Angkor Wat dan Borobudur menunjukkan bahwa arsitektur monumental di Asia Tenggara berfungsi sebagai penanda pencapaian spiritual dan simbol politik, sekaligus menjadi saksi volatilitas geopolitik kawasan (Angkor Wat diserang Ayutthaya pada 1431).
Arsitektur Vernakular Tropis dan Materialitas Inklusif
Arsitektur vernakular Asia Tenggara merupakan respons cerdas terhadap iklim tropis lembab, dengan suhu rata-rata mencapai 26ºC.
Ciri-ciri Adaptasi Iklim:
- Rumah Panggung: Sistem rumah panggung adalah ciri umum di kawasan ini, dengan bentuk atap yang bertumpuk dan membumbung tinggi, berfungsi untuk mengoptimalkan sirkulasi udara dan menyesuaikan diri dengan iklim.
- Material Kayu dan Bambu: Bangunan di Asia Tenggara banyak menggunakan material alami seperti kayu. Khususnya bambu, merupakan material yang mudah didapat, ringan, dan sangat fleksibel. Sifat lentur bambu memungkinkannya mengikuti gerakan akibat gaya eksternal (seperti seismik) tanpa runtuh.
Penggunaan material yang berkelanjutan, lentur, dan mudah didapat ini adalah manifestasi konkret dari etika Budi Pekerti Nusantara, yang menuntut keselarasan dengan alam sekitar. Arsitektur vernakular ini menolak kekakuan demi adaptasi dinamis, mencerminkan pemahaman mendalam tentang siklus alamiah dan daya tahan lingkungan, mirip dengan prinsip filosofis Wu Wei Taoisme.
Perbandingan Tipologi Klasik dan Vernakular Asia
| Wilayah | Tipologi Utama | Ciri Khas Struktural/Material | Respons Fungsional/Kosmik | Contoh Warisan Kunci |
| Asia Selatan (India) | Kuil Hindu/Buddha | Gaya Nagara/Dravidian, potongan batu (rock-cut) | Representasi makrokosmos dan mikrokosmos | Kuil Kailash Ellora, Kuil Meenakshi, Taj Mahal |
| Asia Tenggara (Tropis) | Rumah Vernakular | Rumah panggung, atap bertumpuk tinggi, struktur bambu/kayu lentur | Adaptasi iklim lembab, sirkulasi udara optimal, ketahanan seismik alami | Rumah Panggung Melayu, Dinh Sung Vietnam |
| Asia Tenggara (Monumen) | Candi Kerajaan | Batu andesit/laterit, relief naratif, rekayasa hidrologi tersembunyi | Perjalanan spiritual (Borobudur), Gunung Meru (Angkor Wat) | Angkor Wat, Candi Borobudur |
| Asia Timur (Cina/Korea) | Monasteri/Istana | Sistem tiang dan balok kayu, atap melengkung, material kayu (regulasi suhu) | Simetri Konfusianis, Keseimbangan Yin-Yang (Taegeuk) | Pagoda Kembar Korea, Arsitektur Zen Jepang |
Arsitektur Asia Timur: Sistem Kayu Dan Simbolisme Dinasti
Arsitektur Asia Timur—termasuk Tiongkok, Korea, dan Jepang—seringkali mengandalkan sistem konstruksi kayu yang canggih, yang juga berkontribusi pada estetika dan respons iklim. Di wilayah Asia yang memiliki musim dingin, penggunaan kayu membantu mengatur kelembaban.
Sistem Konstruksi dan Estetika Regional
Penggunaan kayu yang dominan di Tiongkok dan Korea berkontribusi pada ekustik interior yang dapat meredam suara, meskipun terbatas. Selain itu, kayu sering digunakan untuk menyerap energi radiasi matahari, membantu perlindungan bangunan.
Di Korea, simbol Taegeuk (secara harfiah berarti “puncak tertinggi” atau “dualitas besar”) digunakan secara luas, termasuk dalam bendera nasional (Taegeuk-gi). Diambil dari konsep Taiji Tiongkok (Yin-Yang), Taegeuk Korea menggunakan skema warna biru (kekuatan negatif) dan merah (kekuatan positif) untuk melambangkan keseimbangan dan harmoni universal. Simbol ini begitu sentral sehingga digunakan sebagai wadah identitas nasional Korea, bahkan selama masa pendudukan Jepang, menunjukkan bahwa arsitektur simbolis menjadi wadah perlawanan budaya yang stabil.
Simbolisme Kultural Tiongkok
Simbolisme memainkan peran vital dalam arsitektur dinasti Tiongkok, menegaskan legitimasi dan kekuasaan. Naga Tiongkok (Long) melambangkan kekuatan, keberuntungan, dan kekuasaan, khususnya dalam mengendalikan air dan hujan. Naga bersifat yang (jantan) yang melengkapi fenghuang (phoenix) yang bersifat yin (betina), mencerminkan prinsip keseimbangan Yin-Yang. Simbol-simbol ini secara historis merupakan lambang Kaisar China, digunakan dalam arsitektur istana dan kekaisaran untuk memproyeksikan legitimasi kosmik kepada rakyat.
Arsitektur Dan Intervensi Ideologi Di Era Modern
Meskipun arsitektur Asia secara historis berakar pada kearifan dan kosmologi lokal, abad ke-20 menyaksikan intervensi ideologis radikal, terutama di Tiongkok, yang bertujuan mengganti tradisi spasial dengan tatanan yang instrumental.
Transformasi Radikal Tiongkok Pasca-1949: Arsitektur Ideologis Maoisme
Ideologi Maoisme (Pemikiran Mao Zedong) menekankan revolusi berkelanjutan di bawah kediktatoran proletariat, garis massa, perang rakyat, dan penghapusan sisa-sisa budaya lama melalui Revolusi Kebudayaan.
Lompatan Jauh ke Depan (The Great Leap Forward, GLF, 1958-1961) Program industrialisasi besar-besaran ini bertujuan mengubah ekonomi agraris Tiongkok menjadi masyarakat industri yang berkembang pesat. Namun, GLF merupakan bencana besar. Kebijakan ini didasarkan pada keputusan yang salah arah, menolak pengetahuan ahli, dan mempromosikan metode pertanian yang tidak teruji, seperti kampanye melawan burung pipit.
Dampaknya terhadap lingkungan arsitektural dan sosial sangat parah. Puluhan juta petani diperintahkan meninggalkan ladang untuk memproduksi baja di tungku rumahan, yang sebagian besar menghasilkan besi cor yang tidak layak pakai. Program ini secara langsung menghancurkan fondasi ekonomi pedesaan dan menyebabkan kelaparan masif. Diperkirakan sekitar 30 juta orang meninggal karena kelaparan selama periode 1959–1961. Angka ini sangat beragam, dari laporan resmi pemerintah Deng Xiaoping (16,5 juta) hingga klaim Jung Chang (70 juta), namun sebagian besar rekonstruksi demografis mengindikasikan sekitar 30 juta kematian.
Kegagalan Lompatan Jauh ke Depan adalah studi kasus ekstrem tentang bagaimana penolakan terhadap kearifan lokal, materialitas, dan realisme lingkungan—yang dihargai dalam arsitektur vernakular Asia—demi sebuah ideologi murni, dapat menyebabkan keruntuhan struktural sosial dan fisik yang bencana.
Revolusi Kebudayaan (CR, 1966-1976) Revolusi Kebudayaan adalah upaya proaktif untuk membersihkan sisa-sisa budaya lama dan mempromosikan budaya proletar. Secara arsitektural, ini melibatkan penghapusan semua institusi dan upacara keagamaan dan mistik, menggantinya dengan pertemuan politik dan sesi propaganda. Pembersihan politik juga dilakukan secara sistematis, menargetkan tokoh moderat seperti Liu Shaoqi. Warisan Mao, meskipun dikritik keras (70% kegagalan GLF ditimpakan padanya setelah Deng berkuasa) , tetap dihormati secara resmi sebagai pendiri RRT.
Pengaruh Maoisme meluas di luar Tiongkok, menginspirasi gerakan revolusioner di Asia dan di seluruh dunia, termasuk Shining Path di Peru dan dukungan Tiongkok terhadap rezim Khmer Rouge di Kamboja. Ini menunjukkan bahwa cetak biru arsitektur ideologis kontrol total yang diciptakan di Tiongkok direplikasi dalam lanskap politik negara lain.
Dampak Ideologi Modern terhadap Arsitektur Tiongkok
| Periode Ideologis | Tujuan Kunci (Maoisme) | Dampak pada Arsitektur/Lingkungan | Konsekuensi Kemanusiaan/Sosial | Sumber |
| Great Leap Forward (GLF) 1958-1961 | Industrialisasi cepat, Komunisme massal, anti-waste | Penghancuran pertanian tradisional, pembangunan infrastruktur industri yang gagal (tungku baja backyard) | Famine (kelaparan masif), sekitar 30 juta kematian (dengan estimasi berkisar 16.5M hingga 70M) | |
| Cultural Revolution (CR) 1966-1976 | Membersihkan budaya lama, Revolusi Berkelanjutan | Penghancuran warisan keagamaan/mistik, penekanan pada fungsionalisme proletar, penindasan intelektual | Pembersihan elit politik dan intelektual, kekerasan, ketidakstabilan sosial |
Tantangan Etika dalam Arsitektur Global Kontemporer
Di era globalisasi, arsitektur Asia menghadapi tantangan etika yang kompleks. Budaya Asia tradisional secara inheren adalah masyarakat kolektivis, yang menempatkan kepentingan kelompok (in-group) di atas kepentingan individu, menekankan interdependensi, kolaborasi, dan kesetiaan. Nilai-nilai ini terwujud dalam desain ruang komunal, seperti halaman masjid atau sistem rumah panggung yang mendukung interaksi komunitas.
Namun, arus globalisasi mendorong individualisme, di mana realisasi diri dan hak pribadi diletakkan di atas hak kelompok. Pergeseran ini, yang sering dikaitkan dengan gaya hidup hedonisme (mengutamakan kesenangan pribadi untuk mencapai kepuasan) , mengikis ruang kolektif dan mengalihkan fokus desain ke properti dan konsumsi pribadi yang berlebihan.
Tantangan etika ini berujung pada masalah tata kelola. Korupsi, yang didefinisikan sebagai perilaku menyimpang untuk keuntungan pribadi , merupakan pelanggaran etika yang menempatkan kepentingan pribadi atau komunal di atas kepentingan publik. Hal ini sangat bertentangan dengan moralitas kultural di Asia; misalnya, kearifan lokal di Indonesia seperti Siri’ Na Pacce (Bugis) atau ajaran dari Bhagavad Gita yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi/komunal. Oleh karena itu, arsitektur modern di Asia dituntut tidak hanya memahami hukum internasional tetapi juga bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku dalam perencanaan dan pembangunan.
Kesimpulan
Arsitektur Asia telah memberikan kontribusi abadi yang melampaui estetika struktural. Analisis ini menunjukkan bahwa desain di Asia secara inheren diarahkan oleh kerangka kerja etika dan spiritual yang mendalam, mulai dari hierarki Konfusianis dan naturalisme Taois, hingga tatanan kosmik Dharma, dan prinsip Tauhid Islam.
Kearifan arsitektur Asia menyediakan model yang unik dalam merespons lingkungan alam, terutama melalui arsitektur vernakular Asia Tenggara. Penggunaan materialitas yang berkelanjutan dan lentur, seperti bambu dan kayu , menawarkan pelajaran penting dalam ketahanan struktural dan keberlanjutan bagi pembangunan global. Selain itu, sinkretisme yang terwujud dalam bangunan keagamaan, seperti perpaduan budaya lokal dan Buddhis di Borobudur , berfungsi sebagai bukti fisik tentang koeksistensi dan toleransi agama di tengah keberagaman.