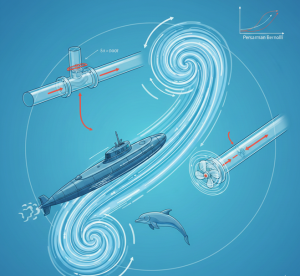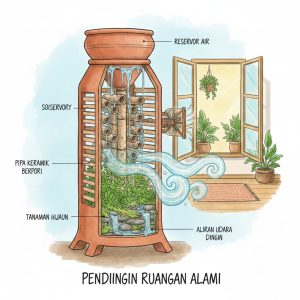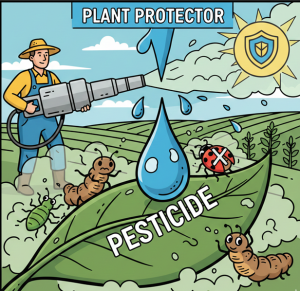Analisis Ekshaustif Perempuan di Tengah Konflik Global
Konflik global kontemporer, yang ditandai oleh kompleksitas, asimetri, dan dampak yang meluas terhadap populasi sipil, menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan sekaligus transformatif. Tinjauan ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai peran dan dampak konflik multidimensional terhadap perempuan, melampaui narasi tunggal tentang korban. Laporan ini menggarisbawahi pergeseran paradigma dari melihat perempuan semata-mata sebagai penerima bantuan pasif menjadi pengakuan atas mereka sebagai subjek aktif yang memiliki agensi dan berperan penting dalam pencegahan, mitigasi, dan resolusi konflik.
Secara teoretis, analisis ini berakar pada perspektif Keamanan Manusia, yang menuntut pendekatan komprehensif terhadap keselamatan individu—di luar keamanan negara—dengan menekankan bahwa semua pihak, termasuk perempuan, memegang peran esensial dalam penciptaan perdamaian dan penyelesaian konflik. Kegagalan untuk mengintegrasikan perspektif gender yang komprehensif dalam domain keamanan akan menghasilkan solusi konflik yang tidak berkelanjutan dan mengabaikan dinamika struktural kerentanan. Laporan ini akan mengupas dualitas peran perempuan, menyoroti peningkatan kerentanan struktural yang mereka hadapi di tengah konflik, kerangka hukum internasional untuk perlindungan, serta evaluasi kritis terhadap implementasi Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS).
Dimensi Kerentanan: Perempuan sebagai Sasaran dan Korban Utama Konflik
Konflik bersenjata dan situasi kekerasan masif secara sistematis mengikis hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Data global menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: dunia seolah melupakan mereka di tengah serangan yang meningkat terhadap hak-hak perempuan, yang mengakibatkan memudarnya kemajuan yang telah dicapai selama beberapa dekade.
Peningkatan Mortalitas dan Kekerasan Seksual Berbasis Gender (SGBV)
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti eskalasi dramatis dalam dampak konflik terhadap perempuan. Proporsi perempuan yang terbunuh dalam konflik bersenjata meningkat dua kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, saat ini terdapat lebih dari 600 juta perempuan dan anak perempuan yang terdampak perang, sebuah peningkatan sebesar 50 persen dibandingkan satu dekade lalu, menunjukkan bahwa perempuan adalah target utama dalam konflik kontemporer.
Salah satu manifestasi paling brutal dari konflik adalah Kekerasan Seksual Berbasis Gender (SGBV), yang semakin digunakan sebagai taktik perang. Kasus kekerasan seksual terkait konflik yang diverifikasi PBB meningkat sebesar 50 persen pada tahun 2023. Kekerasan ini tidak hanya bersifat insidental tetapi sistemik. Di Republik Demokratik Kongo (RDC), khususnya Provinsi Kivu, SGBV merajalela, terutama di lokasi penambangan yang dikuasai oleh mantan kombatan dan kelompok bersenjata. Kehadiran kelompok-kelompok militan bekas Perang Kongo II memicu kekerasan berbasis gender di wilayah timur RDC. Dalam periode Januari hingga September 2014 saja, UNFPA mencatat 11.769 kasus kekerasan seksual dan berbasis gender di beberapa provinsi, dengan 39 persen kasus dilakukan oleh kelompok bersenjata.
Kasus SGBV ini, khususnya di Kivu, menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan individu, tetapi merupakan ancaman sistemik terhadap Keamanan Manusia. Kejahatan ini memiliki dampak besar pada Keamanan Kesehatan, Keamanan Ekonomi, dan Keamanan Pribadi individu dan komunitas secara keseluruhan. SGBV berfungsi sebagai alat untuk merusak struktur sosial, kontrol wilayah, dan kohesi komunitas, terutama di wilayah yang kaya sumber daya yang diperebutkan. Ini menegaskan bahwa upaya pencegahan SGBV harus diintegrasikan ke dalam kerangka keamanan yang lebih luas dan upaya pembangunan ekonomi pasca-konflik.
Kerentanan Struktural, Dislokasi, dan Eksploitasi
Konflik memperburuk kerentanan struktural yang telah ada, terutama melalui dislokasi dan pengungsian. Perempuan lebih rentan saat terjadi bencana atau konflik akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya, layanan kesehatan, dan informasi.
Dalam situasi pengungsian, kerentanan terhadap perdagangan orang (TPPO) meningkat tajam. Kelompok pengungsi, seperti etnis minoritas Rohingya yang mencari perlindungan di negara-negara Asia Tenggara setelah mengalami kekerasan dan pengusiran, seringkali menjadi korban perdagangan manusia. Sindikat kriminal mengeksploitasi mereka untuk tujuan seksual, tenaga kerja, atau organ tubuh. Faktor-faktor yang memperburuk TPPO meliputi diskriminasi, kondisi keamanan yang buruk, kurangnya sumber daya, dan keterbatasan penanganan oleh organisasi regional. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengakui bahwa perdagangan melalui laut telah menjadi kejahatan yang disukai oleh kelompok kejahatan yang lebih besar, menargetkan korban dalam situasi dislokasi di wilayah perairan yang sulit dipatroli. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak menciptakan kerentanan, melainkan menguatkan dan mengakselerasi eksploitasi yang didorong oleh ketidaksetaraan sistemik.
Dampak Ekonomi dan Psikososial Jangka Panjang
Bahkan ketika konflik bersenjata mereda, perempuan terus menghadapi tantangan struktural yang menghambat pemulihan. Ketidakstabilan sosial, yang tercermin misalnya dalam lonjakan kasus perceraian (analog dengan tekanan sosial-ekonomi pasca-konflik atau bencana seperti pandemi COVID-19) , menunjukkan perlunya pemulihan yang inklusif gender.
Masalah hak properti (harta bersama) pasca-konflik atau perceraian menjadi isu kritis, diperumit oleh kurangnya panduan hukum yang jelas, terutama dalam kasus perkawinan tidak tercatat. Sengketa harta ini, yang mencapai 2.316 kasus di Indonesia pada tahun 2023, seringkali menghasilkan keputusan yang bervariasi dan berpotensi tidak adil bagi perempuan. Hilangnya hak properti ini secara signifikan menghambat kemampuan perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan menjadi agen pemulihan komunitas pasca-konflik, yang pada gilirannya melanggengkan kemiskinan berbasis gender. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang tidak sensitif gender terkait hak ekonomi dapat merusak upaya pembangunan perdamaian jangka panjang.
Kerangka Hukum Internasional dan Akuntabilitas
Meskipun tantangan implementasi sangat besar, kerangka hukum internasional telah berkembang pesat untuk memberikan perlindungan normatif yang kuat bagi perempuan di tengah konflik.
Perlindungan dalam Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia
Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949, mengatur perlindungan hak-hak fundamental dalam konflik bersenjata non-internasional. Ketentuan ini menetapkan dasar perlindungan warga sipil, termasuk perempuan, dari kekejaman dan perlakuan tidak manusiawi.
Di tingkat nasional, undang-undang HAM (seperti di Indonesia) menjamin hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Mandat hukum ini mencakup penyediaan dukungan sistem perlindungan, layanan informasi dan tindak cepat, serta rumah aman yang mudah diakses. Jaminan-jaminan ini sangat penting dalam situasi krisis atau konflik.
Yuriprudensi Pidana Internasional tentang Kejahatan Seksual
Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memberikan landasan hukum pidana yang kuat dan progresif untuk menuntut kekerasan berbasis gender. Statuta ini secara eksplisit mengakui pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai Kejahatan Perang dan pelanggaran berat Konvensi Jenewa (dalam konflik internasional), serta pelanggaran serius dari Pasal Umum 3 (dalam konflik non-internasional).
Definisi dalam Statuta Roma bersifat luas, mencakup pemerkosaan, perbudakan seksual (termasuk perdagangan perempuan), pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual berat lainnya, serta persekusi dengan alasan gender sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
Untuk mendukung akuntabilitas, Statuta Roma juga mencakup Aturan Acara yang progresif dan sensitif terhadap kerumitan kejahatan seksual, seperti perlindungan saksi perempuan melalui Unit Korban dan Saksi. Ketentuan ini telah direplikasi dan diadopsi dalam statuta pengadilan campuran (hybrid) dan beberapa yurisdiksi nasional, termasuk Sierra Leone, Timor Leste, dan Pengadilan HAM di Indonesia.
Kesenjangan Implementasi dan Impunitas
Meskipun kerangka hukum normatif yang diatur oleh ICC sangat kuat dan progresif, data menunjukkan adanya kenaikan tajam 50 persen dalam kasus SGBV yang terverifikasi PBB. Disparitas ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam perlindungan perempuan bukanlah kurangnya definisi hukum, melainkan kegagalan dalam penegakan hukum dan akuntabilitas. Impunitas yang meluas memungkinkan pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk menghindari tuntutan yang sukses di tingkat internasional, sehingga gagal menciptakan efek jera yang memadai.
Lokalisasi penegakan hukum—yaitu, adopsi ketentuan Statuta Roma ke dalam yurisdiksi nasional dan pengadilan hibrida—sangat penting. Langkah ini membuat keadilan lebih mudah diakses oleh korban dan menghasilkan yurisprudensi yang lebih relevan dengan konteks konflik lokal, yang merupakan kunci untuk memerangi impunitas di tingkat akar rumput.
Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS): Mandat versus Realitas
Agenda WPS, yang dipelopori oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000), mengakui pentingnya dimensi gender dalam perdamaian dan keamanan internasional. Agenda ini secara eksplisit menyerukan peningkatan peran perempuan dalam peacemaking dan peacebuilding, termasuk mediasi dan resolusi konflik.
Hambatan Struktural terhadap Partisipasi
Meskipun mandat kebijakan ada, implementasi Resolusi 1325 masih jauh dari tercapai. Laporan PBB secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan dan pengambilan keputusan terkait isu perdamaian dan keamanan masih didominasi oleh laki-laki.
Data konkret menunjukkan kesenjangan yang parah dalam representasi formal. Perempuan hanya memegang 17 persen dari jabatan utama PBB yang berkaitan dengan konflik, sementara laki-laki mendominasi sebesar 81 persen. Kondisi ini mencerminkan struktur sosial patriarki yang represif dan bias gender yang secara fundamental menahan potensi setengah dari populasi masyarakat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa selama struktur patriarki ini tetap dominan, perdamaian akan tetap sulit diraih.
Kesenjangan ini merupakan penghalang keamanan yang terukur, yang secara langsung melemahkan efektivitas resolusi konflik. Partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan memiliki korelasi yang jelas dengan kemungkinan yang lebih besar untuk mengesahkan dan mengimplementasikan undang-undang yang mempromosikan kesetaraan gender, termasuk undang-undang terkait penghentian kekerasan domestik, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Kegagalan untuk mencapai kuota partisipasi formal ini berarti potensi transformatif kepemimpinan perempuan dalam upaya mencapai perdamaian sedang melemah.
Tabel 1: Kesenjangan Implementasi Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS)
| Pilar WPS | Mandat Kunci (Resolusi 1325) | Realitas Implementasi (Data Global) | Implikasi Kebijakan |
| Partisipasi | Peningkatan representasi dalam negosiasi dan pengambilan keputusan. | 81% jabatan kunci PBB terkait konflik dipegang laki-laki; Tujuan jauh dari tercapai. | Perundingan damai tidak mencerminkan perspektif masyarakat sipil yang utuh; Perjanjian kurang berkelanjutan. |
| Perlindungan | Perlindungan dari SGBV dan Pelanggaran HAM. | Peningkatan 50% kasus SGBV terverifikasi dan korban tewas meningkat dua kali lipat. | Kerangka hukum ada, tetapi impunitas dan kegagalan penegakan hukum menjadi masalah fundamental. |
| Pencegahan | Mendorong tanggapan sensitif gender terhadap konflik. | Kemajuan hak-hak perempuan memudar karena dominasi struktur patriarki. | Konflik bersenjata bertindak sebagai akselerator ketidaksetaraan struktural yang ada. |
Perempuan sebagai Aktor Konflik Non-Tradisional
Perempuan di wilayah konflik tidak hanya eksis sebagai korban atau penyintas, tetapi juga sebagai agen perdamaian (positive agency) dan, dalam kasus tertentu, sebagai kombatan aktif (negative agency). Memahami spektrum penuh peran ini sangat penting untuk merancang respons yang efektif dan bernuansa.
Peran dalam Pembangunan Perdamaian (Peacebuilding)
Perempuan komunitas seringkali menjadi tulang punggung upaya peacebuilding di tingkat akar rumput. Mereka diakui memiliki peran penting dalam mengakhiri konflik dan memastikan penciptaan perdamaian yang berkelanjutan.
Contoh historis dan kontemporer menunjukkan kontribusi signifikan perempuan dalam situasi pasca-konflik. Misalnya, perempuan Aceh memainkan peran kunci dalam perjuangan mencari kebijakan di wilayah konflik untuk perlindungan dan pembangunan kembali masyarakat. Demikian pula, perempuan telah terlibat dalam upaya peacebuilding untuk merespons konflik Suriah, yang bertujuan untuk membangun kembali struktur sosial yang runtuh. Keterlibatan di tingkat akar rumput ini seringkali lebih efektif dalam menengahi ketegangan lokal dan membangun kepercayaan. Namun, terdapat diskoneksi struktural antara efektivitas kerja perdamaian berbasis masyarakat ini dan proses perdamaian formal yang didominasi oleh aktor laki-laki.
Keterlibatan sebagai Kombatan dan Aktor Kekerasan
Di sisi lain, konflik global juga dicirikan oleh keterlibatan perempuan dalam peran non-tradisional yang melibatkan kekerasan bersenjata atau terorisme. Keterlibatan ini memiliki preseden historis, dimulai setidaknya pada tahun 1985 ketika Partai Sosial Nasionalis Suriah (SSNP) menggunakan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri (Sana Mekhaidali, “Pengantin Selatan”). Kelompok separatis lain, seperti Harimau Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), juga membentuk unit khusus pasukan bunuh diri yang dikomandoi oleh perempuan (“Harimau Hitam”).
Dalam konteks kelompok ekstremis kontemporer seperti ISIS, perempuan dimanfaatkan dalam aksi teror sebagai kombatan aktif. Strategi keterlibatan perempuan dalam ISIS berbeda dari kelompok lain; motivasi mereka dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu, pengaruh kerabat terdekat, pengalaman pribadi, serta identitas sosial mereka sebagai Muslim. ISIS sangat terampil dalam memanfaatkan kampanye media daring dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang manipulatif, memicu radikalisasi dan memfasilitasi partisipasi perempuan.
Peran ganda perempuan ini—sebagai arsitek perdamaian komunitas sekaligus kombatan aktif—menghadirkan tantangan besar bagi program Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) pasca-konflik. Program-program ini sering kali dirancang dengan bias gender laki-laki dan gagal memperhitungkan faktor motivasi unik (psikologis dan sosial) serta potensi trauma spesifik yang dialami oleh perempuan kombatan.
Tabel 2: Spektrum Peran Perempuan dalam Dinamika Konflik Global
| Kategori Peran | Deskripsi dan Fungsi Utama | Motivasi Kunci | Contoh Kontekstual |
| Agen Perdamaian (Peacebuilding) | Mediator lokal, advokat komunitas, pembangunan kembali struktur sosial pasca-konflik. | Kebutuhan mendesak untuk melindungi keluarga dan membangun kembali komunitas. | Aktivis peacebuilding konflik Suriah; Perempuan Aceh. |
| Kombatan/Aktor Kekerasan | Partisipasi aktif dalam pertempuran, logistik, atau operasi teror. | Psikologi individual, pengaruh kerabat, identitas sosial, dan manipulasi daring. | Harimau Hitam LTTE; Kombatan ISIS di Irak/Suriah. |
Kesimpulan
Perempuan di tengah konflik global menghadapi ancaman ganda: peningkatan drastis dalam viktimisasi (ditunjukkan oleh dua kali lipat peningkatan kematian dan 50 persen kenaikan SGBV terverifikasi ), dan marginalisasi struktural dalam proses resolusi konflik formal. Analisis menunjukkan bahwa struktur sosial patriarki yang represif bukan sekadar isu sosial tetapi penghalang keamanan yang terukur.
Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, seperti Statuta Roma ICC yang mengkriminalisasi kejahatan seksual berbasis gender , impunitas tetap merajalela, yang menjadi penyebab utama kegagalan perlindungan. Selain itu, konflik bertindak sebagai akselerator ketidaksetaraan yang sudah ada, memperparah kerentanan ekonomi (hak properti ) dan memicu eksploitasi di kamp pengungsian (TPPO ). Walaupun perempuan menunjukkan kapasitas signifikan sebagai agen peacebuilding di tingkat akar rumput , suara mereka terpinggirkan di meja perundingan formal, yang masih didominasi oleh laki-laki (81 persen).
Berdasarkan analisis kerentanan, akuntabilitas, dan partisipasi, laporan ini menyajikan rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat Agenda WPS dan memastikan keamanan perempuan dalam konflik multidimensional:
- Meningkatkan Representasi dan Reformasi Sektor Keamanan (SSR) yang Sensitif Gender: Diperlukan intervensi kebijakan yang tegas untuk melampaui angka partisipasi 17 persen perempuan dalam jabatan kunci PBB dan memastikan representasi yang setara dalam pengambilan keputusan perdamaian. Mendorong keterlibatan perempuan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemungkinan pengesahan dan implementasi undang-undang yang mendukung kesetaraan gender dan mengakhiri kekerasan. Pendekatan ini harus berfokus pada kualitas substansi perjanjian (isi gender) dan bukan hanya kuantitas perwakilan.
- Memperkuat Akuntabilitas Domestik dan Mengatasi Impunitas SGBV: Pemerintah nasional dan pengadilan harus memastikan bahwa ketentuan Statuta Roma ICC terkait kejahatan seksual berbasis gender diterjemahkan dan diterapkan secara efektif dalam yurisdiksi domestik. Prioritas harus diberikan pada penuntutan kejahatan SGBV yang dilakukan oleh kelompok bersenjata atau aparat negara, menghilangkan impunitas yang telah menyebabkan lonjakan kasus kekerasan seksual. Lokalisasi penegakan hukum adalah kunci keberhasilan akuntabilitas.
- Intervensi Holistik terhadap Kerentanan Ekonomi dan Sosial: Program pemulihan pasca-konflik harus dirancang untuk inklusif gender dan mengatasi ketimpangan akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Ini mencakup perlindungan prioritas terhadap hak properti perempuan pasca-konflik, khususnya harta bersama yang seringkali bermasalah dalam situasi hukum yang tidak jelas. Perlindungan juga harus diperluas untuk memastikan layanan tindak cepat dan rumah aman bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas.
- Penanganan Perdagangan Orang (TPPO) secara Komprehensif di Zona Krisis: Kerja sama antara organisasi internasional seperti IOM dan pemerintah harus ditingkatkan untuk pencegahan dan penanganan TPPO di wilayah perbatasan dan kamp pengungsian. Langkah-langkah pencegahan di hulu, seperti pelatihan untuk pelatih kepada organisasi masyarakat sipil , harus diperkuat, mengakui bahwa dislokasi dan kerentanan struktural adalah faktor risiko utama yang dieksploitasi oleh sindikat kriminal.
- Program DDR yang Berbasis Gender: Untuk mengatasi kompleksitas peran perempuan sebagai kombatan, program Disarmament, Demobilization, and Reintegration harus dirancang ulang agar sensitif gender. Program ini harus mengakomodasi faktor motivasi unik (psikologi, identitas sosial) dan potensi trauma yang dialami perempuan kombatan, menjamin reintegrasi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan.