Sejarah Pemakaian Jilbab di Indonesia dari Berbagai Perspektif
Jilbab di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang jauh lebih kompleks daripada sekadar busana. Perjalanannya mencerminkan narasi historis bangsa yang berliku, di mana jilbab tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai penanda identitas agama, simbol perlawanan politik, ekspresi gaya hidup, dan bahkan indikator status sosial. Laporan ini mengkaji sejarah jilbab di Indonesia secara komprehensif dan multidimensional, menelusuri akarnya dari peradaban kuno hingga dinamika kontemporer, dengan menganalisis interaksi yang rumit antara doktrin teologis, kebijakan negara, dan perubahan budaya. Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang bernuansa dan terperinci mengenai evolusi jilbab sebagai mikrokosmos dari lanskap sosial dan politik Indonesia.
Asal-Usul dan Adopsi Awal: Jilbab di Nusantara Sebelum Abad ke-20
Jilbab atau kerudung (khimar) merupakan tradisi yang memiliki sejarah panjang dan melampaui konteks Islam. Praktik menutupi kepala dan wajah telah ditemukan dalam berbagai peradaban kuno, di mana fungsinya bervariasi dari penanda status sosial, keagamaan, hingga simbol perlindungan. Referensi paling awal terhadap tradisi ini dapat ditemukan dalam kode-kode Assyrian kuno, yang menetapkan bahwa istri, anak perempuan, dan janda harus memakai kerudung ketika berada di tempat umum. Dalam tradisi Yahudi, penggunaan jilbab juga dikaitkan dengan mitos dosa asal Hawa yang harus menyembunyikan diri setelah menggoda Adam. Bahkan dalam bait syair pra-Islam Arab, kerudung telah digambarkan sebagai bagian dari busana perempuan.
Dalam konteks Islam, Al-Qur’an memberikan landasan teologis yang memperdalam makna jilbab dari sekadar tradisi budaya menjadi kewajiban syariat. Ayat-ayat seperti Al-Ahzab: 59 dan An-Nur: 31 menjelaskan jilbab sebagai sarana untuk menutup aurat, menjaga kehormatan (hifẓ karāmah), dan membedakan perempuan merdeka dari budak agar tidak dilecehkan. Berbeda dengan tradisi pra-Islam yang mungkin bersifat sosial dan kultural, Islam memberikan arahan yang jelas mengenai tujuan dan fungsinya sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Pergeseran ini merupakan transformasi kunci yang mengubah pemakaian jilbab dari kebiasaan menjadi ekspresi ideologis.
Jejak Awal di Nusantara: Dari Komunitas Lokal ke Gerakan Pembaharuan
Meski pemakaian jilbab secara masif di Indonesia dikenal pada era modern, jejaknya telah ditemukan dalam catatan sejarah yang lebih tua. Laporan menunjukkan bahwa bangsawan Muslimah di Makassar telah mengenakan jilbab sejak abad ke-17. Di Aceh, ilustrasi dari tahun 1637 dan foto-foto dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menunjukkan perempuan yang sudah menutup kepala, meskipun model jilbabnya masih berupa selendang yang belum sempurna. Namun, pemakaian jilbab pada masa ini tidak universal; catatan juga menunjukkan bahwa banyak perempuan Aceh tidak mengenakan jilbab dalam keseharian mereka.
Di Minangkabau, gerakan Padri pada abad ke-19 secara gigih memperjuangkan penerapan syariat Islam, termasuk kewajiban memakai jilbab, bahkan cadar. Perjuangan ini merupakan salah satu contoh paling awal dari upaya terorganisir untuk mempromosikan jilbab di Nusantara. Data ini menunjukkan bahwa adopsi jilbab di Indonesia pada awalnya bersifat sporadis dan teritorial, terbatas pada kantong-kantong masyarakat Islam yang memiliki tradisi kuat atau berada di bawah pengaruh gerakan reformasi tertentu. Jilbab belum menjadi fenomena nasional atau seragam, melainkan sebuah praktik yang tersembunyi di dalam komunitas dan budaya lokal.
Peran Tokoh dan Organisasi Pra-Kemerdekaan
Memasuki abad ke-20, adopsi jilbab mulai bergerak dari fenomena lokal menjadi bagian dari agenda pergerakan nasional. Tokoh-tokoh reformis Islam memainkan peran sentral dalam mempopulerkan jilbab sebagai bagian dari identitas Muslimah yang terdidik dan modern. Salah satu tokoh kunci adalah K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang aktif menyiarkan kewajiban berjilbab sejak 1910-an. Istrinya, Nyai Ahmad Dahlan, menjadi salah satu pelopor yang secara terbuka mengenakan jilbab dan mendirikan perkumpulan Sopo Tresno untuk perempuan Islam yang fokus pada dakwah, pendidikan, dan sosial.
Selain itu, perjuangannya mematahkan stereotip jilbab yang dikaitkan dengan keterbelakangan. Pahlawan perempuan seperti Hajjah Rangkayo Rasuna Said, seorang pejuang kemerdekaan yang juga berhijab, menunjukkan bahwa jilbab dapat berdampingan dengan peran aktif dan kontribusi signifikan di ruang publik. Peran organisasi perempuan seperti Aisyiyah juga penting, di mana mereka secara terstruktur menyebarkan dakwah tentang jilbab melalui publikasi dan kegiatan. Pergerakan ini merupakan transisi penting yang mengubah jilbab dari sekadar tradisi menjadi bagian dari sebuah proyek ideologis yang terorganisir.
Represi dan Perlawanan: Polemik Jilbab di Era Orde Baru (1980-1991)
Kebijakan Represif Orde Baru: Latar Belakang dan Implementasi
Meskipun telah dipromosikan sejak awal abad ke-20, pemakaian jilbab masih tidak banyak sepanjang tahun 1930-an hingga 1980-an. Namun, seiring dengan gelombang kebangkitan Islam, jumlah pemakai jilbab mulai meningkat. Fenomena ini dipandang sebagai ancaman oleh rezim Orde Baru yang sentralistis dan represif. Pemerintah mencurigai bahwa jilbab adalah manifestasi dari gerakan politik oposisi dan kelompok yang dianggap fundamentalis, terutama yang terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah.
Sebagai respons, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pada awal 1980-an mengeluarkan kebijakan penyeragaman seragam sekolah. Aturan ini dilegitimasi melalui Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 pada 17 Maret 1982, yang secara implisit melarang siswi sekolah negeri mengenakan jilbab. Kebijakan ini bukanlah sekadar masalah seragam, melainkan sebuah alat politik untuk mengontrol dan menekan ekspresi Islam di ruang publik, terutama di lembaga pendidikan yang dianggap sebagai arena krusial bagi stabilitas politik.
Perjuangan dan Perlawanan: Solidaritas dan Kemenangan
Larangan jilbab memicu gelombang perlawanan yang mengubah jilbab dari pakaian biasa menjadi simbol perjuangan dan perlawanan ideologis. Siswi-siswi berjilbab menghadapi diskriminasi yang parah; mereka diancam akan dikeluarkan dari sekolah, dilarang masuk kelas, atau dipaksa untuk membuka jilbab mereka. Kasus-kasus di SMAN 3 Bandung, di mana delapan siswi diancam dikeluarkan, dan Siti Ratu Nasiratun Nisa di SMAN 68 Jakarta yang dikeluarkan karena berjilbab, menjadi contoh nyata dari represifnya kebijakan ini.
Perjuangan ini menggalang solidaritas yang luas. Keluarga, organisasi Islam, dan aktivis mahasiswa bersatu untuk melawan kebijakan ini. Perlawanan ini mengubah isu jilbab menjadi isu nasional yang tidak bisa diabaikan. Tekanan yang kuat dari masyarakat, termasuk protes mahasiswa yang masif pada tahun 1990, membuat pemerintah khawatir akan stabilitas negara. Ini menunjukkan bahwa kontrol represif pemerintah secara tidak sengaja justru memperkuat identitas dan komitmen kelompok yang ditindas.
Akomodasi dan Pencabutan Larangan
Titik balik datang menjelang akhir 1980-an, ketika Presiden Soeharto mulai mencari dukungan dari kaum Muslimin menjelang pemilu. Perubahan sikap ini, yang juga didukung oleh tokoh-tokoh dekat rezim seperti Siti Hardiyanti Rukmana (“Mbak Tutut”) yang mulai tampil berkerudung, menandai fase akomodatif Orde Baru terhadap aspirasi Islam. Pada 16 Februari 1991, pemerintah akhirnya mencabut larangan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/91, yang secara resmi mengizinkan jilbab sebagai seragam sekolah alternatif bagi Muslimah. Pencabutan ini lebih merupakan hasil dari pragmatisme politik dan kebutuhan akan dukungan massa, bukan murni kemenangan ideologis, menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kalkulasi kekuasaan.
Tabel 1: Garis Waktu Polemik Jilbab di Era Orde Baru
| Periode | Peristiwa Kunci | Keterangan |
| Awal 1980-an | Gelombang pertama mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah kembali ke tanah air, membawa pemikiran puritan yang menganggap jilbab sebagai kewajiban. | Ideologi ini disebarkan melalui masjid-masjid dan kelompok studi Islam di kampus-kampus terkemuka seperti UI, ITB, dan UGM. |
| Awal 1982 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, mensosialisasikan kebijakan penyeragaman busana sekolah. | Kebijakan ini bertujuan memisahkan pendidikan dari politik dan agama, yang dinilai sebagai ancaman terhadap ketertiban politik. |
| 17 Maret 1982 | Dikeluarkannya Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 tentang Seragam Sekolah Nasional. | Surat ini menjadi dasar bagi sekolah untuk merepresi siswi berjilbab dengan mengancam akan mengeluarkan mereka dari sekolah. |
| 1982-1989 | Kasus diskriminasi dan perundungan terhadap siswi berjilbab marak terjadi di berbagai kota, seperti SMAN 3 Bandung dan SMAN 68 Jakarta. | Siswi ditekan untuk memilih antara melepaskan jilbab atau pindah ke sekolah swasta. |
| 1990 | Demonstrasi besar-besaran menentang diskriminasi terhadap perempuan berjilbab meledak di kota-kota besar. | Isu “jilbab beracun” pada tahun 1989 menjadi titik balik yang memicu reaksi marah dari umat Islam dan mahasiswa. |
| 16 Februari 1991 | Ditetapkannya Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/91 yang membolehkan jilbab sebagai seragam sekolah alternatif. | Surat ini mengakhiri perjuangan panjang para jilbaber dan membuka jalan bagi meluasnya pemakaian jilbab. |
Jilbab sebagai Gaya Hidup dan Identitas Urban: Era Pasca-Orde Baru
Kebangkitan Revolusi Jilbab 1.0 dan 2.0
Pencabutan larangan jilbab pada tahun 1991 menjadi katalis bagi apa yang disebut “Hijab Revolution 1.0,” yaitu periode di mana pemakaian jilbab diterima secara luas di institusi pendidikan dan masyarakat.Namun, fenomena yang lebih signifikan terjadi pada era 2010-an, yang dikenal sebagai “Hijab Revolution 2.0.” Pada era ini, jilbab mengalami pergeseran makna yang fundamental, dari sekadar simbol kepatuhan beragama menjadi sebuah gaya hidup (lifestyle). Transformasi ini menunjukkan bahwa jilbab tidak lagi dilihat hanya sebagai penutup aurat, melainkan sebagai sebuah ekspresi diri dan bagian dari identitas modern. Proses ini merupakan dampak langsung dari liberalisasi politik dan globalisasi yang membuka ruang bagi ekspresi identitas baru.
Munculnya Komunitas dan Industri Kreatif Jilbab
Pergeseran makna ini didorong oleh kemunculan komunitas Hijabers, sebuah tren baru di kalangan perempuan Muslim perkotaan. Komunitas seperti Hijabers Community (HC), yang didirikan pada tahun 2010 oleh desainer Dian Pelangi, mempromosikan citra Muslimah yang saleh (virtuous) namun tetap “fun,” “colorful,” dan modis (fashionable). Komunitas-komunitas ini bukan hanya menjadi wadah spiritual, tetapi juga platform ekonomi yang mengubah ekspresi religius menjadi industri kreatif yang berkembang pesat. Fenomena ini telah menciptakan sebuah “ekonomi kesalehan” (piety economy), di mana nilai-nilai agama berinteraksi dengan sistem pasar.
Peran desainer busana Muslim seperti Dian Pelangi, Oki Setiana Dewi, dan influencer media sosial seperti Aghnia Punjabi dan Dwi Handayani sangatlah krusial. Mereka menjadi model peran baru yang mempopulerkan berbagai gaya dan tren jilbab, membuatnya lebih menarik dan mudah diakses oleh audiens yang lebih luas. Media sosial menjadi mesin percepatan yang menyebarkan tren ini secara instan, mengubah cara perempuan mengadopsi dan menginterpretasi jilbab. Akibatnya, pemakaian jilbab tidak hanya didasarkan pada motivasi religius murni, tetapi juga didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren dan menjadi bagian dari komunitas.
Jilbab sebagai Simbol Identitas dan Status Sosial
Dalam lanskap sosial kontemporer, makna jilbab menjadi berlapis dan multidimensional. Selain sebagai penanda identitas keagamaan, jilbab juga berfungsi sebagai simbol pribadi dan bahkan status sosial. Bagi sebagian perempuan, jilbab memberikan rasa percaya diri dan menjadi bagian dari ekspresi gaya pribadi yang membuat mereka merasa lebih elegan dan cantik.
Seiring dengan kemunculan berbagai model dan butik khusus, jilbab kini juga dapat menunjukkan kelas sosial tertentu. Tren ini menunjukkan bahwa jilbab telah menjadi alat bagi perempuan Muslim urban untuk mengkomunikasikan identitas “Muslim modern” yang dapat memadukan ketaatan agama dengan modernitas. Jilbab tidak lagi dianggap sebagai simbol kekunoan atau keterasingan, melainkan sebagai sebuah pernyataan identitas yang dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Debat Publik dan Tantangan Kontemporer
Meskipun jilbab telah diterima secara luas, isu-isu teologis dan sosial-politik yang terkait dengannya terus menjadi sumber perdebatan dan ketegangan.
Perdebatan Teologis: Jilbab Wajib atau Pilihan?
Perdebatan tentang status hukum jilbab terus berlanjut di kalangan Muslim di Indonesia. Pandangan yang mewajibkan (wajib) mendasarkan argumennya pada penafsiran tekstual Al-Qur’an (Al-Ahzab: 59, An-Nur: 31) dan hadis, serta konsensus ulama (ijma’) bahwa jilbab adalah kewajiban syariat bagi seluruh perempuan Muslim. Pandangan ini menolak klaim bahwa jilbab hanya pilihan personal atau bahwa perempuan yang tidak memakainya tidak berdosa.
Di sisi lain, terdapat pandangan yang melihat jilbab sebagai isu khilafiyah (perbedaan pendapat yang tidak fundamental). Pandangan ini menekankan bahwa jilbab adalah pilihan personal yang harus dihormati, dan tidak ada jaminan bahwa seorang yang berjilbab lebih saleh daripada yang tidak. Perdebatan ini mencerminkan dinamika intelektual di dalam komunitas Muslim Indonesia, yang berupaya menafsirkan teks suci dalam konteks masyarakat modern yang beragam.
Pandangan Institusi Islam Utama: NU dan Muhammadiyah tentang Jilbab
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki pandangan yang menunjukkan pola toleransi dan pragmatisme khas Indonesia.
Tabel 2: Perbandingan Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang Jilbab
| Aspek | Pandangan Muhammadiyah | Pandangan NU | |
| Status Hukum | Menganggap jilbab sebagai kewajiban religius bagi perempuan Muslim yang telah baligh. | Menganjurkan diskusi yang sehat dan konstruktif, tanpa menyebut fatwa tunggal, namun penafsiran ulama NU cenderung mewajibkan jilbab. | |
| Batasan Aurat | Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, berdasarkan Q.s. an-Nur: 31, Q.s. al-Ahzab: 59, hadis, dan kisah sahabat perempuan Nabi. | Mengakui adanya perbedaan pendapat, namun menekankan bahwa aurat yang rawan (seperti dada) harus ditutup, dan jilbab harus menutup aurat secara umum. | |
| Model Pakaian | Mengizinkan model dan warna busana yang beragam, termasuk kerudung yang menutupi dada, asalkan tidak ketat dan memenuhi ketentuan agama.35 Mereka menolak kewajiban | niqab atau cadar.Tidak memaksakan model spesifik, tetapi menekankan jilbab yang sesuai dengan budaya lokal, asalkan menutupi aurat. | |
| Sikap terhadap Pemaksaan | Secara tegas menentang larangan jilbab pada era Orde Baru dan siap menerima siswi yang didiskriminasi ke sekolah Muhammadiyah. | Menegaskan bahwa pemakaian jilbab di sekolah negeri tidak boleh dipaksakan karena itu adalah ranah individu. |
Isu-isu Kontemporer: Pemaksaan Jilbab
Meskipun jilbab telah diakomodasi secara nasional, kasus pemaksaan masih terjadi di tingkat lokal dan institusional. Studi kasus di SMAN 1 Sumberlawang, Sragen, dan SMAN 1 Banguntapan, Bantul pada tahun 2022 menunjukkan bahwa siswi dipaksa berjilbab oleh guru hingga mengalami trauma dan depresi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa konflik tentang jilbab telah bergeser dari pertentangan antara negara dan rakyat menjadi pertentangan antara institusi atau individu dengan hak asasi manusia.
Di Aceh, pemberlakuan syariat Islam membuat jilbab menjadi wajib bagi setiap perempuan, termasuk non-muslim, yang menuai protes dan dianggap sebagai pelanggaran hak dan bentuk intoleransi. Isu-isu ini menunjukkan bahwa perjuangan terkait jilbab belum selesai. Perdebatan terus berlanjut di ruang publik, terutama di media sosial, di mana perdebatan tentang estetika dan nilai-nilai religius jilbab modern berlangsung sengit.
Analisis dan Kesimpulan: Jilbab sebagai Penanda Perubahan Sosial Indonesia
Perjalanan historis jilbab di Indonesia adalah sebuah narasi tentang pergeseran makna yang kompleks dan dinamis, mencerminkan perjalanan bangsa itu sendiri. Dari analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa makna jilbab telah bergeser secara signifikan melalui empat fase utama:
- Tradisi dan Adat (Pra-1900): Jilbab adalah fenomena lokal yang sporadis, terkait dengan status sosial dan budaya di kantong-kantong Islam yang mapan.
- Identitas Pergerakan (Awal 1900-an): Jilbab menjadi bagian dari proyek modernisasi dan reformasi Islam yang terorganisir, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan dan Rasuna Said.
- Simbol Perlawanan Politik (1980-1991): Kebijakan represif pemerintah Orde Baru secara tidak sengaja mengubah jilbab menjadi simbol perlawanan ideologis.
- Ekspresi Gaya Hidup dan Identitas Diri (Pasca-1991): Setelah larangan dicabut, jilbab bertransformasi menjadi bagian dari budaya pop, industri mode, dan ekspresi identitas pribadi yang multifungsi.
Jilbab, pada akhirnya, adalah sebuah mikrokosmos dari dinamika kompleks yang membentuk identitas Indonesia kontemporer. Sejarahnya merefleksikan perjuangan bangsa melawan kolonialisme, menghadapi otoritarianisme, dan kini bergulat dengan isu-isu pluralisme, hak asasi manusia, dan kapitalisme global. Memahami sejarah jilbab di Indonesia berarti memahami interaksi yang rumit antara agama, politik, dan budaya dalam membentuk identitas sebuah bangsa. Fenomena ini menunjukkan bahwa jilbab tidak bisa dilihat sebagai satu simbol statis, melainkan sebagai sebuah penanda yang kaya akan makna dan terus berevolusi seiring dengan perubahan masyarakat Indonesia.

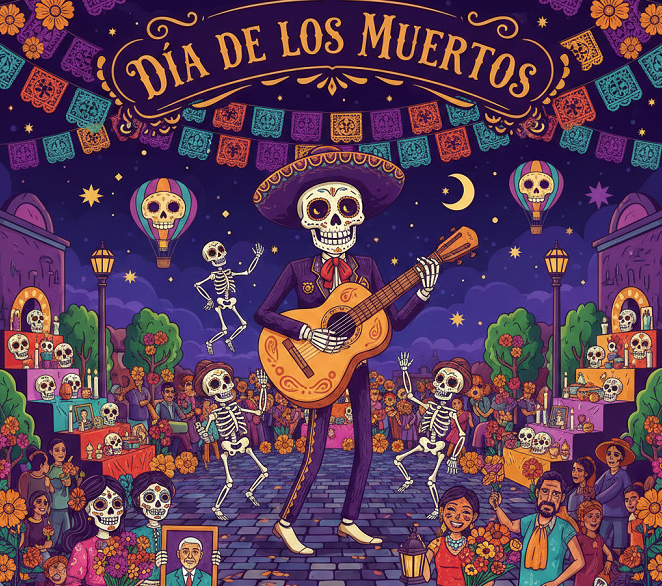

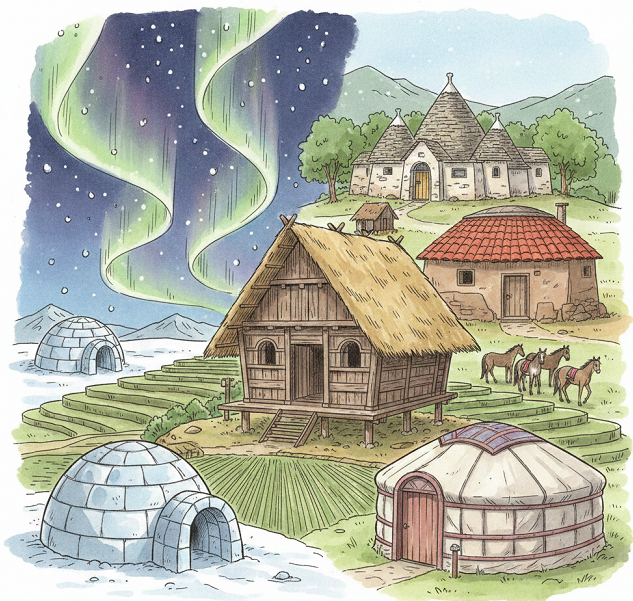









Post Comment