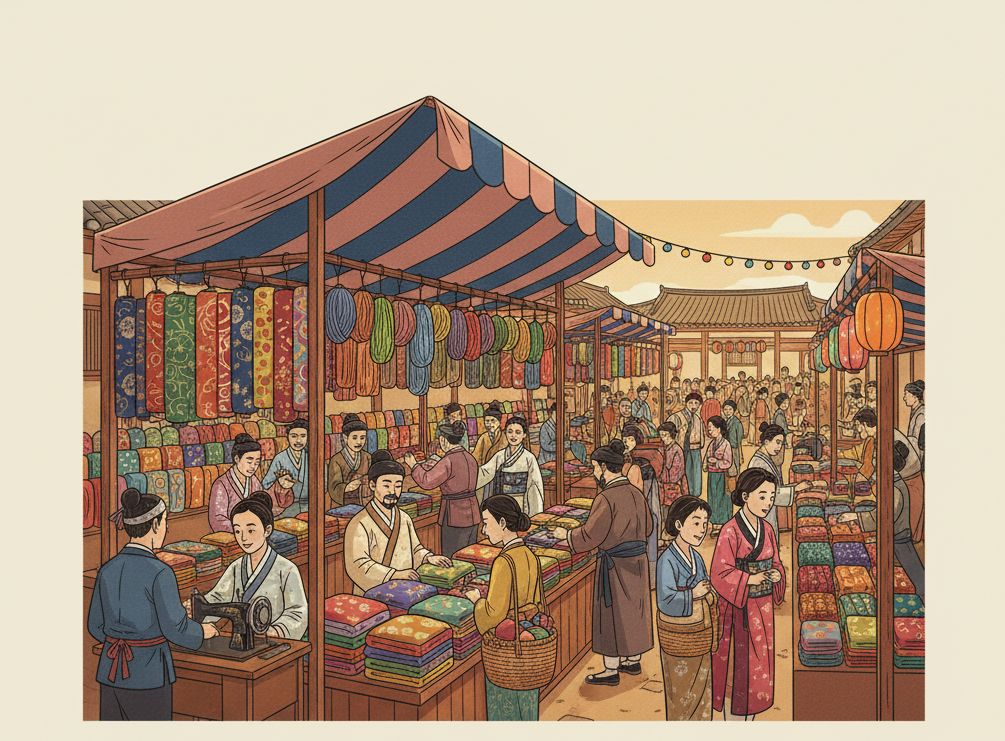Ulasan Pasar Tekstil dan Pakaian Jadi di Indonesia
Industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) di Indonesia berdiri di persimpangan jalan yang kompleks. Secara makro, sektor ini menunjukkan kinerja yang tangguh, mencatatkan pertumbuhan positif dan memberikan kontribusi substansial terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Data investasi dan ekspor juga mengindikasikan adanya momentum pertumbuhan. Namun, narasi optimisme ini kontradiktif dengan realitas di lapangan. Industri TPT, terutama yang berorientasi pada pasar domestik, tertekan oleh gelombang impor ilegal dan diskoordinasi kebijakan pemerintah yang menciptakan ketidakpastian.
Analisis ini menemukan bahwa masa depan industri TPT Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan struktural yang mendesak. Tanpa penyelarasan kebijakan yang tegas dan pengawasan yang efektif terhadap impor ilegal, potensi pertumbuhan yang ada—seperti peluang dari pergeseran rantai pasok global dan peningkatan daya beli domestik—akan sulit direalisasikan. Tulisan ini menggarisbawahi perlunya modernisasi industri, diversifikasi produk ke segmen bernilai tambah tinggi, dan adopsi praktik berkelanjutan sebagai fondasi untuk membangun daya saing jangka panjang.
Kinerja Ekonomi dan Dinamika Ketenagakerjaan
Kontribusi Industri Tekstil terhadap Perekonomian Nasional
Industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) di Indonesia merupakan salah satu sektor manufaktur unggulan yang vital bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2024, sebuah angka yang melampaui pertumbuhan PDB nasional pada periode yang sama. Kinerja yang solid ini diterjemahkan menjadi kontribusi ekonomi yang signifikan, di mana industri TPT menyumbang sebesar Rp218,2 triliun terhadap PDB nasional sepanjang tahun lalu. Capaian ini juga didukung oleh pertumbuhan subsektornya, dengan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 5,90% dan industri TPT tumbuh 2,64% pada kuartal pertama 2024.
Meskipun kontribusi PDB-nya substansial, analisis investasi menunjukkan bahwa sektor TPT masih menghadapi tantangan dalam menarik modal dalam skala besar. Total nilai investasi di sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki meningkat dari Rp24,6 triliun pada 2022 menjadi Rp27,9 triliun pada 2023, dengan nilai Rp6,9 triliun pada kuartal pertama 2024. Meskipun demikian, proporsi investasi sektor tekstil terhadap total investasi industri pengolahan non-migas nasional pada tahun 2024 hanya sebesar 3%. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan sektor lain seperti makanan dan minuman (32%) dan logam dasar (14%). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun investasi di sektor ini bertambah, skalanya belum sebanding dengan sektor prioritas lain. Adapun struktur industri TPT terbilang padat, dengan 1.992 perusahaan besar dan sedang di industri tekstil dan 1.960 di manufaktur pakaian jadi yang beroperasi pada 2023.
Gambaran Ketenagakerjaan: Antara Statistik dan Realitas di Lapangan
Industri TPT dikenal sebagai sektor padat karya yang menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, industri TPT telah menyerap 3,97 juta tenaga kerja, yang merupakan 19,9% dari total tenaga kerja industri manufaktur.
Namun, data makro ini menyembunyikan realitas ketenagakerjaan yang jauh lebih suram. Industri TPT, terutama di subsektor tekstil (hulu), mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif. Jumlah tenaga kerja di sektor tekstil turun drastis dari 1.248.080 orang pada 2015 menjadi 957.122 orang pada 2024. Tulisan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebutkan bahwa hingga Mei 2024, total PHK di industri TPT mencapai 10.800 tenaga kerja, dengan angka sesungguhnya yang diperkirakan jauh lebih besar karena banyak pekerja kontrak yang tidak tercatat. Data lain dari Kementerian Ketenagakerjaan bahkan mencatat hampir 60.000 orang terkena PHK dari Januari hingga Oktober 2024, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling terdampak.
Kondisi ini menciptakan narasi yang sangat kontradiktif antara pertumbuhan PDB yang positif dan PHK yang masif. Pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan sektor ini mungkin didorong oleh segmen-segmen tertentu, seperti perusahaan berorientasi ekspor yang memiliki efisiensi tinggi, atau didorong oleh lonjakan permintaan di segmen produk tertentu. Namun, pertumbuhan ini tampaknya tidak merata dan tidak cukup kuat untuk menopang seluruh rantai nilai, terutama perusahaan yang berfokus pada pasar domestik. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas yang memungkinkan pertumbuhan output dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, namun di saat yang sama banyak perusahaan yang tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menutup operasinya. Kasus pailitnya raksasa tekstil seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi bukti nyata bahwa tekanan pasar eksternal dan masalah internal dapat menyebabkan kegagalan perusahaan skala besar, meskipun data makro menunjukkan tren positif secara umum.
Tabel 1.1: Statistik Kinerja Makro Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Indonesia (2023-2024)
| Indikator Kinerja | Data Kunci (2023-2024) | Implikasi |
| Kontribusi PDB | Rp218,2 triliun (2024) | Menunjukkan peran vital industri TPT dalam perekonomian nasional. |
| Pertumbuhan PDB (yoy) | 4,26% (2024) | Menunjukkan sektor ini tumbuh positif, melebihi pertumbuhan PDB nasional. |
| Investasi | Rp27,9 triliun (2023), naik dari Rp24,6 triliun (2022) | Mengindikasikan adanya minat investasi, namun kontribusinya masih kecil. |
| Penyerapan Tenaga Kerja | 3,97 juta orang (Agustus 2024) | Sektor padat karya yang menyumbang 19,9% dari total tenaga kerja manufaktur. |
| Jumlah PHK | Hampir 60.000 orang (Januari-Oktober 2024) | Kontradiktif dengan data penyerapan tenaga kerja, menandakan krisis di lapangan. |
| Jumlah Perusahaan | 1.992 (tekstil) & 1.960 (pakaian jadi) unit usaha besar/sedang (2023) | Menggambarkan skala industri yang luas dan beragam. |
| Biaya Bahan Baku | Rp121,249 miliar (2023) | Menunjukkan biaya bahan baku adalah komponen biaya utama yang menekan industri. |
Dinamika Perdagangan dan Persaingan Global
Tren Ekspor dan Pasar Strategis
Dari sisi perdagangan internasional, industri TPT Indonesia menunjukkan performa ekspor yang menjanjikan. Nilai ekspor industri ini mencapai US1,02miliarpadaFebruari2025,naik1,4111,96 miliar, menandai pertumbuhan sebesar 2,67% dan berkontribusi 6,08% dari total ekspor industri manufaktur nasional. Amerika Serikat (AS) secara konsisten menjadi pasar utama ekspor, menyerap lebih dari 50% dari total ekspor pakaian jadi Indonesia sejak 2018. Pada Februari 2025, ekspor ke AS naik 4,13% secara bulanan menjadi US$17,4 juta, dan secara tahunan volume ekspor ke AS mencapai 153.500 ton pada 2024. Negara tujuan ekspor penting lainnya termasuk Jepang, Jerman, dan Korea Selatan.
Ancaman Impor: Legal vs. Ilegal
Meskipun neraca perdagangan TPT resmi mencatatkan kenaikan surplus sebesar 20,99% pada 2024, realitas di pasar domestik sangat tertekan. Ancaman terbesar datang dari serbuan produk impor, terutama yang ilegal. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) memperkirakan adanya 72.250 kontainer TPT ilegal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia dalam lima tahun terakhir, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp46 triliun. Impor ilegal ini tidak hanya mencuri pangsa pasar, tetapi juga merusak harga dan menekan margin keuntungan produsen lokal, yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan pabrik dan PHK massal.
Kondisi ini menciptakan “defisit tersembunyi” dalam perdagangan TPT. Surplus perdagangan resmi mencerminkan daya saing industri TPT Indonesia di pasar global, namun keberadaan impor ilegal yang masif menunjukkan bahwa pemerintah kehilangan kendali atas pasar domestiknya sendiri. Hal ini menciptakan dua realitas yang berbeda: industri yang berorientasi ekspor mungkin bertahan atau bahkan tumbuh, sementara industri yang berfokus pada pasar domestik runtuh. Kegagalan ini tidak hanya merusak industri, tetapi juga menghancurkan lapangan kerja dan menyebabkan kerugian besar bagi pendapatan negara.
Analisis Perbandingan: Indonesia vs. Vietnam dan Bangladesh
Untuk memahami posisi Indonesia di peta persaingan global, penting untuk membandingkannya dengan negara-negara pesaing utama, khususnya Vietnam dan Bangladesh. Kedua negara ini, seperti Indonesia, bukan bagian dari lima besar eksportir tekstil global tetapi merupakan pemain kunci.
Bangladesh memiliki keunggulan utama dalam biaya tenaga kerja yang sangat kompetitif, yang memungkinkan produksi tekstil dengan harga lebih rendah. Sektor garmen di negara ini menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan ekspornya. Namun, keunggulan ini datang dengan tantangan serius, termasuk upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan masalah lingkungan yang parah akibat praktik fast fashion.
Vietnam, di sisi lain, menekankan pada modernisasi. Negara ini dikenal karena infrastruktur yang sangat baik, termasuk pelabuhan modern dan jaringan transportasi yang efisien, yang memfasilitasi proses ekspor dan menurunkan biaya logistik. Pabrik-pabrik di Vietnam memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem ERP, IoT, dan teknologi digital twin untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol kualitas. Meskipun upah di sektor manufaktur Vietnam lebih tinggi dibandingkan Bangladesh, tenaga kerjanya dikenal terampil dengan program pelatihan yang terstruktur.
Posisi Indonesia berada di antara kedua model ini. Indonesia tidak memiliki upah serendah Bangladesh, tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal adopsi teknologi dan infrastruktur dibandingkan Vietnam. Namun, dengan meningkatnya biaya tenaga kerja di Vietnam dan tuntutan global yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, Indonesia memiliki jendela peluang strategis. Merek-merek global kini mencari alternatif selain Tiongkok dan semakin mengaudit pabrik berdasarkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Untuk memanfaatkan peluang dari tren near-shoring ini, Indonesia harus membenahi masalah internalnya, seperti biaya produksi yang tinggi, ketergantungan pada bahan baku impor, dan inkonsistensi regulasi. Tanpa reformasi ini, peluang tersebut berisiko jatuh ke tangan pesaing.
Tabel 2.1: Perbandingan Daya Saing Industri Tekstil Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh
| Kriteria | Indonesia | Vietnam | Bangladesh |
| Biaya Tenaga Kerja | Moderat, variatif di setiap wilayah ([25]) | Relatif lebih tinggi, dengan upah manufaktur sekitar 8380 ribu VND/bulan ([16]) | Sangat kompetitif, menjadi daya tarik utama ([13]) |
| Infrastruktur Logistik | Terpusat di Jawa, dengan pelabuhan utama seperti Tanjung Priok ([10]) | Efisien dan modern, dengan pelabuhan canggih ([13]) | Rantai pasok yang sudah mapan dan jaringan ekspor luas ([13]) |
| Keunggulan Teknologi | Implementasi Industri 4.0 masih hadapi tantangan | Mengadopsi teknologi canggih seperti ERP, IoT, dan digital twin | Menggunakan sistem ERP dan pemantauan digital untuk efisiensi |
| Isu Keberlanjutan | Mulai berinvestasi dalam standar ESG dan kebijakan hijau | Menerapkan teknologi dan proses produksi hemat energi | Hadapi tantangan serius terkait polusi air dan udara) |
| Fokus Pasar Utama | Amerika Serikat, Jepang, Jerman | AS dan pasar global lainnya | Pasar global, didukung harga yang kompetitif |
Lanskap Kompetitif dan Analisis Kasus Studi
Profil Pemain Utama dan Dinamika Pasar
Lanskap kompetitif industri TPT Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar. Terdapat setidaknya 22 emiten industri TPT yang terdaftar di bursa saham. Di antara mereka, PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) menjadi pemain dengan pendapatan terbesar pada 2024, mencapai Rp13,9 triliun, diikuti oleh PT Pan Brothers Tbk (PBRX) dengan pendapatan Rp5,1 triliun. Selain perusahaan publik, terdapat juga pemain besar yang terintegrasi penuh dari hulu ke hilir, seperti PT Kahatex dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang memproduksi benang, kain, hingga pakaian jadi. Kehadiran perusahaan-perusahaan terintegrasi ini menunjukkan kemampuan industri dalam mengelola seluruh rantai produksi, memberikan keunggulan kompetitif signifikan dalam hal kualitas dan efisiensi operasional.
Kasus Studi: Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)
Kejatuhan Sritex, yang dulunya merupakan salah satu perusahaan tekstil terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh industri. Kehancuran perusahaan ini tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan eksternal. Tulisan menunjukkan bahwa faktor internal, seperti beban utang yang membengkak hingga US$1,6 miliar pada 2022 dan kegagalan manajemen dalam mengelola utang dan ekspansi yang berisiko, menjadi penyebab utama. Sritex kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya dan gagal mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan kreditur.
Namun, faktor eksternal turut memperparah kondisi. Krisis ekonomi global pasca-pandemi dan serbuan produk impor ilegal dari Tiongkok membanjiri pasar domestik. Produk impor ilegal ini, dengan harga yang jauh lebih murah, secara signifikan merusak daya saing produk lokal seperti yang diproduksi oleh Sritex, menekan margin keuntungan, dan akhirnya mendorong perusahaan ke jurang kebangkrutan. Kejatuhan Sritex menunjukkan bahwa bahkan pemain besar pun rentan terhadap kombinasi manajemen yang lemah dan lingkungan pasar yang tidak terlindungi. Kegagalan ini menyoroti perlunya tata kelola perusahaan yang kuat dan kebijakan pemerintah yang protektif dan konsisten.
Strategi Adaptasi dan Keberlanjutan: Contoh PT Pan Brothers Tbk
Sebagai respons terhadap tantangan pasar dan tuntutan global, beberapa perusahaan menerapkan strategi adaptasi yang berfokus pada keberlanjutan dan digitalisasi. PT Pan Brothers Tbk (PBRX), misalnya, menempatkan diri sebagai pemimpin dalam industri garmen yang berkelanjutan. Perusahaan ini mengadopsi program Pembangunan Berkelanjutan yang berlandaskan pada konsep ‘Triple Bottom Line’—People, Planet, Profit—dan selaras dengan 10 tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Strategi ini mencakup langkah-langkah konkret seperti mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030, menggunakan energi terbarukan, dan menerapkan manajemen limbah yang bertanggung jawab.
Di samping itu, PBRX juga berinvestasi dalam digitalisasi dan teknologi Industry 4.0 untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Pilihan strategis PBRX ini sejalan dengan temuan analisis bahwa merek global kini semakin menuntut standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dari pabrik pemasok mereka. Strategi PBRX menunjukkan bahwa investasi dalam keberlanjutan dan teknologi bukan lagi sekadar biaya, melainkan prasyarat untuk mendapatkan kontrak dari pembeli internasional. Dengan memprioritaskan praktik yang etis dan ramah lingkungan, perusahaan Indonesia dapat meningkatkan reputasinya dan mengamankan posisi yang lebih baik dalam tren near-shoring global, bersaing bukan hanya pada harga, tetapi juga pada nilai tambah dan praktik yang bertanggung jawab.
Kerangka Kebijakan Pemerintah dan Regulasi
Regulasi Impor: Sebuah Arena Pertarungan Kebijakan
Kerangka kebijakan pemerintah dalam mengatur impor tekstil menjadi faktor krusial dalam menentukan nasib industri dalam negeri. Pada satu sisi, terdapat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 5 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memperkuat industri TPT dengan mengatur penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai syarat impor. Aturan ini dirancang untuk memulihkan industri padat karya dan mengendalikan masuknya produk impor.
Namun, pada sisi lain, kebijakan ini berbenturan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi ini justru merelaksasi Permendag sebelumnya (Nomor 36 Tahun 2023) dengan menghapus persyaratan Pertek dari Kemenperin untuk beberapa komoditas, termasuk tekstil. Relaksasi ini, yang disinyalir sebagai respons terhadap penumpukan kontainer di pelabuhan, memfasilitasi masuknya produk impor, dan menurut pelaku industri, justru mempercepat kehancuran industri TPT nasional.
Pertentangan antara Permenperin dan Permendag ini adalah contoh nyata dari diskoordinasi antar-kementerian yang menimbulkan risiko sistemik. Kebijakan yang saling bertolak belakang ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, merusak kepercayaan investor, dan secara tidak langsung membiarkan impor ilegal merajalela. Insentif investasi yang ditawarkan pemerintah tidak akan efektif jika masalah utama, yaitu banjir impor ilegal, tidak diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu menyelaraskan kebijakannya dan memperkuat pengawasan untuk memastikan lingkungan bisnis yang adil dan stabil.
Insentif dan Peta Jalan Industri Masa Depan
Pemerintah juga sedang menyiapkan insentif pajak, seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk industri padat karya pada tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan daya saing. Namun, pelaku industri, melalui Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), mengkritik bahwa insentif ini tidak akan efektif tanpa menyelesaikan masalah utama, yaitu serbuan produk impor ilegal.
Selain insentif fiskal, pemerintah telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 sejak 2018 sebagai peta jalan untuk mentransformasi sektor manufaktur. Di sektor TPT, adopsi Industri 4.0 menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk fungsional seperti pakaian olahraga dan medis. Namun, implementasi program ini masih menghadapi hambatan seperti miskonsepsi antara Industry 3.0 dan 4.0, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil.
Di sisi keberlanjutan, pemerintah telah menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) melalui Permenperin Nomor 40 Tahun 2022 sebagai langkah proaktif dalam merespons tuntutan pasar global. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong produsen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan menurunkan emisi gas rumah kaca, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Proyeksi Pasar dan Arah Masa Depan
Proyeksi Pertumbuhan dan Faktor Pendorong
Terdapat dualisme yang jelas dalam proyeksi masa depan industri TPT Indonesia. Di satu sisi, tulisan dari Mordor Intelligence memproyeksikan pertumbuhan pasar yang stabil. Pasar tekstil Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari US 40,15 miliarpada 2025 menjadiUS 46,07 miliar pada 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sebesar 2,79%. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor makro:
- Peningkatan Daya Beli Domestik: PDB Indonesia yang terus tumbuh telah meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk produk pakaian bermerek dan berkualitas tinggi, menciptakan permintaan yang stabil di pasar domestik.
- Tren Near-Shoring: Merek-merek global mengalihkan sebagian produksi mereka dari Tiongkok ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam strategi “China+1” untuk mengurangi risiko ketergantungan. Perjanjian perdagangan baru dan peningkatan standar ESG di pabrik-pabrik Indonesia semakin mengamankan kontrak-kontrak ekspor bernilai tinggi.
- Perluasan E-commerce: Peraturan pemerintah yang mendukung penjualan online telah mempermudah produsen lokal, khususnya UMKM, untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan perputaran modal kerja.
Namun, proyeksi optimis ini berlawanan dengan pandangan pesimis dari APSyFI, yang memproyeksikan industri TPT masih akan terpuruk pada 2025 jika pemerintah tidak mengambil tindakan tepat. Pandangan ini menekankan bahwa faktor-faktor fundamental seperti banjir impor ilegal dan beban tambahan dari kenaikan PPN tidak akan teratasi dalam waktu dekat, sehingga menggerus daya saing industri dari dalam. Analisis menunjukkan bahwa masa depan industri ini sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah struktural yang mendesak, terutama penegakan hukum terhadap impor ilegal dan harmonisasi kebijakan antar-kementerian.
Peluang dalam Diversifikasi dan Keberlanjutan
Proyeksi pertumbuhan juga menyoroti pergeseran fokus produk. Pertumbuhan tercepat diperkirakan datang dari segmen-segmen bernilai tambah tinggi, seperti tekstil industrial/teknis dengan CAGR 4,2% dan kain non-tenun (non-wovens) dengan CAGR 4,1%. Produk-produk ini meliputi geotextile, bahan baku untuk otomotif, hingga kain untuk masker medis dan popok higienis. Ini mengindikasikan bahwa industri perlu bergeser dari sekadar memproduksi pakaian jadi massal ke produk-produk khusus yang menawarkan margin lebih baik dan permintaan lebih stabil.
Selain itu, bahan baku juga menunjukkan tren menarik. Meskipun serat sintetis, terutama poliester, akan terus mendominasi pasar, penggunaan serat daur ulang (seperti benang PET daur ulang) semakin mendapatkan momentum. Hal ini didorong oleh tekanan dari merek-merek global untuk praktik manufaktur yang lebih sirkular. Investasi dalam fasilitas daur ulang botol menjadi serat akan menjadi kunci untuk memanfaatkan tren keberlanjutan global ini.
Rekomendasi Strategis
Berdasarkan analisis yang komprehensif, berikut adalah rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada:
Rekomendasi untuk Pemerintah
- Penyelarasan Kebijakan dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus segera menyelaraskan regulasi impor antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pengawasan Bea Cukai harus diperketat secara signifikan untuk memberantas impor ilegal yang menjadi penyebab utama kehancuran industri dan PHK massal. Tanpa langkah ini, insentif apapun tidak akan efektif.
- Dukungan untuk Modernisasi Industri: Pemerintah perlu memberikan insentif yang ditargetkan untuk membantu produsen mengatasi masalah struktural, seperti biaya energi yang tinggi dan ketergantungan pada bahan baku impor. Fasilitasi akses ke pembiayaan berbiaya rendah juga krusial untuk modernisasi mesin-mesin yang sudah usang.
Rekomendasi untuk Pelaku Industri
- Diversifikasi Produk: Produsen harus secara strategis bergeser dari produksi fesyen massal ke segmen-segmen bernilai tambah tinggi seperti tekstil teknis dan industrial. Investasi dalam riset dan pengembangan akan membuka peluang di pasar yang lebih stabil dan menguntungkan.
- Adopsi Teknologi dan Keberlanjutan: Perusahaan harus memprioritaskan investasi dalam teknologi Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Seiring dengan itu, implementasi praktik manufaktur berkelanjutan dan kepatuhan terhadap standar ESG tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan untuk menarik dan mempertahankan kontrak dari pembeli internasional yang sadar lingkungan.
Kesimpulan
Industri tekstil Indonesia menghadapi dilema akut. Di satu sisi, data makro menunjukkan kinerja yang positif, didukung oleh prospek pertumbuhan dari permintaan domestik dan tren global seperti near-shoring. Di sisi lain, realitas di lapangan sangatlah rapuh. Fondasi industri terkikis oleh masalah fundamental yang tidak terselesaikan, terutama serbuan produk impor ilegal dan ketidakpastian regulasi. Masa depan industri TPT Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah mendesak ini, sementara pelaku industri secara proaktif beradaptasi melalui diversifikasi dan modernisasi. Tanpa kolaborasi yang kuat dan tindakan yang tegas dari semua pihak, potensi besar yang dimiliki industri ini akan terus terkikis, mengancam kelangsungan hidupnya dan menyebabkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang signifikan.