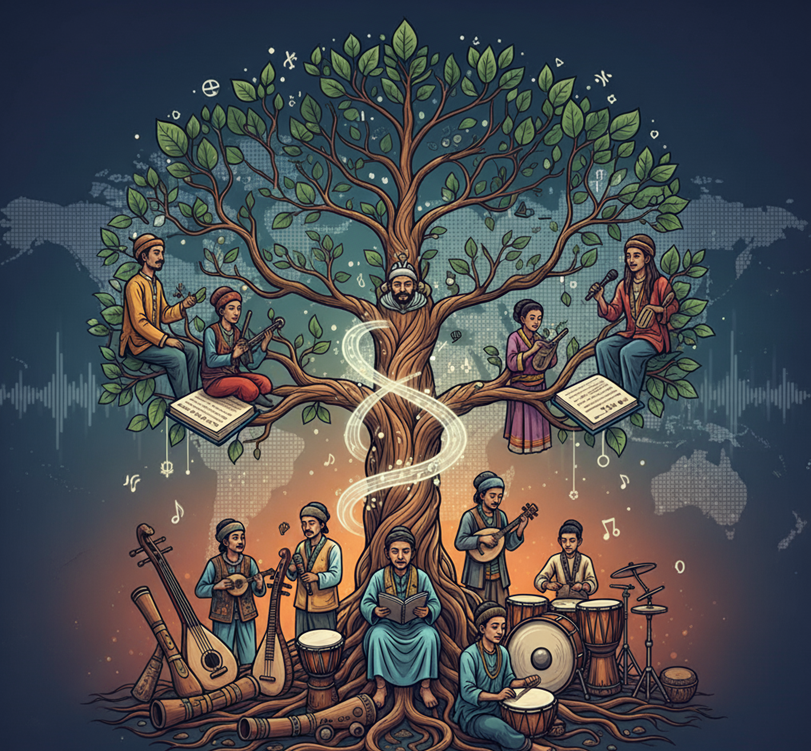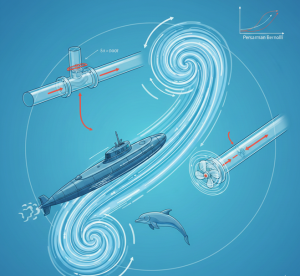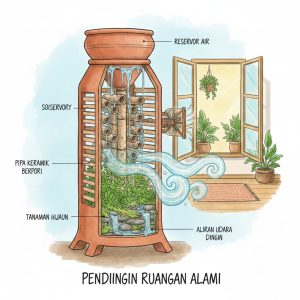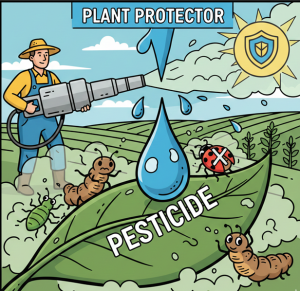Ulasan tentang Etnomusikologi di Indonesia
Etnomusikologi di Indonesia, sebuah disiplin ilmu yang telah mengalami transformasi signifikan dari kajian eksternal yang bersifat kolonial menjadi gerakan internal yang berorientasi pada pelestarian dan pemberdayaan budaya. Etnomusikologi di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat penelitian akademik, tetapi juga sebagai “pamong kebudayaan” —seorang pemandu dan penjaga tradisi musikal di tengah derasnya arus globalisasi.
Analisis ini mengelaborasi sejarahnya, dimulai dari era perintis asing yang mendokumentasikan musik Nusantara, hingga pembentukan lembaga pendidikan domestik yang melahirkan etnomusikolog dari kalangan “orang dalam”. Tulisan ini menyoroti keragaman musik Nusantara melalui studi kasus Gamelan dari Jawa dan Bali, Gondang Batak, dan Sasando NTT, yang masing-masing merepresentasikan filosofi, spiritualitas, dan adaptasi budaya yang unik.
Selain itu, tulisan ini memetakan tantangan kritis yang dihadapi musik tradisional di era kontemporer, seperti komersialisasi yang mengikis kesakralan dan penurunan minat generasi muda. Sebagai respons, diusulkan strategi multi-lapis untuk pelestarian, termasuk integrasi pendidikan, dokumentasi digital berbasis teknologi, dan inovasi artistik yang berakar pada tradisi. Tulisan ini menegaskan bahwa keberlanjutan etnomusik di Indonesia membutuhkan intervensi aktif yang menggabungkan metodologi ilmiah, kreativitas artistik, dan pemahaman sosial yang mendalam.
Etnomusikologi sebagai Disiplin Ilmu di Indonesia
Bagian ini meletakkan fondasi konseptual dan historis etnomusikologi, menyoroti pergeseran paradigma dari sudut pandang eksternal ke pendekatan internal yang berakar pada budaya Indonesia. Disiplin ini, yang melampaui musikologi tradisional yang fokus pada aspek teknis musik Barat, menawarkan lensa untuk memahami musik sebagai sebuah fenomena yang terintegrasi secara holistik dengan kehidupan manusia.
Definisi dan Ruang Lingkup Etnomusikologi
Etnomusikologi didefinisikan secara luas sebagai studi interdisipliner tentang musik yang menekankan dimensi budaya, sosial, material, kognitif, dan biologis. Berbagai akademisi telah merumuskan definisi yang mencerminkan evolusi disiplin ilmu ini. Jaap Kunst, salah satu pionir, memandang etnomusikologi sebagai “studi musik tradisional dan instrumen musik dari seluruh lapisan kebudayaan umat manusia, dari mulai orang-orang primitif hingga bangsa-bangsa beradab”. Definisi ini, meskipun bersejarah, mencerminkan kecenderungan etnosentrisme pada masanya, di mana musik non-Barat dipandang sebagai “eksotik” atau “primitif”.
Seiring waktu, paradigma bergeser. Bruno Nettl, Willi Apel, dan Mantle Hood mendefinisikan etnomusikologi sebagai ilmu yang mempelajari musik dalam kebudayaan manusia, terutama di luar peradaban Barat. Mantle Hood, khususnya, mendeskripsikan etnomusikologi sebagai “suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek penyelidikan seni musik sebagai gejala-gejala fisik, psikologi, estetik, dan budaya”. Pergeseran ini menunjukkan pengakuan yang lebih besar terhadap musik sebagai sebuah sistem budaya yang kompleks dan bukan sekadar objek “eksotik” untuk dikoleksi. Ini adalah pergeseran yang fundamental dari pandangan yang bersifat superior ke pandangan yang lebih menghargai. Mantle Hood, misalnya, mendorong pendekatan “bi-musicality” yang mengharuskan peneliti untuk belajar memainkan musik yang mereka teliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami musik “dari dalam,” merasakan tantangan teknis, konseptual, dan estetiknya, serta membangun koneksi sosial yang lebih dalam dengan komunitas yang diteliti.
Lintasan Sejarah Etnomusikologi di Indonesia: Dari Peneliti Asing hingga “Orang Dalam”
Lintasan sejarah etnomusikologi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua babak utama: era perintis asing dan era pembentukan institusi domestik. Babak pertama dimulai dengan kedatangan para peneliti Barat yang memiliki minat untuk mempelajari musik di luar budayanya sendiri. Salah satu tokoh paling penting adalah etnomusikolog Belanda, Jaap Kunst, yang tinggal di Indonesia dari tahun 1919 hingga 1934. Ia melakukan rekaman ekstensif terhadap musik Indonesia dan menjadikan temuannya sebagai bahan ajar dan dasar pengembangan konsep etnomusikologi. Karyanya menjadi fondasi penting bagi kajian musik Nusantara di kancah internasional. Walter Spies, Colin Mcphee, Wim Van Janten, dan Mantle Hood juga merupakan nama-nama asing yang banyak meneliti dan menulis buku tentang musik etnis Indonesia pada masa awal ini.
Namun, pendekatan eksternal ini seringkali dikritik karena dianggap bersifat amatir dan dominatif, seolah-olah musik di luar Eropa hanya menarik dipelajari dari sudut pandang antropologi dan sosiologi, bukan untuk diakui pada tingkat kebudayaan dan keilmuannya. Perkembangan ini menunjukkan adanya sebuah dekolonisasi pengetahuan, di mana narasi dan interpretasi tidak lagi didominasi oleh sudut pandang asing. Bukti adanya kajian “orang dalam” sebenarnya sudah ada jauh sebelum etnomusikologi menjadi disiplin formal di Indonesia. Misalnya, Raden Machyar Angga Koesoemadinata telah merumuskan teori-teori karawitan Sunda ke dalam buku sejak tahun 1940-an.
Titik balik terjadi dengan pendirian institusi pendidikan formal di dalam negeri. Program Studi Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara (USU) berdiri pada tahun 1979 , disusul oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta pada tahun 1988. Pendirian lembaga-lembaga ini menandai babak baru, di mana etnomusikologi tidak lagi hanya dikaji oleh orang asing, tetapi juga dikembangkan dan diajarkan oleh, untuk, dan dari masyarakat Indonesia sendiri. Lulusan dari program-program ini diharapkan tidak hanya menjadi peneliti, tetapi juga “pamong kebudayaan” dan “pembaca situasi” yang membantu masyarakat mengendalikan dan mengarahkan perkembangan budaya mereka. Lulusan etnomusikologi kini tidak hanya berorientasi pada teori, melainkan juga pada praxis (tindakan praktis) seperti advokasi, konservasi, revitalisasi, dan inovasi tradisi musik Nusantara.
| Tahun | Tonggak Sejarah Etnomusikologi di Indonesia | Tokoh & Institusi Terkait |
| 1919-1934 | Jaap Kunst melakukan penelitian dan merekam musik Indonesia secara ekstensif. | Jaap Kunst, Mantle Hood, Walter Spies |
| 1940-an | Teori karawitan Sunda mulai dirumuskan oleh ahli karawitan lokal. | Raden Machyar Angga Koesoemadinata |
| 1979 | Pendirian Program Studi Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara (USU). | USU, The Ford Foundation, Monash University |
| 1988 | Pendirian Program Studi Etnomusikologi di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. | ISI Surakarta |
Keragaman Etnomusik Nusantara: Studi Kasus Analitis
Bagian ini menganalisis beberapa contoh representatif musik tradisional Indonesia untuk mengilustrasikan kekayaan etnomusik dan fungsi-fungsinya yang beragam. Musik-musik ini tidak hanya menawarkan pengalaman estetika, tetapi juga berfungsi sebagai cerminan filosofi, spiritualitas, dan identitas budaya masyarakatnya.
Gamelan: Kontras Estetika Jawa dan Bali
Gamelan adalah ansambel musik perkusi tradisional yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya di pulau Jawa dan Bali. Meskipun memiliki instrumen dasar yang serupa (metalofon, gong, dan kendang), Gamelan Jawa dan Gamelan Bali memiliki karakteristik yang sangat berbeda, yang mencerminkan filosofi budaya masyarakatnya.
Gamelan Jawa dikenal dengan nuansanya yang tenang, khidmat, dan filosofis. Musiknya dirancang untuk menenangkan jiwa pemain dan pendengar, menciptakan suasana yang seimbang dan menenangkan. Konsep karawitan, yang berasal dari kata Jawa rawit yang berarti ‘rumit’ atau ‘halus’, mengacu pada idealisasi kehalusan dan keanggunan dalam musik Jawa. Gamelan Jawa sering digunakan dalam konteks upacara keagamaan, pernikahan, dan pertunjukan wayang kulit , di mana ia berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kekhidmatan dan ketenangan spiritual.
Sebaliknya, Gamelan Bali dikenal dengan tempo yang dinamis, irama yang kompleks, dan energi yang hidup (vibrant), mencerminkan semangat rakyat Bali yang ekspresif. Gamelan Bali menampilkan teknik permainan kotekan, sebuah teknik interlocking yang menuntut koordinasi tinggi antar pemain untuk menciptakan pola ritme yang rumit dan cepat. Musik ini tidak hanya berfungsi sebagai pengiring upacara keagamaan yang meriah, seperti upacara pitra yadnya di Bali , tetapi juga sebagai elemen sentral yang menyemarakkan perayaan dan festival. Perbedaan yang mencolok ini menunjukkan bagaimana musik, dalam konteks etnomusikologi, tidak hanya menjadi cerminan, tetapi juga pembentuk identitas komunal yang unik.
| Aspek | Gamelan Jawa | Gamelan Bali |
| Tempo | Lebih lambat, tenang, dan khidmat | Lebih cepat dan dinamis |
| Irama | Kompleks, halus, dan berjenjang | Kompleks dan energetik, menggunakan teknik kotekan |
| Fungsi Utama | Ritual, meditasi, dan iringan wayang kulit | Iringan upacara adat dan perayaan yang meriah |
| Filosofi | Mengutamakan kehalusan dan ketenangan spiritual | Mengutamakan ekspresi, energi, dan perayaan komunal |
| Tujuan Musik | Menenangkan jiwa pemain dan pendengar | Menciptakan suasana yang meriah dan bersemangat |
Gondang Batak: Jembatan Menuju Dunia Spiritual
Gondang merupakan ansambel musik yang memegang peranan krusial bagi masyarakat Batak di Sumatera Utara. Secara khusus, ansambel gondang sabagunan menempatkan gordang—sebuah set gendang kayu yang dilapisi kulit sapi atau kerbau—sebagai instrumen bass utama. Fungsi utama Gondang melampaui sekadar hiburan; musik ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan spiritual. Masyarakat Batak menggunakan Gondang dalam upacara syukuran atau ritual yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara manusia dengan roh nenek moyang mereka.
Penggunaan Gondang dalam upacara adat, seperti saat menyambut pejabat pemerintah atau dalam acara perkawinan dan menari secara adat , menunjukkan bagaimana musik tradisional berfungsi ganda. Musik ini tidak hanya menjadi medium sakral untuk berkomunikasi dengan alam gaib, tetapi juga menjadi penanda identitas dan kebanggaan komunal yang diperlihatkan di ranah publik.
Sasando NTT: Simbol Adaptasi Budaya
Sasando adalah alat musik berdawai unik dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Terbuat dari tabung bambu dan wadah resonansi dari anyaman daun lontar, Sasando dimainkan dengan cara dipetik menggunakan kedua tangan secara berlawanan. Kisah penciptaannya, yang terikat pada legenda Sangguana yang membuat alat musik berbeda untuk meminang putri Raja , menunjukkan asal-usulnya yang kaya akan narasi budaya.
Meskipun secara tradisional digunakan untuk mengiringi nyanyian dan tarian, Sasando juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Alat musik ini dapat dimainkan dalam berbagai genre, dari musik tradisional hingga pop. Perkembangan Sasando listrik adalah contoh konkret dari inovasi yang berbasis pada tradisi. Kisah Sasando merupakan metafora untuk etnomusikologi itu sendiri—yaitu, bagaimana warisan budaya dapat dan harus beradaptasi untuk tetap relevan di era modern tanpa kehilangan esensinya.
Fungsi Sosial dan Ritual Musik Tradisional
Secara umum, musik tradisional di Indonesia memiliki fungsi yang jauh melampaui hiburan semata. Musik-musik ini tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran multifungsi:
- Sarana Ritual dan Keagamaan: Banyak musik tradisional, seperti Gamelan di Bali dan Gondang di Batak, diyakini memiliki kekuatan spiritual atau magis dan digunakan sebagai pelengkap tradisi dalam upacara kematian, perkawinan, atau persembahan kepada leluhur.
- Identitas dan Pendidikan: Musik tradisional merupakan cerminan kearifan lokal, nilai luhur, dan pandangan hidup masyarakat. Musik ini menjadi media yang memperkenalkan generasi muda pada nilai-nilai leluhur, seperti yang terlihat pada penggunaan talempong di Minangkabau yang menyampaikan pesan kebersamaan.
- Sarana Komunikasi: Di beberapa daerah, bunyi-bunyian tertentu dari instrumen musik digunakan sebagai tanda atau sarana komunikasi. Contoh klasik adalah penggunaan kentongan di Jawa untuk memberikan peringatan atau menyampaikan pesan kepada masyarakat.
| Nama Musik/Instrumen | Asal Daerah | Fungsi Utama |
| Musik Krumpyung | Yogyakarta | Iringan nyanyian vokal (tembang) |
| Keroncong | Jakarta | Musik yang berkembang dari pengaruh Portugis, kini menjadi genre yang dipadukan dengan gamelan. |
| Gong Luang | Bali | Iringan musik yang meriah, mirip gendhing Jawa namun dengan citarasa yang berbeda. |
| Gambang Kromong | Betawi | Awalnya menggunakan nada pentatonis dan alat musik Tiongkok, kini menjadi musik pertunjukan dengan lirik jenaka. |
| Krombi | Papua | Alat musik petik yang dimainkan dengan cara ditepuk. |
| Huda | Minangkabau | Musik tradisional bernuansa Islami yang dipadukan dengan budaya lokal. |
| Cilokak | Lombok | Musik tradisional yang dimainkan dengan berbagai instrumen seperti gambus dan seruling. |
| Karang Dodou | Kalimantan Timur | Iringan upacara adat saat pembacaan mantra pemberian nama bayi. |
| Tabuh Salimpat | Jambi | Dimainkan dengan alat musik kerenceng, gambus, dan rebana. |
| Angklung Buhun | Jawa Barat | Iringan tarian musik tanam di daerah Baduy. |
Tantangan Kontemporer dan Prospek Masa Depan
Musik tradisional di Indonesia kini menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlanjutannya, terutama dari arus globalisasi dan modernisasi. Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang untuk inovasi dan revitalisasi.
Erosi Nilai Akibat Komersialisasi dan Globalisasi
Salah satu dilema terbesar yang dihadapi musik tradisional adalah komersialisasi, terutama melalui pariwisata. Meskipun komersialisasi terbukti dapat melestarikan bentuk luar suatu tradisi, seringkali ia mengikis kesakralan dan esensi aslinya.
Fenomena ini dapat diamati pada kasus Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Pertunjukan ini, yang awalnya berakar pada tradisi dan ritual, diubah menjadi atraksi pariwisata untuk menarik pengunjung. Perubahan ini mengakibatkan modifikasi substansial, di mana pertunjukan diatur agar lebih cepat, persembahan sesaji dibuat untuk estetika visual, dan durasi ibadah dipercepat agar tidak membosankan penonton. Perubahan-perubahan ini, meskipun bertujuan untuk memperkuat nilai jual, berpotensi menghilangkan makna, keaslian, dan nilai guna spiritualnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam bagi etnomusikolog dan seniman: di titik mana adaptasi dengan pasar menjadi kompromi yang membahayakan identitas budaya itu sendiri?
Penurunan Minat Generasi Muda: Sebuah Kesenjangan Budaya
Kurangnya minat generasi muda terhadap musik tradisional adalah tantangan nyata yang mengancam mata rantai pewarisan budaya. Di tengah dominasi budaya populer global yang disebarkan melalui media massa , musik tradisional seringkali dianggap “kuno” atau tidak relevan.
Masalah ini sangat krusial karena sebagian besar musik tradisional diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, melalui proses mendengar, meniru, dan berlatih langsung dengan para ahli atau sesepuh. Jika minat generasi muda menurun, proses transmisi oral ini akan terputus, dan warisan budaya tersebut terancam punah. Hal ini menciptakan kesenjangan budaya, di mana generasi baru kehilangan koneksi dengan identitas dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam musik tradisional mereka.
Inovasi dan Kolaborasi: Jalan ke Depan
Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada konservasi pasif, tetapi juga pada inovasi dan revitalisasi aktif.
- Integrasi dengan Pendidikan Formal: Pendidikan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecintaan terhadap musik tradisional. Dengan memasukkan musik daerah ke dalam kurikulum sekolah, anak-anak dapat belajar tentang berbagai alat musik tradisional, teknik memainkannya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
- Pemanfaatan Teknologi: Teknologi menawarkan alat yang kuat untuk pelestarian. Dokumentasi digital, arsip online, dan penggunaan multimedia dapat melestarikan musik tradisional yang terancam punah dan memperkenalkannya kepada khalayak yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Platform digital dapat digunakan untuk menyimpan dan berbagi rekaman, serta membuat tutorial online yang membantu generasi muda belajar teknik musik tradisional.
- Kreasi Kontemporer: Etnomusikologi tidak hanya mengkaji musik masa lalu, tetapi juga musik kontemporer yang memadukan elemen-elemen tradisional. Banyak komposer modern yang mengeksplorasi dan menggabungkan kekayaan musik tradisional ke dalam karya baru mereka. Contohnya adalah karya Zoel Mistortoify yang menggabungkan elemen seni Madura dan Jawa. Pendekatan ini membuktikan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sumber inspirasi kreatif yang tak terbatas, yang memungkinkan musik tradisional untuk tetap relevan dan menarik bagi audiens modern.
| Strategi | Pemangku Kepentingan | Tujuan & Dampak |
| Integrasi Kurikulum Sekolah | Pemerintah, Lembaga Pendidikan | Menumbuhkan kesadaran dan kecintaan sejak dini, memastikan pewarisan nilai budaya. |
| Dokumentasi & Arsip Digital | Lembaga Penelitian, Seniman | Melestarikan warisan musik yang terancam punah, membuat materi dapat diakses oleh masyarakat luas. |
| Kolaborasi Seni Kontemporer | Seniman, Industri Musik | Menciptakan karya baru yang menarik minat generasi muda, membuktikan bahwa tradisi adalah sumber kreatif yang hidup. |
| Penyelenggaraan Festival | Komunitas, Pemerintah Daerah | Mempromosikan musik tradisional, menjadi wadah pertunjukan, dan ajang pertemuan sosial. |
| Edukasi & Advokasi Publik | Etnomusikolog, Komunitas | Meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya melalui media sosial, seminar, dan workshop. |
Kesimpulan
Etnomusikologi sebagai Penjaga dan Penggerak Budaya
Analisis ini menyimpulkan bahwa etnomusikologi di Indonesia telah berhasil bertransformasi dari sekadar studi akademik menjadi sebuah gerakan budaya. Peran etnomusikolog kini adalah untuk meneliti, tetapi juga untuk membimbing masyarakat, mengadvokasi tradisi, dan memastikan keberlanjutan budaya. Kelangsungan musik tradisional tidak bisa dijamin hanya dengan konservasi pasif. Ia memerlukan intervensi aktif yang menggabungkan metode ilmiah dengan kreativitas artistik dan pemahaman sosial.
Disiplin ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana musik membentuk dan merefleksikan identitas kultural, sejarah, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menganalisis beragam musik seperti Gamelan, Gondang, dan Sasando, terbukti bahwa musik tradisional adalah elemen hidup yang terus berperan penting dalam membentuk dan memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia. Etnomusikologi adalah alat yang krusial untuk menafsirkan dan mengarahkan perkembangan musik di tengah kompleksitas dunia modern.