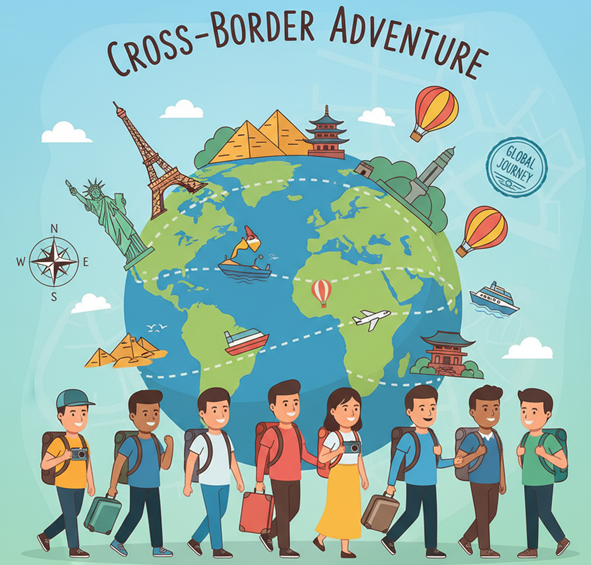Optimalisasi Pariwisata Lintas Batas (Cross-Border Tourism) Indonesia
Latar Belakang dan Definisi Border Tourism di Indonesia
Pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan Indonesia merupakan komponen strategis dalam pembangunan nasional yang lebih luas. Visi pengembangan ini telah bertransisi, tidak lagi semata berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, melainkan sebagai instrumen vital untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Program Border Tourism bertujuan memperkuat kedaulatan negara, sekaligus berfungsi sebagai sarana diplomasi dan penguatan hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga.
Dalam kerangka pembangunan, upaya ini selaras dengan arah kebijakan untuk memperkuat infrastruktur dan mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Pariwisata perbatasan diposisikan sebagai daya ungkit (leveraging force), yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, tetapi juga sebagai motor penggerak untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dengan demikian, investasi infrastruktur di perbatasan diharapkan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi lokal.
Negara-negara Tetangga dan Garis Batas Strategis (Darat dan Maritim)
Indonesia memiliki kompleksitas perbatasan yang unik sebagai negara kepulauan, menuntut strategi pengembangan pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi geografis. Secara maritim, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste, dan Australia.
Penetapan batas maritim seringkali melibatkan isu-isu regulasi yang sensitif. Misalnya, perbatasan maritim dengan Timor Leste di sebelah Utara (Selat Ombai dan Selat Leti) masih memerlukan perundingan lebih lanjut karena tumpang tindih wilayah laut teritorial. Hal serupa terjadi pada penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Palau di Samudera Pasifik. Kepastian hukum atas batas-batas ZEE sangat krusial, terutama bagi potensi wisata bahari dan pengelolaan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, batas darat Indonesia berada di tiga pulau besar: Kalimantan (berbatasan dengan Malaysia), Papua (dengan Papua Nugini), dan Nusa Tenggara Timur (dengan Timor Leste).
Komodifikasi Kedaulatan dan Transformasi Destinasi
Fenomena menarik yang teramati dalam pengembangan Border Tourism di Indonesia adalah komodifikasi simbol kedaulatan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang megah, modern, dan berarsitektur menawan, telah bertindak sebagai representasi fisik dari kehadiran negara dan penguatan kedaulatan. Pembangunan ini secara langsung memicu peningkatan kunjungan wisatawan, khususnya dari pasar domestik, yang datang untuk melihat dan mengabadikan simbol nasional tersebut.
Ini menunjukkan adanya rantai sebab-akibat: pembangunan PLBN megah menarik kunjungan wisatawan domestik sebagai wujud kebanggaan nasional, sehingga PLBN bertransformasi secara fungsi dari sekadar pos keamanan menjadi destinasi wisata edukasi dan spot foto. Implikasinya, keberhasilan awal
Border Tourism di Indonesia lebih didorong oleh daya tarik simbolisme domestik dan kebanggaan akan pembangunan, ketimbang arus masif pelintas batas asing. Hal ini menjamin bahwa investasi besar dalam infrastruktur pertahanan dan keamanan (PLBN) segera memberikan dampak sosial-ekonomi lokal, bahkan sebelum target wisatawan mancanegara terpenuhi.
Berikut adalah matriks geopolitik yang mengelompokkan kawasan perbatasan berdasarkan negara tetangga dan fokus pengembangannya.
Matriks Geopolitik Batas Negara dan Fokus Pengembangan Pariwisata
| Negara Tetangga | Jenis Batas Utama | Kawasan Pengembangan Utama | Fokus Wisata Regional |
| Malaysia | Darat (Kalimantan), Laut (Riau, Kaltara) | PLBN Aruk, Entikong, Badau, Labang, Temajuk, Natuna, Riau | Ekowisata, Budaya Adat, Simbol Kedaulatan, Wisata Bahari Pesisir |
| Timor Leste | Darat (NTT), Laut | PLBN Motaain, Motamasin, Wini | Wisata Edukasi, Arsitektur Lokal, Simbol Kedaulatan |
| Papua Nugini (PNG) | Darat (Papua) | PLBN Skouw, Sota | Wisata Edukasi, Study Tour, Potensi Alam Lokal (Kampung Mosso) |
| Singapura | Laut (Riau) | Pulau Terluar (Natuna, Pulau Senua), Pesisir Riau | Wisata Bahari, Island Hopping, Exit-Entry Point Yacht |
Kerangka Kebijakan dan Peran Infrastruktur Negara (PLBN)
Visi Pemerintah dan BNPP dalam Pengembangan Wilayah 3T
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan. BNPP tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator utama dalam pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata. Kerangka pembangunan kawasan perbatasan bertujuan secara eksplisit untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat infrastruktur pendukung. Sebagai komitmen nyata, BNPP berupaya meningkatkan kapasitas UMKM di wilayah perbatasan melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan.
Transformasi PLBN Terpadu: Dari Gerbang Keamanan Menjadi Destinasi Wisata
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern di Indonesia dirancang sebagai fasilitas terpadu (integrated facility), memisahkan zona inti (layanan Customs, Immigration, Quarantine/CIQ dan keamanan) dari zona penunjang, yang mencakup pasar wisata, fasilitas kuliner, dan area permainan anak-anak. Transformasi ini menjadikan PLBN sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan.
Contoh utama keberhasilan ini terlihat di Kalimantan dan Papua:
- PLBN Aruk (Kalimantan Barat) dinilai sebagai tempat wisata terpopuler di kawasan perbatasan. Bangunan megah dengan kombinasi arsitektur etnik-modern yang dikelilingi pemandangan pegunungan menjadi daya tarik tersendiri. Tingginya kunjungan domestik, seperti tercatat 1.737 wisatawan dalam seminggu libur Lebaran, memberikan dampak ekonomi langsung pada pengusaha kuliner dan aksesoris di zona penunjang.
- PLBN Entikong (Kalimantan Barat) juga menjadi tujuan utama warga lokal untuk berswafoto dan menyaksikan langsung pintu perbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia. Pembangunan yang pesat di Entikong membangkitkan rasa bangga dan menjadikan kawasan tersebut sebagai daya tarik baru.
- PLBN Skouw (Papua) berfungsi sebagai ikon perbatasan RI-PNG dan pusat edukasi. Kawasan ini sering menjadi tujuan study tour bagi siswa-siswi (misalnya dari SD Juara Al Hikmah dan Komunitas Bimbel Cerdasnya Papua) yang mempelajari prosedur lintas batas, simulasi pemeriksaan dokumen keimigrasian dan karantina, serta meninjau simbol kedaulatan seperti Patung Garuda dan Monumen Kerja Sama RI-PNG.
- PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini (NTT) menampilkan adopsi kekayaan arsitektur budaya lokal. PLBN Motaain, misalnya, menyerap desain Rumah Adat Matubesi, sementara Motamasin mengadaptasi corak tenun setempat. Desainnya menggunakan konsep green design dengan pemanfaatan pencahayaan alami dan material lokal, yang memperkuat identitas budaya di batas negara.
Strategi Cross-Border Tourism dan Peningkatan Aksesibilitas
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan BNPP berupaya mengoptimalkan PLBN bukan hanya sebagai gerbang, tetapi sebagai simpul konektivitas (connected hub). Salah satu upaya adalah melalui penyelenggaraan event besar, seperti revitalisasi Festival Cross Border di Jayapura, yang menargetkan ribuan wisatawan mancanegara melalui kegiatan seni, budaya, dan olahraga.
Untuk menarik wisatawan internasional, pemerintah berencana memfasilitasi akses masuk, termasuk wacana pembebasan visa kedatangan (free visa). Namun demikian, regulasi lintas batas masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Sebagai contoh, pelintas dari Papua Nugini yang memasuki wilayah Indonesia masih diwajibkan memiliki dokumen lengkap, seperti Kartu Lintas Batas (KLB), paspor, dan dokumen pendukung lainnya, yang berpotensi menjadi hambatan birokrasi bagi pergerakan wisata harian. Secara infrastruktur, BNPP terus mendorong peningkatan konektivitas fisik dan digital di kawasan perbatasan untuk memfasilitasi arus barang dan orang.
Analisis Fungsional PLBN Terpadu sebagai Destinasi Wisata
| PLBN (Provinsi) | Negara Batas | Desain Arsitektur / Simbol Kedaulatan | Fungsi Wisata Utama | Dampak Ekonomi Lokal |
| Aruk (Kalbar) | Malaysia | Kombinasi Etnik-Modern, Pemandangan Gunung | Wisata Simbol Kedaulatan, Pasar Wisata, Kuliner | Kenaikan aktivitas ekonomi UMKM di zona penunjang |
| Skouw (Papua) | PNG | Ornamen khas budaya lokal | Wisata Edukasi, Study Tour, Ikon Perbatasan | Mempromosikan kuliner PNG, akses ke destinasi alam tersembunyi |
| Sota (Papua Selatan) | PNG | Konsep terintegrasi (komersial, fasilitas umum/sosial) | Titik Nol Kilometer, Event Olahraga (Bersepeda) | Potensi event tourism, pemberian sertifikat bagi pengunjung |
| Motaain (NTT) | Timor Leste | Rumah Adat Matubesi, Green Design | Simbol Kedaulatan, Warisan Budaya Lokal | – |
Analisis Regional Kawasan Perbatasan Darat
Koridor Kalimantan (Indonesia-Malaysia)
Pengembangan pariwisata di perbatasan Kalimantan mengadopsi model terintegrasi, di mana PLBN berfungsi sebagai gerbang utama yang terhubung dengan kekayaan ekowisata dan budaya Dayak yang lestari.
Dampak Ekonomi dan Ekowisata Kalimantan Barat
Keberfungsian PLBN Aruk telah terbukti menjadi motor pertumbuhan. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat perbatasan, dengan rata-rata indeks ekonomi meningkat dari 58,51 (sebelum PLBN) menjadi 65,06 (setelah operasional PLBN), menunjukkan PLBN menjadi andalan pertumbuhan ekonomi lokal.
Di PLBN Badau, kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang, tetapi juga akses menuju keajaiban alam dan budaya lestari di Kapuas Hulu. Potensi utamanya meliputi Taman Nasional Danau Sentarum, kawasan konservasi dengan keindahan hutan rawa, perbukitan, serta flora dan fauna langka. Danau Sentarum menjadi daya tarik bagi pecinta alam dan peneliti, menawarkan penginapan unik di pulau-pulau kecil.
Model Ekowisata Berkelanjutan: Komunitas Adat Sungai Utik
Destinasi unik di dekat PLBN Badau adalah Komunitas Masyarakat Adat Sungai Utik, yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan. Komunitas Dayak Iban ini berhasil menjaga hutan adat mereka dan melestarikan budaya turun-temurun, menawarkan model ekowisata berkelanjutan yang ideal.
Daya tarik budaya di Sungai Utik sangat autentik. Wisatawan dapat mengunjungi Rumah Panjae (Rumah Panjang Tradisional) yang masih dihuni. Seni tato Iban, yang bukan sekadar dekorasi tubuh tetapi warisan identitas spiritual dan sosial yang mendalam, juga menjadi fokus pembelajaran. Selain itu, terdapat seni tenun Iban, serta kerajinan anyaman tikar Bemban dan anyaman rotan yang menonjol dengan motif dekoratif terinspirasi dari alam mimpi dan kehidupan spiritual suku Iban. Masyarakatnya dikenal sangat ramah, dan filosofi mereka—menganggap Bumi sebagai Ibu, Hutan sebagai Ayah, dan Air sebagai Darah—menjamin praktik pertanian regeneratif yang selaras dengan ekosistem.
Diferensiasi Model Bisnis di Kalimantan Utara
Di Kalimantan Utara, pengembangan kawasan Lumbis Ogong berfokus pada pasar internasional. PLBN Labang (Nunukan), yang baru diresmikan pada tahun 2024, diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
Lebih lanjut, di Kecamatan Lumbis Pansiangan, dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mengembangkan Wisata Gerbang Satria. Pokdarwis ini telah mengambil langkah proaktif dengan menjalin kerjasama dengan agen travel di Kota Kinabalu, Malaysia. Tujuannya adalah mempromosikan paket wisata lintas batas secara langsung, bahkan menargetkan turis dari negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Tiongkok yang umumnya berkunjung ke Gunung Kinabalu (Sabah). Model ini menunjukkan adanya diferensiasi model bisnis di mana PLBN tidak hanya menunggu kunjungan, tetapi secara aktif memasarkan potensi lokal. Di tempat lain, Pulau Sebatik juga dikenal dengan ikon wisatanya, Pantai Batu Lamampu, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Pengembangan pariwisata perbatasan Kalimantan mengadopsi model berlapis: pertama, mengandalkan Simbol Kedaulatan (PLBN Aruk/Entikong) untuk daya tarik domestik massal; kedua, fokus pada Ekowisata dan Budaya (Badau/Sungai Utik) sebagai daya tarik berkelanjutan dan special interest; dan ketiga, menjalankan Pemasaran Outbound (Labang/Gerbang Satria) untuk menargetkan pasar regional. Keberhasilan jangka panjang menuntut adanya keseimbangan alokasi sumber daya antara pembangunan fisik PLBN dan pendampingan Pokdarwis/UMKM dalam mengemas atraksi budaya dan alam yang berkelanjutan, khususnya dalam konsep Border Edu-Ecotourism seperti yang diinisiasi di Desa Temajuk, Sambas.
Koridor Nusa Tenggara Timur (Indonesia-Timor Leste)
PLBN di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang meliputi Motaain, Motamasin, dan Wini, didesain untuk merepresentasikan kedaulatan negara melalui arsitektur yang menghormati warisan budaya lokal. Selain desain yang memikat, kawasan ini menghadapi tantangan keamanan terkait pergerakan orang. Pengelola PLBN Motamasin, misalnya, harus mengatasi masalah praktik pelintasan ilegal melalui “jalur tikus” dengan menerapkan tindakan tegas berupa deportasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek pariwisata dikembangkan, fungsi dasar pengawasan dan keamanan perbatasan tetap menjadi prioritas.
Koridor Papua (Indonesia-Papua Nugini)
Di perbatasan RI-PNG, fokus pengembangan pariwisata adalah edukasi dan penggalian potensi alam yang belum tersentuh. PLBN Sota di Merauke, yang berada di Titik Nol Kilometer, telah diakui oleh Kemenparekraf layak menjadi destinasi wisata berkat konsepnya yang terintegrasi (komersial, fasilitas umum/sosial). Rencana ambisius termasuk penyelenggaraan event olahraga, seperti bersepeda dari Sota ke Kota Merauke, untuk menarik wisatawan dan menciptakan event tourism. Selain itu, direncanakan pemberian sertifikat khusus bagi pengunjung yang telah mencapai Titik Nol Kilometer di Sota.
Sementara itu, PLBN Skouw di Jayapura berperan aktif sebagai pusat edukasi, terutama bagi pelajar. Namun, potensi alam di sekitarnya, khususnya di
Kampung Mosso (Distrik Muara Tami), belum termanfaatkan secara maksimal. Kampung Mosso memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk kolam air panas, kolam air berwarna hijau, air terjun, kolam pemancingan, dan desa adat.
Kendala utama dalam pengembangan potensi Mosso adalah keterbatasan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola objek wisata, serta minimnya perhatian dan regulasi pemerintah yang jelas. Kasus Mosso menggarisbawahi adanya pemutusan hubungan (disconnect) antara pembangunan infrastruktur keras (PLBN yang megah) dan pengembangan kapasitas serta legalitas pada tingkat desa wisata. Perwakilan Imigrasi dan aparat lokal juga menekankan perlunya pengurusan izin pariwisata yang jelas kepada masyarakat adat terkait hak wilayah guna mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Analisis Kawasan Perbatasan Maritim dan Pulau Terluar
Pengembangan pariwisata di kawasan maritim menuntut fokus pada potensi bahari, island hopping, dan terutama, penentuan jalur pelayaran internasional resmi (exit-entry point).
Kepulauan Riau (vs. Singapura dan Malaysia)
Secara geostrategis, Provinsi Riau berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya lokasi unggulan untuk wisata lintas batas maritim. Pintu masuk utama untuk wisata pesisir adalah Pelabuhan Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, dengan pantai-pantai seperti Pantai Koneng dan Pantai Purnama sebagai unggulan.
Di Kepulauan Natuna, yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, potensi wisata bahari sangat besar. Destinasi seperti Pulau Senua terkenal sebagai pusat konservasi penyu dan spot snorkeling dengan terumbu karang yang terjaga. Pulau Sekatung dan Tanjung Datuk juga menawarkan pesona alam yang memikat. Model pengembangan di Pulau Nikoi, Riau, menunjukkan potensi devisa besar, di mana pengelolaan wisata bahari menyumbang pajak daerah yang signifikan, membuktikan bahwa optimalisasi Pulau-Pulau Kecil (PPK) dapat menjadi motor ekonomi yang kuat.
Strategi Pengembangan PLBN Serasan sebagai Exit-Entry Point
PLBN Serasan di Natuna adalah kasus strategis yang menunjukkan pergeseran fokus pengembangan perbatasan maritim. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara intensif mendorong Serasan untuk dioptimalkan sebagai titik keluar-masuk (exit-entry point) bagi kapal wisata asing, seperti yacht atau cruise, mengingat posisinya yang berada di jalur pelayaran internasional.
Visi menjadikan Serasan sebagai connected hub bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional, memfasilitasi akses ekspor langsung, dan menciptakan efisiensi logistik yang akan mendorong hilirisasi industri pengolahan di Natuna.
Namun, realisasi visi ini menghadapi tantangan regulasi yang besar. Untuk menjadikan Serasan sebagai pelabuhan internasional, diperlukan penetapan dermaga sebagai bagian dari kawasan pabean dan kesiapan layanan CIQ yang efisien. Meskipun Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan kesiapan karena Serasan telah menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Kementerian Perhubungan menekankan perlunya revisi Peraturan Pemerintah agar Serasan resmi masuk dalam daftar exit-entry point di Kepulauan Riau. Ini menunjukkan bahwa di perbatasan maritim, hambatan utama bukan terletak pada pembangunan fisik, tetapi pada harmonisasi kebijakan lintas sektoral dan kepastian hukum untuk operator kapal asing.
Tantangan, Dampak, dan Rekomendasi Strategis
Tantangan Utama Pengembangan Pariwisata Perbatasan
Pengembangan pariwisata di perbatasan harus mengatasi tantangan pembangunan di wilayah 3T, ditambah dengan kompleksitas birokrasi lintas batas.
Isu Aksesibilitas dan Konektivitas
Meskipun PLBN telah dibangun megah, masih terdapat kesenjangan infrastruktur yang parah di daerah penyangga. Contohnya, Desa Temajuk, meskipun memiliki potensi ekowisata, masih kesulitan menarik kunjungan karena keterbatasan jalan dan aliran listrik. Kesenjangan infrastruktur ini menghambat upaya promosi yang dilakukan oleh Pokdarwis lokal. Oleh karena itu, BNPP terus mendorong peningkatan konektivitas fisik dan, yang tidak kalah penting, konektivitas digital, yang krusial untuk pemasaran UMKM melalui media sosial.
Hambatan Regulasi dan Kepastian Hukum
Aspek regulasi menciptakan hambatan yang signifikan, baik di perbatasan darat maupun laut. Di perbatasan darat, persyaratan dokumen CIQ yang ketat bagi pelintas batas harian (misalnya Kartu Lintas Batas di perbatasan PNG) dapat menghambat fleksibilitas cross-border tourism.
Di perbatasan Papua (Kampung Mosso), kendala legalitas muncul dalam bentuk kurangnya regulasi yang jelas terkait izin pariwisata yang mengakui hak wilayah adat masyarakat setempat. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan konflik dan menghambat pemanfaatan potensi wisata baru. Sementara di perbatasan maritim, tantangan kritis adalah regulasi pusat. Realisasi PLBN Serasan sebagai exit-entry point internasional sepenuhnya bergantung pada keputusan dan revisi Peraturan Pemerintah oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini menyoroti bahwa PLBN Maritim lebih membutuhkan investasi pada harmonisasi kebijakan (software) daripada infrastruktur fisik (hardware).
Peningkatan Kapasitas SDM Lokal
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan manajemen di tingkat lokal seringkali menjadi penghambat utama. Kasus Kampung Mosso menunjukkan bahwa meskipun potensi alam melimpah, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengolahnya membuat potensi tersebut tidak maksimal. Keberhasilan pariwisata sangat bergantung pada faktor soft skill, seperti keramahan masyarakat, penetapan harga yang wajar, standar higienitas, dan pelayanan profesional. BNPP berupaya mengisi kesenjangan ini melalui Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan intensif untuk UMKM dan Pokdarwis, termasuk digitalisasi marketing dan tata kelola desa wisata.
Dampak Sosial-Ekonomi Pariwisata Perbatasan
Pengembangan pariwisata perbatasan memberikan dampak positif yang terukur:
- Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Keberfungsian program Cross-Border Tourism, terbukti di PLBN Aruk, telah meningkatkan indeks pembangunan ekonomi lokal dan menjadi katalisator pertumbuhan daerah.
- Penguatan Identitas Nasional dan Diplomasi: Pariwisata perbatasan memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tetangga. Selain itu, PLBN berfungsi sebagai pusat penanaman pemahaman dini tentang kedaulatan negara melalui kegiatan edukasi bagi generasi muda.
- Pelestarian Budaya dan Konservasi: Model ekowisata seperti di Komunitas Adat Sungai Utik menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi motor penggerak pelestarian budaya adat dan kearifan lokal, terutama filosofi masyarakat yang menjaga keseimbangan dengan alam.
Rekomendasi Kebijakan Mendalam: Peta Jalan Pengembangan Pariwisata Perbatasan Berkelanjutan
Untuk memastikan investasi PLBN menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, fokus kebijakan harus bergeser dari pembangunan fisik (hard power) menjadi penguatan kapasitas manajerial dan kepastian regulasi (soft power).
Harmonisasi Regulasi dan Kemitraan Lintas Sektor
Diperlukan percepatan harmonisasi regulasi di tingkat pusat. BNPP, Kemenhub, dan Kemenparekraf harus memastikan penetapan definitif PLBN Serasan dan titik maritim strategis lainnya sebagai exit-entry point kapal wisata dengan segera merevisi Peraturan Pemerintah yang terkait. Selain itu, harus dilakukan peninjauan ulang terhadap prosedur CIQ di koridor darat, khususnya untuk wisatawan harian, guna mendukung fleksibilitas Cross-Border Tourism sambil tetap menjaga keamanan.
Implementasi Model Pengembangan Atraksi Berbasis Komunitas (AAA Focus)
Peta jalan ke depan harus mengintegrasikan PLBN sebagai Amenitas dan Akses dengan Atraksi Ekowisata dan Budaya Lokal sebagai konten utama. Model pengembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan regional:
- Kalimantan: Fokus pada outbound marketing dan digitalisasi untuk menargetkan pasar regional (model Gerbang Satria).
- Papua: Prioritas pada mediasi legal antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memberikan kejelasan izin pariwisata dan hak wilayah di kawasan berpotensi tinggi seperti Kampung Mosso. Investasi harus diarahkan pada pendampingan manajerial dan tata kelola desa wisata.
Peningkatan Aksesibilitas dan Diplomasi Pariwisata
Pemerintah wajib memperluas dan memperkuat infrastruktur jaringan digital di desa-desa penyangga perbatasan untuk mendukung upaya promosi mandiri oleh Pokdarwis. Selain itu, pariwisata harus digunakan sebagai alat diplomasi. Indonesia perlu mengembangkan paket wisata kolaboratif dengan operator pariwisata dari Kuching, Tawau, Dili, atau Port Moresby, memperkuat hubungan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pariwisata lintas negara. Pemberian sertifikat bagi pengunjung Titik Nol Kilometer di Sota dapat diperluas ke PLBN lain untuk menciptakan branding pariwisata berbasis simbol kedaulatan di seluruh Indonesia.
Matriks Analisis Pengembangan Kawasan Pariwisata Perbatasan (AAA Framework)
| Kawasan Utama | Potensi Utama (Attraction) | Kebutuhan Mendesak (Amenity & Accessibility) | Tantangan Kunci (Constraint) | Model Pengembangan Disarankan |
| Kalimantan Darat | Ekowisata Konservasi (Sentarum), Budaya Adat (Sungai Utik) | Digitalisasi Pemasaran, Akses Jalan Pedesaan, Kemitraan Outbound | Koordinasi Lintas Sektor untuk Ecotourism, SDM Hospitality | Border Edu-Ecotourism Berbasis Masyarakat |
| Natuna/Riau | Wisata Bahari Pulau Terluar, Jalur Yacht Internasional | Kejelasan dan Kecepatan Regulasi Exit-Entry Point, Kesiapan CIQ Maritim | Hambatan regulasi pusat (Kemenhub), sensitivitas isu maritim | Connected Hub Pariwisata Bahari & Geostrategis |
| Papua (Skouw/Mosso) | Kolam Panas, Air Terjun, Desa Adat | Regulasi Hak Wilayah/Izin Pariwisata, Pendampingan Manajemen Wisata Lokal | Keterbatasan Kapasitas SDM Lokal, risiko konflik hak wilayah | Integrasi PLBN (Edukasi) dengan Pengembangan Atraksi Alam/Budaya Berbasis Legalitas Adat |