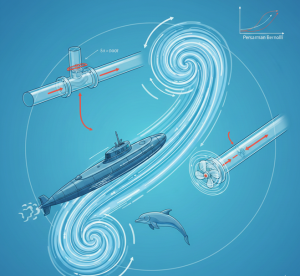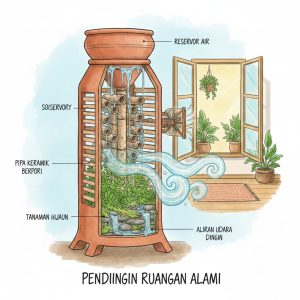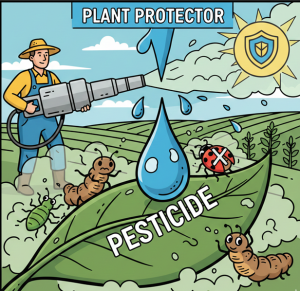Keroncong, Akulturasi Musikal dan Jati Diri Bangsa Indonesia
Musik keroncong, sebuah genre yang telah melintasi batas geografis dan zaman untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia. Berawal sebagai adaptasi musik Portugis pada abad ke-16, keroncong berevolusi di tangan komunitas lokal, menyerap tradisi musikal Nusantara, dan bertransformasi menjadi “simfoni akulturasi” yang unik. Tulisan ini menguraikan tiga fase utama perjalanan keroncong: asal-usulnya yang hibrida di Kampung Tugu, peran krusialnya sebagai media perjuangan dan ekspresi nasionalisme, serta dinamika masa kini yang mencakup tantangan penurunan popularitas dan upaya revitalisasi melalui inovasi dan adaptasi digital. Analisis ini menyoroti bagaimana keroncong bukan sekadar genre musikal, melainkan sebuah artefak hidup yang mencerminkan sejarah panjang perpaduan budaya dan ketangguhan bangsa.
Pendahuluan: Keroncong, Sebuah Simfoni Akulturasi Budaya Indonesia
Keroncong adalah sebuah fenomena budaya yang melampaui sekadar genre musik. Keroncong merupakan cerminan nyata dari sejarah akulturasi yang kompleks di Indonesia, yang berawal dari percampuran budaya Barat dan Timur sejak masa kolonial. Genre ini secara historis telah melalui serangkaian transformasi, dari awal kemunculannya sebagai bentuk hiburan populer hingga perannya yang monumental sebagai media perjuangan kemerdekaan. Musik ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk mengekspresikan nasionalisme dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Keroncong yang dikenal dengan alunan melankolis dan lembutnya telah berhasil mengukuhkan diri sebagai warisan budaya nasional yang patut dilestarikan.
Awal Mula Keroncong: Jejak Portugis di Tanah Batavia dan Tugu
Dari Moresco Menuju Keroncong: Kedatangan Musik dan Instrumen Portugis
Asal-usul musik keroncong dapat ditelusuri kembali ke abad ke-16, ketika para pelaut dan pedagang dari Kekaisaran Portugis membawa tradisi musik mereka ke kota-kota pelabuhan di Nusantara. Genre-genre seperti Moresco, Fado, dan Cafrinho menjadi cikal bakal yang memperkenalkan penggunaan instrumen petik Eropa seperti gitar, biola, dan cello kepada masyarakat lokal.
Sebuah paradoks menarik muncul dari sejarah ini: genre Moresco, yang menjadi fondasi keroncong, pada perjalanannya tidak lagi eksis di negara asalnya, Portugal. Namun, di Indonesia, musik ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang pesat menjadi sebuah genre yang diakui secara luas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi wadah pasif, melainkan sebuah laboratorium budaya yang memberikan konteks sosial dan musikal yang unik. Musik-musik ini diadopsi oleh warga kelas bawah dan komunitas yang terpinggirkan di Batavia, yang sering disebut dengan istilah “buaya darat”. Terlepas dari pengawasan ketat, musik ini tumbuh subur dan berevolusi secara organik. Perpaduan genre Portugis yang sederhana dengan tradisi musikal Indonesia yang kaya, seperti gamelan, menciptakan sebuah hibrida baru yang lebih kompleks dan relevan secara lokal.
Kelahiran di Kampung Tugu dan Etimologi Keroncong
Kisah transformasi musikal ini berpusat pada komunitas budak Portugis yang dimerdekakan, yang dikenal sebagai Mardijkers, di Kampung Tugu, Batavia (sekarang Jakarta Utara). Komunitas ini memainkan peran fundamental sebagai titik nol kelahiran genre yang kemudian dikenal sebagai Keroncong Tugu. Selama periode yang disebut “evolusi panjang” dari tahun 1552 hingga 1879, genre ini mulai mengambil bentuknya. Barulah setelah tahun 1880, dengan penemuan ukulele modern di Hawaii, keroncong memasuki fase “evolusi pendek” menuju bentuknya yang dikenal saat ini.
Nama “keroncong” sendiri berasal dari onomatope, yaitu peniruan bunyi yang dihasilkan oleh instrumen ukulele saat dimainkan dengan teknik petikan rasgueado. Suara crong-crong yang khas dari instrumen ini memberikan nama pada genre musik tersebut.
Instrumentasi dan Karakteristik Musikal Awal
Ansambel keroncong tradisional memiliki formasi alat musik yang unik, terdiri dari perpaduan instrumen Eropa yang dimainkan dengan cara yang mengadopsi tradisi musikal Indonesia. Instrumen utama yang digunakan meliputi biola, seruling, gitar, cello, kontrabas, dan sepasang ukulele yang dikenal sebagai cak dan cuk.
Interaksi antara instrumen-instrumen ini menunjukkan sebuah proses “Indigenisasi” yang cerdas. Cuk, ukulele dengan tiga senar nilon, sering memainkan arpeggio. Sementara itu, cak, ukulele dengan empat atau lima senar baja, memainkan petikan berirama. Kedua instrumen ini saling berinteraksi secara “mengunci” (interlocking), menciptakan pola ritme yang rumit dan dinamis. Pola permainan ini memiliki kemiripan yang jelas dengan cara instrumen-instrumen dalam orkestra gamelan berinteraksi untuk membangun lapisan ritmik.
Adaptasi serupa juga terjadi pada instrumen lain. Cello dimainkan dengan gaya pizzicato (dipetik) untuk menggantikan peran gendang, sementara kontrabas sering dimainkan secara minimalis untuk meniru bunyi gong besar dalam gamelan. Dengan demikian, orkestra keroncong bukanlah sekadar replikasi ansambel Eropa, melainkan sebuah adaptasi kreatif yang menerjemahkan logika musikal lokal ke dalam instrumen-instrumen diatonis, menjadikannya sebuah genre yang memiliki fondasi musikal ganda.
Proses dan Evolusi Keroncong: Dari Hiburan Rakyat Menjadi Musik Perjuangan Bangsa
Keroncong di Era Pra-Kemerdekaan: Musik Populer dan Egaliter
Pada awal abad ke-20, keroncong mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia. Genre ini sering dipentaskan dalam berbagai pertunjukan, seperti teater komedi stambul, dan menjadi bagian penting dari acara sosial. Keroncong berhasil mengisi celah di antara genre musik yang ada. Keroncong bukanlah musik klasik Barat yang dianggap elitis dan hanya dinikmati oleh kaum bangsawan dan elit kolonial, juga bukan musik gamelan yang sering kali terikat pada upacara adat atau ritual sakral. Keroncong menjadi sebuah ars nova yang egaliter, dapat diakses dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, menjadikannya populer di kalangan komunitas Betawi dan kelompok etnis Banda.
Peran Keroncong dalam Perjuangan Kemerdekaan
Seiring berjalannya waktu, peran keroncong semakin signifikan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, keroncong bertransformasi dari sekadar hiburan menjadi media yang efektif untuk menyuarakan semangat nasionalisme. Lagu-lagu seperti “Bengawan Solo” karya Gesang Martohartono menjadi simbol perjuangan dan semangat cinta tanah air. Lagu “Sepasang Mata Bola” karya Ismail Marzuki dikenal sebagai lagu yang mengobarkan semangat para pejuang. Lirik-liriknya yang puitis dan sering kali heroik, namun dibalut dalam nuansa romantis, mampu memompa semangat tempur rakyat melawan kolonialisme.
Pada masa pendudukan Jepang, meskipun sempat dicekal, keroncong justru dimanfaatkan sebagai media propaganda. Menanggapi hal ini, para komponis Indonesia menunjukkan kecerdasan mereka dengan menciptakan lagu-lagu perlawanan yang dibungkus dalam metafora yang halus. Peran Radio Republik Indonesia (RRI) juga sangat penting dalam menyebarkan keroncong ke seluruh Nusantara, menjadikannya saluran utama untuk mempopulerkan musik kebangsaan.
Lahirnya Langgam Jawa: Sentuhan Gamelan yang Melahirkan Irama Baru
Proses akulturasi yang lebih mendalam terjadi di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Surakarta. Di sini, keroncong menyerap pengaruh kuat dari musik gamelan, khususnya tangga nada pentatonisnya. Perpaduan ini melahirkan sebuah genre baru yang dikenal sebagai Langgam Jawa.
Langgam Jawa memiliki beberapa perbedaan musikal yang mendasar. Pertama, liriknya ditulis dalam bahasa Jawa. Kedua, Langgam Jawa mengadopsi skala lima nada yang mendekati laras pelog atau slendro gamelan, meskipun masih menggunakan interval Barat. Ketiga, ritme dan perpindahan nadanya cenderung lebih lambat, yang memungkinkan penyanyi untuk menambahkan banyak cengkok (ornamentasi vokal) yang khas. Bahkan, cara memainkan instrumen cak dan cuk berubah menjadi arpeggio yang meniru bunyi instrumen siter.
Fenomena ini adalah manifestasi paling jelas dari hibriditas keroncong yang memungkinkan genre ini beresonansi lebih dalam dengan identitas budaya Jawa, menjamin popularitasnya di wilayah tersebut dan melahirkan genre baru yang ikonik.
Tokoh Sentral dan Karya Ikonik: Maestro di Balik Eksistensi Keroncong
Analisis Peran dan Kontribusi Maestro Legendaris
Kekuatan musik keroncong tidak lepas dari kontribusi para maestro yang mendedikasikan hidupnya untuk genre ini. Beberapa tokoh kunci yang membentuk dan mempertahankan keroncong hingga saat ini adalah:
- Gesang Martohartono: Dijuluki “maestro keroncong Indonesia”, Gesang berasal dari Surakarta dan merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu otodidak. Ketenarannya mendunia berkat lagu ciptaannya, “Bengawan Solo,” yang telah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa dan bahkan menjadi bagian dari film di Jepang. Fakta bahwa Gesang kurang menguasai teori musik menunjukkan bahwa esensi keroncong tidak terletak pada keahlian teknis semata, tetapi pada penjiwaan dan bakat alami.
- Ismail Marzuki: Komponis visioner dari Jakarta ini memainkan peran penting dalam menggunakan keroncong sebagai media patriotisme. Ia menciptakan sekitar 200 lagu, banyak di antaranya menjadi lagu nasional. Karya-karyanya, seperti “Sepasang Mata Bola” dan “Selendang Sutra”, berhasil membangkitkan semangat perjuangan rakyat dengan lirik yang heroik namun dikemas dalam nuansa romantis.
- Waljinah: Dikenal sebagai “Ratu Keroncong,” Waljinah adalah penyanyi legendaris yang mempopulerkan Langgam Jawa. Ia berhasil membawa genre ini ke panggung nasional dan bahkan berkolaborasi dengan musisi dari berbagai genre, seperti yang dilakukannya dalam musik orkestra Erwin Gutawa. Kemampuan Waljinah untuk “menempatkan diri” (empan papan) di berbagai lingkungan musik membuktikan kelenturan keroncong sebagai genre yang dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensi tradisinya.
Keberadaan para maestro ini membuktikan bahwa keroncong bukanlah genre yang stagnan, melainkan sebuah genre yang terus hidup dan diperkaya oleh bakat-bakat lokal. Berikut adalah tabel yang merangkum kontribusi mereka.
Kontribusi Maestro Keroncong
| Maestro | Karya Ikonik (Contoh) | Kontribusi Signifikan |
| Gesang Martohartono | “Bengawan Solo,” “Jembatan Merah,” “Caping Gunung” | Mempopulerkan Langgam Jawa secara global; Menjadikan keroncong dikenal di luar negeri, terutama Jepang |
| Ismail Marzuki | “Sepasang Mata Bola,” “Aryati,” “Selendang Sutra” | Menggunakan keroncong sebagai media perjuangan dan nasionalisme; Menciptakan lagu-lagu heroik dalam balutan romantis |
| Waljinah | “Walang Kekek,” “Nyidamsari,” “Jenang Gulo” | Dijuluki “Ratu Keroncong”; Mempopulerkan Langgam Jawa dan berhasil membawa genre ini ke berbagai kalangan |
Keroncong Masa Kini: Adaptasi, Tantangan, dan Prospek Masa Depan
Tantangan di Era Disrupsi: Stigma dan Penurunan Popularitas
Setelah era keemasannya pada tahun 1920-an hingga 1960-an, keroncong menghadapi tantangan besar akibat masuknya musik populer, rock, dan genre kontemporer lainnya. Sejak saat itu, keroncong dianggap sebagai musik kuno (old-fashioned) dan secara stereotip dianggap hanya cocok untuk kalangan lanjut usia.
Penurunan popularitas ini didorong oleh beberapa faktor. Kurangnya dukungan media, seperti radio dan televisi, untuk mempromosikan keroncong membuat genre ini semakin jauh dari masyarakat. Selain itu, kelangkaan komposer yang menciptakan lagu-lagu keroncong baru dan metode pembelajaran di sekolah yang dianggap membosankan juga berkontribusi pada kesulitan menarik minat generasi muda.
Adaptasi dan Inovasi: Keroncong Modern dan Fusion
Dalam upaya untuk bertahan, keroncong telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi. Munculnya genre Pop Keroncong, yang dipelopori oleh musisi seperti Hetty Koes Endang pada tahun 1960-an, menandai upaya untuk memodernisasi keroncong dengan menambahkan instrumen modern seperti gitar elektrik, drum, dan keyboard.
Lebih dari itu, keroncong juga telah berkolaborasi secara luas dengan genre lain, menciptakan berbagai bentuk fusion. Contohnya adalah Campursari di Jawa, yang memadukan keroncong dengan musik tradisional Jawa dan dangdut. Musisi kontemporer juga mengaransemen ulang lagu-lagu pop modern ke dalam gaya keroncong.
Upaya Pelestarian di Berbagai Lini
Eksistensi keroncong saat ini ditopang oleh berbagai upaya pelestarian yang dilakukan oleh komunitas, pemerintah, dan musisi. Festival musik seperti Solo Keroncong Festival dan Keroncong Plesiran Yogyakarta menjadi platform penting untuk menampilkan keroncong, baik dalam bentuk orisinal maupun modern. Festival ini, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Keroncong Svarnanusa, bertujuan untuk merevitalisasi genre ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, akan signifikansinya sebagai warisan budaya nasional.
Di era digital, strategi pelestarian juga beradaptasi. Dokumentasi lagu-lagu keroncong lama ke dalam format digital dan promosi melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menjadi langkah krusial untuk membuatnya lebih mudah diakses. Selain itu, kolaborasi antara musisi keroncong tradisional dan modern menjadi cara efektif untuk menciptakan karya baru yang menarik minat pendengar dari berbagai kalangan.
Perbandingan Keroncong Tradisional dan Modern
| Aspek | Keroncong Tradisional (Asli) | Keroncong Modern (Fusion) |
| Tujuan Utama | Pelestarian genre klasik; Mempertahankan kemurnian tradisi musikal | Menarik audiens muda; Menciptakan suara baru dan unik |
| Alat Musik | Biola, seruling, cak, cuk, gitar, cello, kontrabas | Menambahkan instrumen modern seperti drum kit, gitar elektrik, keyboard, dan saksofon |
| Ciri Musikal | Ritme arpeggio (crong-crong); Melodi vokal yang melankolis dan bernada panjang; Harmoni I-IV-V-I | Ritme yang lebih dinamis dan progresif; Perpaduan lirik keroncong dengan melodi pop |
| Repertoar | Lagu-lagu klasik keroncong dan langgam Jawa yang memiliki struktur baku | Mengaransemen ulang lagu-lagu pop atau genre lain ke dalam gaya keroncong (contoh: lagu pop tahun 2000-an) |
Dinamika antara keroncong tradisional dan modern ini bukanlah sebuah kontradiksi. Sebaliknya, hal ini adalah sebuah dialektika yang krusial untuk kelangsungan hidup genre ini. Upaya untuk bertahan dengan mempertahankan instrumen orisinal, seperti yang dilakukan Orkestra Gita Puspita [27], sama pentingnya dengan upaya beradaptasi untuk menarik minat generasi baru. Tanpa purisme, identitas keroncong akan hilang. Namun, tanpa inovasi, genre ini akan mati, tergerus oleh zaman. Kedua pendekatan ini merupakan dua sisi dari koin yang sama: pelestarian budaya yang dinamis.
Kesimpulan
Keroncong telah membuktikan dirinya sebagai sebuah “simfoni akulturasi” yang melintasi batas geografis dan zaman. Dari akarnya di musik Portugis, keroncong telah menyerap elemen-elemen musikal lokal dan bertransformasi menjadi sebuah genre yang unik dan otentik. Kekuatan terbesarnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi, menyerap elemen budaya lokal, dan menjadi corong ekspresi perjuangan bangsa.