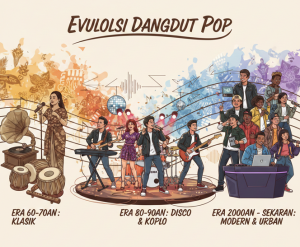Hegemoni Budaya dan Ketahanan Nasional: Analisis Mendalam terhadap Kewajiban Busana Driglam Namzha di Bhutan dalam Arus Globalisasi
Eksistensi suatu negara bangsa di era kontemporer sering kali diuji oleh kemampuannya untuk mempertahankan distingsi identitas di tengah arus homogenisasi global. Kerajaan Bhutan, sebuah negara kecil yang terkurung daratan di pegunungan Himalaya, menyajikan salah satu studi kasus paling ekstrem dan menarik mengenai intervensi negara dalam pelestarian budaya melalui kebijakan Driglam Namzha. Kebijakan ini, yang secara harfiah mengatur etiket dan tata cara berpakaian warga negara, bukan sekadar instrumen estetika, melainkan sebuah manifestasi kedaulatan yang dirancang untuk membentengi jati diri nasional dari pengaruh eksternal yang dianggap merusak. Analisis mendalam terhadap kebijakan ini mengungkapkan kompleksitas yang melampaui sekadar kain dan benang, melibatkan dimensi politik kekuasaan, integrasi etnis, serta strategi ekonomi untuk bertahan hidup di dunia yang didominasi oleh fenomena fast fashion dan konsumerisme massa.
Genealogi dan Fondasi Filosofis Driglam Namzha
Memahami Driglam Namzha memerlukan penelusuran terhadap etimologi dan akar sejarahnya yang mendalam. Kata “Driglam” dalam bahasa Dzongkha merujuk pada ketertiban, disiplin, adat istiadat, dan aturan, sementara “Namzha” berarti sistem atau konsep. Secara kolektif, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai “Aturan untuk Perilaku yang Disiplin” atau secara lebih puitis sebagai “Jalan Menuju Harmoni”. Sistem ini tidak muncul dari kevakuman politik, melainkan merupakan warisan dari abad ke-17 yang diperkenalkan oleh Zhabdrung Ngawang Namgyal, tokoh pemersatu Bhutan yang mendirikan negara ini sebagai entitas politik dan spiritual yang terpisah dari Tibet.
Filosofi Driglam Namzha berakar kuat pada nilai-nilai Buddhisme Mahayana dan adat istiadat istana yang disesuaikan dengan sensitivitas lokal Bhutan. Ini adalah sebuah kode perilaku yang mencakup tiga domain utama: disiplin fisik, disiplin verbal, dan disiplin mental. Secara mental, Driglam Namzha menuntut kesadaran batin, kasih sayang, dan pengendalian diri. Secara verbal, ia mengatur cara bicara yang sopan dan penggunaan honorifik yang mencerminkan hierarki sosial. Secara fisik, manifestasi yang paling terlihat adalah aturan berpakaian yang dikenal sebagai busana nasional.
| Dimensi Disiplin | Fokus Pengaturan | Tujuan Filosofis |
| Mental | Pikiran, niat, kesetiaan pada Raja dan Negara | Mencapai ketenangan batin dan harmoni sosial |
| Verbal | Nada bicara, volume suara, penggunaan honorifik | Menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati |
| Fisik | Busana (Gho/Kira), cara berjalan, cara duduk, sujud | Menciptakan identitas visual yang seragam dan bermartabat |
Pemerintah Bhutan memandang Driglam Namzha sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa hormat, kerendahan hati, dan ketenangan dalam masyarakat. Dalam pandangan otoritas Bhutan, cara seseorang berpakaian dan berperilaku di ruang publik adalah cerminan dari karakter batinnya dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang beradab. Nilai intrinsik dari kode ini terletak pada ekspresi kesantunan, dekorum, dan keanggunan yang dianggap sebagai warisan unik yang harus dijaga agar Bhutan tetap berbeda dari dunia luar.
Evolusi Kebijakan: Dari Tradisi Menuju Mandat Hukum
Meskipun Driglam Namzha telah ada selama berabad-abad sebagai norma sosial, transformasinya menjadi kewajiban hukum yang ketat terjadi pada tahun 1989. Di bawah kepemimpinan Raja Keempat, Jigme Singye Wangchuck, pemerintah menaikkan status kode etik busana dari sekadar rekomendasi menjadi mandat nasional. Kebijakan ini mewajibkan semua warga negara Bhutan untuk mengenakan busana nasional di tempat umum selama jam kerja, di sekolah, kantor pemerintah, dan pada acara-acara resmi.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran akan pengaruh budaya Barat yang mulai merambah melalui pariwisata dan media. Dalam konteks geopolitik, Bhutan yang terjepit di antara dua raksasa ekonomi dan populasi—India di selatan dan Tiongkok di utara—memandang budaya sebagai satu-satunya instrumen untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Jika sebuah bangsa kehilangan keunikan budayanya, maka landasan eksistensi politiknya dianggap akan melemah.
Implementasi mandatori pada tahun 1989 ini sering kali disebut sebagai bagian dari kebijakan “Satu Bangsa, Satu Rakyat” (One Nation, One People). Pemerintah berargumen bahwa keseragaman dalam penampilan publik akan memperkuat persatuan nasional dan mencegah erosi nilai-nilai tradisional. Namun, penegakan hukum ini pada masa itu sangat ketat, di mana warga yang tidak mematuhi aturan berpakaian di tempat umum dapat dikenakan denda berat atau bahkan hukuman penjara.
Struktur dan Spesifikasi Teknis Busana Nasional
Busana nasional Bhutan terdiri dari dua pakaian utama: Gho untuk pria dan Kira untuk wanita. Setiap lipatan, aksesori, dan warna memiliki makna simbolis dan aturan penggunaan yang spesifik di bawah kerangka Driglam Namzha.
Gho: Busana Pria
Gho adalah jubah sepanjang lutut yang dililitkan di sekitar tubuh dan diamankan di pinggang dengan sabuk kain yang disebut Kera. Salah satu fitur paling unik dari Gho adalah kantong besar yang terbentuk di bagian depan perut melalui cara melipat kainnya, yang disebut Hemchu. Secara tradisional, Hemchu digunakan sebagai kantong serbaguna untuk membawa barang-barang seperti mangkuk makanan, dompet, dan saat ini, ponsel pintar.
Kelengkapan Gho mencakup:
- Tego: Jaket dalam berwarna putih dengan manset panjang yang dilipat kembali (disebut Lagey) untuk memberikan tampilan formal.
- Kaus Kaki dan Sepatu: Pria biasanya mengenakan kaus kaki hitam setinggi lutut dan sepatu kulit formal atau bot tradisional yang disebut Tsholham pada acara resmi.
- Kabney: Selendang sutra mentah yang wajib dikenakan saat mengunjungi Dzong (benteng pemerintah/biara) atau menghadap pejabat tinggi.
Warna Kabney merupakan indikator pangkat sosial dan otoritas yang sangat kaku dalam struktur kekuasaan Bhutan.
| Warna Kabney | Status / Jabatan |
| Saffron (Kuning) | Raja (Druk Gyalpo) dan Kepala Biara (Je Khenpo) |
| Oranye | Menteri dan anggota kabinet |
| Merah | Dasho (pejabat tinggi atau anggota keluarga kerajaan) |
| Hijau | Hakim |
| Biru | Anggota Parlemen |
| Putih dengan Garis Merah | Gup (Kepala Desa) |
| Putih (Sutra Mentah) | Warga negara biasa |
Kira: Busana Wanita
Kira adalah gaun sepanjang mata kaki yang terdiri dari selembar kain persegi panjang besar yang dibungkuskan ke tubuh, dijepit di bahu dengan bros perak atau emas yang disebut Koma, dan diikat di pinggang dengan Kera. Kira melambangkan keanggunan dan kesopanan wanita Bhutan.
Elemen pendukung Kira meliputi:
- Wonju: Blus lengan panjang yang dikenakan di bawah Kira, biasanya terbuat dari sutra atau katun.
- Toego: Jaket luar pendek yang dikenakan di atas Kira untuk menambah lapisan estetika dan formalitas.
- Rachu: Selendang bordir sempit yang disampirkan di bahu kiri wanita, setara dengan Kabney pada pria dalam fungsi seremonial.
Berbeda dengan Kabney pria, warna Rachu bagi wanita umumnya tidak mencerminkan pangkat politik tertentu secara kaku, melainkan lebih pada keindahan artistik dan status sosial umum melalui kualitas tenunan dan motifnya.
Perspektif Komparatif: Bhutan dan Prancis
Perbandingan antara kewajiban busana di Bhutan dan larangan atribut tertentu di Prancis menyajikan dikotomi yang menarik dalam filsafat hukum dan politik identitas. Di Prancis, prinsip Laïcité atau sekularisme mendorong negara untuk melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan yang mencolok di ruang publik seperti sekolah, dengan alasan menjaga netralitas dan nilai-nilai republik. Sebaliknya, di Bhutan, negara justru mewajibkan penggunaan atribut budaya untuk memperkuat identitas nasional.
| Aspek | Bhutan (Driglam Namzha) | Prancis (Laïcité) |
| Tindakan Negara | Mewajibkan (Preskriptif) | Melarang (Proskriptif) |
| Justifikasi Utama | Pelestarian identitas budaya dan kedaulatan | Netralitas negara dan kebebasan dari pengaruh agama |
| Lokasi Penegakan | Kantor pemerintah, sekolah, tempat suci | Sekolah umum, kantor pemerintah |
| Fokus Atribut | Busana nasional (Gho/Kira) | Simbol agama (Hijab, Burqa, Yarmulke, Salib) |
| Dampak pada Minoritas | Asimilasi budaya paksa bagi kelompok non-Drukpa | Diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu (Muslim) |
Di Prancis, larangan jilbab dan cadar dipandang oleh pendukungnya sebagai langkah untuk membebaskan perempuan dan menjaga kesatuan bangsa di bawah nilai sekuler. Namun, kritikus berpendapat bahwa ini adalah bentuk diskriminasi yang membatasi kebebasan beragama. Di Bhutan, kewajiban busana nasional dipandang sebagai upaya mempertahankan jati diri dari “invasi budaya Barat,” namun bagi kelompok minoritas, hal ini dirasakan sebagai penghapusan identitas etnis mereka sendiri. Kedua negara, meskipun dengan metode yang berlawanan (satu melarang, satu mewajibkan), sama-sama menggunakan pakaian warga negara sebagai alat untuk mencapai tujuan stabilitas nasional dan homogenitas identitas di ruang publik.
Kontroversi dan Krisis Kemanusiaan: Kasus Lhotshampa
Meskipun Driglam Namzha sering dipuji karena keindahan estetikanya, implementasinya sebagai kebijakan mandatori pada tahun 1989 memicu salah satu konflik etnis paling mendalam di wilayah Himalaya. Kebijakan ini merupakan bagian dari gerakan “Bhutanisasi” yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan elit Ngalop (Bhutan Utara) atas kelompok etnis lainnya, terutama warga Lhotshampa.
Lhotshampa adalah warga keturunan Nepal yang tinggal di bagian selatan Bhutan dan memiliki budaya, bahasa, serta agama yang berbeda dari mayoritas Buddha di utara. Bagi mereka, kewajiban mengenakan Gho dan Kira—yang merupakan pakaian tradisional etnis Ngalop—adalah bentuk penindasan budaya. Bahan wol berat dari Gho dan Kira juga dianggap sangat tidak praktis dan menyiksa di iklim selatan Bhutan yang panas dan tropis, kontras dengan pegunungan utara yang dingin.
Rangkaian peristiwa yang mengikuti dekrit 1989 meliputi:
- Penerapan Sensus 1988: Digunakan untuk mengategorikan warga berdasarkan status kewarganegaraan yang ketat, yang sering kali mendiskualifikasi warga Lhotshampa meskipun mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi.
- Penghapusan Bahasa Nepal: Bahasa Nepal dikeluarkan dari kurikulum sekolah di wilayah selatan.
- Tindakan Keras Militer: Protes terhadap kebijakan Driglam Namzha dan hukum kewarganegaraan pada tahun 1990 dibalas dengan penangkapan, penyiksaan, dan pembakaran rumah.
Krisis ini menyebabkan eksodus besar-besaran, di mana lebih dari 100.000 warga Lhotshampa (sekitar seperenam dari total populasi Bhutan saat itu) melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Nepal dan India. Hingga saat ini, sebagian besar dari mereka belum diizinkan kembali ke Bhutan, meskipun ada tekanan internasional. Kontroversi ini menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian budaya yang terlihat indah di permukaan dapat memiliki implikasi yang sangat destruktif ketika dipaksakan dalam masyarakat yang multietnis.
Strategi Bertahan di Era Fast Fashion: Kedaulatan melalui Tekstil
Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam perdebatan global saat ini adalah: di dunia yang semakin seragam karena dominasi industri fast fashion, apakah pemaksaan baju adat adalah strategi terbaik untuk bertahan? Bhutan menjawab tantangan ini melalui integrasi antara busana nasional dan filosofi Gross National Happiness (GNH).
Industri tekstil di Bhutan adalah salah satu pilar identitas nasional yang paling vital. Berbeda dengan industri fashion global yang mengandalkan produksi massal dan eksploitasi tenaga kerja, tekstil Bhutan didasarkan pada prinsip slow fashion. Kain tenun tangan tradisional seperti Kishuthara atau kain wol Yathra dari wilayah Bumthang adalah karya seni yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan.
| Perbandingan Industri | Fast Fashion Global | Tekstil Tradisional Bhutan |
| Kecepatan Produksi | Mingguan (Tren berubah cepat) | Bulanan/Tahunan (Klasik dan tahan lama) |
| Material | Sintetis (Poliester, nilon) | Serat alami (Sutra mentah, wol yak/domba, katun) |
| Teknik | Mesin otomatis massal | Alat tenun tradisional (Backstrap loom) |
| Dampak Lingkungan | Tinggi (Polusi, limbah tekstil) | Rendah (Ramah lingkungan, berkelanjutan) |
| Nilai Budaya | Komoditas murni | Warisan leluhur dan identitas spiritual |
Kebijakan wajib busana menciptakan pasar domestik yang stabil bagi para penenun lokal, mencegah industri tekstil tradisional mereka punah ditelan oleh impor pakaian murah dari India atau Tiongkok. Dalam pandangan sosiologis, busana nasional berfungsi sebagai “perisai” terhadap efek disrupsi modernitas. Tanpa kewajiban ini, ada ketakutan bahwa generasi muda akan sepenuhnya beralih ke jeans dan T-shirt, yang pada akhirnya akan mematikan pengetahuan teknis menenun yang telah diwariskan selama berabad-abad.
Namun, tantangan ekonomi tetap ada. Tekstil tenun tangan berkualitas tinggi sangat mahal, sehingga banyak warga mulai beralih ke kain buatan mesin yang meniru motif tradisional namun diproduksi di luar negeri. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana identitas visual tetap terjaga di permukaan, namun basis ekonomi dari pengrajin lokal mulai terancam oleh globalisasi ekonomi.
Dinamika Sosial Kontemporer: Antara Kebanggaan dan Kepatuhan
Di abad ke-21, terutama dalam periode 2024-2025, penegakan Driglam Namzha mengalami pergeseran ke arah yang lebih fleksibel. Di ibu kota Thimphu, adalah hal umum melihat pemuda mengenakan Gho atau Kira selama jam kerja, namun segera berganti menjadi pakaian Barat seperti jaket kulit dan jeans setelah matahari terbenam.
Diskusi di forum-forum daring seperti Reddit mencerminkan spektrum opini yang luas di kalangan warga Bhutan saat ini. Beberapa poin penting yang muncul meliputi:
- Kritik terhadap Elitisme: Muncul pendapat bahwa Driglam Namzha sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat hierarki sosial dan menunjukkan penghormatan yang berlebihan kepada elit politik dan agama, daripada sekadar melestarikan budaya.
- Beban Performatif: Beberapa warga merasa bahwa penggunaan busana nasional di tempat yang tidak sesuai, seperti saat berobat di rumah sakit, adalah tindakan yang tidak masuk akal dan membebani.
- Pergeseran Gender: Terdapat keprihatinan mengenai cara masyarakat memandang pakaian wanita. Muncul istilah ejekan seperti “blux” di kalangan akademisi untuk melakukan slut-shaming terhadap wanita yang dianggap tidak berpakaian cukup tradisional atau konservatif, yang menunjukkan adanya tekanan sosial yang masih kuat terkait moralitas dan busana.
- Adaptasi Modern: Para desainer muda Bhutan mulai bereksperimen dengan memodifikasi Gho dan Kira agar lebih nyaman digunakan dalam kehidupan urban yang sibuk, mengubahnya dari “seragam wajib” menjadi “kanvas ekspresi pribadi”.
Pemerintah sendiri mulai melonggarkan beberapa aturan. Di bawah kepemimpinan modern, penekanan dialihkan dari hukuman fisik ke arah persuasi budaya. Busana nasional kini lebih dipromosikan sebagai simbol patriotisme dan keunikan yang memberikan Bhutan keunggulan dalam industri pariwisata “nilai tinggi, dampak rendah”. Wisatawan pun sering didorong untuk mencoba mengenakan busana nasional sebagai bentuk apresiasi budaya, asalkan dilakukan dengan rasa hormat dan cara yang benar.
Paradoks “Shangri-La” dalam Representasi Global
Dunia internasional sering kali memandang Bhutan melalui lensa eksotisme sebagai “Shangri-La” yang tersisa—sebuah tempat di mana kebahagiaan diukur di atas pertumbuhan ekonomi dan semua orang mengenakan pakaian tradisional yang indah. Representasi ini sangat efektif untuk menarik minat wisatawan mewah dan merek fashion kelas atas (seperti Bulgari) yang ingin menggunakan latar belakang Bhutan untuk kampanye produk mereka.
Namun, sosiolog memperingatkan bahwa citra ini sering kali menghapus realitas hidup warga Bhutan yang sebenarnya. Bagi banyak wanita di pedesaan, kehidupan sehari-hari masih diisi oleh kerja keras di ladang dan tugas domestik yang berat, jauh dari citra “wanita pra-industri yang tersenyum” yang sering muncul dalam brosur pariwisata. Kebahagiaan di Bhutan, menurut survei, tidak selalu lebih tinggi dari rata-rata global, dan wanita Bhutan sering melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan pria karena beban kerja yang ganda.
Mitos Shangri-La ini, di satu sisi, membantu Bhutan mempertahankan posisinya dalam ekonomi global melalui pariwisata, namun di sisi lain, ia memaksa warga untuk terus melakukan “performa budaya” demi memenuhi ekspektasi dunia luar. Driglam Namzha menjadi bagian dari performa ini—sebuah cara untuk meyakinkan dunia (dan diri mereka sendiri) bahwa Bhutan tetap tidak berubah di tengah gempuran modernitas.
Kesimpulan dan Analisis Sintetis
Kebijakan Driglam Namzha di Bhutan menyajikan sebuah tesis yang kuat mengenai bagaimana negara kecil dapat melawan arus homogenisasi global melalui intervensi budaya yang radikal. Di tengah dominasi fast fashion yang merusak lingkungan dan melenyapkan keanekaragaman lokal, pilihan Bhutan untuk mewajibkan busana tradisional adalah strategi ketahanan yang efektif untuk menjaga kelangsungan industri tekstil domestik dan memperkuat rasa identitas nasional.
Namun, kesimpulan ini tidak boleh mengabaikan biaya sosial dan politik yang telah dibayar. Kasus kelompok minoritas Lhotshampa menjadi bukti nyata bahwa keseragaman budaya yang dipaksakan dapat berujung pada eksklusi sosial dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Sebuah identitas nasional yang tangguh seharusnya tidak hanya dibangun di atas keseragaman visual, tetapi juga di atas inklusivitas terhadap keragaman internal bangsa itu sendiri.
Masa depan Driglam Namzha kemungkinan besar terletak pada evolusi menuju bentuk yang lebih demokratis dan adaptif. Jika kode etik ini dapat bertransformasi dari sebuah kewajiban hukum yang kaku menjadi sebuah pilihan identitas yang didasarkan pada kebanggaan tulus—sebagaimana yang mulai terlihat pada generasi muda dan desainer modern—maka Bhutan akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup secara budaya tanpa harus mengorbankan harmoni sosialnya. Kunci keberhasilan pelestarian budaya di era global bukanlah fosilisasi tradisi, melainkan ketahanan yang dinamis, di mana busana nasional tidak lagi menjadi beban, melainkan simbol kedaulatan diri di dunia yang semakin seragam.