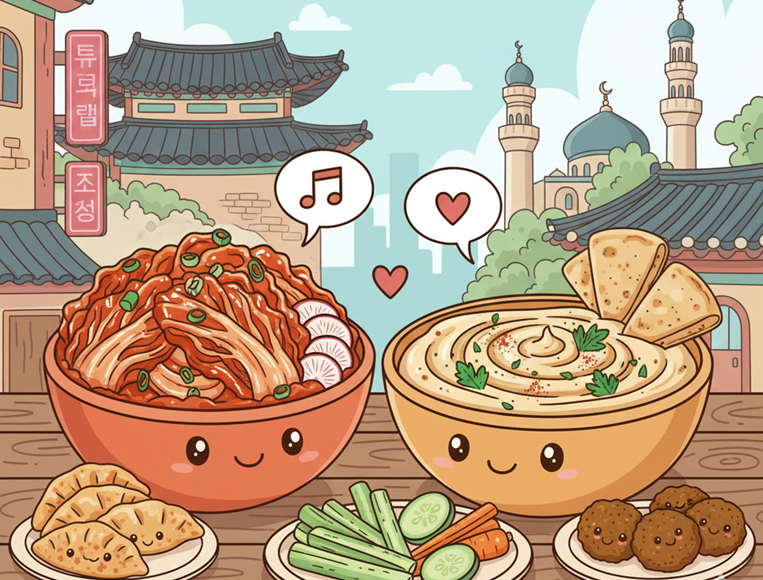Perang Kimchi dan Hummus: Saat Makanan Menjadi Sengketa Identitas
Dalam konstelasi geopolitik kontemporer, definisi kedaulatan telah meluas melampaui batas-batas teritorial fisik hingga mencakup domain budaya yang sangat personal, di mana makanan berfungsi sebagai instrumen utama dalam proyeksi kekuatan lunak atau soft power. Fenomena ini, yang secara akademis diidentifikasi sebagai gastronasionalisme, menggambarkan penggunaan makanan dan sejarah kulinernya sebagai sarana untuk mempromosikan nasionalisme dan memperkuat identitas nasional. Ketika sebuah hidangan tradisional diklaim oleh lebih dari satu negara, meja makan berubah menjadi medan tempur diplomatik yang “panas”, memicu ketegangan yang melibatkan kementerian luar negeri, organisasi standarisasi internasional, hingga pertempuran narasi di media sosial.
Evolusi makanan dari sekadar kebutuhan biologis menjadi simbol harga diri bangsa merupakan konsekuensi dari globalisasi yang, di satu sisi, mendorong homogenitas budaya, namun di sisi lain memicu resistensi dalam bentuk politik identitas yang lebih tajam. Dalam konteks ini, ulasan ini akan membedah secara mendalam bagaimana sengketa kuliner, khususnya “Perang Kimchi” antara Korea Selatan dan China serta “Perang Hummus” di Timur Tengah, merepresentasikan ketegangan eksistensial mengenai asal-usul, kepemilikan budaya, dan legitimasi sejarah. Analisis ini juga akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme internasional seperti UNESCO dan ISO berperan sebagai wasit sekaligus katalisator dalam persaingan identitas global yang semakin terfragmentasi.
Dialektika Fermentasi: Geopolitik di Balik Perang Kimchi
Perselisihan antara Korea Selatan dan Republik Rakyat China (RRC) mengenai kimchi merupakan studi kasus paling menonjol mengenai bagaimana nasionalisme digital dapat meningkatkan sengketa kuliner menjadi krisis diplomatik regional. Inti dari konflik ini bukan sekadar tentang resep sayuran fermentasi, melainkan tentang persepsi terhadap “imperialisme budaya” dan upaya untuk mendefinisikan kembali batas-tahun sejarah Asia Timur. Bagi Korea Selatan, kimchi adalah representasi ontologis dari identitas bangsa, dengan 95% populasi mengonsumsinya setiap hari dan menjadikannya komponen wajib dalam setiap jamuan makan.
Katalisator ISO 24220 dan Eskalasi Media
Ketegangan mencapai titik didih pada November 2020 ketika Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) merilis standar ISO 24220 untuk pao cai, sejenis sayuran asin fermentasi dari Sichuan, China. Meskipun dokumen ISO secara eksplisit menyatakan bahwa standar tersebut “tidak berlaku untuk kimchi”, media pemerintah China, Global Times, merilis laporan provokatif yang menyebutkan bahwa pencapaian tersebut adalah “standar internasional untuk industri kimchi yang dipimpin oleh China”. Klaim ini segera ditafsirkan oleh publik Korea Selatan sebagai upaya sistematis untuk melakukan apropriasi budaya.
Reaksi dari Seoul bersifat cepat dan multidimensional. Kementerian Pertanian, Pangan, dan Pedesaan Korea Selatan mengeluarkan klarifikasi resmi bahwa standar internasional untuk kimchi sebenarnya telah ditetapkan oleh Codex Alimentarius (badan standar pangan PBB/FAO) sejak tahun 2001. Perbedaan teknis antara kedua hidangan ini menjadi titik tekan utama dalam diplomasi publik Korea untuk membedakan identitas nasional mereka dari pengaruh tetangga raksasanya.
| Fitur Pembeda | Kimchi (Korea Selatan) | Pao Cai (Sichuan, China) |
| Bahan Utama | Sawi putih (Napa Cabbage), lobak, pasta cabai, bawang putih, jahe | Berbagai sayuran (sawi hijau, wortel, buncis), sering tanpa cabai merah |
| Metode Fermentasi | Fermentasi asam laktat dengan penambahan jeotgal (ikan/udang asin) | Perendaman dalam air garam (brine), terkadang dengan penambahan cuka |
| Mikrobiologi | Dominasi bakteri asam laktat (Leuconostoc, Lactobacillus) | Variasi mikroba tergantung pada komposisi air garam |
| Status Hukum | Standar Codex (FAO) tahun 2001 | Standar ISO 24220 tahun 2020 |
| Fungsi Budaya | Inti identitas nasional, ritual Gimjang (UNESCO) | Lauk regional, sering kali diproduksi secara industri |
Nasionalisme Digital dan Konflik Influencer
Sengketa ini semakin dipanaskan oleh pengaruh media sosial. Kasus video Li Ziqi, seorang influencer ternama China, yang menampilkan pembuatan sayuran fermentasi dengan teknik yang mirip kimchi namun dilabeli sebagai warisan China, memicu kemarahan netizen Korea. Di sisi lain, muncul klaim dari pihak China bahwa karena Korea Selatan mengimpor sebagian besar kimchi murah untuk konsumsi komersial dari China, maka China memiliki hak ekonomi atas industri tersebut. Kontroversi terbaru muncul pada acara Netflix “Super Rich in Korea” yang menggunakan terjemahan bahasa Mandarin “la bai cai” (sawi pedas) untuk merujuk pada kimchi, yang kemudian diprotes oleh warga Korea hingga akhirnya diubah menjadi “Xinqi”—nama resmi bahasa Mandarin yang direkomendasikan pemerintah Korea Selatan untuk membedakan diri dari pao cai.
Upaya Korea Selatan untuk mematenkan nama “Xinqi” mencerminkan strategi diplomasi linguistik guna mengamankan kekayaan intelektual budaya di pasar global yang didominasi oleh pengaruh China. Namun, resistensi dari konsumen China terhadap istilah baru ini menunjukkan bahwa identitas kuliner tidak dapat dengan mudah diubah melalui kebijakan administratif semata; ia membutuhkan pengakuan organik dari komunitas internasional.
Perang Hummus: Piring sebagai Medan Tempur Eksistensial di Levant
Jika Perang Kimchi berakar pada ketegangan sejarah Asia Timur, maka “Perang Hummus” di Timur Tengah merupakan proyeksi langsung dari konflik teritorial dan hak asasi manusia yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara Israel, Lebanon, dan Palestina. Hummus, saus kental dari buncis (chickpeas) dan tahini, telah menjadi simbol sentral dalam perdebatan mengenai apropriasi budaya, di mana satu pihak melihatnya sebagai simbol persatuan dan pihak lain melihatnya sebagai upaya penghapusan identitas pribumi.
Legitimasi Sejarah vs. Realitas Modern
Secara historis, bukti tertulis mengenai hidangan mirip hummus ditemukan dalam manuskrip masakan Suriah abad ke-13 yang dikaitkan dengan Ibn al-Adim. Bahan-bahan utamanya—buncis, wijen, lemon, dan bawang putih—telah dikonsumsi di wilayah Levant selama ribuan tahun. Namun, pasca berdirinya negara Israel pada tahun 1948, hummus diadopsi sebagai “hidangan nasional” tidak resmi oleh imigran Yahudi, baik mereka yang berasal dari Eropa maupun dari negara-negara Arab (Yahudi Mizrahi).
Kritikus, khususnya dari kalangan akademisi Palestina dan pejabat Lebanon, berargumen bahwa klaim Israel atas hummus adalah bentuk “pencucian kuliner” (culinary whitewashing). Mereka menekankan bahwa mempresentasikan hidangan yang telah ada jauh sebelum pembentukan negara Israel sebagai produk budaya Israel adalah bentuk penyangkalan terhadap kontribusi budaya Arab dan Palestina. Sebaliknya, banyak orang Israel berargumen bahwa makanan adalah milik bersama yang melintasi batas-batas agama dan politik, mengutip keberadaan komunitas Yahudi yang telah lama tinggal di wilayah tersebut dan berbagi tradisi kuliner yang sama.
Diplomasi Rekor Dunia Guinness
Persaingan ini mencapai puncaknya pada periode 2008-2010 dalam bentuk kompetisi rekor dunia. Koki Lebanon, didorong oleh kemarahan bahwa pasar global mulai menganggap hummus sebagai ciptaan Israel, berinisiatif untuk memecahkan rekor sajian hummus terbesar guna membuktikan kepemilikan budaya mereka. Persaingan ini bukan sekadar tentang ukuran, melainkan tentang pengakuan internasional atas “keaslian” sebuah bangsa.
| Tahun | Aktor Utama | Berat Hummus (kg) | Motivasi Diplomatik |
| 2009 | Lebanon (Koki Nasional) | 2.000 | Mengukuhkan hummus sebagai warisan asli Lebanon di mata dunia. |
| 2010 | Israel (Abu Gosh) | 4.000 | Menunjukkan popularitas hummus di Israel dan menantang klaim eksklusivitas. |
| 2010 | Lebanon | 10.452 | Secara simbolis mencocokkan luas wilayah Lebanon () untuk menegaskan kedaulatan. |
Dalam konteks hukum, Lebanon bahkan mencoba meniru strategi Uni Eropa untuk mendapatkan perlindungan Protected Designation of Origin (PDO) bagi hummus, namun upaya ini gagal karena hidangan tersebut diproduksi secara luas di berbagai negara, sehingga sulit untuk mengklaim originasi geografis yang unik secara hukum internasional.
Jollof Wars: Supremasi Rasa dan Warisan Kolonial di Afrika Barat
Berbeda dengan sengketa di Asia atau Timur Tengah yang cenderung antagonis, “Jollof Wars” di Afrika Barat merupakan bentuk persaingan identitas yang lebih ceria namun tetap memiliki signifikansi ekonomi dan budaya yang mendalam bagi Senegal, Nigeria, dan Ghana. Perdebatan ini berfokus pada dua hal: siapa yang menciptakan hidangan tersebut dan siapa yang memasaknya dengan rasa terbaik.
Pengakuan UNESCO dan Legitimasi Senegal
Pada tahun 2021, UNESCO memberikan kemenangan moral bagi Senegal dengan menetapkan Ceebu jën (versi Senegal dari Jollof Rice) sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan. Penetapan ini secara resmi mengakui Senegal sebagai tempat asal hidangan tersebut, yang berakar dari komunitas nelayan di pulau Saint-Louis. Sejarah menunjukkan bahwa Jollof Rice muncul dari persimpangan antara tradisi lokal dan tekanan ekonomi kolonial Prancis antara tahun 1860-1940, di mana beras pecah yang diimpor dari Indochina menjadi bahan pokok yang lebih terjangkau dan kemudian dicintai oleh masyarakat lokal.
Komersialisasi dan Bangga Nasional
Meskipun Senegal memiliki legitimasi sejarah, Nigeria dan Ghana tetap menjadi pemain dominan dalam mempopulerkan Jollof secara global melalui musik Afrobeats dan media sosial. Persaingan antara “Nigeria Jollof” yang dikenal dengan aroma asapnya dan “Ghana Jollof” yang menggunakan beras basmati menjadi alat diplomasi publik yang efektif untuk menarik wisatawan dan mempromosikan ekspor rempah-rempah. Bagi negara-negara ini, keberhasilan kuliner diukur dari pengakuan publik internasional, bukan sekadar sertifikasi organisasi dunia.
Pertempuran Hukum atas Nama: Pisco, Halloumi, dan Baklava
Di luar sengketa emosional, terdapat pula sengketa teknis yang berpusat pada hak kekayaan intelektual dan indikasi geografis yang memiliki dampak langsung pada perdagangan internasional.
Pisco: Peru vs. Chile
Sengketa atas brendi anggur Pisco merupakan konflik hukum tertua di Amerika Selatan, yang berakar pada periode pasca-Perang Pasifik. Peru berargumen bahwa Pisco adalah nama tempat (pelabuhan Pisco) dan oleh karena itu hanya produk dari wilayah tersebut yang berhak menyandang namanya. Chile, sebagai produsen yang lebih besar secara volume, mengklaim tradisi produksi yang sama panjangnya. Konflik ini memaksa produsen di kedua negara untuk menggunakan label yang berbeda di pasar tertentu guna menghindari hambatan hukum.
| Aspek Produksi | Pisco Peru | Pisco Chile |
| Bahan Baku | 8 varietas anggur spesifik | Terutama varietas Muscat |
| Distilasi | Sekali distilasi dalam pot tembaga | Bisa distilasi berulang kali |
| Penuaan | Tidak boleh ada penuaan kayu (purity) | Boleh menggunakan tong kayu ek |
| Kadar Alkohol | Harus tetap setelah distilasi (tidak boleh ditambah air) | Boleh ditambah air untuk mengatur kadar alkohol |
Halloumi dan Baklava: Identitas Mediterania
Siprus telah berjuang keras untuk mengamankan status PDO bagi keju Halloumi guna mencegah produksi “tiruan” dari Bulgaria atau Inggris. Sengketa ini sangat krusial karena ekspor Halloumi menyumbang persentase signifikan terhadap PDB Siprus. Sementara itu, perdebatan mengenai Baklava antara Turki dan Yunani mencerminkan sejarah panjang Kekaisaran Ottoman, di mana makanan menjadi salah satu dari sedikit elemen budaya yang tetap menyatukan kedua bangsa di tengah sejarah politik yang pahit.
Gastrodiplomacy: Makanan sebagai Alat Kekuatan Lunak
Untuk memitigasi sengketa dan memaksimalkan potensi ekonomi, banyak pemerintah mengadopsi kampanye diplomasi kuliner yang terstruktur. Thailand adalah pionir dengan program “Global Thai” yang diluncurkan pada 2002, yang berhasil meningkatkan jumlah restoran Thai di dunia dan secara langsung mendorong lonjakan pariwisata hingga 200%. Strategi ini melibatkan:
- Investasi Finansial: Pinjaman bagi warga negara yang membuka restoran di luar negeri.
- Standardisasi Kualitas: Sertifikasi “Thai SELECT” untuk memastikan otentisitas rasa.
- Nation Branding: Mengubah citra negara dari destinasi wisata seks menjadi pusat kuliner dunia.
Peru mengikuti jejak ini dengan kampanye “Cocina Peruana para el Mundo”, yang menggunakan kebanggaan kuliner sebagai alat integrasi sosial pasca-konflik internal dan memposisikan koki sebagai duta besar diplomatik. Pengalaman kedua negara ini membuktikan bahwa makanan dapat menjadi jembatan diplomasi jika dikelola dengan visi strategis yang mengedepankan kolaborasi daripada konfrontasi.
Analisis Sosiologis: Mengapa Kita Bertarung demi Sepiring Makanan?
Secara sosiologis, sengketa kuliner terjadi karena makanan memenuhi fungsi sebagai “nasionalisme banal”—pengingat harian akan identitas nasional yang dikonsumsi secara harfiah ke dalam tubuh. Menurut sosiolog Michaela DeSoucey, gastronasionalisme adalah mekanisme pertahanan budaya terhadap homogenisasi global. Ketika batas-batas teritorial menjadi semakin kabur karena migrasi dan internet, piring makanan tetap menjadi batas simbolis yang nyata.
Makanan juga merupakan bentuk “modal budaya” (Bourdieu) yang memberikan status bagi sebuah bangsa di panggung internasional. Memiliki hidangan nasional yang diakui dunia bukan hanya tentang kebanggaan, tetapi juga tentang pengakuan atas kecanggihan peradaban, karena masyarakat agraris yang “menetap” dianggap memiliki budaya kuliner yang lebih tinggi daripada bangsa nomaden dalam narasi nasionalistik tradisional.
Kesimpulan: Navigating the Politics of the Plate
Sengketa identitas makanan yang “panas”—mulai dari Kimchi hingga Hummus—menunjukkan bahwa di era modern, kedaulatan budaya sama pentingnya dengan kedaulatan politik. Makanan bukan sekadar urusan rasa di lidah; ia adalah bahasa kekuasaan, memori kolektif, dan simbol harga diri bangsa yang mampu memicu krisis diplomatik sekaligus membangun jembatan perdamaian.
Pelajaran dari berbagai “Perang Makanan” ini adalah bahwa klaim atas asal-usul sering kali lebih didorong oleh kebutuhan akan legitimasi saat ini daripada fakta sejarah yang absolut, mengingat sejarah kuliner secara inheren bersifat hibrida dan lintas batas. Tantangan bagi diplomasi masa depan adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan terhadap warisan budaya nasional tanpa terjatuh ke dalam eksklusivisme agresif yang menghambat pertukaran budaya global. Meja makan, jika dikelola dengan rasa hormat dan diplomasi yang cerdas, tetap menjadi ruang terbaik bagi umat manusia untuk menemukan kesamaan di tengah perbedaan identitas yang tajam.