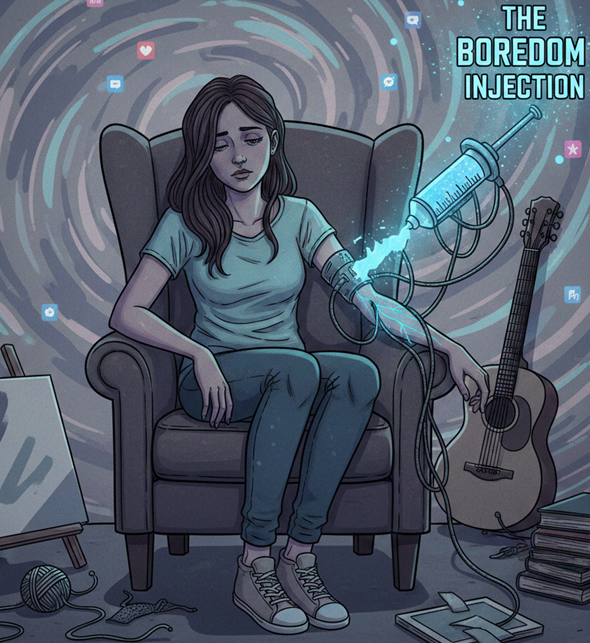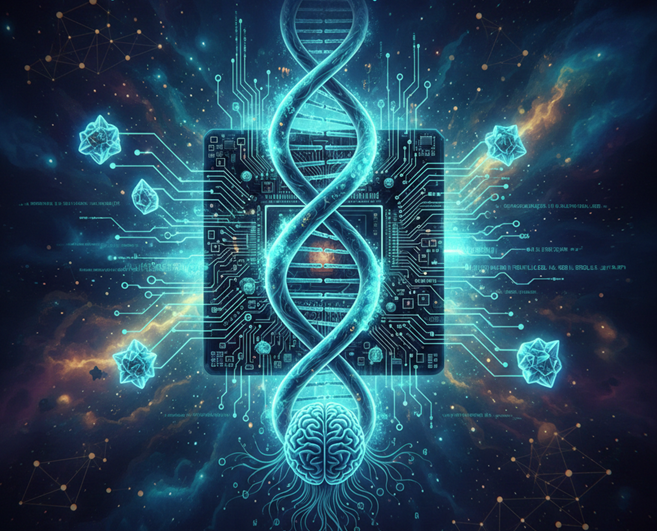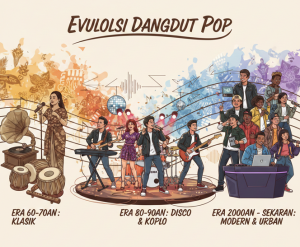Ketika Desainer Barat Meminjam Dari Timur: Kajian Kritis Etika Apropriasi Budaya Dalam Fashion Internasional
Latar Belakang dan Urgensi Isu: Dari Inspirasi ke Eksploitasi
Industri fashion global, terutama sektor mewah, telah menunjukkan peningkatan ketergantungan pada apa yang disebut sebagai mode etnik, yaitu perpaduan antara desain modern dengan unsur-unsur budaya dan tradisi dari berbagai kelompok etnis. Fenomena ini pada dasarnya menawarkan keunikan dan keaslian yang tidak dapat ditemukan dalam desain konvensional. Namun, praktik “peminjaman” ini seringkali melintasi batas dari inspirasi kreatif yang etis menuju eksploitasi yang merugikan.
Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meninjau secara kritis bagaimana elemen busana tradisional digunakan atau disalahgunakan. Penggunaan elemen budaya Timur oleh merek Barat berisiko mereduksi nilai budaya menjadi sekadar komoditas , sehingga menghilangkan nilai historis dan sosial yang kuat yang melekat pada artefak budaya tersebut. Dorongan utama di balik kecenderungan ini adalah kapitalisme budaya, di mana peningkatan konsumerisme global memacu industri mode mewah untuk terus mencari estetika baru dan unik dari sumber luar. Ketika sumber inspirasi ini diambil dari budaya minoritas—seringkali tanpa biaya akuisisi atau kompensasi—apropriasi menjadi strategi yang didorong oleh keuntungan di bawah kedok “kreativitas,” sebuah praktik yang memperkuat pola ekstraksi ekonomi yang tidak seimbang.
Kerangka Terminologi: Mendefinisikan Batasan Etis (Apropriasi vs. Apresiasi)
Pemahaman yang jelas mengenai batasan etis adalah inti dari diskusi ini. Perbedaan fundamental antara apropriasi budaya dan apresiasi budaya ditentukan oleh konteks sosial, niat pelaku, dan yang paling penting, hubungan antara budaya dominan dan budaya terpinggirkan. Apresiasi ditandai dengan penghormatan dan pengakuan yang mendalam, sedangkan apropriasi adalah tindakan mengambil elemen budaya tanpa penghormatan, menghasilkan eksploitasi.
Kriteria pembeda yang ditekankan oleh para ahli menunjukkan bahwa apropriasi sering terjadi ketika budaya dominan mengeksploitasi budaya minoritas, menciptakan ketimpangan kekuasaan dan memicu tuduhan ketidakpekaan. Jika ditinjau dari perspektif historis, apropriasi budaya bukan hanya masalah desain yang mirip, melainkan manifestasi neo-kolonialisme ekonomi. Hal ini merupakan kelanjutan dari pola historis di mana kekayaan intelektual atau sumber daya (Ekspresi Budaya Tradisional atau EBT) dari Global South diambil oleh entitas Barat untuk keuntungan komersial tanpa mekanisme pengembalian yang adil. Kegagalan untuk menerapkan benefit sharing atau kompensasi yang adil adalah analogi modern dari pengambilan bahan mentah tanpa kompensasi yang layak.
Table I. Kriteria Pembeda Apropriasi dan Apresiasi Budaya dalam Fashion
| Kriteria Etika | Apropriasi Budaya (CA) | Apresiasi Budaya (CApp) |
| Dinamika Kekuasaan | Ketimpangan kekuasaan; Budaya dominan mengeksploitasi budaya minoritas | Keseimbangan; Kemitraan setara yang menghormati otonomi komunitas. |
| Niat dan Konteks | Komersialisasi murni; Tanpa pemahaman mendalam/penghormatan historis | Penghargaan, pengakuan, dan pemahaman mendalam atas makna budaya. |
| Kompensasi | Nihil; Keuntungan dinikmati sepihak (merek mewah) 6 | Benefit sharing wajib; Kompensasi finansial yang adil melalui skema royalti/lisensi. |
| Izin/Persetujuan | Tidak ada Prior Informed Consent (PIC) | PIC formal, keterlibatan aktif komunitas, dan pengakuan kepengarangan. |
Analisis Teoritis Apropriasi Budaya dalam Rantai Pasokan Mewah
Komodifikasi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT): Proses Dekontekstualisasi Motif
Merek mewah cenderung memisahkan elemen desain tradisional dari asal-usulnya, sebuah proses yang dikenal sebagai dekontekstualisasi. Komersialisasi remix berisiko mereduksi nilai budaya menjadi komoditas semata dan mengabaikan hak kreator asli, terutama dari kelompok terpinggirkan. Meskipun mode etnik seharusnya menawarkan keunikan dan keaslian, praktik apropriasi justru menghilangkan keaslian tersebut dengan menghilangkan fungsi simbolis dari motif.
Ketika motif yang memiliki makna spiritual, status sosial, atau historis yang mendalam (misalnya, pola tenun dari komunitas adat) dipindahkan ke catwalk Barat dan dijual sebagai “tren musiman,” nilai intrinsiknya dihilangkan. Merek-merek mewah umumnya hanya berfokus pada daya tarik visual daripada nilai intrinsik.3 Proses ini seringkali memicu protes dan reaksi negatif yang signifikan dari komunitas asal. Kasus-kasus seperti pengambilan motif mamianqun Tiongkok dan blus Tlahuitoltepec Meksiko 8 mengilustrasikan bagaimana EBT dikomodikasi dan diubah menjadi item mode premium, yang diklaim sebagai “siluet khas” merek mewah tersebut.
Harm Ekonomi dan Reputasi: Dampak Komersialisasi Massal
Dampak ekonomi apropriasi budaya sangat merugikan komunitas asal. Kerugian finansial terjadi ketika merek mewah Barat meraih keuntungan besar, sementara komunitas yang menciptakan desain asli tidak menerima kompensasi yang adil. Sebagai contoh, merek seperti Dior menjual rok yang sangat mirip dengan mamianqun seharga $3.800, melebihi 100 kali lipat harga produk yang sama dari desainer Tiongkok asli, yang justru menawarkan kualitas dan detail yang lebih tinggi.
Merek mewah berupaya meyakinkan konsumen global bahwa produk mereka adalah “desain orisinal” dengan harga yang sangat premium, sehingga secara langsung merampas keuntungan finansial dan merusak pasar produk otentik yang ditawarkan oleh desainer budaya asal. Dalam konteks domestik Indonesia, kegagalan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebabkan kerugian signifikan, seperti pemalsuan wayang kulit di pasar global yang merugikan ekonomi lokal hingga miliaran rupiah setiap tahun. Lebih jauh lagi, penggunaan elemen budaya tanpa persetujuan atau benefit sharing dapat menodai reputasi perusahaan , memicu reaksi keras yang memaksa merek untuk berhati-hati, terutama di pasar sensitif dan berpengaruh seperti Tiongkok atau Meksiko.
Studi Kasus Konflik Etika di Panggung Global
Bagian ini membahas pola apropriasi yang berulang melalui studi kasus kontroversial yang menyoroti tuntutan etika, hukum, dan ekonomi yang diajukan oleh komunitas asal di Asia dan Global South.
Kasus Dior: Kontroversi Motif Tiongkok (Mamianqun)
Pada Juli 2022, Dior menghadapi kritik tajam setelah meluncurkan rok lipit wol dan mohair seharga $3.800. Rok tersebut memiliki lipatan dan desain yang sangat mirip dengan mamianqun (rok berlipit muka kuda), sebuah busana tradisional Hanfu yang dikenakan oleh wanita di Dinasti Ming, Tiongkok.
Kritik utama difokuskan pada klaim Dior yang menyebut desain tersebut sebagai “siluet khas Dior” (hallmark Dior silhouette). Media Tiongkok, termasuk People’s Daily, mengecam merek mewah Prancis tersebut karena mengambil elemen budaya secara tidak tahu malu tanpa pengakuan atau penghormatan. Kritik ekonomi menyoroti ketidakadilan harga, di mana Dior menjual produknya lebih dari seratus kali lipat harga produk otentik yang ditawarkan oleh desainer Tiongkok, padahal desainer asli menawarkan bordir dan teknik tenun emas tradisional yang lebih kompleks dengan harga yang jauh lebih rendah (sekitar $100). Sebagai respons, Dior hanya menghapus rok tersebut dari situs webnya di Tiongkok tanpa pernyataan atau permintaan maaf publik. Respons ini menunjukkan bahwa sensitivitas budaya seringkali didorong oleh tekanan pasar—mengingat Tiongkok diproyeksikan menjadi pasar mewah terbesar pada tahun 2025—dan keinginan untuk menghindari kontroversi, alih-alih didasarkan pada komitmen etika yang mendalam. Dalam konteks ini, kekuatan konsumen yang terorganisir di pasar non-Barat berfungsi sebagai mekanisme regulasi informal yang efektif.
Kasus Isabel Marant: Pola Berulang dan Tuntutan Komunitas Adat Meksiko
Kasus Isabel Marant menyoroti pola apropriasi yang berulang terhadap desain komunitas adat Meksiko. Marant dituduh mengambil desain blus yang secara spesifik menyerupai blus Tlahuitoltepec dari komunitas Santa Maria Tlahuitoltepec, Oaxaca. Selain itu, Marant juga dikecam karena menggunakan pola unik dari komunitas Purepecha untuk sebuah jubah.
Komunitas Mixe, yang merupakan pemilik budaya blus tersebut, menuntut ganti rugi atas plagiarisme. Meskipun Marant awalnya berdalih bahwa ia tidak mengklaim kepengarangan dan menelusuri desainnya kembali ke desa Meksiko, konflik ini memicu pertarungan hukum. Sebuah pengadilan sipil di Paris akhirnya memutuskan bahwa “baik Isabel Marant maupun Antik Batik tidak dapat [mengklaim] hak atas kemeja huipil karena itu adalah artefak budaya masyarakat Mixe”. Secara politik, kasus ini memicu reaksi keras; Menteri Kebudayaan Meksiko secara resmi menuduh Marant, dan Kongres Oaxaca mendeklarasikan desain tradisional mereka sebagai Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage), sebuah langkah simbolis untuk mengakui keunikan dan asal-usulnya. Meskipun putusan pengadilan memberikan kemenangan signifikan dalam pengakuan hak kolektif atas EBT, ganti rugi finansial yang diperintahkan seringkali minimal—misalnya hanya $3.000 untuk biaya hukum —jauh dari kerugian ekonomi aktual yang dialami komunitas akibat eksploitasi. Hal ini menunjukkan adanya celah antara pengakuan hukum formal dan kompensasi material yang adil.
Table II. Analisis Kasus Apropriasi Merek Mewah Terpilih
| Merek/Kasus | Budaya Asal | Item/Motif yang Diambil | Kritik Utama Etika & Ekonomi | Respons Merek |
| Dior (2022) | Tiongkok (Dinasti Ming) | Rok Lipit (Mamianqun) | Klaim sebagai “siluet khas Dior”; Mark-up harga $>100x$; Merugikan desainer asli Tiongkok. | Penghapusan diam-diam produk di Tiongkok; Tidak ada permintaan maaf publik. |
| Isabel Marant | Mixe/Tule, Oaxaca, Meksiko | Blus Tlahuitoltepec/ Cape Pola Purepecha | Plagiarisme; Penggunaan tanpa Prior Informed Consent; Melanggar status artefak budaya. | Mengakui asal; Membayar biaya hukum (minimal); Dikecam oleh Menteri Kebudayaan Meksiko. |
Kerangka Hukum dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional (HKI-EBT)
Isu apropriasi budaya tidak dapat diselesaikan tanpa mengatasi kerentanan struktural dalam perlindungan hukum atas EBT, terutama di negara-negara Timur, yang menjadikan mereka target eksploitasi yang mudah.
Batasan HKI Konvensional: Fokus Individual vs. Kepemilikan Komunal
Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional di Barat dibangun di atas filosofi perlindungan hak monopoli individu (invention) dan pemberian keuntungan finansial kepada penemu. Konsep ini berbenturan secara fundamental dengan hak atas EBT, di mana kepemilikan dan tata nilai bersifat komunal dan dikembangkan secara kolektif dari waktu ke waktu.
Tantangan filosofis muncul dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang kuat atas Pengetahuan Tradisional dan EBT tanpa menghilangkan karakteristik tradisionalnya, mengingat konsep HKI yang menargetkan kemampuan individual. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan khusus (sui generis) yang mengakui hak kolektif dan komunal atas warisan budaya.
Tantangan Implementasi UU Hak Cipta Indonesia: Kasus Motif Lokal
Secara hukum, Indonesia telah memiliki kerangka kerja yang mengakui perlindungan EBT. Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit mengakui perlindungan atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara (Pasal 38 ayat 1). Selain itu, motif juga termasuk jenis Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi (Pasal 40 ayat 1 huruf j).UU ini juga secara eksplisit mengakui perlindungan atas pengetahuan tradisional yang diadaptasi (Pasal 10 dan 38).
Namun, implementasi di tingkat komunitas adat masih sangat lemah. Kurangnya kesadaran mengenai mekanisme hak cipta adalah hambatan praktis yang utama. Dilaporkan bahwa hanya sekitar 20% komunitas adat yang pernah mengikuti sosialisasi HKI pada tahun 2022. Akibatnya, pendaftaran hak cipta sering diabaikan. Sebagai contoh, pengrajin motif sinsen silok Kapuas Hulu belum mendaftarkan hak cipta mereka karena kurangnya pemahaman dan respons pemerintah yang minim. Kelalaian pendaftaran formal ini membuat motif seperti batik Cirebon atau sinsen silok Kapuas Hulu rentan terhadap plagiarisme dan pencurian oleh desainer internasional tanpa royalti. Permasalahan mendasar di Asia/Timur bukan terletak pada ketiadaan hukum, tetapi pada aksesibilitas, kapasitas implementasi, dan kegagalan fungsional sistem HKI domestik dalam menjangkau dan memberdayakan komunitas pencipta.
Mekanisme Keterlibatan Etis dan Kemitraan yang Adil
Untuk menggeser praktik industri fashion dari apropriasi ke apresiasi, diperlukan adopsi kerangka kerja yang didasarkan pada pengakuan formal, persetujuan, dan pembagian manfaat yang adil (benefit sharing).
Prinsip Kunci: Implementasi Prior Informed Consent (PIC)
Prior Informed Consent (PIC) adalah pilar etika utama yang direkomendasikan secara internasional oleh badan-badan seperti WIPO dan UN Declaration on Rights of Indigenous Peoples. Permintaan PIC disarankan sebelum mengintegrasikan elemen budaya apa pun ke dalam desain untuk menghindari paparan media yang merugikan dan tuntutan hukum.
Mengadaptasi model informed consent dari konteks etika profesional , PIC dalam fashion harus mencakup beberapa elemen penting:
- Penjelasan Mendetail: Komunitas harus menerima penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami mengenai prosedur komersial yang akan dilakukan, meliputi tujuan, risiko (seperti dekontekstualisasi dan komodifikasi), manfaat yang dijamin, serta alternatif penggunaan.
- Kebebasan Memilih: Komunitas harus diberikan kebebasan penuh untuk menerima atau menolak kolaborasi dan memiliki hak untuk menarik kembali persetujuan mereka kapan saja tanpa hukuman.
- Kapasitas Komunitas: Proses PIC harus memastikan bahwa perwakilan komunitas yang sah memiliki kapasitas, pengetahuan komersial, dan dukungan hukum yang memadai untuk memahami implikasi skala pasar global.
PIC yang efektif harus secara eksplisit mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan yang ada. Ini memastikan bahwa komunitas tidak hanya “mengizinkan” penggunaan, tetapi juga “memahami” nilai finansial dari desain mereka di pasar mewah, sehingga dapat menegosiasikan bagian yang sepadan dari harga jual premium ($3.800).
Model Kompensasi dan Benefit Sharing yang Terstruktur
Benefit sharing adalah cara yang paling konkret dan dapat diukur untuk memberikan kompensasi finansial yang adil bagi komunitas asal. WIPO telah menguraikan enam langkah yang harus dipertimbangkan perusahaan fashion ketika berkolaborasi dengan komunitas adat, baik melalui penggunaan desain spesifik, adaptasi desain, atau produksi produk oleh perajin adat.10 Namun, saat ini hanya 5% perusahaan yang melaporkan konsultasi dengan pemimpin adat mengenai dampak rantai pasokan dan praktik mereka.
Mekanisme implementasi yang disarankan meliputi:
- Lisensi dengan Royalti Transparan: Merek harus membayar royalti berbasis persentase penjualan global—bukan biaya datar (one-time flat fee)—yang dialokasikan ke dana perwalian yang dikelola oleh komunitas atau organisasi yang mewakilinya.
- Pembangunan Kapasitas: Kolaborasi harus mencakup investasi dalam infrastruktur lokal, pelatihan HKI, dan akses ke pasar global, seperti yang dicontohkan oleh kolaborasi apik antara label urban dan pengrajin tenun Toraja (Cotton Ink x Torajamelo).
- Kemitraan Jangka Panjang: Kemitraan harus bergeser dari kegiatan filantropi (CSR) menjadi model bisnis yang integral, menjamin fair trade dan mewujudkan prinsip kesetaraan (equity).
Standar Industri: Mendorong Transparansi dan Fair Trade Fashion
Konsumen saat ini semakin menuntut keaslian, keberlanjutan, dan kesetaraan dari merek yang mereka dukung. Merek mewah tidak lagi hanya ditujukan untuk pasar kelas atas tertentu, tetapi juga bagi konsumen menengah yang menuntut transparansi dan makna yang lebih dalam.
Pengembangan standar industri yang seragam sangat diperlukan. Standar ini dapat berupa sertifikasi Fair Trade Cultural Expressions yang setara dengan standar fair trade untuk bahan baku. Sertifikasi ini akan memaksa merek untuk melaporkan konsultasi mereka dengan komunitas adat dan memastikan bahwa kolaborasi etis menjadi prasyarat untuk reputasi merek yang positif.
Table III. Protokol Keterlibatan Etis Berbasis PIC dan Benefit Sharing
| Langkah Etis Utama | Tindakan Kebutuhan Merek Mewah | Kebutuhan Komunitas Asal | Dasar Referensi |
| 1. Pengakuan Formal | Menghentikan klaim “inspirasi” atau “desain orisinal” untuk EBT yang telah ada. | Deklarasi Warisan Budaya Takbenda (seperti Oaxaca). | WIPO/CI Principles |
| 2. Prior Informed Consent (PIC) | Proses formal, terdokumentasi, melibatkan perwakilan komunitas yang diakui. | Penjelasan lengkap mengenai risiko komersial, harga jual, dan total keuntungan yang diproyeksikan. | UN Declaration on Rights of Indigenous Peoples |
| 3. Benefit Sharing | Skema royalti berbasis persentase penjualan global, bukan hanya donasi satu kali. | Pendaftaran HKI komunal (EBT) yang didukung pemerintah (Pasal 38, 40). | Prinsip Equity |
| 4. Kemitraan Produksi | Melibatkan perajin adat dalam rantai pasokan, membayar upah adil (fair trade) dan memastikan alih pengetahuan dua arah. | Pembangunan kapasitas literasi hukum dan bisnis. | Model Kolaborasi Lokal yang Sukses |
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Lanjut
Apropriasi budaya dalam fashion mewah adalah masalah struktural yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan global dan kegagalan sistem HKI konvensional untuk melindungi hak kepemilikan komunal. Merek-merek Barat telah mengambil nilai budaya historis, mengkomodifikasikannya dengan harga premium (seperti kasus Dior dan mamianqun), dan mengabaikan kreator asli, menimbulkan kerugian ekonomi, spiritual, dan reputasi. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun pengadilan dapat memberikan pengakuan legal terhadap status artefak budaya (seperti dalam kasus Isabel Marant), kompensasi finansial yang adil masih minimal. Solusi yang efektif harus mencakup reformasi etika melalui Prior Informed Consent (PIC) dan penguatan kerangka hukum wajib untuk benefit sharing.
Rekomendasi Aksi untuk Merek Global, Pemerintah, dan Komunitas Asal
Untuk mencapai transisi yang adil dari apropriasi ke apresiasi, tindakan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan.
Rekomendasi untuk Merek Fashion Mewah Global
- Mandatori PIC dan Benefit Sharing: Merek harus mengadopsi prinsip-prinsip keterlibatan WIPO sebagai kebijakan rantai pasokan wajib. Setiap penggunaan EBT harus didahului oleh PIC yang transparan dan diikuti oleh benefit sharing finansial, idealnya melalui skema royalti berbasis persentase penjualan global.
- Audit Rantai Kreatif: Merek wajib melakukan audit internal untuk memastikan desainer dididik tentang etika budaya dan menghentikan klaim kepengarangan yang menyesatkan, seperti mengklaim EBT sebagai “siluet khas Dior”.
Rekomendasi untuk Pemerintah Negara Asal (Contoh: Indonesia)
- Penguatan HKI-EBT Proaktif: Pemerintah harus memprioritaskan pendaftaran EBT secara proaktif dan masif. Daripada hanya menunggu komunitas mendaftar, pemerintah (melalui Kemenparekraf atau Ditjen KI) harus meluncurkan program door-to-door untuk mendokumentasikan dan mendaftarkan motif tradisional (seperti motif Sinsen Silok Kapuas Hulu atau batik Cirebon) secara kolektif di bawah kepemilikan Negara/Komunitas.
- Literasi Hukum Komunal: Peningkatan sosialisasi HKI harus dilakukan secara agresif di kalangan komunitas adat (meningkatkan angka dari 20% yang aware), dengan fokus pada pemahaman manfaat ekonomi pendaftaran dan mekanisme negosiasi lisensi yang adil.
- Rekomendasi untuk Komunitas Adat dan Organisasi Non-Pemerintah
- Penguatan Struktur Perwakilan: Komunitas harus didorong dan didukung untuk membentuk badan atau dewan perwakilan resmi yang memiliki kapasitas hukum dan komersial yang memadai untuk bernegosiasi dengan merek global dan mengelola dana benefit sharing secara transparan.
- Dokumentasi EBT: Komunitas perlu didorong untuk mendokumentasikan EBT mereka secara sistematis, menjadikannya bukti otentik kepemilikan yang kuat dalam menghadapi tuntutan hukum dan komersial di tingkat internasional.
Dengan mengintegrasikan prinsip etika, pengakuan hukum, dan kompensasi ekonomi, industri fashion global dapat beralih dari siklus ekstraktif apropriasi menuju kemitraan yang menghargai inovasi tradisional dan menjamin keberlanjutan budaya.